16. Wedding Ring
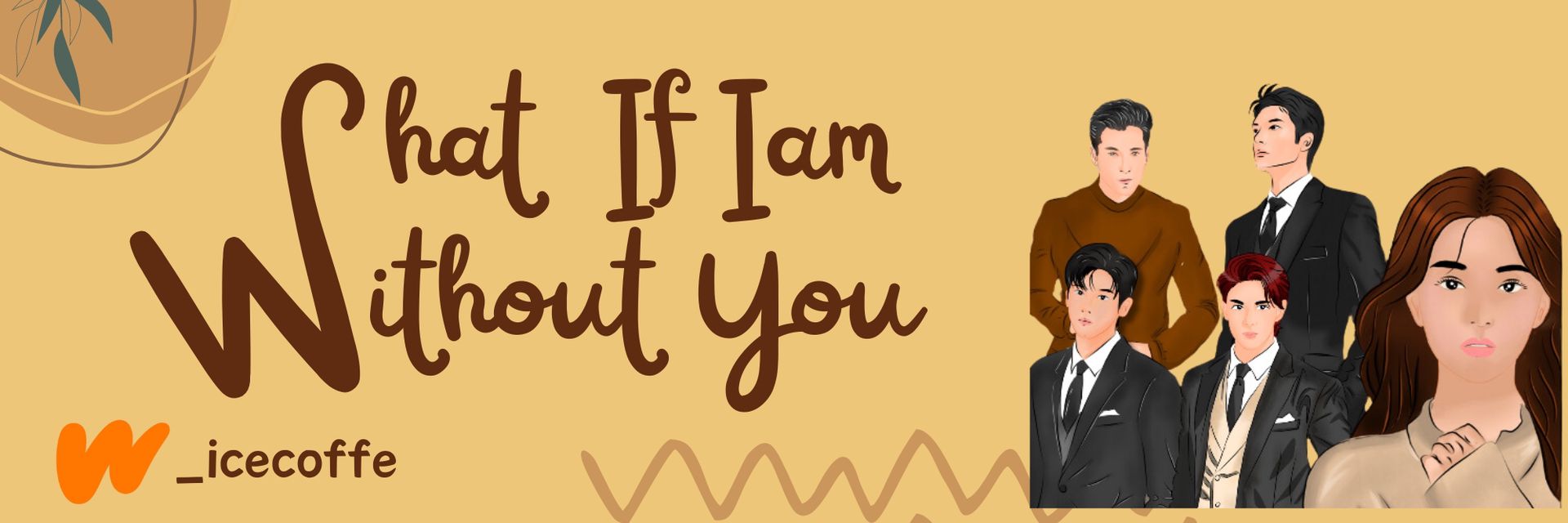
"Padahal ini nggak perlu, Kak."
Candra mendesah lantas mengalungkan stetoskop ke lehernya. Dagunya mengedik ke arah Reyga yang duduk di sofa single seater tengah memperhatikan Kiana dengan raut khawatir.
"Dia yang memaksaku ikut. Katanya mau mastiin kalau kamu beneran nggak apa-apa."
Kiana tersenyum tipis menatap Reyga. Dia tahu kekhawatiran yang pria itu rasakan.
"Pokoknya setelah ini, kamu nggak boleh ke mana-mana lagi," tukas Reyga, seraya meraih tangan Kiana. "Aku takut hal begini terulang lagi. Kamu tau nggak sih betapa cemasnya aku saat kamu susah dihubungi?"
"Maaf." Hanya itu yang bisa Kiana katakan sambil menunduk.
Di ranjang pasien, Raven berdecak. Wajah masamnya belum juga hilang sejak kedatangan Candra dan Reyga. Apalagi melihat Reyga selalu berada di dekat Kiana. Namun, siapa yang peduli dengan rasa kesalnya sekarang?
Candra berdiri, lantas tersenyum miring menghampiri ranjang Raven. "Sebaiknya turutin aja kemauan Nenek. Lagi pula, di sana kamu akan dapat perawatan yang lebih bagus."
Nek Gatri bilang akan membawa Raven sore ini juga ke Jakarta dan meminta dokter yang menangani pria itu untuk memberi surat rujukan.
Segalanya kacau. Jika Raven kembali ke Jakarta, kesempatan bersama Kiana pasti terbatas dengan kondisinya yang begini. Namun, dia juga tidak bisa membantah titah sang nenek.
"Boleh kuperiksa lukamu?"
"Nggak perlu," tukas Raven cepat. Dia melirik kesal Kiana dan Reyga yang tengah mengobrol dengan suara pelan. "Apa kalian berdua nggak bisa keluar dari sini? Aku mau istirahat."
Di posisinya Candra pura-pura terkesiap kaget sambil menyentuh dadanya. Mukanya sengaja dibikin sedih untuk mendramatisir. "Ya ampun, adikku jahat sekali. Padahal aku sudah menempuh perjalanan jauh demi melihat keadaan adikku tercinta, tapi malah diusir. Tega!"
"Nggak usah lebay!" decak Raven, menarik bantal dan memukulkannya ke pundak Candra. "Sana keluar kalian," usirnya tanpa beban.
Dengan sebal Candra berdiri, dan mengerling kepada Reyga. "Rey, kita cabut aja. Saudara kita sedang nggak mau diganggu," ujar Candra sambil melambaikan tangan, meminta Reyga keluar.
"Ayo, Kiana. Kita keluar dulu. Biarkan Kak Raven istirahat," ucap Reyga berdiri, tangannya terulur.
Baru saja Kiana akan menyambut uluran tangan itu. Namun di atas bed Raven bersuara.
"Kiana tetap di sini. Aku butuh bantuannya buat ngupasin apel."
"Memang kamu nggak bisa kupas apel sendiri?" tanya Reyga dengan alis sebelah yang terangkat. Raut mukanya terlihat kecut dan kesal.
Sebenarnya dia sudah kesal kepada Raven sejak kakak keduanya itu dengan seenaknya membawa Kiana pergi atas nama urusan pekerjaan. Seandainya Kiana tidak ikut Raven pergi, sudah pasti wanita itu akan baik-baik saja bersamanya. Tidak peduli mau sang kakak, Reyga tetap menarik Kiana menuju pintu.
Raven hanya mendengus, membiarkan keduanya menjauh. Dia memilih mengambil sebuah apel dan pisau kecil yang ada di nakas sisi kanan bed. Dengan bibir mengerucut pria itu mulai mengupas apel berwarna merah tersebut. Namun baru saja menyayat kulit apel itu, dia terpekik. Membuat Reyga dan Kiana yang sudah membuka pintu seketika terkejut dan refleks memutar badan.
Kiana kontan melepas pegangan tangan Reyga lalu berjalan cepat mendekati Raven yang meringis kesakitan.
"Kak, kamu nggak apa-apa?" Dengan penuh rasa khawatir, Kiana menarik tangan Raven segera. Dia terkesiap saat melihat darah segar keluar dari ujung jari telunjuk Raven.
"Sakit, Ki."
"Makanya hati-hati." Kiana menarik dua lembar tisu kering dan membungkus jari Raven yang terluka dengan tisu tersebut.
"Tadi kan aku minta kamu buat kupasin apel itu. Tapi kamu nggak peduli."
"Iya, maaf. Biar aku kupasin nanti," ujar Kiana seraya menekan jari Raven agar darah tidak mengucur keluar lagi.
Dia tidak tahu jika Reyga di ujung pintu tengah mengepalkan tangan sambil mengetatkan rahang memperhatikan perlakuan kekasihnya itu kepada Raven. Tanpa peduli dengan apa yang mereka lakukan, Reyga memutuskan keluar menyusul Candra lebih dulu.
***
"Masih sepuluh menit lagi kan?" tanya Kiana dengan mata masih tertuju ke layar laptop saat Muri mengingatkan tentang rapat yang harus dia hadiri.
"Iya, Bu."
Perhatian Kiana teralihkan ketika pintu ruangannya terbuka dari luar. Tak lama Reyga dengan setelan jasnya muncul dari sana, menunjukkan senyum manisnya.
Melihat kemunculan pria itu, Muri pun pamit undur diri.
"Kamu kok di sini? Memang nggak sibuk?" tanya Kiana membalas senyum tunangannya yang bergerak mendekat.
Senyum Reyga melebar saat dia memutari meja kerja Kiana dan mendekati wanita itu. "Ada yang ingin aku tunjukkan."
Memutar kursi, Kiana pun menghadap pria itu. "Oh ya? Apa itu?"
Dari dalam saku jas, Reyga mengeluarkan sesuatu. Sebuah kotak beludru berwarna biru tua yang lantas dia buka tepat di depan wajah Kiana.
Wanita dengan rambut sebahu itu mengerjap melihat sepasang cincin platina dengan model sederhana. Ada permata kecil berkilau di salah satu cincin yang berukuran lebih kecil dari lainnya.
"Ini—"
"Cincin pernikahan kita," potong Reyga cepat sembari terus mengawasi ekspresi Kiana. "Gimana? Kamu suka? Aku pastikan yang ini ukurannya pas di jari kamu."
Sebenarnya Kiana terkejut. Dia tidak menyangka kalau Reyga sudah mempersiapkan cincin pernikahan. "Aku suka tapi—"
"Mau dicoba?" Seolah tidak membiarkan Kiana berkomentar, Reyga mengambil satu cincin yang memiliki permata kecil.
Tidak ada pilihan lain, Kiana pun terpaksa membiarkan saat Reyga menarik tangannya dan menyematkan cincin tersebut. Pria itu tersenyum memandang penuh binar ketika cincin itu sangat pas di jari manis kanan Kiana.
"Kali ini pilihanku pas kan?"
Kiana mengangguk dan tersenyum kecil sembari ikut memandangi cincin yang tersemat di sana.
"Dua Minggu lagi," ujar Reyga tiba-tiba ketika Kiana masih asyik mengamati cincin itu.
Kalimat itu sontak membuat Kiana menyatukan kedua alis. Dia mengangkat wajah dan menatap tunangannya dengan raut heran. "Apanya yang dua Minggu?"
"Pernikahan kita."
Secara refleks mulut Kiana terbuka. Namun dia segera menutup mulutnya lagi saat sadar reaksinya berlebihan. "Ke—kenapa tiba-tiba?" tanya Kiana bingung. Diam-diam dia melepas cincin dari jarinya dan menaruhnya kembali di kotak beludru.
"Ini bukan tiba-tiba, Kiana. Sebelumnya kita sudah membicarakan ini. Keluargaku ingin pernikahan kita dipercepat, tapi saat kita mau membicarakan hal ini lebih lanjut kamu keluar kota sehingga rencana itu harus kita tunda. Sekarang aku udah nggak mau menundanya lagi. Aku nggak mau kejadian di Lombok terulang lagi."
Reaksi Kiana tidak sesuai dengan harapan pria itu. Reyga bisa melihat keengganan di mata wanitanya. Jujur pria itu agak kecewa. Entah kenapa sejak pulang dari Lombok, Reyga merasa Kiana berbeda. Wanita itu bukan hanya makin sibuk, tapi juga hampir tidak punya waktu untuknya lagi. Reyga merasa diabaikan akhir-akhir ini.
"Tapi dua minggu itu terlalu cepat, Rey. Persiapan nikah itu nggak mudah. Apalagi aku masih banyak kerjaan yang harus kutangani sebelum Kak Raven kembali ngantor."
Raven. Itu juga yang menjadi sebab Reyga memutuskan ingin segera menikahi Kiana. Mungkin ini hanya perasaannya, tapi dia merasa ada sesuatu yang sulit dijelaskan antara Kiana dengan kakak keduanya itu. Sikap peduli Kiana terhadap Raven, menurutnya telah berlebihan.
Reyga masih ingat beberapa kejadian di pesawat pribadi waktu mereka pulang dari Lombok bersama. Betapa kesalnya Reyga saat tiba-tiba Kiana memotong pembicaraan seriusnya begitu melihat Raven kesulitan makan sendiri. Wanita itu bahkan lebih memilih menyuapi Raven daripada lanjut bicara dengannya. Atau ketika Raven mengeluh sakit, wanita itu pun dengan sigap menghampiri. Bukannya Reyga egois mengingat Raven masih dalam kondisi kurang sehat, tapi baginya semua itu terlalu berlebihan. Raven tidak separah itu!
"Kak Raven masih dalam proses pemulihan, Rey. Aku merasa bertanggung jawab karena dia begitu gara-gara menolongku."
Itu dalih Kiana—yang tidak tahu kenapa terdengar hanya alasan saja di telinga Reyga.
Bersamaan dengan itu pintu ruangan diketuk. Kepala Muri menyembul. "Maaf, Bu. Sudah waktunya berangkat sekarang," ucap sekretaris itu mengingatkan.
"Oke, Mur." Kiana beranjak menutup laptop. "Rey, aku ada meeting. Kita bicarakan ini nanti."
Reyga menghela napas panjang dan terpaksa mundur. Dia melihat dengan tatapan getir saat Kiana berdiri dari kursi lalu menyambar blazer.
"Apa malam ini kita bisa makan malam?" tanya Reyga kemudian. Mencoba peruntungan karena dia yakin Kiana tidak bisa makan siang bersamanya.
Bibir Kiana merapat, bola matanya bergerak ke atas, mencoba mengingat jadwalnya hari ini. "Mungkin bisa. Nanti aku kabari," sahutnya tersenyum tipis. "Sampai nanti." Heels wanita itu mengetuk lantai dengan nyaring, meninggalkan Reyga yang masih saja terpaku di posisinya.
Tidak ada pelukan atau sekedar ciuman singkat. Sedikit demi sedikit Kiana mengubah kebiasaan yang sudah berjalan selama dua tahun belakangan ini. Reyga membuang napas dan meraup wajah. Rasanya begitu lelah berjuang. Sekarang dia merasa tengah berjuang sendirian. Disambarnya kotak beludru yang dia pikir bisa mengejutkan kekasihnya itu, lantas segera beranjak keluar.
Sembari mengayunkan langkah, tangannya mengambil ponsel dari saku jas, menghubungi seseorang. Tidak lama setelah dia meletakkan benda pipih persegi tersebut ke dekat telinganya, suara seseorang yang dia hubungi di seberang sana menyahut.
"Aku tau kamu pasti berubah pikiran."
"Aku harus ke mana?" tanya Reyga tanpa ekspresi. Langkahnya makin cepat menjauhi ruangan besar Kiana di gedung milik Danapati Group ini.
"Tower 77, lantai 12."
"Lima belas menit lagi aku sampai."
"Oke, Honey."

Siapa itu kira-kira yang Reyga telpon?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro