3. Langgar Ikatan Pernikahan
Suara dari pertemuan telapak tanganku dan kulit wajah Zafran sempat memberikan sengatan ketakutan dalam diri, tetapi aku memaksa untuk tetap tegak sembari menatap lurus pada pria yang tampak sangat tercengang itu.
Aku sudah mengantisipasi kemarahan yang mungkin akan ditunjukkan oleh Zafran, sehingga kedua kakiku secara teratur mundur dua langkah. Sebenarnya gentar, tetapi karena di sini aku selalu meyakinkan diri sendiri bahwa tidak salah, maka tatap aku mantapkan untuk mengarah lurus pada pria itu.
"Setelah semena-mena sama masa depan saya, sekarang Anda bahkan tidak mau memberikan saya kesempatan bernapas sebelum masuk ke neraka Anda, Pak Zafran? Anda ini manusia atau jelmaan iblis?!"
Masih dalam suasana yang dipengaruhi oleh amarah, aku memberanikan diri mengatakan hal itu dengan urat-urat leher menonjol. Aku menatap tanpa segan sedikit pun pada pria itu walau terdengar suara deham keras di belakang punggungku.
Itu suara ibu, yang aku yakini sedang berusaha memberikan peringatan.
Sementara ayah tiba-tiba sudah berdiri di sampingku, menggeser secara paksa agar aku mundur sehingga ia bisa maju ke depan seolah menjadi perisai. Aku menghela napas panjang, demi menenangkan diri. Agar tidak ada suatu hal buruk terjadi pada sosok pahlawan di hadapanku ini—walau ayah lebih sering menyebalkan.
"Maafkan anak saya, Pak. Dia sedikit tertekan menjelang pernikahan ini, dan memang umumnya para calon pengantin perempuan begitu, karena mempertimbangkan sulitnya beradaptasi di kehidupan baru nantinya. Mohon maafkan anak saya, Pak, tolong."
Ayah menjeda ucapannya barusan dengan menoleh padaku, memberikan isyarat melalui tatap dan gerakan wajah agar aku meminta maaf, tetapi jelas jawabannya adalah enggan. Aku tidak bersalah di sini, karena pria sialan itu yang mengundang masalah lebih dulu.
"Saya boleh masuk ke dalam untuk bahas ini?" tanya Zafran, entah untuk mengalihkan obrolan atau karena tidak kuat menahan malu akibat tamparan tadi.
Cih—aku melipat tangan depan dada—kalau masih punya malu, seharusnya dia ingat umur, dan bandingkan dengan usiaku! Dasar tua bangka tidak tahu malu!
Ayah dengan sangat segan segera mempersilakan Zafran untuk menuju rumahnya, sementara aku berjalan di belakang kedua lelaki itu dengan perasaan jengkel. Demi apa, aku semakin terjebak dan tertekan di situasi buruk ini.
Usia pria itu berapa kemarin? Dia tampak sudah tua, jadi satu-satunya harapan yang membuatku bisa mengangkat kaki berjalan memasuki rumah adalah anggapan kematian untuk pria itu secepat mungkin, sehingga aku bisa mengambil semua harta kekayaannya.
Terdengar jahat dan licik, tetapi hanya hal itu saja yang bisa mengobati beban hatiku sejak perencanaan pernikahan ini.
Memasuki rumah, pria itu dijamu seperti tamu terhormat oleh ibu. Beberapa kue dan segelas kopi disajikan di depannya, pun untuk bapak. Lalu di hadapanku dan ibu masing-masing segelas teh hangat.
Aku hanya menatap uap tipis dari gelas kaca di hadapan dalam diam, sementara tiga manusia lainnya dalam ruangan ini sibuk berdiskusi tentang masa depanku yang suram, sementara tidak ada satu pun yang mencoba menyelamatkanku dari ancaman tersebut.
Mataku memejam erat, merasai sesak kecewa oleh takdir yang Allah berikan ini. Tanganku bahkan bergerak ke dada kiri untuk menekan, bahkan sesekali memukulnya dengan sangat kuat.
"Kamu baik-baik saja, Jihan?"
Sialnya, dari tiga manusia yang dua di antaranya adalah orang tuaku, kenapa manusia sialan itu yang harus bertanya?
Aku memasang wajah masam, sembari memberikan dua buah gelengan penolakan.
"Nggak ... papa," jawabku dengan sedikit tersendat. Namun kemudian aku memikirkan sesuatu, tentang ketidaksanggupan diri ini mendengar takdir suram di depan mata sekarang. Jadilah, aku gegas berdiri dengan kepala tertunduk. "Aku izin ke kamar. Mau istirahat," ucapku.
"Jihan, tapi, Nak, ini kan tentang—" Ayah mau mencegah, tetapi tidak bisa menghentikan langkahku menjauh dari mereka bertiga.
"Ayah urus aja, bebas. Pendapat aku juga nggak didengar."
Suaraku jelas dibuat marah, dan niatku sama sekali agar diikuti ayah atau ibu hanya demi dibujuk. Tidak sama sekali. Hanya sekadar memberitahu mereka, bahwa aku belum siap dan butuh waktu untuk hal seberat ini, sehingga mereka berkenan mau negosiasi pada si tua arogan itu agar mau memenuhi perjanjian awal mengenai tanggal pernikahan.
Tiba di kamar, pintu kamar aku banting dengan tidak pelan, kemudian tengkurap di atas kasur yang sempit sembari menghela napas panjang beberapa kali demi mengurangi kadar sesak dalam dada.
Di beberapa saat tertentu, air mata mengalir tanpa diminta ketika bayangan saat bersama ustaz Fatih terulang lagi.
Apa Allah sungguh menyiapkan kejutan dari rencananya ini? Aku sungguh ... tidak bisa membayangkan satu hal indah pun dalam pikiran, dari pernikahan ini.
Ya Allah ... kenapa bukan ustaz Fatih saja? Kenapa bukan pria itu saja yang melamar? Bahkan jika pria itu enggan atau malu datang ke rumah, aku siap datang melamar pria itu sebagaimana Khadijah meminang Rasulullah shalallahu alaihi wasallam sebagai suaminya.
Sungguh ... aku selalu memikirkan opsi itu sejak bertemu ustaz Fatih. Namun, pernikahan dengan si tua itu menjadi penghalang cita-cita muliaku.
Astagfirullah, ya Allah .... Aku enggan berburuk sangka pada-Mu, tetapi sungguh, aku sulit ... bahkan sangat tidak bisa menerima takdir ini ya Allah. Tolong kembalikan waktu ke jembatan hari itu, agar aku bisa tidak acuh pada siapapun yang bunuh diri di sana.
Sungguh, ya Allah ....
Aku menangis putus asa, sembari menenggelamkan wajah pada seprai. Bahkan mengambil bantal tambahan untuk membekap celah wajah. Jilbab yang menutupi kepala, aku pastikan dalam kondisi buruk, tetapi aku terlalu malas untuk mengeceknya.
Hingga suara pintu terbuka mengalihkan perhatianku. Tangis putus asa tanpa suara yang amat sangat menyayat hati terpaksa aku hentikan sejenak, demi mendengar suara si pembuka pintu. Apakah ayah atau ibu, dan aku penasaran mengenai hasil diskusi mereka hari ini.
Meski demikian, aku masih enggan melirik ke arah pintu agar memperjelas kemarahan dalam hati saat ini.
"Sudah deal, Jihan."
Sial, ini bukan suara orang tuaku. Segera aku berbalik, dan menemukan bahwa sosok yang berdiri di ambang pintu adalah si biang masalah.
Ya Allah ... si manusia tanpa adab itu bahkan membuka pintu kamar anak gadis orang tanpa permisi! Bagaimana caranya aku bisa menaruh sedikit rasa suka—sebagai sesama manusia—pada pria itu?!
Bahkan meskipun kami akan menikah, ia tetap saja tidak berhak melakukan itu. Sekarang, aku susah payah menarik rok yang sedikit tersingkap hingga betis, agar kembali turun dan menutupi hingga tidak ada kaki yang terlihat.
"Kita akan menikah pekan depan. Siap atau tidak," kata pria itu tegas, seolah enggan menerima sedikit pun bantahan jenis apa pun.
"Pak, minimal punya adab! Kenapa tidak ketuk pintu lebih dulu baru buka?! Bagaimana kalau saya—"
"Maaf. Saya cuman mau infokan hal itu. Assalamualaikum."
"Tidak wa alaikumussalam!" balasku tegas. "Tidak ada kedamaian dan kesejahteraan untuk manusia arogan seperti Anda!"
Namun, Zafran enggan peduli. Ia hanya perlu menarik gagang pintu hingga tertutup sempurna, dan seolah masalahnya denganku sudah selesai.
Sial—ah, astagfirullah.
Astagfirullah.
Aku terus menggunakan satu kata itu agar terus dipenuhi kesabaran, demi menjaga image sebagai wanita sholehah, tetapi ... astagfirullah, maafkan aku ya Allah, untuk kali ini, tetapi makhluk ciptaan-Mu satu itu memang memiliki sifat ...
"Babi kau, Zafran!"
*
Aku seharusnya diberikan penghargaan sebagai aktris paling hebat sejagat raya yang bisa menahan tangis di ujung mata, ketika di hari terkutuk—biasanya spesial bagi orang lain—mendapati bahwa sosok pengisi nasehat rumah tangga malah ... ustaz Fatih.
Ya Allah ... tolong bisikkan pada pemuda itu bahwa yang aku inginkan adalah dia yang duduk di sampingku, dan kami pegal bersama karena menyalami banyak tamu yang datang hari ini, lalu lanjut ritual malam pertama sampai tepar di kasur dan bangun jam—astagfirullah.
Berlebihan, Jihan!
Aku memejam kuat saat pikiran aneh itu muncul di saat pikiranku sedang kalut, tetapi sungguh. Aku ingin pria itu yang duduk di sampingku, bukan malah mengarahkan agar aku tunduk dan patuh pada si tua bangka ini.
Lebih beratnya lagi, sesekali tatapku dan ustaz Fatih bertemu. Ia tampak sangat sendu dan dalam ketika lirikannya lurus padaku. Kedua sudut bibirnya tertarik membentuk segaris senyum, tetapi tidak memiliki kesan manis, ramah, atau baik dan sejenisnya. Pria itu seolah sedang tersenyum di atas luka, dan hal itu semakin diperjelas melalui binar netranya.
Aku tanpa sadar meneguk ludah, dan tidak bisa fokus pada setiap kajian yang pria itu sampaikan saat ini. Napasku sempat tertahan, dan baru bisa diembuskan panjang saat ustaz Fatih sudah mengalihkan pandangan pada para saksi atau pria di sampingku saat ini.
"Kamu sangat serius mendengarkan ceramah, Jihan." Zafran di sampingku berbisik, membuatku tanpa sadar mengepalkan tangan dan meremas kebaya yang kukenakan sekarang dengan sangat kuat. "Bagus, supaya kamu patuh sebagai istri nantinya."
Aku tidak menjawab, karena jika sedikit saja suaraku keluar, yakin dan pasti itu adalah teriakan penuh makian pada si tua bangka ini. Aku memilih menunduk dalam, sembari memperhatikan kemarahan yang ditunjukkan oleh tanganku.
Tidak ada satu hal pun yang bisa aku nikmati dari acara sederhana ini. Bahkan kehadiran sosok yang selalu aku impikan pun, tidak memberikan kebahagiaan sedikit pun. Waktu terasa begitu lama berlalu, tetapi tetap saja aku pada akhirnya dipertemukan dengan ustaz Fatih dalam jarak satu meter tepat di hadapanku saat ini.
"Selamat atas pernikahannya, semoga sakinah, mawadah, warahmah." Ustaz Fatih memberikan doa dan harapan itu dengan senyum terbaiknya, sembari melirik aku dan Zafran secara bergantian.
Untuk hal itu, aku segera memalingkan wajah ke arah lain, enggan mengikuti Zafran untuk mengaminkan doa barusan. Posisi menunduk aku pertahankan sampai sebuah bisikan lirih bercampur nada gemetar menyapa telingaku.
"Harapan saya untuk ditakdirkan Allah bersama kamu, cukup sampai di sini."
Aku segera menengadah, dan menemukan bahwa pemuda tersebut masih belum beranjak dari posisinya. Aku ingin bertanya lebih lanjut mengenai maksud ucapan ustaz Fatih barusan, tetapi ia sudah pindah berjabat tangan dengan Zafran sembari mengucap selamat, kemudian pergi begitu saja.
Sementara aku masih blank di tempat, sehingga tamu berikutnya hanya kusodorkan tangan untuk bersalaman tanpa peduli siapa dia. Otakku masih bimbang, memasukkan suara bisikan tadi sebagai kenyataan atau sekadar khayalan belaka.
Aku berharap, itu hanyalah suara dari dalam hati—walau mustahil karena suara itu jelas terdengar bariton dan berat. Namun jika itu kenyataan, sungguh, aku akan dua kali lipat merasakan sakit lebih daripada saat ini.
Karena ternyata ... ustaz Fatih juga menyukaiku.
Ah ... astagfirullah.
*
Malam ini, sedang ada perhitungan isi amplop. Aku hanya menyimak dalam diam, sementara Zafran yang menghitung semuanya. Ayah ada di luar, dan ibu sedang di dapur.
"Modal untuk membuat pernikahan sederhana, ternyata tidak berbanding lurus dengan pengeluaran untuk persiapannya, sementara isi amplop ... hanya setengah dari total pengeluaran karena tamu dibatasi." Zafran menengadah, memberitahukan info itu padaku.
Cuih. Jadi, ia hanya mengharapkan amplop dari percepatan pernikahan kami. Dasar manusia tua!
"Jadi, kenapa? Mau batalin pernikahannya karena nggak bisa balik modal?" balasku, bertanya dengan ketus.
"Bukan begitu," jawab Zafran. Ia meletakkan setumpukan uang itu di atas meja, kemudian menindihnya dengan rokok yang baru dikeluarkan dua batang. "Semua penghasilan dari kerjaan dadakan saya, sudah saya keluarkan untuk acara pernikahan, dan tidak ada yang tersisa selain amplop ini."
Sebelah alisku terangkat, menuntut penjelasan lanjutan.
"Kamu katanya tidak mau pakai uang haram."
Raut wajahku seketika lega. Bukan karena merasa puas atas sikap bijak pria di depanku ini, melainkan akibat munculnya sebuah ide dalam benak.
"Iya. Aku tidak mau menggunakan atau menyentuh apalagi makan uang harap, sebab daging yang tumbuh dari hasil makanan atau uang haram, maka api neraka lebih baik untuknya." Aku mencopas kalimat ustaz Fatih, dengan nada penuh penegasan sebagai tanda tidak ingin mentoleransi apa pun terhadap pria di hadapanku ini. "Rumah kamu, dari uang apa?"
Zafran tidak bisa menjawab. Bibirnya tampak kaku, dengan mata bergerak ke kanan-kiri kebingungan. Sesekali, terlihat sangat gugup ketika ia meneguk ludah secara kasar.
"Uang haram, 'kan? Mobil juga, pakaian kamu bahkan dari hasil riba. Aku tidak mau bersinggungan dengan semua barang-barang itu."
"Jadi?" tanya Zafran kebingungan. Ia seharusnya sudah paham ke mana jalur bicaraku, tetapi malah terlihat pura-pura tidak tahu.
"Aku tidak mau ke rumah kamu untuk sementara waktu, sampai kamu siapkan rumah sendiri, dari uang halal."
"Jihan ...." Zafran memelas, terdengar begitu frustrasi karena bersamaan dengan itu ia mencondongkan tubuhnya ke depan. "Kapan akan terkumpul uangnya kalau saya harus kerja serabutan lebih dulu? Puluhan tahun juga belum tentu, Jihan. Jarak dari sini ke rumah saya juga jauh. Saya juga tidak bisa tinggal di sini, karena urusan saya di rumah juga banyak. Jangan—"
"Katanya aku boleh melakukan apa pun kecuali menolak pernikahan." Tanpa ekspresi, aku langsung memotong kalimat dari Zafran. "Jadi, apa selain pemaksa dan arogan, Anda juga bukan pria sejati karena selalu ingkar janji, Pak Zafran? Jadi, apa sisi pria sejati dari diri Anda sebenarnya?"
"Jihan." Zafran memanggil, hendak bernegosiasi, tetapi aku menolak dengan segera berdiri.
"Aku mengantuk, pegal. Kasur saya cuman untuk satu orang, itu pun masih sempit. Anda bisa tidur di sofa kalau mah menginap di sini, atau kalau mau pulang, silakan. Tapi saya tidak akan mau ke rumah Anda yang sekarang ini." Aku memberikan keputusan telak.
Tanpa mengharapkan balasan, aku segera berbalik. Menemukan sosok ibu sudah berdiri di ambang pintu dapur menatapku keheranan bercampur khawatir. Sebuah senyum aku tampilkan untuk menenangkan wanita itu, kemudian berjalan ke arah kamar.
Tidak lupa, sengaja memperdengarkan suara pintu ditutup dan dikunci, agar pria itu paham harus melakukan apa: pergi dari rumah ini.
Lupakan malam pertama, karena bagiku ini hanyalah malam pembuka siksaan batin di masa depan.
Aku merebahkan tubuh di kasur usai melepaskan jilbab instan berwarna hitam. Seketika terbayang suara ustaz Fatih yang secara jelas mengatakan bahwa dirinya sempat berharap agar bisa berjodoh denganku, dalam arti kata lain ... pemuda itu juga memiliki rasa padaku.
Sementara berpikir, aku juga mengangkat kelima jari kiri untuk menyentuh menggunakan telunjuk kanan pada salah satu cincin yang tersemat di jari manis. Ini adalah tanda pengikat bahwa tubuhku sudah jadi milik orang lain, tetapi hati ini ... selamanya akan selalu dimiliki oleh ustaz Fatih.
Dengan keberadaanku di rumah ini—setidaknya dalam waktu beberapa bulan hingga tahunan sampai Zafran membeli rumah baru—aku tiba-tiba terpikirkan sesuatu yang terlarang tetapi selalu kuimpikan.
Mengejar ustaz Fatih sekali lagi, mengabaikan ikatan fisik ini—cincin aku lepaskan untuk ditaruh di atas meja—dan berjuang bersama-sama agar bisa lepas dari pernikahan ini dan kami bisa merangkai masa depan penuh kebahagiaan.
Ya Allah, apakah boleh?
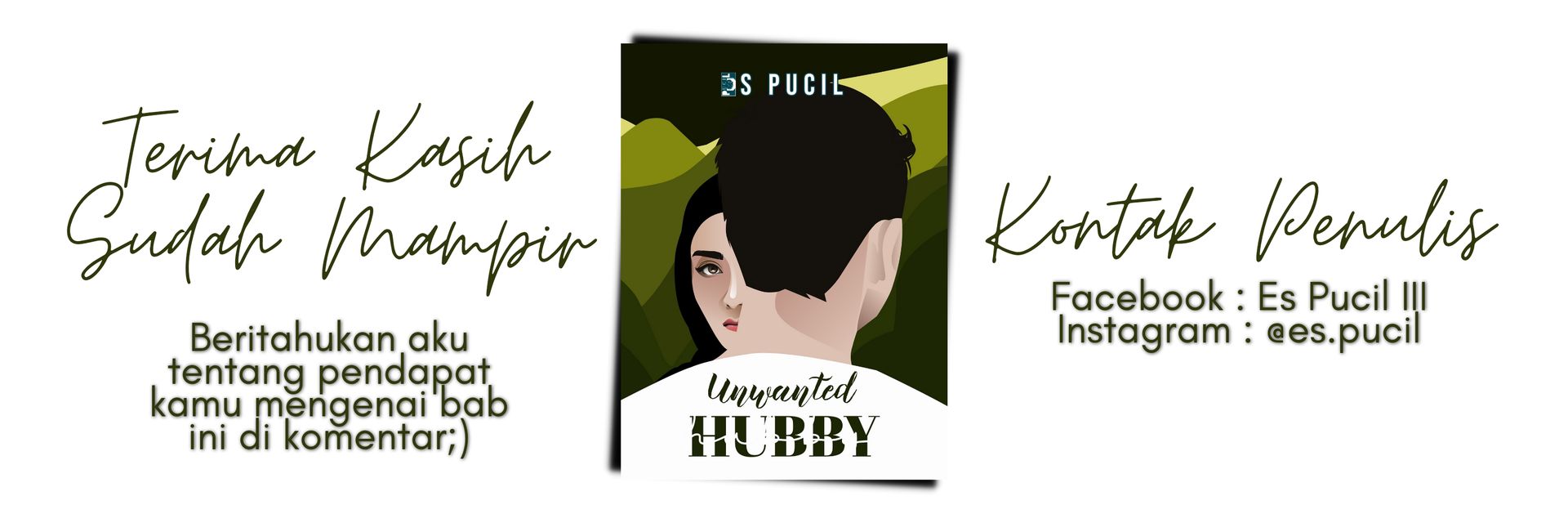
Eh, loh ... lah? "Boleh" apa ini, Jihan? 👀😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro