Cuitan Cerita Pilu Hardinata.
kylazaa_'s presented,
TJOEITAN TJERITA PILOE HARDINATA
ft,
wong kunhang
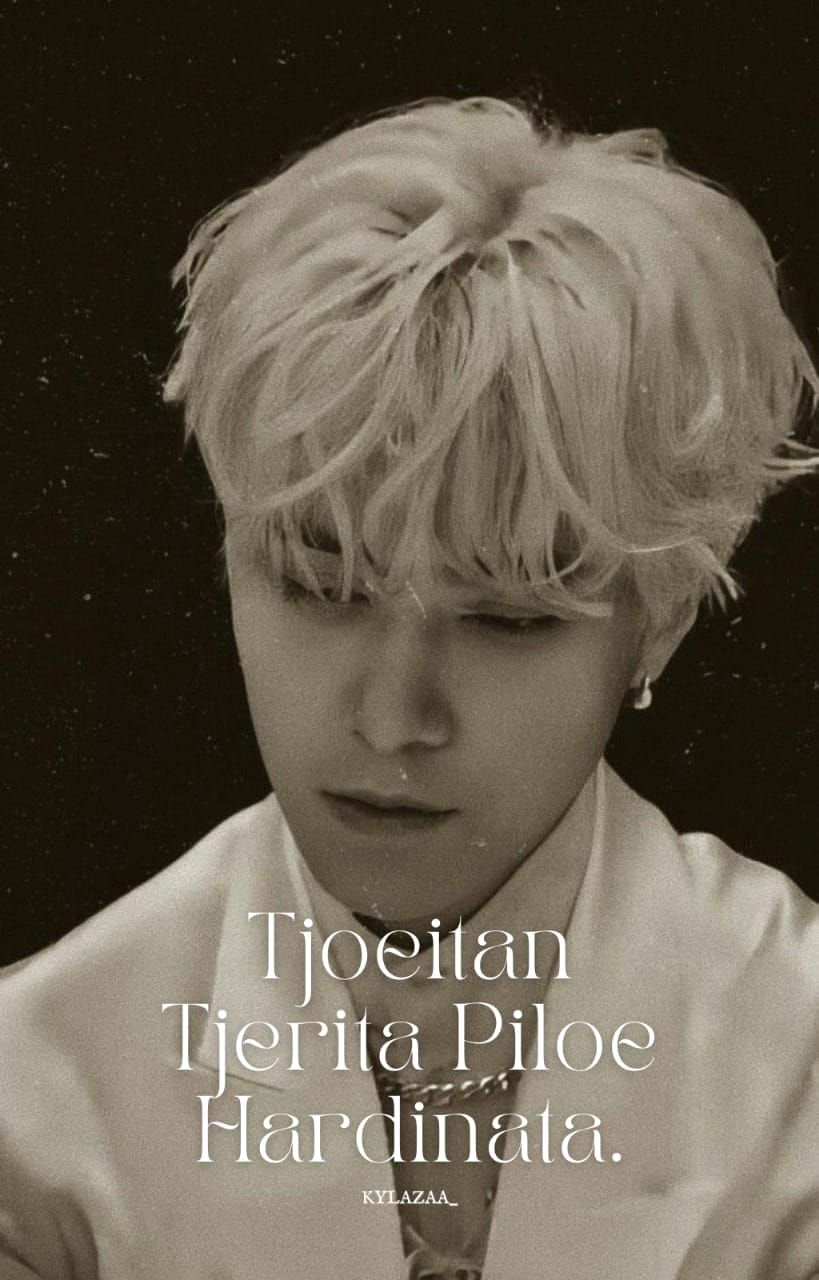
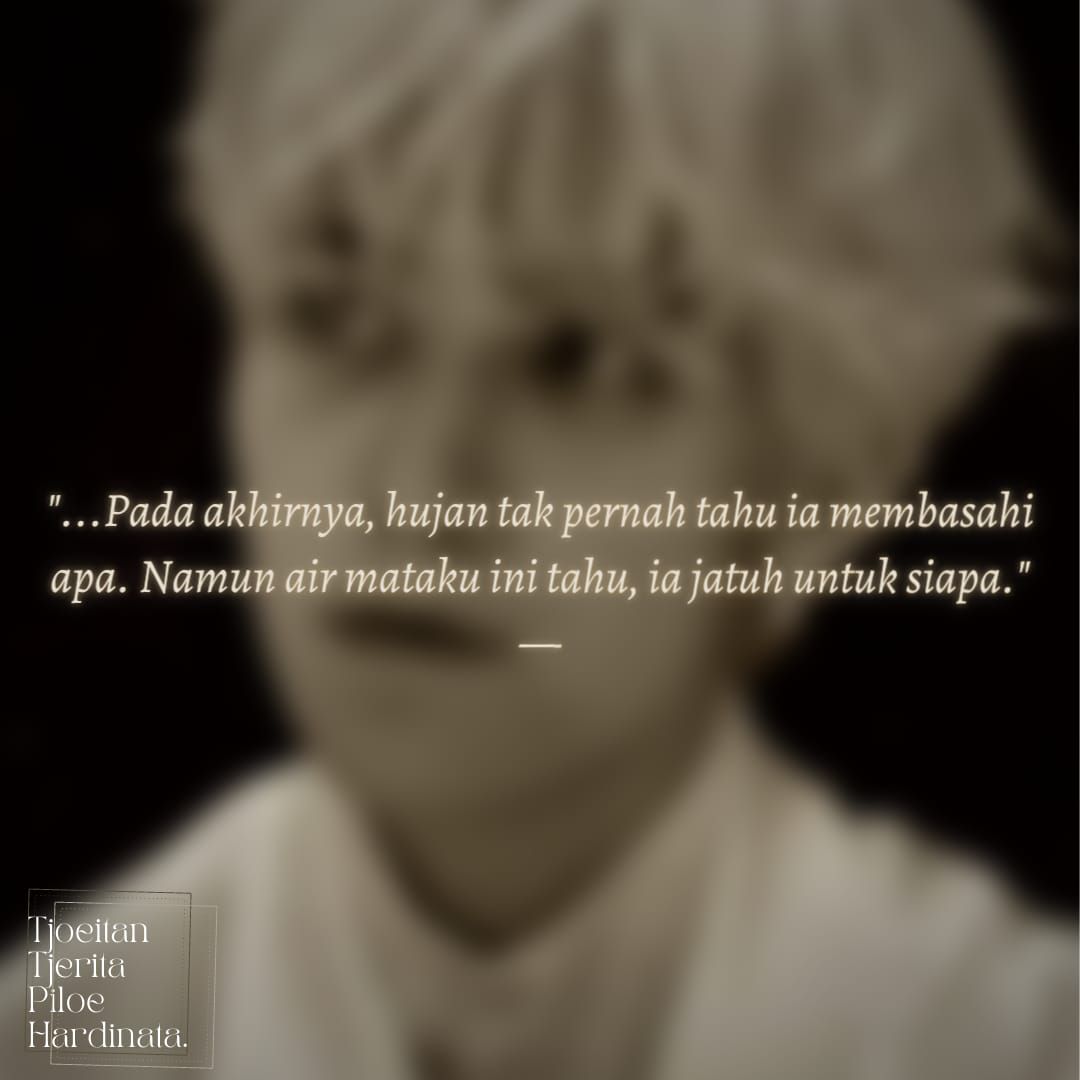
[oneshoot - 4,5k words]
. . .
; [i - prologue]
Agustus, 1988.
Kurang lebih, dasawarsa yang lalu.
Namun irisnya senantiasa melukiskan corak akan kenestapaan. Padahal, itu sudah dasawarsa yang lalu. Purnama pada malam, tak sebenderang masa itu. Tiupan anila pula mega yang berarak, seolah mengejeknya dengan ironi. Bila dikecam harus menjawab sederet pertanyaan perihal mengikhlaskan; iya, dirinya memang sudah mengikhlaskan—mengikhlaskan, bukan merelakan.
Baris seloka yang ia rangkai—terhitung saat rani itu masih ada disisi—masih ia simpan dan jaga, mungkin hingga mati. Pula benda bahari yang senantiasa ada dalam genggamnya; sebuah potret arkais dimana dirinya masih bisa mengenal apa itu senyum tulus—sebab gadisnya itu, ialah entitas sesungguhnya dari makna bahagia.
Kurang lebih, dasawarsa yang lalu.
Saat para serdadu mengepungnya seraya mengarahkan pistol-pistol itu bak dirinya hanyalah seonggok serangga. Penganggu. Kala itu, dibalik aksa yang menilik tajam; terdapat rasa nyeri yang terus menghujam. Dasawarsa yang lalu, ia benar-benar hidup anantara beri kami uang, atau kami rampas nyawamu begitupula keluarga kecilmu.
Kenyataan pahitnya, keluarga kecil itu sudah lebih dahulu dirampasnya tanpa raut wajah yang bersimbah akan dosa.
Terekam jelas bak rentetan rekaman lawas. Beberapa jilid dalam rentang kisahnya yang tak kuasa untuk kembali ia ulas. Dengan embusan napas yang kuat, dirinya membalikan bingkai itu hingga ainnya menangkap sebuah coretan abstrak dua dekade yang lalu.
'Bila kamu adalah senja, maka jadikanlah aku salah seorang pemujamu yang paling ditunggu kehadirannya.'
Termaktub bak ukiran tangan diatas batu. Kekal, amerta, dan akan selalu terkenang sepanjang hayat. Berusaha tuk menghapus jejak kanin pada relung hatinya, dengan lemah sang arjuna pun bangkit dari duduknya lalu kembali masuk pada gubuk yang selalu menjadi saksi gama harubirunya di bentala Batavia.
Ini kisah seorang lanang berasma Hardinata—lahir di ranah kincir angin, dengan nama Herold Van Tholense. Resmi menjadi warga pribumi sejak kenal dengan seorang puan berasma Gauri.
Agaknya, ini semua perihal untaian warita masa lampaunya. Kala ia hidup, mencoba asin garamnya lika-liku awal perjalanan hingga dirinya terbuai; dan melupakan bahwa masih ada kata epilog di dalamnya. Iya, lagi-lagi ini kisah tentang dirinya bersama warna-warni sukmanya—Gauri Panca Gayatri.
.
.
.
.
; [ii]
Juli, 1947.
Dini hari pada tanggal 21 Juli 1947, ibukota Republik lebih ramai daripada biasanya. Suara gaduh bergemuruh, pekik kasar para pendatang memekakan rungu rakyat Nusantara. Tepat pada saat yang sama, ada salah seorang nona bersurai pendek sebahu tengah merajut sebuah topi kupluk yang akan ia berikan pada adik kecilnya.
"Mbak Gauri! Mbak nggak dengar apa?!"
Yang dipanggil hanya bisa mendongak, menatap linglung anak kecil dihadapannya. "Dengar apa, dik? Mbak nggak dengar suara apa-apa tuh."
"Bala tentara Belanda kembali datang kemari! Mbak, cepat-cepat keluar!"
Mendengar seruan dari Yuda—sosok anak kecil yang merupakan adiknya—Gauri lantas dengan gesit menaruh peralatan merajutnya di laci meja. Masa bodoh dengan benang rajut yang belum tergulung dengan rapi. Tanpa menunggu waktu yang lama, sang hawa gegas melangkahkan tungkai jenjangnya keluar dari wisma.
Keduanya berlari kencang guna melihat sekumpulan serdadu yang terhalangi oleh rakyat pribumi. Gauri dan Yuda mana bisa melihat. Orang dengan tinggi sepenggalah dan besar, menghalangi aksanya yang berpendar kesana-kemari.
"Kok tiba-tiba begini, sih, dik?! Malam-malam begini—"
"Yuda mana tahu, mbak. Yuda juga kebangun tadi saking takutnya. Bisa-bisanya mbak gak denger suara itu." Tutur Yuda, tanpa melunturkan air durjanya yang buncah pula resah.
Gauri lantas berjinjit, hulunya menoleh kesana-kemari namun tetap saja, ia tidak bisa melihatnya. Yang sanggup ia tangkap hanyalah pembicaraan kecil antara salah seorang serdadu, dengan salah satu warga di kota mereka. Dengan perasaan kecewa, Gauri bermasam durja sambil mengenggam hasta kurus adik satu-satunya.
"Yuda ingat peristuwa saat itu?"
Keningnya berkerut. "Ingat, memangnya kenapa?"
Gauri memutar bola matanya malas. "Belanda melanggarnya. Mereka melanggar perjanjian itu."
"Mbak tahu darimana?"
"Mbak dengar percakapan mereka. Gini-gini, mbak tahu bahasa Belanda dikit-dikit, ya!"
Si bungsu hanya bisa mencibir ocehan Gauri laksana pawana yang berembus. Keduanya sama-sama senyap kala ada sesosok pemuda—dengan sandang lengkap khas seorang pendhéga Belanda—tiba bersamaan dengan kuda yang ditungganginya. Nusantara bak dibuat terbuai akan karisma dari sosok panglima itu. Namun tidak kala pemuda itu menembakan sebuah senapan angin ke udara, hingga menimbulkan suara bising yang dapat merobek fatamorgana.
"Waar is je stomme leider?! Schiet op, kom voor mij!" (Mana pemimpin kalian yang bodoh itu?! Cepat, datang ke hadapan saya!)
Sontak, mahajana nian terpegan kala pradana Belanda menyerukan soal keberadaan pemimpin Nusantara. Termasuk Gauri dan Yuda, keduanya saling bertatap pandang hingga pada akhirnya, terdengar sayup-sayup suara tegas entah darimana namun dapat menjelmakan atmosfer yang panas pula sengit itu.
"Ik ben achter je. Verdomme, blinde leider."(Aku di belakangmu, pemimpin buta sialan.)
"God wacht op uw dood, Herold Van Tholense—ik bedoel, beste meneer Hardinata." (Tuhan sedang menunggu kematianmu, Herold van Tholense -- maksudku, Tuan Hardinata yang terhormat.)
Kepalan hasta Hardinata menjadi saksi bisu sebuah dendam yang sedari dulu ia semat abadi dalam nadinya. Gauri yang ada di barisan paling belakang hanya bisa menggigit jari seraya merapalkan doa di dalam hati: semoga pujaan hatinya, baik-baik saja di sana.
—
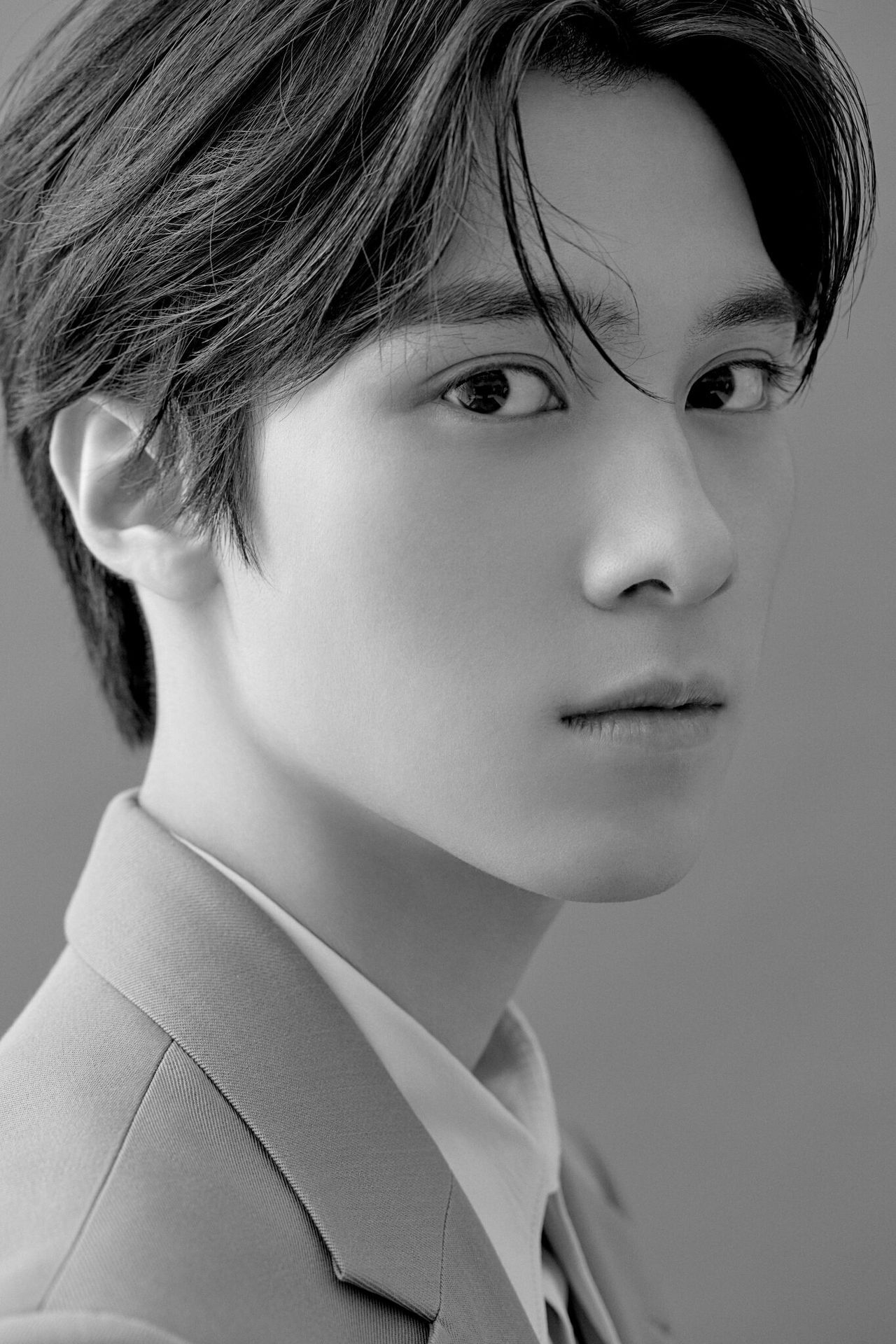
1.1 : Hardinata Gauthama.
.
.
.
.
; [iii]
"Semalam Yuda mengejek, jika saya tidak bisa berbahasa Belanda. Als het duidelijk is, weet ik iets van het Nederlands van jou." (Padahal sudah jelas, aku tahu sedikit bahasa Belanda darimu.)
Tepat di teras, Gauri dan Hardinata duduk beriringan ditemani oleh secawan kopi yang baru saja Gauri siapkan untuknya. Alap santun, sang adam hanya bisa tersenyum tipis mendengar celotehan puan pemilik kurva terindah sejagad Nusantara. Sembari menyesap cairan kopi itu sedikit, Hardinata pun melaungkan pertanyaannya. "Apa Yuda tidak bisa berbahasa Belanda?"
"Bukan tidak bisa, Ia hanya tidak menguasainya."
"Ajarkanlah. Atau mungkin, kau bisa membawa Yuda kemari. Studeer met mij." (Belajar bersamaku.)
Gauri terkekeh pelan mendengarnya. "Jangan berlagak. Aku tidak suka bila Yuda melihat luka-lukamu yang sudah jelas—dapat membuatku meringis sedih..."
Nona bersurai aswad itu langsung merunduk dalam. Hardinata justru mengusap lembut helai demi helai rambut Gauri. Bila dideskripsikan separah apa lukanya, ini tidaklah seberapa dibanding melihat raut sedih itu tercetak jelas pada durja dara kesayangannya. "Ik ben goed. Aku tidak apa-apa, Gauri. Memang sudah sepantasnya aku begini." (Aku baik.)
Gauri menggeleng kuat. "Jangan kau berpikir bila ini semua salahmu. Tidak, Hardinata. Kau tahu? Ini semua bukan kesalahanmu. Batavia diliput duka, sebab Tuhan ingin menaikan derajat kita. Hardinata, dengan adanya kontribusi kau untuk menjadi warga negara Indonesia, itu sudah cukup membantu. Jadi, jangan samakan dirimu yang sekarang dengan dirimu yang ada di masa lampau. Kau orang baik, Hardinata."
"Bagaimana aku bisa disebut orang baik, jika nama Herold Van Tholense selalu terngiang-ngiang di rungu kebanyakan orang?" lanang itu berdecak sebal. "Herold yang kasar, terlalu egois—ia juga individualis. Aku minta maaf untuk hal itu."
Gauri tersenyum adun. "Tidak mengapa, Hardinata," lalu selepasnya, puan itu bersandar pada bahu lebar milik sang arjuna. "Orang baik tidak perlu pengakuan dari khalayak ramai. Hanya aku, Yuda, serta Tuhan yang tahu. Kau sudah terlalu banyak berjuang, jadi—hou moed? Geef niet op!" (Semangat terus, ya? Jangan putus asa!)
Selaksa harsa terus meliputi keduanya. Semoga saja, ini semua amerta adanya.
—
Agustus, 1947.
"Heb de zin gehoord: 'dood de leider en vernietig dan de mensen.', niet?"
(Pernah mendengar ungkapan: 'bunuh pemimpin, lalu hancurkan rakyatnya', tidak?)
Seseorang menyahut dengan amat hati-hati. "Dat weet ik niet zeker. Dat wil zeggen, vernietig je niet eerst de mensen die het dichtst bij hem staan, dan vernietig je indirect ook Herold's leven?"
(Saya tidak yakin dengan hal itu. Maksudnya, jika kamu tidak menghancurkan orang-orang terdekatnya terlebih dahulu, maka secara tidak langsung kau menghancurkan kehidupan Herold juga?)
Seluruh pasang mata menyorot penuh ke arahnya. Begitupula Jansen—pemimpin daripada para serdadu itu. Jansen bak terdiam seribu klausa hingga pada akhirnya ia menyuarakan pendapatnya. "Kau tahu? Herold is slim en scherpzinnig. Dengan kita membunuh orang terdekatnya, menjadi tanda bahwa kita terlalu mengambil tindak cepat untuk membuat Herold murka!" pekik nyaring Jansen membuat atmosfer ruangan nian menyuram. (Herold itu cerdas dan cerdik.)
Kort—insan yang menjawab pertanyaan Jansen tadi gegas meminta ampun. "Het spijt me mijnheer. Saya tidak bermaksud membangkang, Tuan Jansen." (Saya minta maaf, Pak.)
"Lupakan itu. Kali ini, kita susun rancangannya," Jansen bangkit dari duduknya, seraya berjalan pelan mengitari anak-anak buahnya. "Ik heb een geweldig idee. Kort, karena sejak awal kau mencari masalah denganku, maka dengan ini saya putuskan untukmu turun langsung guna mencari tahu letak kediaman Herold Van Tholense." (Saya punya ide bagus.)
Kort mengangguk tegas seraya berdiri tegak bersamaan dengan hastanya yang mengambil sikap hormat kepada sang pradana. "Alles wat ik voor u doe, commandant!" (Semua akan saya lakukan untukmu, komandan!)
.
.
.
.
; [iv]
Akasa Batavia dina ini nampak berseri, sebab baskara yang muncul begitu membuat hati tentram bersorai. Pawana berembus sejuk pula sekumpulan cucakrawa yang terbang bak mengambang di udara. Sama seperti apa yang tengah alam rasakan; Hardinata dan Gauri dina ini tampak serasi. Tubuh yang dibalut dengan sandang sederhana. Gauri dengan surai yang diikat kuda, pula Hardinata dengan kening paripurnanya. Lokakarya yang teramat permai di mata.
"Pak, Bu. Selamat pagi," tegur seorang wanita paruh baya pada keduanya.
Hardinata lantas membalas,."Ook goedemorgen, Mevrouw. Semoga harimu menyenangkan." (Pagi juga, Bu.)
Lakuna ayu Gauri muncul ke permukaan. Begitu syahdu hati dirasa kala mahajana mulai menerima keberadaan Hardinata. Bukan perihal mudah untuk mereka menerima kedatangan sang taruna yang terbilang tiba-tiba itu. Namun, sebab bekal tekad dan keyakinan yang kuat, masyarakat pun pelan-pelan dapat menerima sosok baru dari Herold Van Tholense.
"Mereka baik," ujar tiba-tiba Hardinata.
Gauri terkekeh manis, "Sama sepertimu."
"Philanderer."
Puan itu mengrenyit. "Phi—apa? Kau tidak mengajarkan kalimat itu padaku."
"Yang berarti, tukang merayu."
Mendengar jawaban dari Hardinata, pipi Gauri lantas memanas. "Dasar menyebalkan!" tukasnya, namun dengan senyum yang merekah malu-malu.
Pada kesempatan kali ini, kedua muda dan mudi itu hendak berkeliling ke penjuru kota. Menyaksikan dengan mata mereka sendiri perihal keadaan rakyat pribumi. Sektor perdagangan, sistem tukar-menukar, juga melihat beberapa dokar yang berlalu-lalang.
Ajun dari berkeliling bukan sembarang berkeliling biasa. Hardinata hendak melihat warga-warganya, dan memastikan juga bila diantaranya tidak ada yang kekurangan. Sebenarnya, Gauri juga turut andil untuk hal yang seperti ini sebab—ekhm, Hardinata belum terlalu menguasai bahasa dengan amat lancar.
Dan, berhentilah mereka di salah satu tempat--di mana ada seorang anak kecil bersama dengan kedua adiknya; tidur nyenyak di tepi jalan hanya beralaskan jeluang surat kabar. Gauri dengan perlahan membungkuk, memperhatikan kondisi keduanya sembari tersenyum pedih. Wadon itu lantas menatap pria yang ada disampingnya. "Kau bawa uang tidak?"
"Bawa. Ingin memberinya berapa banyak?"
"Sebanyak yang kau punya."
Hardinata dengan tegas berbisik pada Gauri. "Kalau sebanyak itu, bagaimana dengan orang lain disekitar—"
Memotong ucapan sang lanang, Gauri menggeleng yakin. "Aku ada. Jadi, ini giliranmu yang pertama memberikannya pada mereka."
"Heel goed, prinses."(Baiklah, tuan puteri.)
"Sama-sama."
Dengan perlahan, sang adam menyerogoh beberapa lembar kertas uang dan sekantong emas itu kepada Gauri. Gauri melengkungkan kurva tipis pada romannya, seraya menyimpan uang dan sekantong emas itu tepat di bawah tas yang menjadi pengganti bantal empuk mereka. Gauri sesekali mengusap surai bocah itu lembut sambil merapalkan doa dari dalam hati.
Nurani Hardinata bergeletar hebat tiap memandang paras adun puspa hatinya itu.
Jadi terbayang kala dulu, ia pernah jatuh cinta—jatuh sejatuh-jatuhnya pada seorang nisa. Nisa yang dahulu selalu menjadi incaran dari ganasnya Herold Van Tholense; insan yang paling disegani penduduk Nusantara.
Tak ada bedanya. Serupa. Keduanya mempunyai ciri-ciri yang sama, hanya berbeda terkait bagaimana Herold dan Hardinata memperlakukannya.
Iya, rasa itu sudah tersimpan apik dalam benaknya. Termaktub sedari iris keduanya bersirobok. Lanang itu; entah Herold ataupun Hardinata, masih setia dengan perasaannya pada satu sosok nona manis berasma Gauri Panca Gayatri.
"Hardinata, sudah. Mari berkeliling lagi."
Ia merasa bersalah.
"Hardinata...,?"
Apa betul ... apakah betul jikalau dirinya adalah orang yang baik?
Lagi dan lagi, Hardinata kembali diliput oleh rasa sakit lan benci. Benci, mengapa dahulu ia berbuat hal keji pada warga pribumi—termasuk Gauri, juga keluarga kecilnya. Hanya tersisa Yuda; ia amat merasa berdosa pada semesta.
Sebab ulah tangannya sendiri, keluarga Gauri lenyap laiknya isapan jempol kala Herold memberikan tembakan mati.
"Nah, kan. Kau melamun lagi. Apa yang sedang kau pikirkan, hm?"
Dirinya tersentak kala tapak asta Gauri hinggap di pundaknya.
"T-tidak, Gauri. Iya, aku hanya ... tidak apa-apa. Sungguh." Ayatnya terbata-bata seraya melayangkan senyum canggungnya.
Dengan tangkas, Gauri menarik tangan kekar Hardinata lalu membawanya pergi bak seorang gadis kecil yang dimintai sebuah boneka kelinci kepada ayahnya. "Kita harus bergerak cepat. Waktu kita tidak lama, dan kabar buruknya, aku lupa membelikan Yuda sebuah liontin titipannya." Terang Gauri, yang dapat membuat hati Hardinata menghangat bak patera di musim semi.
Masih setia dengan tungkai yang berlari cepat, namun tidak sampai membuat kegaduhan. Aksa Hardinata sempat menangkap sebuah raga yang memikat atensinya. Kendati dirinya langsung saja berhenti tanpa aba-aba, membuat Gauri sontak ikut terhuyung ke belakang.
Puan itu bertanya, "Ada apa?"
"Beri aku uang."
"Kau seram."
Hardinata langsung gelalapan. "T-tidak, aku bukan bermaksud untuk memalakmu. Seperti yang kau bilang, di sana ada kakek tua yang membutuhkan. Merkt u het niet?" (Apa kau tidak menyadarinya?)
Gauri lantas melirik. "Eum..., aku tidak yakin dia penduduk sekitar sini."
Gauri nampak tak berkutik kala hulu Hardinata digelengkan pelan sambil jemari telunjuknya digerakan searah dengan hulunya. "Tidak boleh berpikiran negatif. Kita hampiri saja dulu dirinya." Petuah sang tuan hingga membuat Gauri mau tak mau menyetujui.
Hardinata—taruna dengan karisma yang tiada duanya itu dengan santun menyapa pria tua penuh jenggot putih di dagunya. "Goedemorgen, meneer. Perkenalkan, nama saya Hardi—"
"Herold Van Tholense, niet?"
Hardinata langsung bungkam. Berbanding balik dengan taruni disebelahnya yang nampak mengrenyit pelik tatkala dirinya merasa tak asing dengan paras sosok pria paruh baya itu. Suara parau yang nampak dibuat-buat juga—
"Grapje. Jij Hardinata, dat weten we allemal."
(Bercanda. Kau Hardinata, kami semua tahu itu.)
—artikulasi yang nampak jelas; selalu terekam pada bilik paradigmanya.
Embusan napas Hardinata mendeskripsikan seutuhnya. Kelegaan juga rasa senang. Namun, bual basung namanya jikalau Gauri tidak mencurigai si 'kakek tua' itu.
"Bapak terlalu berlebihan. Saya dan Gauri kemari guna memberi bapak sekantong emas juga beberapa lembar uang. Silakan diterima--" tutur kata Hardinata mendadak dipotong tegas oleh datuk tua tersebut.
"Aku butuh beras. Bukan uang maupun emas." Ujarnya.
Hardinata tersenyum manis. "Kalau begitu, bapak bisa mampir ke rumah kecil kami. We hebben daar een paar zakken rijst."(Kita punya beberapa kantong beras di sana.)
"Tidak," selak Gauri sambil aksanya menilik silet kearah si 'kakek tua'. "Saya curiga bapak ada ikatan tertentu dengan atasan bapak. Ik herinner me je nog goed."(Aku masih mengingatmu dengan baik.)
Amarah Gauri bak tak terbendung lagi. Sepersekon kemudian, hasta sang hawa merampas rosa sekantong emas yang ada di tangan Hardinata. Selepas itu, sang nona justru menatap sekilas datuk tua itu hingga pada akhirnya memilih tuk melenggang pergi tanpa memberi simpati kepada si aki-aki.
"Ayo Hardinata, kita pergi dari sini."
Selepas akara keduanya gata, samar-samar lakuna pada rupa terpahat miring laiknya memandang remeh taruna dan taruni tersebut. Ainnya menyorot tajam, bersamaan dengan hastanya yang terkepal kuat bak terkandung banyak kesumat didalamnya.
"Wacht maar, Herold." Desusnya. "Uw leven, of het leven van degenen die het dichtst bij u staan."
(Tunggu saja, Herold.) – (Hidupmu, atau kehidupan orang-orang terdekatmu.)

1.2: Herold Van Tholense – Panglima Pertama Belanda, Sebelum Jansen.
.
.
.
.
; [v]
Maret, 1950.
Sudah lewat dwiwarsa yang lalu sejak Belanda mulai menginjakan kaki tuk memorak-porandakan Nusantara. Intimidasi, pemungutan pajak diluar nalar, penindasan pada rakyat yang tak berdosa; juga pada Hardinata. Belanda mengerahkan seluruh taktik licik yang ada pada isi kepalanya guna merampas harta kekayaan bumi pertiwi pada masa itu.
Semarak burung kutilang yang bersiul merdu di nabastala, kini Nusantara laksana kartika di malam gempita. Swantantra, atma bak hutan belantara. Rindang, seluruh penghuni bumi pertiwi tidak lagi merasakan sesak paraunya tinggal bersamaan dengan Belanda.
Hal yang sama jelas terasa dalam benak Gauri. Taruni yang tiada hentinya berdiri tepat disisi Hardinata—yang warsa ini, resmi berkepala tiga. Yuda kembali bersekolah seperti biasanya. Siang hari ini, si bungsu lebih memilih tuk menghabiskan waktu bersenai bersama rekan sebayanya.
"Sudah makan siang?"
Sang adam mendongak, memperhatikan paras sani dara yang tengah mencetus kurva kearahnya. Hardinata membalas dengan gelengan kecil, tanda kalau ia belum menikmati jam makan siangnya. Maklum, semesta. Sejak kemarin, Hardinata sibuk dengan siklusnya, yaitu: berangkat pagi, pulang pagi.
Gauri menepuk pundak Hardinata dua kali. "Bawa masuk sepatunya, lalu makan siang. Lingkaran hitam pada matamu makin jelas terlihat." Tuturnya terus terang.
"Heleen ada di mana?"
"Kamar. Ia sedang tidur."
"Lalu, kau sudah tidur belum?"
Gauri mendengus pelan. "Aku mengantuk, maar ik wil nog steeds op je wachten." (Namun aku masih ingin menunggumu.)
Hardinata berdiri dari duduknya sambil membawa dua kasut putih metanya. Dengan laun, hastanya menarik pucuk hulu Gauri yang kemudian pada keningnya ia beri kecupan singkat—sebagai tanda afeksi yang dapat meredam pilu yang membiru. "Bedankt dat je eral tijd bent." Lontar parau Hardinata seraya menatap puannya nuraga. (Terima kasih untuk selalu ada.)
"Kembali kasih," sekala Gauri tersenyum penuh arti. "Semangat terus. Buat aku, buat Heleen juga."
Petuah Gauri membuat jantungnya bergeletar tak harmoni. "Pasti. Ayok, kita masuk. Perutku sudah keroncongan." Katanya sementelah dirinya bisa kembali berdamai dengan ritme jantungnya yang tak menentu.
Kedua insan itu masuk ke dalam. Dan hal pertama yang tak pernah lupa Hardinata lakukan ialah menyapa puteri satu-satunya. Heleen Van Tholense, gadis cantik yang baru saja menyapa dunianya 2 bulan yang lalu. Bak pinang dibelah dua; hidung bangir sang anak, sama seperti kepunyaannya. Aksa apik juga bulat, sama seperti Gauri. Surai lebat sang puteri juga nampak menarik atensi Hardinata. Semua ini layaknya bunga tidur yang selalu dirinya impikan; membangun gubuk anjangsana keluarga kecilnya.
Namun satu yang Hardinata takutkan untuk saat ini—dan mungkin, seterusnya.
Bak komedi putar, hidup ini terus bergerak memutar. Kaleidoskop satu dengan yang lainnya itu bisa disebut parsial--atau mungkin paradoks. Namun baginya, hidup adalah bagaimana cara untuk menentukan pilihan juga bersikap lapang dada.
"Maaf, Pak Hardinata atas kelancangan saya. Namun, pagi-pagi tadi saya mendengar sebuah kabar genting, Pak. Entah kapan, namun pasti. Belanda katanya akan kembali lagi."
Sebenarnya berita itu sudah jauh hari ia dengar. Bukan mencoba tuk melupakan, ia hanya enggan berita ini terdengar sampai rungu Gauri. Hardinata mencoba tuk tertutup berkenaan dengan segala sesuatu terkait keluarga kecilnya.
"Makan siang hari ini pakai tempe dan sayur asem kesukaanmu saja, ya. Aku tidak sempat belanja, entah—rasanya, aku kurang enak badan..."
Persekon sementelahnya ia mendongak, lalu mengembuskan napas pelan. "Beristirahatlah. Sudah kubilang, jangan terlalu keras bekerja di sawah. Aku hanya takut kau kelelahan, namun tetap saja. Keras kepala." Ceracau Hardinata sembari memasang wajah jenaka; mengejek Gauri yang selalu membicarakan kesehatannya, namun tidak memedulikan dirinya sendiri.
Jemari lentik itu menjentik tepat pada pucuk hidungnya. "Iya-iya. T-tapi bagaimana, ya ... kau lelah tidak hari ini?"
"Hm?" deham Hardinata. "Kau mau meminta apa?"
"Hari ini giliranku untuk bekerja di sawah. K-kalau kau tidak keberatan ... boleh tolong gantikan aku t-tidak...?"
"Oh? Tentu boleh, apapun un—"
Gauri dengan cepat memangkas ucapannya. "Bawa Heleen sekalian."
Kening itu berkerut, menimbulkan sejuta pertanyaan dalam isi kepalanya. "Untuk apa aku membawa Heleen pergi ke sawah? Ia masih terlalu kecil, Gauri."
"Justru itu...," Gauri nampak resah. "Kau harus membawanya. D-dokter bilang, penyakitku cepat tertular. Aku takut terjadi apa-apa pada Heleen."
"Kau ini," decak Hardinata.
Dirinya jelas khawatir. Nampak sedu kala Gauri berdalih seraya menatapnya lirih; itu sudah cukup membuatnya kehabisan akal. Perlahan ia merapikan sudu pula garpu diatas piring, lanang berkepala tiga itu tak jemu tuk menuruti keinginan sosok Gauri. "Baiklah, aku akan membawanya. Jaga dirimu baik-baik, dan beristirahatlah."
"Kau juga."
"Aku? Kenapa?" raut pelik terpahat apik pada figur abyasa.
Sesekali napas gadis bersurai gelap itu berembus, "Jangan terlalu memaksakan diri bila kau penat. Serta, jaga dirimu dan Heleen baik-baik. Ik hou van jou." (Aku sayang padamu.)
Enggan membuat kepalanya nian pening, Hardinata lekas mengangguk yang kemudian ia tutup dengan kecupan singkat pada kening permaisurinya.
"Ik ook hou van je. Kalau begitu, aku pergi dulu, ya." (Aku juga sayang padamu.)
Kepergian Hardinata dan Heleen menyisakan sebuah ulu yang berdenyut kebas dalam hayatnya. Sekala rinai mata itu jatuh pada pipinya, Gauri menulis selampit larik aksara pada satu pigura yang berbunyi:
'Bila kamu adalah senja, maka jadikanlah aku salah seorang pemujamu yang paling ditunggu kehadirannya.'
Batavia, 3 Maret 1950.
. . .
Dalam gama menuju lahan di mana Gauri pergi bekerja. Hardinata berjalan melewati banyak bebatuan juga saluran air yang mengaliri sawah. Lima menit yang lalu, ia sempat bertemu dengan Yuda yang asyik bermain kelereng dengan mitra sejawatnya. Hardinata dengan tegas menyuruh Yuda kembali ke wisma guna menjaga Gauri di sana. Tak lupa ia jua memberinya beberapa lembar uang untuk dibelikan sebuah obat. Yuda yang malu kena omel oleh Hardinata, mau tak mau pulang ke rumah dengan bermasam durja. Sungguh malang nasibnya.
Kini, tanggung jawabnya ada pada sosok malaikat kecil dalam gendongannya. Heleen terpaksa ia bawa sebab perintah dari permaisurinya itu. Tidak terlalu menyusahkan, namun cukup rumit—sebab Hardinata tidak biasa mengurusi anak kecil.
"Bu Yanti,"
Yang dipanggil menoleh, "Eh! Pak Hardi! Ini anaknya, ya...? Ayu poool, mirip kayak bapak sama ibunya yang ganteng dan cantik, hehehe."
Hardinata hanya tersenyum kecil sebagai balasan. "Ibu berlebihan, saya jadi malu."
"Yang berlebihan mah cukup berat badan saya aja, pak! Ih nyebelin, untung ganteng." Guyon Bu Yanti yang masih sibuk bermain dengan pipi gembil Heleen. "Ngomong-ngomong, ada keperluan apa bapak kemari?"
Hardinata menepuk keningnya pelan. "Oh iya," lalu terkekeh kecil. "Saya kemari ingin menggantikan pekerjaan istri saya, Gauri."
Bu Yanti langsung terdiam seribu frasa, hingga sepersekon kemudian, kerutan dahinya itu terlukis dengan nyata. "Bu Gauri...? Senin ini, dia tidak ada giliran, bapak ganteng."
"Eh?"
Bu Yanti mengangguk yakin. "Bener, toh. Bu Gauri itu kebagiannya dina ahad, kamis, dan selasa."
Lantas, atas maksud apa Gauri berkilah perihal pekerjaannya di sawah? Apa puan itu rela membuatnya penat nan payah untuk sekadar pergi tanpa membawakan hasil? Ya, memang; biar dirasa nasi kita sesuap, air seteguk—sementelah pun ia sudah telanjur sampai di sini.
Hardinata benar-benar sudah kehabisan jawaban.
Tanpa menghirapkan fatsun yang ada dalam atma, Hardinata pamit balik kepada Bu Yanti. "Kalau begitu, terima kasih infonya, Bu. Saya harus cepat-cepat pulang sekarang."
Belum sempat Bu Yanti menyetujui, Hardinata bertolak diri dengan berbagai macam asumsi. Heleen yang ada dalam gendongannya selalu ia jaga—sesuai pesan Gauri. Namun mengapa; ada apa dengan dara itu? Perasaannya campur aduk; waswas, cemas, buncah, gelisah—firasatnya begitu buruk, entah kenapa.
Baru setengah perjalanan menuju arah pulang, kendati langkah tungkai para warga memenuhi rungunya. Bergerombol bak mengepungi diri. Tanpa disadar, mereka telah membuatnya terheran-heran.
Raut sedu macam apa yang terlukis pada mimik wajah mereka?
Dengan lantang Hardinata memekik frustrasi. "Ada apa kalian berkerubung seperti ini?!" ia menatap eksistensi satu persatu dari mereka. "Jangan membuat saya panik!"
"Terjadi pertumpahan darah lagi, Pak!" seru seseorang.
Hardinata menoleh ke arah suara, "Pertumpahan darah apa?! Bicara yang jelas!" bahana tegas Hardinata menjelmakan sebuah atmosfer yang cukup mendebarkan.
Lagi-lagi, entah siapa yang menyahut; namun itu sudah cukup menjadi saksi bisu fuadnya yang rapuh.
"Tepat di rumah bapak—Gauri beserta Yuda, mati di tangan Belanda!"
Kosong.
Omong kosong apalagi itu?
Baru saja ia mengucapkan kalimat cinta pada nonanya...
Sebenarnya...,
Rencana tuhan itu apa...?
Dan ... di mana lagi akan ia cari, rumah untuknya berkeluh kesah?
"Tak ada yang amerta. Semua akan binasa pada masanya."
.
.
.
; [vi - epilogue]
Apa yang gadisnya inginkan, pasti ia turuti.
Apa yang sang gadis larang untuknya, rela ia jabani.
Bukan perihal siapa yang berbicara.
Namun, siapa yang benar-benar cinta.
Hardinata kini sudah rimpuh. Usianya lapuk dimakan zaman. Namun isi hatinya kekal abadi hanya untuk satu nona manis: Gauri Panca Gayatri.
Beribu-ribu salah ia lakukan. Dan satu yang menjadi sesalnya, belum hitungan kelima ia mengatakan cinta—nonanya sudah gata tanpa meninggalkan sepatah kata.
Pada baya yang ke-60 warsa, jari-jarinya masih setia menyusun baris demi baris aksara yang ia harap, dapat menjadi obat pelipur laranya. Jeluang usang pula pena tua itu senantiasa menemani hari-harinya. Hardinata, ini lah epilog yang tidak dikau pikirkan jauh-jauh hari. Pasalnya, kanin dalam diri itu, masih saja bertengger bak merpati di dahan kayu jati.
"Kau tahu? Kenyataan itu pahit, karena tidak ada dirimu di dalamnya. Tapi apa kau tahu? Imajinasiku kelewat indah, karena ada engkau di dalamnya. Ini semua hanyalah tentang kehadiranmu, mijn beste..."
Tulis sang lanang, dengan senyum pedih pula rasa nyeri yang tiada habis menghantam karangnya.
[]. Usai
.
.
.
;
EXTRA CHAPTER!
Usang dan berdebu, namun tersimpan banyak warita yang takkan pernah jua kulupa. Pigura-pigura tua dihadapanku kini menyisakan sebuah ruang kelabu dalam benakku. Aku tak pernah menyangka, jikalau aku besar dan tumbuh dengan nama 'Tholense'; Ayahku, beliau adalah sosok yang kuat.
"Sudah lama sekali aku tidak mampir, ya, Ayah?"
Aku bertanya. Seolah beliau benar-benar ada disini. Kenyataannya adalah nihil, berbicara dengan tumpukan kertas pula sisa tinta daripada sebuah pena yang sudah habis--bahkan mengering. Benar sekali, Ayah sangat suka menulis. Dan topik pembahasan kesukaannya adalah, tentang Ibu.
Dahulu, aku masih sangat kecil. Namun terekam jelas pada bilik ingatanku jikalau pada saat itu Ayah frustrasi bukan main. Ayah benar-benar menjagaku dengan begitu ketat, beliau takut diriku terluka walau hanya segores jarum kecil.
Usai kepergian Ibu, Ayah memutuskan untuk pergi menjauh dari pemukiman. Pada saat itu Ayah benar-benar buntu; entah jalan mana yang harus ia tempuh, ia hanya ingin rehat sejenak dari hiruk pikuk mahajana.
Bodohnya Ayahku dulu, ia melepaskan tanggung jawabnya begitu saja. Rakyatnya disana begitu sengsara, namun Ayah benar-benar tidak bisa berpikir jernih saat itu. Aku yang masih ada dalam gendongannya hanya terus memekik, hingga Ayah tersenyum pedih menatapku. "Ayah minta maaf, Nak ... Persediaan susumu sudah habis." bisiknya padaku.
Padahal pada saat itu, aku meminta Ayah agar jangan bersedih. Agaknya, beliau tidak paham atas rengekan yang kulontarkan padanya.
Ayah benar-benar mengurung diri. Hidup sebatang kara di hutan--yang kini sebagian lahannya sudah dipakai untuk kepentingan industri--hingga akhirnya pada saat aku menginjak umur yang ke-tujuh, Ayah menyuruhku untuk mencari beberapa kayu bakar dan menitipkan salam padaku agar berhati-hati. Aku menuruti, dan tak lama setelah itu; aku kembali pulang.
Namun yang kulihat hanyalah sebuah pemandangan menyedihkan. Ayah tergeletak tak bernyawa tepat di teras rumah dengan para serdadu yang nampak asing mengelilingi wismaku.
Salah seorang dari mereka datang kepadaku, dan berkata, "Saya paham bahwa kau masih usia belia. Maka dari itu, ikut kami pergi hingga dirimu siap untuk hidup mandiri bak burung yang pergi meninggalkan sarangnya."
Pada saat itu, aku benar-benar tak habis pikir. Isi kepalaku kosong. Sakit rasanya melihat Ayah diseret menjauh dari rumah, lalu dibuang begitu saja ke sungai yang berarus deras. Namun aku mengerti, bahwa ini semua adalah cara terbaik untuk Tuhan mengabulkan tiap doa yang selalu Ayah damba pada kalimat dalam bukunya.
Buku yang sedang kucari itu kini ada ditanganku. Dengan perlahan aku mengusap sampul buku bahari itu, lalu membukanya selembar demi selembar; hingga aku tak kuasa menahannya, derai air mataku mengalir begitu saja. Begitu dalamnya rasa cinta Ayah kepada Ibu, pelita yang selalu terangi tiap detik berharga Ayah.
Sungguh, warita ini akan selalu kukenang dan takkan pernah kuberi titik untuk Ayah dan Ibu.
Karena keduanya laksana kisah yang tak pernah berakhir. Jikalaupun ini adalah akhir dari kisah mereka, sesungguhnya yang fana adalah waktu; dan mereka amerta adanya.
-
TUNTAS.

RAMPUNG: 09 MEI 2021.
DIPUBLIKASIKAN : 13 NOV 2021.
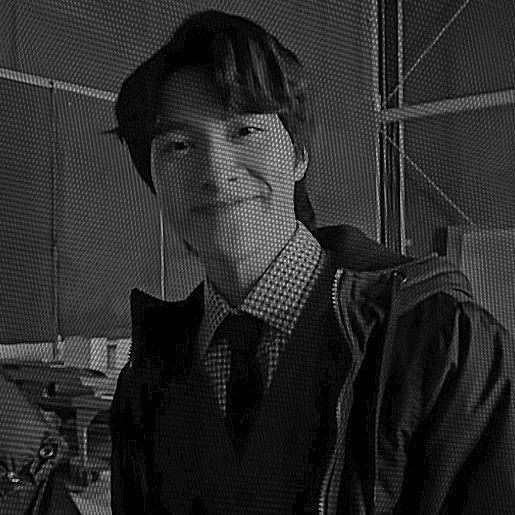
Hendery Wong as Hardinata / Herold.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro