THIO - Perang 6.1
Rasa bersalah itu mirip seperti jelangkung, tapi versi lebih resek. Datang tak dijemput, tapi pulangnya minta diantar. Nggak pergi-pergi biarpun sudah diusir dengan berbagai cara.
Aku terdiam di atas tempat tidur. Menatap langit-langit apartemenku yang berwarna putih polos. Mata menolak untuk terpejam karena otakku lari ribuan kilometer per jam. Isinya tidak jauh-jauh dari rentetan kalimat yang dimuntahkan oleh Jesse dan ditambah dengan wajah kecewa ibuku. Kombinasi sempurna yang membuatku muak dengan diriku sendiri.
Ucapan Jesse menyentil tepat di hatiku. Dan menyentil adalah understatement. Ini seperti kalimat yang cowok itu lontarkan membuldoser hatiku dan menyisakan rasa malu. Tidak ada yang memaksaku melakukan ini memang. Aku juga bisa mengambil langkah seribu seperti Andini, seperti kakakku itu yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitar yang ikut terkena imbas dari perbuatannya. Namun, aku tidak melakukan hal itu dan menerima nasib burukku begitu saja. Aku memilih untuk tinggal dan mencoba menghilangkan malu yang sudah menyelubungi keluargaku.
Aku sudah dewasa untuk dipaksa melakukan hal di luar kehendakku dan ketika aku menyetujui hal ini, itu berarti aku seharusnya siap menerima risiko yang juga hadir dari pilihan yang kubuat. Namun, yang aku lakukan hanyalah menghindar. Kabur dari masalah yang aku tahu pasti penyebabnya karena tahu aku tidak memiliki jalan keluar atau sekedar celah untuk kabur meskipun harus mematahkan tulang-tulang di tubuhku seperti di film-film.
Ponsel berada di dalam tangan kananku kini kembali berada tepat di depan wajah. Pesan dari Jesse belum ditutup sedari malam tadi saat aku menerimanya.
Deretan nama jalan serta nomor rumah, ditambah dengan link google maps mengisi pesan di atasnya, disusul dengan pesan dari cowok itu. Ini alamat rumah saya.
"Rumah saya," ucapku membaca isi pesan itu. "Rumah, ya?" ulangku, sedikit lebih kencang. Rasa asing yang menari-nari di lidahku. Aku berusaha mencecapnya untuk merasai kata itu, tetapi tidak ada satu pun yang dapat membuatku merasa hangat yang menyelubungi dada seperti kata orang-orang. Ada lubang kosong mengaga yang terlalu lebar untuk ditutupi di sana, terlalu lebar hingga aku takut kalau aku terbenam di sana.
Aku mengenyahkan perasaan itu dengan gelengan kepala. Membiarkan tubuhku menjadi sedikit lebih rileks dengan udara dingin dari pendingin ruangan yang membuat bulu kudukku meremang di bawah terpaannya. Mataku baru terpejam dalam lima tarikan napas, tetapi ponselku yang bergetar memaksaku untuk membukanya kembali.
"Ibu," bisikku pelan. Jemariku langsung mengangkat panggilan itu dengan jantung yang tiba-tiba saja memburu. Panggilan di tengah malam menuju subuh seperti ini tidak pernah membawa kabar baik kan?
"Halo, Bu?"
"Aliyah," suara lemah ibuku langsung menyusup memasuki telinga. Tanpa bertatapan langsung saja wajah sendu ibuku langsung terbayang. Matanya yang dibingkai dengan garis-garis selalu tampak lembut, juga dengan senyum mengembang. Ibu adalah contoh yang tepat untuk menggambarkan sosok ibu peri baik hati.
"Kenapa, Bu? Kok sudah bangun? Atau belum tidur?"
"Ibu kebangun."
Aku mendengar helaan napas panjang nan berat di awal kalimat tadi. Aku tahu rasanya mencoba menghilangkan berat yang memenuhi dada dengan helaan napas seperti tadi. Tidak membantu sama sekali.
"Nggak ngantuk lagi?"
"Enggak." Jeda. "Ibu kepikiran kamu. Kamu baik-baik aja di sana?" Aku menahan napas mendengar pertanyaan Ibu. "Maaf Ibu bikin kamu ada di posisi sekarang," lanjutnya lagi dengan suara bergetar dan disusul dengan isakan pelan yang coba ditahan oleh beliau.
"Yang harusnya minta maaf itu Andini, bukan Ibu."
"Harusnya ibu juga nggak bilang kamu gantiin Andini. Ibu mau hubungin kamu, tapi malu. Harusnya Ibu nggak membebankan kesalahan Andini ke kamu."
Aku menarik napas dalam, mengisi paru-paruku dengan udara untuk mematikan amarah yang menggumpal di dada. Aku marah terhadap diriku sendiri, tetapi menumpahkannya kepada orang lain yang juga menjadi korban Andini. Malah seharusnya rasa sakit hati cowok itu lebih parah dari yang kurasakan. Dan kini Ibu juga meminta maaf.
"Aku punya pilihan, Bu. Aku bisa kabur, tapi aku nggak lakukan. Jadi ini memang keputusanku." Aku mengucapkannya untuk menenangkan Ibu tetapi itu justru terdengar seperti aku mengatakannya untuk diriku sendiri.
Ibu menyusut hidungnya. "Jesse baik sama kamu?"
Tergantung kategori baik itu bagaimana, dumelku dalam hati. Tapi, hei, aku sedang berusaha menenangkan ibuku jadi yang aku katakan adalah "Baik, Bu. Kami mau pindah ke rumahnya besok."
Topik Andini terlewatkan begitu saja dan tidak ada di antara kami yang membahasnya. Ibu menanyakan bagaimana kebiasaan kami ketika bersama dan aku jawab dengan kebohongan paling wahid yang pernah keluar dari mulutku. Telepon itu akhirnya dimatikan ketika ibuku yakin betul kalau aku tidak ada masalah setelah statusku berubah menjadi istri orang. Aku meringis.
"Pagi nanti gue harus ke rumah Jesse berarti," kataku dengan berat hati. Karena mataku tidak mungkin lagi terpejam, aku memilih untuk membereskan beberapa barang yang dapat langsung kuangkut. Beberapa helai baju ganti dan juga beberapa peralatan kerja yang dapat aku cicil sekaligus dapat kukerjakan di sana langsung. Beberapa resin yang menunggu curing sengaja ditinggal karena aku pasti harus ke sini lagi untuk mengambil sisanya yang tidak lagi banyak. Aku dapat membawanya dengan kereta nanti.
Tiga boks berukuran besar sudah siap untuk dibawa ke rumah Jesse. Aku terpaksa mengeluarkan ongkos lebih dan menggunakan taksi kali ini. Biarlah.
Aku tiba di rumah Jesse di siang hari. Ada mobil berwarna silver milik cowok itu yang terparkir di depannya. Mataku memindai rumah bagian depan. Ada taman yang ukurannya cukup luas di sebelah carport yang dapat memuat dua mobil. Beberapa tanaman dengan daun berbagai macam bentuknya dan berada dalam pot berjejer rapi. Jangan tanya namanya padaku karena sumpah bagiku semuanya sama. Tanaman. Titik.
Pak Sopir yang baik hati membantuku membawa boks sampai ke depan pintu rumah, untung saja pagarnya terbuka. Aku memberikan tips untuk bantuannya tadi dan membawa satu boks ke dalam rumah Jesse. Berbeda dengan bagian luar rumah yang berwarna putih polos dengan warna hijau dari tanaman sebagai pelengkapnya, bagian dalam rumah sangat...hangat karena sentuhan warna cokelat dan krem. Mataku memicing ketika melihat beberapa wana pink di pernak-pernik kecil yang tersebar di berbagai sudut dan aku langsung tahu kalau rumah ini adalah hasil kompromi Jesse dan Andini. Tidak mungkin cowok itu memberikan warna pink kan? Eh, atau diam-diam cowok itu suka warna pink?
"Saya pikir kamu nggak akan datang dan kabur seperti kakakmu." Sapaan mengejek itu sudah pasti dikeluarkan oleh Jesse yang muncul dari salah satu kamar.
"Saya belum sempat lihat-lihat, tapi setannya keburu keluar," katakku bosan. Aku tidak memberikan waktu untuk Jesse memberikan balasan dari ucapanku tadi. "Kamar saya di mana?"
Jesse berdecak lalu menunjuk ke pintu di seberang tempatnya berdiri. Aku tidak mau berbasa-basi dengan cowok itu sehingga langsung memasuki kamar yang membuat rahangku terjatuh ke lantai. Semuanya serba...pink. Di tembok tempat ranjangnya berada, ada warna putih berbentuk awan yang berbondong-bondong memenuhinya. Tempat tidurnya bahkan sama mengerikannya seperti lemari baju yang berada di ujung ruangan, dekat jendela besar.
Canopy bed dengan tirai berwarna pink
Pink.
Tolong digaris bawahi, ditebalkan, dan dibuat kapital semua.
PINK
"Bagus kan kamarnya?"
12/7/22
#QOTD Part 6.2 enaknya kapan nih?
Jangan lupa vote, komen dan follow akun WP ini + IG @akudadodado yaaw. Thank you :)
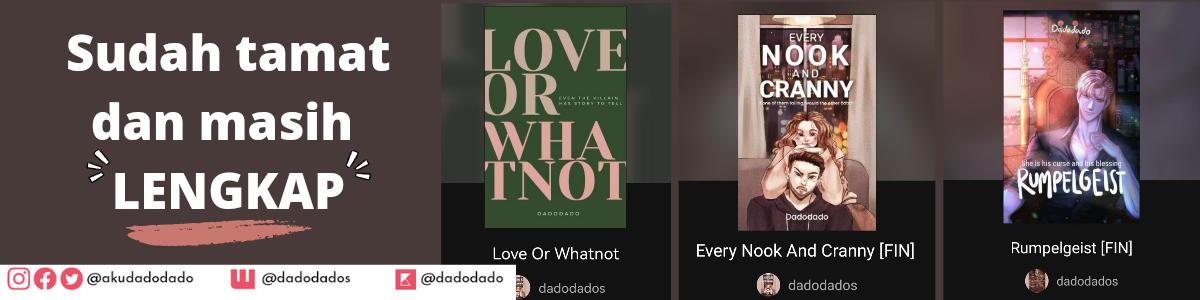

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro