04 - 𝐂𝐢𝐮𝐦 𝐃𝐮𝐥𝐮
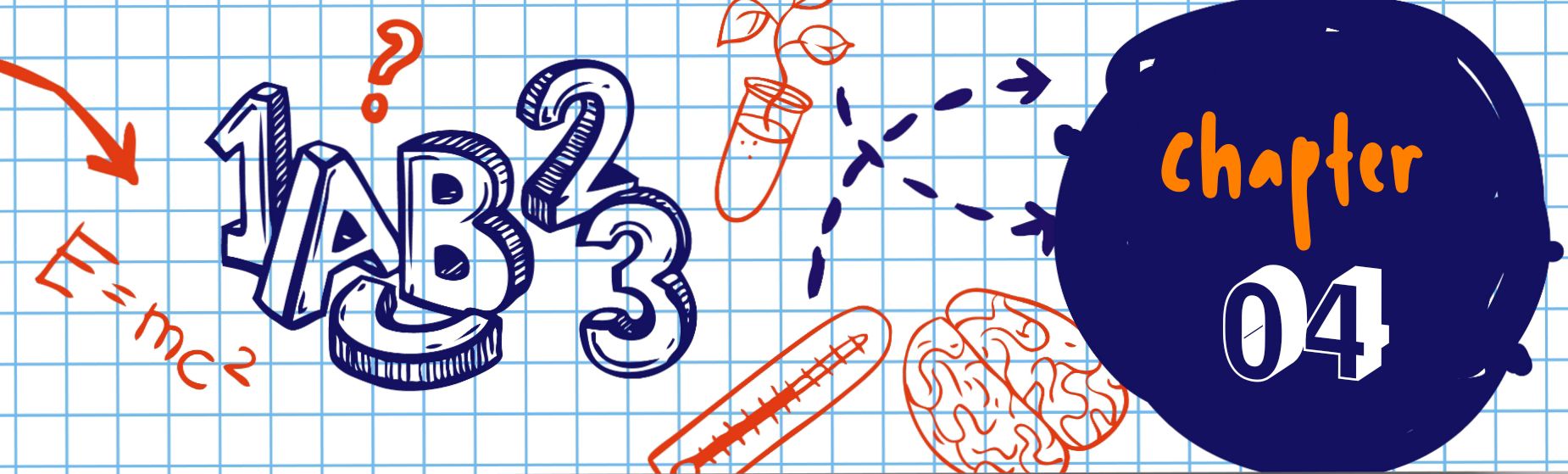
CHAPTER 04
[Estu Herjuno]
Ketemu Lana di parkiran Nuski adalah kebetulan aneh yang tanpa sadar ternyata gue mengharapkannya. Kikan menaruh helmnya di spion motor gue sebelum turun dan mulai berkelakar dengan Lana. Ritual cewek pun dimulai.
"Lo cantik banget, sih, gwela!" puji Kikan yang sama sekali nggak pernah gue dengar dari mulutnya untuk cewek lain.
Lana mengibaskan tangannya. "Ini kali keberapa kamu bilang gitu." Lana terkekeh sambil bikin manufer tangan yang uwu ke Kikan.
"Lah, emang cantik. Ya, nggak, Jun?" si Kampret.
Gue mendadak gugup seolah mau jawab pertanyaan senilai satu milyar dolar. Gue berusaha mengalihkan pandangan ke arah selain Lana. Tapi magnet itu menggeret fokus mata gue ke wajahnya. Satu, dua, tiga, empat detik. Dalam diri gue ingin mengangguk sekencang mungkin. Tapi gengsi gue memilih untuk mengangkat kedua bahu. Lalu berjalan mendahului mereka.
Kikan dan makhluk surgawi itu berjalan di belakang gue. Ngobrolin entah apa.
Karena beda kelas, jadi kami bertiga akan berpisah di persimpangan pintu masing-masing. Kikan di sebelas XI IPS 2, gue di IPA 2, dan Lana di IPS 1 sekelas sama Sidney. Itulah kenapa Sid wadul ke gue tentang cendrawasih di kelasnya udah kayak apa reportasenya. Lana ini lah, itu lah. Dan sekarang, Sid yang gue maksud itu sedang berlari mendekat dari arah koridor kelas sepuluh. Palingan habis dari kelas gebetannya.
"Sup!" Sidney merangkul dan segera gue tepis.
"Sepagi ini lo udah ngebucin?" tanya gue kalem sambil lanjut berjalan. Entah, nggak bisa sebebas itu sekarang. Rasanya gue harus jaga sikap kalau di depan Lan-, di depan orang baru.
"Bukan ngebucin. Cuma ngelakuin tugas seorang pencinta. Dan cinta gue buat Sahnaz itu seperti bunga yang harus disiram tiap waktu."
Gue mengangguk. "Kayaknya bungamu itu bakal subur. Karena tiap waktu disiram sama pupuk kandang."
"Maksud lo gue pupuk kandang?"
"Yes, and you must be proud for that."
"Why? Kenapa gue harus bangga jadi pupuk kandang?" Kami berjalan pelan. Gue paling geli kalau ngobrol sama orang yang dosis ekstrovernya kebanyakan seperti Sid. Dan gue curiga ada satu lagi ―cowok yang kemarin ngajak gue bikin channel.
Sementara itu gue jalannya setengah nunduk karena menghindari beberapa anak cewek kelas sepuluh yang kadang suka diem-diem memfoto gue. Tau-tau ada aja notifikasi menandai di instagram. Beberapa dari mereka ada yang pembaca gue. Dan gue nggak pernah siap untuk berinteraksi dengan mereka. Kapan pun, di mana pun. Girls, just leave me alone, please.
"Karena dengan pupuk kandang bunga cinta Sahnaz akan tumbuh subur. Dan lo harusnya bangga jadi pupuk kandangnya," kata gue lagi.
Sidney diam, mungkin dia sedang berpikir. "Jun, gue pupuk kandang banget?"
Gue tertawa dalam hati. Melipat bibir ke dalam supaya nggak kelepasan tertawa.
"Bukannya pupuk kandang itu komposisinya ada air seni binatang, kotoran, sepah pakan, dan amonia yang pesing itu? Kan gue wangi."
Tapi, ekstrover adalah orang yang paling enak buat dibercandai. Termasuk Sidney. "Ya memang. Dari pada pupuk kimia? Buatan. Nggak organik. Nggak begitu menyehatkan. Pupuk kandang itu jenis pupuk yang paling murni loh. Dan cinta lo ke Sahnaz murni, kan?" gue berlagak serius jelasinnya.
"Ya murni lah," jawab Sid. "Organik."
Lalu gue menepuk-nepuk pundak Sid. "Jadilah pupuk kandang yang membanggakan."
Sid tiba-tiba menyeringai bangga. "Pupuk kandang not that bad, ya."
"Perfect," gue tersenyum membodohi.
"Tapi, Sid. Kamu nggak harus jadi pupuk kandang kalau mau bikin bunga itu tumbuh subur dan mengakar kuat," Sid menoleh ke belakang ketika Lana tiba-tiba bergabung dalam percakapan. Sementara gue tidak tertarik untuk menoleh. "Kamu bisa jadi sun ray. Karena mau sebanyak apa pun pupuk kandang yang dikasih ke bunga, kalau sinar mataharinya nggak ada, ya bunganya tumbuh payah. Atau cukup jadi sesederhana air yang kamu bilang buat nyiram tadi. Itu masih bisa diperluas maknanya, kan? Jatuh cintalah dengan cara yang indah."
Sidney seperti langsung setuju. Dia menyikut lengan gue. "Seenggaknya anak pinter di sini bukan cuma satu," kata Sidney menyindir gue. "Lana, gue hutang nyawa sama kamu."
Gue berdecap seraya memutar bola mata, "Teorinya, jatuh cinta sama seseorang ada efek sampingnya yang bisa bikin 'goblok'. Dan ini cuma bisa dimengerti oleh mereka yang pernah naksir aja," ucap gue.
"Idiiih, geli gue dengernya," seloroh Kikan dari belakang. "Kayak yang lo pernah jatuh cinta aja."
"Pernah lah!"
"WHAT?!" seru Kikan dan Sidney nyaris bersamaan.
"Kapan? Di mana? Sama siapa? Sama cowok apa cewek?" tanya Sidney memastikan.
Gue lekas menjitak kepala Sidney. "Ya cewek lah!" Ssst, jaga sikap, Jun.
"Siapa?" tanya Kikan menyusul.
"Namanya Lilis Safitri."
"Anjrit! Itu nama ibu gue!" Sidney meninju lengan gue cepat-cepat. Lalu semuanya tertawa. Gue bahkan mendengar sedikit dari mulut Lana.
Masih dengan sisa tawa, gue berkata, "Gue selalu bisa merasakan jatuh cinta ketika menulis. Dan itu cukup."
"Nah, nyatanya lo emang masih senaif itu," ujar Sidney.
Karena keasikan ngobrol sampai nggak kerasa kami tiba lebih dulu di kelasnya Sidney. Itu artinya Lana juga akan masuk.
"Beri jalan, beri jalan. Orang ganteng mau masuk," seru Sidney sambil masuk ke dalam kelas. Dan dia disambut sorakan tak setuju sama anak-anak kelasnya.
Saat gue mau jalan ke kelas, Kikan menahan gue dengan memegangi selempang tas gue.
"Duh, Lan, sori banget ya yang semalam. Beneran deh, gue nggak bisa nemenin kamu ke Remember Me. Gue harus ke binatu," kata Kikan seperti menyesali sesuatu.
"Nggak apa-apa. Kan aku cuma minta ditemeni aja. Dan itu kalau kamu bisa aja kok."
Lalu Kikan melirik gue dengan sebuah rencana. Jangan bilang kalau-.
"Tapi Juno bisa kok." Ini Kikan beneran bahaya. Gue pastinya terkejut dengan pernyataannya tadi, yang jelas-jelas gue nggak pernah tahu apa yang lagi mereka bicarakan. Gue menatap Kikan dengan isyarat kamu-lagi-apa-apaan?
"Ih, nggak perlu," reaksi Lana juga segan. "Aku cuma mau ambil baterai jam kok. Waktu itu yang punya toko bilang kalau baterai tambahannya bisa diambil misal stoknya udah ada. Soalnya jenis beterai jamku beda."
Gue melempar tatapan ke arah lain.
"Nah, makanya. Juno lebih sering main ke sana ketimbang gue. Dan semalam gue udah BILANG ke Juno," Kikan melirik ke gue. Penekanan dalam kalimat Kikan menandakan dia sedang bermain skenario. "Dia bisa nemenin kamu ke sana. Pakai motor dia."
Gue melangkah ingin melarikan diri tapi Kikan masih memegangi selempang tas gue. Terpaksa gue menatap ke arah Lana. And her face makes me feel weak. Mulut gue mendadak kemarau. Sekali lagi gue melempar tatapan ancaman ke Kikan.
"Jadi, kamu mau berangkat habis sekolah, kan?" tanya Kikan mendesak Lana.
"Iya, tapi-."
"Deal. Juno bisa banget."
Sebelum Kikan semakin jauh, gue menyela. "Bukannya tadi kamu di parkiran? Bawa motor sendiri, kan?"
Yang jawab malah Kikan, "Lana nggak bawa motor, Juno. Nggak ada anak pertukaran yang bawa motor. Lana kalau berangkat dari wisma seringnya sama Pak Murdi."
Setahu gue Pak Murdi memang salah satu guru yang ikut menangani urusan pertukaran pelajar. Guru bahasa Jepang yang kalau kata anak Bahasa paling spesial cara ngajarnya.
Kikan berkedip memaksa. Seolah menempatkan gue pada opsi yang tidak bisa dielak.
Gue sedikit mendengus. Apa boleh buat. "Kalau jam terakhir selesai, kamu jangan jauh-jauh," kata gue menghindari kontak mata. "Kalau bisa tunggu di depan kelas." Byar byar byar.
Kikan mengangkat dagu agar Lana menjawab.
"Ini nggak apa-apa?"
Gue nggak enak juga kalau akhirnya nolak. "Pake helm Kikan, ya."
"Oh," jawabnya masih bingung. "Oke."
"Tapi jangan ngeluh kalau helm Kikan bau ketombe."
Itu detik-detik sebelum Kikan ngomel panjang lebar.
***
Saat bel penanda pulang berbunyi, gue merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Perut gue mules, jantung dangdutan, dada gue menghangat, napasnya juga, dan rasanya ingin momen setelah ini skip saja. Padahal gue juga ada perlu ke Remember Me dengan atau tanpa dia.
Gue menunggu anak kelas pada keluar semua. Setelah nggak ada yang tersisa gue lalu mengemas alat tulis ke dalam tas. Keluar dari deret kursi. Tarik napas dalam-dalam. Busungkan dada. Dan melangkah. Semoga Tuhan memegangi hati manusia cemen ini.
Beberpa langkah sebelum sampai di ambang pintu, gue berhenti. Anxiety menyerang. Perlu pakai parfum nggak, ya? Lalu gue mundur selangkah. Buru-buru membuka tas dan mengambil satu kaleng parfum Aks. Semprot sana, semprot sini. Dan-.
"Masih lama?" gue nyaris melonjak saking kagetnya. Lana sedang berdiri di ambang pintu.
Gue kikuknya lagi kayak apa. Lalu gue menyemprotkan parfum ke udara.
"Kelas ini bau," ucap gue tak masuk akal. Salah tingkah.
"Jadi nggak? Bentar lagi mau hujan. Kalau nggak jadi aku mau order ojol aja."
"Ayo." Napas gue ngos-ngosan meski nggak kentara.
Lana mengangguk.
Dari sekian banyak momen gerak lambat yang pernah gue lihat di film-film. Kali ini seolah itu terjadi di dalam kehidupan gue. Jalan sebelahan sama Lana rasanya beda. Suhu di sekitarnya terasa panas. Atau ini cuma perasaan gue saja? Dan tentunya, banyak pasang mata yang mendadak fokus ke kami berdua.
Sesampai di parkiran gue menyerahkan helm Kikan ke Lana.
"Cium dulu deh," kata gue.
Lana menatap gue dengan sudut alis yang membingungkan, "Hah?"
Gblk!
"Um, anu. Maksud aku, helmnya. Cium dulu helmnya, takut bau ketombe Kikan. Bukan aku. Maksudnya itu bukan helm aku. Helmku wangi. Helm Kikan suka aneh. Helmnya yang dicium. Maksudnya diendus. Pake hidung," gue gelagapan.
"Oh."
Sial. Ini gue yang salah ngomong, atau dia yang salah tangkap?
"Wangi sampo, kok." Ada senyum yang mendesak di bibirnya. Dan entah kenapa itu seperti memicu senyum gue juga. Tapi gue tahan.
"Udah? Naik kalau gitu," kata gue. Entah kenapa kami malah terperangkap dalam tatap. Sebelum kemudian kami terkekeh malu seraya memalingkan wajah masing-masing.
"Buru. Nanti aku makin eror," kata gue sambil berkedip.
Teorinya, jatuh cinta sama seseorang ada efek sampingnya yang bisa bikin 'goblok'. Dan sepertinya gue mulai goblok.
"Iya, ini mau naik."
Gue hampir tiap hari boncengin Kikan. Tapi boncengin Lana terasa ada yang berbeda. Pokoknya beda seratus delapan puluh rokaat.
Badan gue masih panas dingin bahkan setelah motor gue berjalan selama lima menit dari parkiran. Yang di belakang gue juga sepi nggak ngomong apa-apa. Namun ketika gue udah buka mulut mau ngomong. Eh, dia bersuara duluan.
"Aku kayaknya mematahkan hati banyak cewek deh pas jalan sama kamu di sekolah tadi," katanya.
"Kenapa gitu?" gue jawab ragu-ragu.
"Tatapan mereka aneh. Kayak nggak suka banget lihat aku pas itu."
"Ah biasa aja. Mereka cuma iri."
"Iya. Iri karena aku jalan sama penulis keren."
Seketika gue mikir kalau Lana adalah pembaca gue juga. Lalu mulai agak ancang-ancang.
"Aku nggak sekeren itu. Tapi Lana tahu dari mana aku nulis? Baca tulisanku juga?" gue antisipasi.
"Tahu aja. Sidney banyak cerita tentang kamu di kelas. Seolah dia itu buzzer kamu gitu."
"Astaga!"
"Kenapa?"
"Sid emang gitu. Suka melebih-lebihkan. Dan gue nggak punya buzzer."
Lana terkekeh di belakang. "Tapi boleh ya aku baca tulisanmu di Wattpad?"
"Jangan dong."
"Kok jangan?"
"Malu."
Perlahan gue menghentikan laju motor karena di depan sedang lampu merah.
Gue membuka kaca helm. "Jangan baca tulisanku, ya?"
"Kenapa?"
"Tulisanku kayak cakaran ayam."
"Lah? Kan semua tulisan di Wattpad bentuknya sama aja."
Gue terkekeh. "Pokoknya jangan."
"Aku penasaran aja. Kata anak-anak memang bagus tulisanmu."
"Sepenasaran itu?
"Lumayan."
"Tapi penasaran itu belum seberapa kalau dibandingkan sama penasaranku ke cowok yang waktu itu ngobrol sama Lana di depan Remember Me." Bablas slurr.
"Dennias?"
"Namanya Dennias?"
"Dennias Lionhart."
"Pacar, ya?"
"Ex."
"Cool," reaksi gue. "Jangan pernah balikan, ya."
"Lah kenapa?"
Beberapa detik gue memikirkan jawabannya. Sayangnya tidak menemukan jawaban yang pantas untuk disampaikan. Kadang lebih bagus seperti itu. Biarkan pertanyaan 'kenapa' menggantung di udara kalau ingin percakapan-percakapan berikutnya tetap ada.
Jarak ke Remember Me tersisa ratusan meter lagi saat air langit menyerbu bumi. Dengan segera gue menepikan motor ke sebuah toko bangunan tutup yang berkanopi. Ada tiga pengendara motor yang berteduh di sana sebelum kami.
"Lana oke?" tanya gue sambil mengelap air di baju seragam.
"Ini cuma air."
Gue tersenyum lebar. "Berteduh sebentar, ya?"
"Nggak masalah. Selama nggak keburu tutup aja toko barang antiknya," jawab Lana.
"Nggak, dong. Aku udah ada janji sebelunya sama Mas Bahri. Dan ada urusan lain di sana."
"Oh. Jadi aku nggak ganggu banget, ya?"
"Aman," kata gue dengan gerakan tangan. "Hei. Sori. Waktu itu aku belum tahu Lana anak Nuski juga."
Lana tertawa sebentar, "Kenapa minta maaf? Aku bukan anak Nuski. Cuma siswi pertukaran."
"Yaaa, aku ngerasa salah bersikap aja waktu itu."
"Nggak ada yang salah."
"Aku salah karena sempat ketus."
"Terserah kamu deh. Kalau pengin dimaafin, ya, aku maafin. Whatevs."
Gue tersenyum lebar sekali lagi.
"Kamu yang sekarang seperti bukan kamu yang tadi pagi," kata Lana.
"Masa? Mungkin karena kena air hujan."
"Oh, anak rinai? Anak senja juga?"
Gue menyipit pura-pura berpikir, "N-no," sanggah gue dengan gelengan pelan. "Aku justru nggak pernah nyaman sama hujan apalagi senja. Hujan itu basah dan merepotkan. Aku tahu itu berkat dari Tuhan, dan banyak yang suka. Aku cuma kurang suka dengan suasananya aja. Bukan sedang tidak menyukai pemberian Tuhan. Ya sama seperti jengkol. Itu pemberian Tuhan, ada yang suka, ada yang tidak. Sesederhana itu. Nggak perlu diperdebatkan," jawab gue. "Aku lebih suka hari yang cerah. Terutama di momen matahari pukul sembilan pagi sampai menjelang pukul sebelas. Dan suasana matahari antara pukul dua sampai pukul tiga sore. Hujan bikin mataharinya sembunyi. Senja berarti matahari lekas surup. Lalu datang malam. Aku nggak suka malam."
"Kamu banyak nggak sukanya." Bibir Lana tersenyum sebelah. "Cool."
Mata gue menyipit, "That's my word!"
Kami berdua terkekeh.
"Tapi kebanyakan penulis dan introver suka banget loh sama hujan dan senja. Lalu kopi, puisi, dan ratapan luka."
Seketika gue tertawa sampai menengadahkan kepala. "Fun fact, aku penulis yang paling payah kalau disuruh bikin pwisie."
"Imppossible."
Gue lalu mengacungkan dua jari, "Serius."
"Masa sih?"
"Ya."
"Like, for real?" wajah manisnya menantang kesungguhan gue.
Gue menggaruk kepala yang tidak gatal. Tersenyum aneh. "Y-ya."
"Kalau gitu harus dibuktiin."
"Lah, yang ada, pembuktian itu kalau akunya ngaku-ngaku puitis."
Lana terkekeh kemudian. "Nggak, aku bercanda. Percaya kok."
"Tapi kalau Lana pengin aku akan coba bikin malam ini," nggak tahu kenapa gue malah bilang begitu.
"Bikin puisi? Jangan maksain deh."
"Umm, semacam itu. Ya makanya ini mau buktiin kalau aku nggak bisa bikin puisi."
Lagi-lagi dia cuma terkekeh. "Tentang?"
Gue lalu menatap jauh ke depan. "Mungkin puisi tentang petani di sawah atau nelayan yang berjuang di atas riak-riak."
"Tuh, ngomong aja udah puitis. Udah, ah."
"Tadi cuma ungkapan."
Kami melangkah mundur karena angin membuat cipratan hujan sampai ke bawah kanopi.
"Lana kedinginan?" tanya gue.
"Hm?" Lana menoleh ke gue. Namun bukannya menjawab, ekspresi wajahnya malah berubah cemas begitu melihat wajah gue. Kemudian entah kenapa dia buru-buru mengais tasnya. Dia mengeluarkan tisu untuk kemudian disodorkannya ke hidung gue. Tanpa mengatakan apa pun dan hanya napasnya yang naik turun tak pasti.
Tak perlu penjelasan darinya, gue langsung menyadari satu hal. Gue segera mengambil alih gumpalan tisu itu dari tangan Lana.
"Ini udah biasa," kata gue.
"Udah biasa mimisan?"
Gue mengangguk. "It's okay." Gue mengelap aliran darah yang agak merah kehitaman. "I'm fine."
***
Hehehe, "I'm fine." ceunah.
Suka nggak sama Bab ini?
Sekuel sudah ada. Silakan kunjungi ceritanya di TheReal_SahlilGe
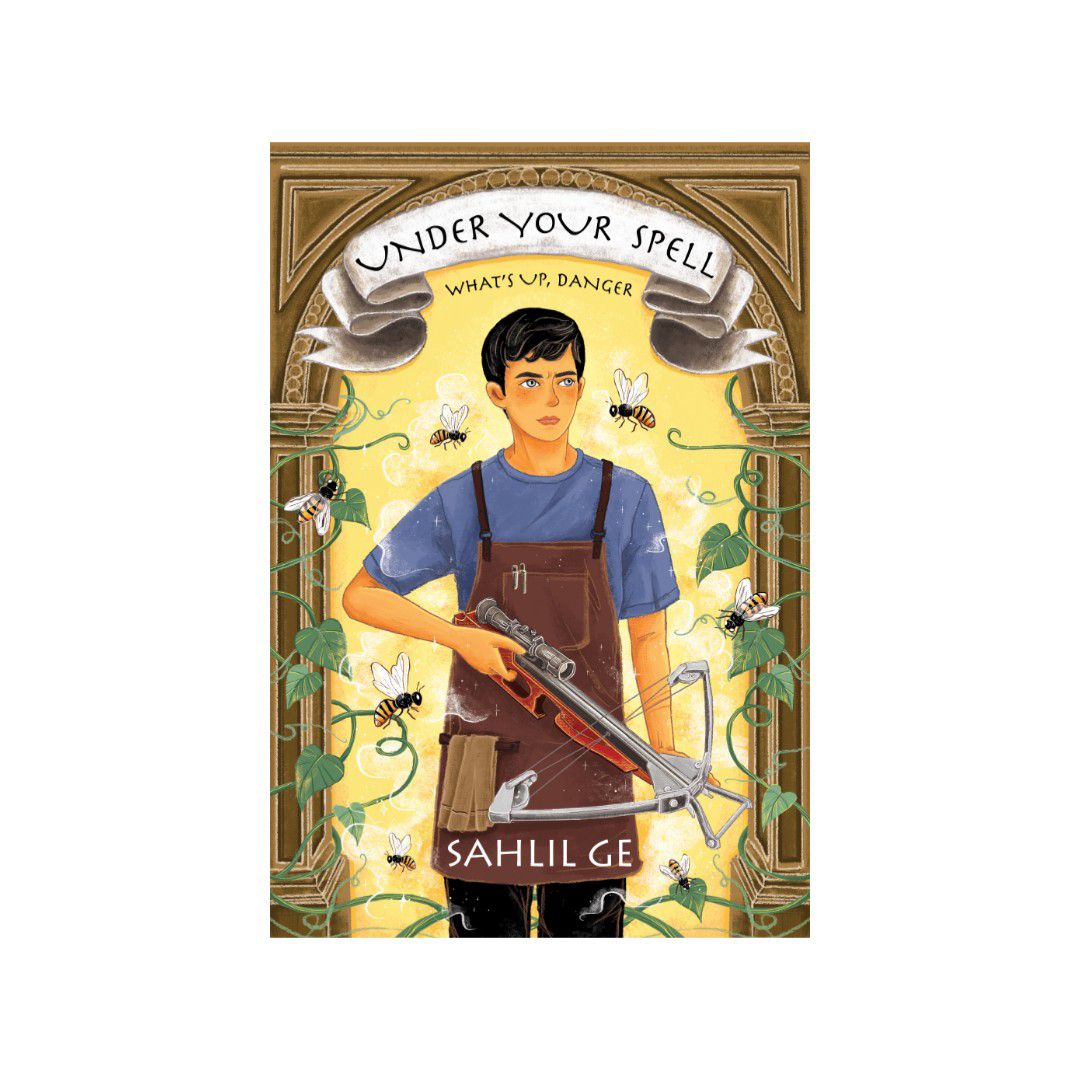
________________________
Sampai jumpa lagi Senin nanti.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro