Chapter 23
Selamat datang di chapter 23
Tinggalkan jejak dengan vote, komen atau benerin typo-typo yang bertebaran
Thanks
Happy reading everybody
Hopefully you will love this story like me
❤️❤️❤️
____________________________________________________
“Fuck mencintaimu dalam diam. Aku ingin mencintaimu dengan ugal-ugalan.”
—Tanpa Nama
____________________________________________________
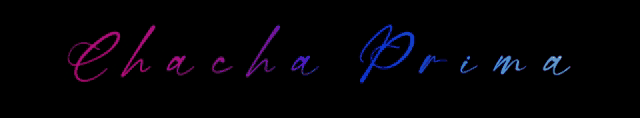
Sembari memejam, Jameka mengeluarkan karbon dioksida melalui hidung dan mulut. Kelegaan memang terasa, tetapi ia sadar tidak akan bertahan lama. Masih ada yang harus ia hadapi dan hasilnya belum tentu melegakan juga. Apalagi dilihat dari konteksnya. Jameka yakin “kelegaan” hanya diprediksi satu persen saja. Selebihnya ....
Jameka menghentikan pikirannya. Sebelum menuruni tangga pesawat di urutan penumpang terakhir, matanya menyipit, tangannya memayungi wajah ketika memindah tatapan ke atas guna mengecek cuaca Jakarta yang terang benderang.
Padahal tadinya Jameka mengira akan ada penundaan penerbangan atau semacamnya, yang rupanya tidak terjadi. Jadwal pesawatnya tepat waktu sehingga secara otomatis juga tiba tepat waktu. Harapannya untuk berlama-lama terkungkung dalam kelegaan selama di New York atau di pesawat sebelum berhadapan dengan sesuatu di Jakarta tidak terkabul. Entah hanya perasaan Jameka semata atau memang benar adanya waktu cepat berlalu.
Setelah menyematkan kacamata hitam, Jameka mengantre koper di ban berjalan. Tidak sampai lima menit berselang, ia sudah menggeretnya keluar dari pintu kedatangan. Di sekelilingnya ramai orang berlalu-lalang dengan urusan masing-masing. Seorang wanita sedang menelepon meminta maaf kepadanya ketika tak sengaja menyenggol kopernya. Jameka cuek saja dan lanjut mencari-cari taksi. Menemukan satu, ia melambai-lambai kepada sang sopir.
“Tolong koper saya, Pak,” pinta Jameka kepada sopir taksi yang turun dari kendaraan tersebut untuk menyambut Jameka. Sambil tersenyum ramah, pria tua itu kemudian mengangguk dan membantu Jameka memasukkan koper ke bagasi.
“Ke mana ini, Teh?” tanya sang sopir dengan logat Bandung kental. Logat itu mengingatkan Jameka akan Kevino yang notabene orang Bandung. Janji mengunjungi orang tua pria itu telah Jameka langgar secara sepihak demi menuntaskan urusannya. Kini ia berdebar-debar sebab kecemasan mulai merasukinya. Ia mengalihkan pikiran itu sejenak untuk menjawab sopir taksi ke mana ia akan pergi.
Kendaraan mulai berjalan. Jameka melihat ke luar jendela. Ia tak fokus memperhatikan sesuatu sebab Kevino masih membekas dalam pikirannya. Bagaimanapun, seminggu tanpa memberi kabar kepada Kevino pasti akan sangat membuat kebingungan pria itu. Jameka amat sadar, tetapi harus melakukannya lantaran ingin menuntaskan masa lalu. Bila ada Kevino yang menemani proses tersebut, Jameka tak yakin bisa. Menurutnya, sesuatu seperti itu harus datang dari hati pribadi masing-masing. Bukan atas kehendak atau paksaan orang lain.
Beberapa rencana sudah tersusun rapi dalam benak Jameka. Pertama-tama setelah mendarat di Jakarta, ia akan langsung ke mansion papanya, bertekad menceritakan semua tentang River tanpa ada yang ditutup-tutupi. Segala persiapannya sudah matang. Termasuk mentalnya dalam menghadapi potensial serentetan kata kemarahan dan wejangan dari papanya. Setelahnya, ia akan segera menelepon Kevino.
“Bener yang ini, Teh?” tanya sopir.
Gerbang besi hitam raksasa yang catnya sudah mengelupas di sana-sini dan luarnya agak ditumbuhi rumput liar membentuk semak-semak samar menjadi sasaran pengelihatan Jameka. Memang kalau tampak fasad, mansion itu seperti kurang terurus. Mirip bangunan tua tak berpenghuni. Terakhir kali rumah papanya terlihat kinclong kala keluarga Kevino bertandang untuk acara jodoh-jodohan. Tidak heran dengan kondisi seperti sekarang sang sopir mempertanyakan kepastian tujuan Jameka.
“Iya, yang ini,” balas Jameka lagi-lagi tak ambil pusing dengan kernyitan di dahi sopir yang menandakan bingung sekaligus penasaran.
Jameka meluncur turun, menderap ke depan gerbang, selanjutnya memindai sidik jari, dan secara otomatis pagar itu bergerak terbuka. Menimbulkan derit yang cukup memekakkan telinga. Biasanya memang ada sekuriti yang membukakan, tetapi semuanya diberhentikan kerja untuk berhemat. Jayden menggantinya dengan sistem keamanan berupa perangkat mesin dan komputer. Termasuk sensor mobil pribadi yang bisa secara otomatis membuka gerbang.
Sopir sempat terpukau oleh kecanggihan gerbang usang itu, tetapi segera melakukan pekerjaannya mengendarai taksi melalui jalan berpaving merah pudar menuju pelataran luas.
Ketika tiba di bangunan depan mirip lobi, Jameka memperhatikan kaskade yang air mancurnya dipadamkan. Cat putih yang melapisi bagian luar maupun dalamnya juga sudah banyak yang mengelupas dan ditumbuhi lumut. Beberapa kepala patung-patung bangau putus, juga bagian kakinya. Sejak mengalami pemerosotan pemasukan Heratl, papanya menjual ikan-ikan koi kesayangan yang menjadi penghuni kolam tersebut.
Jadi, kaskade itu kini kosong, tetapi ada beberapa titik genangan air keruh bekas hujan. Ada yang bergerak-gerak di kubangan-kubangan tersebut. Jameka mengira mungkin itu kecebong. Ada juga beberapa daun palem yang jatuh dan terapung. Dilihat dari warnanya yang cokelat terang, Jameka merasa miris. Pasti daun-daun itu sudah lama berada di sana dan tidak ada orang yang membersihkan. Kondisi ini sungguh menguras hati Jameka, tetapi papanya juga bebal tak mau meninggalkan mansion ini dan tinggal bersamanya di kondominium.
“Makasih, Pak,” pungkas Jameka kepada sopir yang membantu menurunkan koper dari bagasi setelah proses pembayaran.
Berhubung sudah tidak ada urusan lagi, kendaraan itu pun melaju keluar. Gerbang depan otomatis tertutup. Di waktu yang sama, Mbak Mar—satu-satunya asisten rumah tangga yang masih dipertahankan bekerja di sini—berlari-lari kecil menuruni undakan menuju Jameka.
“Loh, Non .... Tumben masih siang udah dateng? Kok, bawa koper segala?” tanya wanita itu dengan raut wajah bingung yang tidak dapat disembunyikan.
“Iya, mau nyetok baju di sini sekalian makan siang,” kilah Jameka yang tidak menjawab pertanyaan awal Mbak Mar. “Papa mana, Mbak?”
“Lagi sama Bang Tito di sebelah taman kolam renang, Non.”
Jameka berhenti berjalan, melepas kacamata hitam dan menjadikannya bando sembari menghadap Mbak Mar. “Lagi sama siapa, Mbak?” tanyanya, mengira barang kali salah dengar. Pasalnya belakangan ini Tito kerap kali mengisi pikirannya.
“Bang Tito, Non.”
Jameka praktis ber-cak. Kenapa lagi, sih, kadal sawah satu itu? Bukannya masih di UK? Kenapa udah balik? Mana sama Papa pula! Jameka tidak membutuhkan bertemu dengan Tito sekarang dan mungkin untuk waktu yang lumayan lama. Mendengar nama pria itu disebut Mbak Mar saja sudah membuat jantungnya jumpalitan dan nyeri di dadanya tak bisa dengan mudah ia abaikan. Apalagi harus bertatap muka dengan pria itu. Bisa gila Jameka.
Gelombang dilema melanda Jameka. Sebaiknya apa yang harus ia perbuat? Pura-pura tidak mengenal pria itu dan langsung bertemu papanya atau putar balik haluan? Apabila ia kabur sekarang, itu tidak lucu. Pasti terlihat aneh. Belum lagi taksi tadi juga sudah pergi dan Jameka belum mau mengaktifkan ponsel untuk memesan kendaraan mana pun. Pasti Kevino akan membanjiri notifikasinya. Lagi pula bila ia menunda-nunda niatnya menceritakan ini kepada papanya, pasti rencana selanjutnya juga akan tertunda.
Jameka kembali ber-cak. Tito memang ahli mengacaukan segalanya.
“Sejak kapan Tito di sini?” tanya Jameka yang akhirnya memutuskan untuk menghadapi pria itu dengan gagah berani. Apabila Tito bisa berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara mereka, Jameka juga pasti bisa.
Mbak Mar yang mengambil alih koper Jameka pun menjawab, “Udah dari kemarin, Non. Nginep sini kayak biasanya, kok.”
Sumpah demi apa pun? Sesungguhnya apa yang dipikirkan pria itu? Sudah membuat Jameka kelimpungan soal potensi hamil, setelah pertengkaran mereka di malam itu, sekarang Tito malah menginap di rumah orang tuanya? Kadal sawah satu itu benar-benar edan.
Jameka nyaris menghentakkan kaki mirip bocah ngambek. Dada kembang kempis yang bertolak belakang dengan wajah datarnya mengiringi langkah cepatnya menuju taman kolam renang samping. Ia menemukan papanya bersama Tito sedang mengobrol. Tito berjongkok sambil mengaduk-aduk tanah menggunakan sekrup kecil. Sedangkan Papanya duduk di kursi lipat yang biasanya digunakan untuk memancing, sedang memperhatikan Tito. Posisi mereka bersebelahan dan sama-sama membelakangi Jameka. Bangunan samping memayungi mereka dari cahaya matahari sehingga teduh. Keduanya memang akrab dari dulu. Dan Tito memang supel dengan siapa pun.
“Lumayan, kan, Om. Bisa nanem tomat kayak gini buat sambel. Besok kita nanem cabe, ya?” ajak Tito.
Allecio mengangguk-angguk seraya menggosok dagu, puas melihat hasil kinerja Tito. “Lumayan banget ini. Bisa berhemat. Mau bikin sambel tinggal metik doang kalau udah tumbuh. Ayoklah kita tanem cabe besok.”
“Kalau nanem cabe harus pakai sarung tangan. Biar tangan kita nggak pedes, Om.”
“Asal jangan pedes kayak omongan Jameka sama Jayden, To. Hahaha!"
“Yoi, Om! Hahaha!”
Langkah Jameka berhenti dengan mulut menganga mendengar obrolan mereka. Oh! Jadi seperti ini obrolan mereka saat di belakangnya?
“Apa-apaan ini?”
Baik Tito maupun Allecio kompak menghentikan tawa guna menghadap belakang, ke sumber suara wanita yang amat mereka kenal. Reaksi kaget mereka serupa. Hanya sedikit, tidak berlebih meski mendapati Jameka bertolak pinggang. Mereka bahkan bertingkah biasa saja seakan-akan tidak baru saja membicarakan Jameka dan Jayden.
“Eh, ada Yang Mulai Ratu,” gumam Tito sambil meringis.
Tuh, kan, kadal sawah ini malah cengar-cengir! Dasar grandong! Jameka sebal sekali.
Allecio bertanya pada Jameka. “Jame? Kok, ke sini?” Matanya menyipit lantaran posisi Jameka yang menantang matahari.
Bukannya menjawab papanya, Jameka malah mengomel, “Jadi gini obrolan Papa sama Tito di belakangku?”
Tito pura-pura mengaduk-aduk tanah lalu merapikan tanaman sambil bersiul. Sedangkan Allecio mengikuti Tito nyengir kuda.
“Baru kali ini doang, Jame,” jawab papanya.
“Kok, aku nggak yakin, ya, Pa?”
“Keyakinan itu urusan masing-masing, Yang Mulia Ratu,” sambar Tito. “Perasaan gue udah pernah bilang.”
“Diem lo kadal sawah!”
“Punya mulut masa kagak boleh ngomong? Selama ngomong nggak bayar gue bakal ngomong.”
“Gue tanya Papa, bukan lo, ya, Kadal!”
“Gue jubir Om Alle.” Tito mencari bala bantuan. “Iya, kan, Om?”
Jameka makin geram. “Sejak kapan?”
“Sejak zaman purba. Masa lo baru tahu? Cupu.”
“Tito Alvarez! Gue geplak pala lo, ya!” Jameka sudah mengangkat tangannya, tetapi buru-buru dicegah papanya.
“Jameka. Udah .... Kalian ini dari dulu masih aja suka adu mulut,” komentar Allecio yang heran melihat Jameka selalu marah-marah kepada Tito. Dan Tito selalu suka menyulut emosi Jameka. Seperti belum puas bila Jameka belum marah kepadanya. Anehnya, mereka selalu bersama-sama sejak dulu. Tak peduli seberapa marahnya Jameka kepada Tito. Menurut Allecio itulah yang dinamakan sahabat sejati; mereka sudah tahu seluk beluk masing-masing.
Namun, yang sampai saat ini tak diketahui Allecio ialah keluarga Tito. Ia hanya tahu Tito temannya Jayden—yang otomatis juga berteman dengan Jameka—sejak hampir sepuluh tahun lalu. Tidak lebih. Tidak tahu asal usul atau latar belakang keluarga Tito. Sebab sejak dulu hingga sekarang Tito tak pernah membahasnya sama sekali. Allecio juga tak berani bertanya. Meski demikian, ia tahu walau badan pria itu penuh tato dengan tampilan mirip preman, Tito pria yang menyenangkan. Tidak segahar kelihatannya.
Tito sering menginap di sini, bahkan menganggap mansion ini sebagai rumah. Tito tanpa sungkan mengambil makanan atau minuman yang ada di meja makan atau kulkas. Kadang-kadang mencomot sepotong tempe goreng yang baru saja diletakkan Mbak Mar di meja makan. Tidurnya pun di sembarang tempat mirip kucing. Kadang di sofa depan TV, kadang di gazebo sebelah kolam renang, kadang juga di kamar tamu. Tak jarang juga Tito bertingkah seperti teman seusia Allecio, mengimbangi obrolan Allecio, tanpa peduli jarak umur mereka layaknya anak dan orang tua.
Allecio selalu menyadari, Tito selama ini tahu tempat dan posisi. Pria itu apa adanya, tetapi masih memiliki batasan. Mengenal Tito bertahun-tahun menjadikan Allecio menganggap Tito sebagai anaknya sendiri. Begitu pula dengan Lih Gashani. Terutama ketika anak-anak Allecio tak sedang berkunjung lantaran sibuk dengan urusan masing-masing. Allecio terkadang suka menelepon Tito atau Lih untuk ditemani bermain catur, memancing di laut, atau sekadar mengobrol sambil minum kopi dan merokok. Dengan catatan mereka juga tidak sibuk. Seperti kemarin. Ketika ia menelepon Jameka dan mendapati ponsel putrinya mati, Allecio tak ambil pusing dan segera menelepon Tito yang kebetulan baru tiba di Jakarta dijemput Lih. Jadi, keduanya kemari, tetapi Lih tidak ikut menginap.
“Kagak bisa lihat gue sama Om Alle lagi nanem tomat? Siapa tahu lo mau gantung diri di sini. Udah gue siapin, nih. Talinya modal sendiri, ya,” sambar Tito sembari menunjuk-nunjuk tanaman yang baru saja ditanamnya. Nadanya kali ini sinis betul. Lagi pula, apa yang ada di pikiran Jameka sampai pergi ke New York selama seminggu? Sudah begitu ponselnya dimatikan. Apakah jangan-jangan wanita itu sudah tahu kebusukan Kevino sehingga bergalau ria di sana? Ataukah Jameka memutuskan kembali bersama River lantaran sadar kalau Kevino lebih bejat?
Beberapa waktu lalu Carissa menelepon Tito dan menceritakan semuanya tentang Kevino.
Asyik-asyik berpikir dengan cara apa ia harus menyerobot secara ugal-ugalan hubungan percintaan antara Jameka dengan River ataupun Kevino, sambil menepuk-nepuk tanah, Tito kaget sekali saat mendapat serangan pukulan di punggungnya dari Jameka.
“Kurang ajar! Dasar grandong! Gue gebukin lo sampai bonyok! Berani-beraninya lo nyuruh gue bundir! Kadal sawah kagak tahu diri! Lo aja sono yang bundir! Sini gue bantuin!” Jameka menarik-narik kaus Tito dari belakang sampai nyaris tercekik. Selain itu Jameka juga mencakar lengan-lengan dan menjambak-jambak Tito.
“Woi! Lo mau bunuh gue? Jameka! Lepasin! Gue kecekik! Hoi!”
Allecio yang syok lekas-lekas menarik-narik tangan putrinya. “Jameka .... Udah .... Udah .... Mbak Mar .... Tolong, Mbak ....”
•••
Allecio mendudukkan Jameka dan Tito di gazebo. Ia berdiri di depan mereka sambil bersidekap, memperhatikan keduanya secara bergantian. Mulai dari Tito yang rambutnya acak-acakan, telah melepas kaus untuk mengusap-usap lengan penuh goresan bekas cakaran Jameka seraya melirik wanita itu dengan tatapan kesal. Kemudian Allecio memperhatikan Jameka. Putrinya melihat kuku-kukunya dengan gaya anggun, dengan kaki disilangkan, sesekali juga menyugar rambut.
“Kalian ini, kan, bukan anak kecil lagi. Kenapa masih berantem?” tanya Allecio tak habis pikir. “Terutama kamu, Jameka.”
“Loh, kok, aku? Dia yang mulai. Jangan salahin aku, dong, Pa,” jawab Jameka tanpa memindah tatapan ke kuku-kukunya. Ia agak menyesal karena cat merahnya banyak yang mengelupas. Mungkin ia akan menggantinya dengan cat kuku warna lain nanti.
Tito jelas tersinggung. “Lo sendiri yang mulai.”
“Lo yang mulai!”
“Lo!”
“Stop! Berhenti! Kalian ini! Jameka, minta maaf ke Tito,” titah Allecio.
Jameka memelotot. “Ogah banget, Pa. Kenapa jadi aku yang minta maaf? Dia yang harusnya minta maaf ke aku!”
“Lo ngerasa nggak ada salah sama gue gitu? Harusnya, kan, lo yang minta maaf. Rambut gue rontok, lengan gue perih semua, nih,” cerocos Tito gemas, lalu melempar kausnya ke muka Jameka.
Jameka praktis berjingkat. “Ih! Bau banget kaus lo! Hoek! Jijik!” Jameka melempar kaus itu entah ke mana.
Tito malah tertawa kencang. “Itu namanya bau ketampanan,” komentarnya riang. “Awas, itu mengandung mantra pemikat. Bisa-bisa lo klepek-klepek sama gue. Hati-hati, bau keringet gue bikin lo ketagihan.”
“Iyuh! Najis!”
“Tuh, kan, mulai klepek-klepek.”
“Gue jijik, bukan klepek-klepek!”
“Masa, sih? Kok, muka lo merah gitu? Salting, ya?”
“Muka gue marah karena marah! Masih kurang jelaskah?”
Tito malah mendekati wajah Jameka sambil memelotot. “Mana, sih? Kok, gue ngelihatnya beda?”
Jameka spontan menjauh. “Tito Alvarez!” bentaknya.
“Apa Yang Mulia Ratu Jameka Michelle?” goda Tito dengan nada manja-manja. Masih dengan diselingi tawa. Ia bahkan menaik-turunkan kedua alisnya.
Dari raut marah dan jijik, Jameka jadi ngeri. “Pa, lihat, deh. Tito kesurupan! Hiii!” Jameka mengusap-usap kedua lengan dan menggeser duduknya menjauhi Tito.
Dengan kurang ajarnya, Tito menimpali, “Kesurupan lo, ya, Jameka?”
Amarah Jameka tersungut lagi. “Lo pikir gue kuntilanak?”
“Bukan gue yang ngomong, loh.” Tito angkat tangan dan meminta bala bantuan. “Om, bukan aku, kan? Tapi kalau boleh nambahin, lo kayak kuntilanak merah, Jame.”
“Tito!” Jameka ngamuk dan menghadiahi Tito dengan cakaran lagi.
Sementara itu, Allecio yang bertambah pusing pun berujar, “Udahlah. Kalian urus sendiri aja urusan kalian. Makan siang lebih enak daripada ngurus tingkah bocah kayak kalian.”
“Pa, ikut ....” Jameka berhenti menjambaki rambut Tito untuk menyusul papanya.
Tito mengikuti Jameka. “Aku juga laper. Ngomong sama mbak kunti emang bikin laper.”
Sumpah demi perdamaian dunia! Gggrrr! Jameka berhenti dan menghadap Tito yang berjalan di belakangnya. “Mau lo apa, sih, To? Lo, tuh, kayak beda orang, tahu, nggak?”
Tito bingung dan membiarkan Allecio masuk dulu. “Beda orang gimana?”
“Terakhir kita teleponan, lo bilang kangen gue. Sekarang lo ngatain gue kuntilanak merah. Mau lo apa, sih, To? Gue nggak ngerti kenapa lo suka banget bikin gue darah tinggi,” terang Jameka putus asa.
“Masa gitu aja nggak tahu? Harus banget dikasih tahu?”
“Anggep aja gue oon. Makanya harus lo kasih tahu.”
Lalu dengan tampang serius, dengan rambut acak-acakan dan bertelanjang dada, Tito Alvarez menukas, “Gue suka lo, Jameka Michelle. Bisa nggak lo nggak usah sama siapa-siapa? Sama gue aja?”

____________________________________________________
Thanks for reading this chapter
Thanks juga yang udah vote, komen atau benerin typo-typo
Kelen luar biasa
And it’s a lot to me
Bonus foto Jameka Michelle

Tito Alvarez

Well, see you next chapter teman-temin
With Love
©®Chacha Prima
👻👻👻
Selasa, 2 Januari 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro