21. Kakak
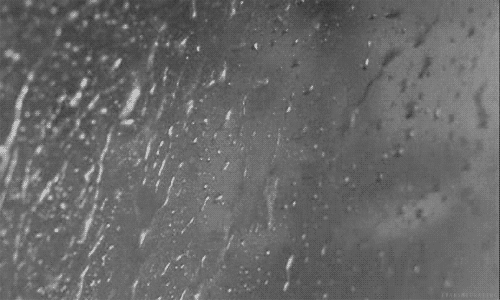
Seketika Joan melompat untuk menawarkan bantuan, Orlen tahu bahwa petaka lebih besar akan datang, mengalahkan gemuruh pelan badai di luar penginapan.
Ini tidak seharusnya terjadi.
Tapi, tidak, Orlen membutuhkan itu. Ia membutuhkan pertolongan. Ia sudah muak dengan kegilaan di penginapan terkutuk ini. Orlen tahu ia tidak bisa lepas dari jerat yang membuatnya selalu terbayang-bayang malaikat kematian, tetapi tak ada salahnya mencoba.
Selagi malaikat kematian masih berdiam tanpa gerak, maka itu berarti Orlen bisa melakukan apa pun—
"Kau sudah selesai?" suara Vanya memantul keras pada dinding-dinding kamar Orlen. Orlen menatapnya dengan heran. Apa? Apa yang sudah selesai? Perutnya mendadak mulas.
"Bawa ia ke atap." Jantung Orlen serasa melesak ke perut saat mendengar Vanya berkata lagi. "Takkan ada yang ke sana karena hujan masih cukup deras. Mari kita selesaikan ini dengan cepat."
"Apa maksudmu?" Orlen tak bisa menahan suaranya lagi. Ia menatap Vanya dengan pasi.
Namun Vanya hanya menatap nyaris tanpa ekspresi. "Orlen." Kelembutan suara Vanya membuatnya merinding. "Nollan membunuh Joan."
Orlen refleks tertawa sumbang. Ia nyaris saja menegur Vanya, memintanya agar tidak bercanda di saat seperti ini, tetapi ketenangan di wajah gadis berkacamata itu membuat tawa Orlen reda.
Matanya berkaca-kaca. "Kau kejam."
"Nollan yang melakukannya. Lagi pula kau semestinya tahu risiko jika ada orang asing yang mengetahui ini." Vanya mengangkat bahu. "Sekarang, apa kau akan berdiam di sini? Pergilah ke sana."
Saat Orlen tak bergerak selain gemetaran di tempatnya, Vanya mendesah.
"Aku memberimu kesempatan," bisiknya pelan. "Lakukan apa yang kau mampu dan barangkali kau bisa menyelamatkan semua orang yang tersisa."
Termasuk Batara. Kesadaran itu menyerang hati Orlen hingga nyeri menyengat. Kakaknya. Jika Orlen gagal mengikuti perintah Vanya, maka Batara juga tidak akan selamat.
Tapi, pada akhirnya, Orlen tak bisa melakukan ini lagi. Kematian Xiran adalah pemicu pertamanya. Kemudian Erika. Lalu Joan, pria yang hanya berniat menolongnya.
Apakah itu setimpal dengan keselamatan satu orang saja?
Dan, di atas itu semua, memberi kesempatan? Apa Vanya kira dirinya adalah seorang dewa? Orlen ingin sekali meneriakinya, berkata bahwa ia bukanlah boneka yang bisa disuruh-suruh lagi. Ia tak mau terlibat pembunuhan lebih banyak. Ia akan melakukan apa pun itu agar tidak ada mayat bergelimpangan, dan menemukan cara lain untuk menyelamatkan Batara—
Orlen berlari.
Ia meninggalkan Vanya, memacu langkah menuju atap, mencari sisa-sisa harapan yang diumpankan padanya. Saat melewati dapur yang temaram, Orlen menyambar senter dan pisau tanpa pikir panjang.
Jarinya gemetar dan Orlen mencengkeram erat-erat gagang pisau. Keringat hangat merembes dari kulit telapak. Tangannya kini yang berguncang pelan, dan Orlen merutuki diri sendiri.
Tidak ada kesempatan lain. Ia harus melakukan ini—sekarang atau tidak sama sekali. Ia memikirkan abangnya Batara di suatu tempat yang jauh, kemudian Xiran yang ... astaga, hatinya berdenyut nyeri sekarang.
Dan, Joan! Padahal aktor itu cuma ingin membantu. Saat Joan menghampirinya, Orlen tahu bahwa Joan tak berniat ikut menuduh. Hanya ia. Setelah kematian Xiran, serta situasi kacau orang-orang yang semula Orlen kira mampu percayai, hanya Joan yang menjadi secercah cahaya bagi Orlen.
Lalu cahaya itu dipadamkan.
Setibanya di atap, Orlen tak melihat ada siapa-siapa. Terkutuklah kegelapan total yang menyengat bulu kuduknya bagai pelukan malaikat maut. Saat Orlen menyorot pepohonan raksasa di sekeliling penginapan, ia merasa begitu kecil dan tertekan. Seolah ada yang lebih hebat daripada segala kegilaan ini.
Orlen menurunkan senter lagi, menembus derasnya hujan yang berhamburan di lantai atap, tetapi ia masih tak menemukan apa pun. Tak ada jejak kejahatan maupun aroma kematian.
Apa ia terlambat? Hujan bisa menghapus bukti dengan cepat.
Namun, belum sempat berbalik, Orlen akhirnya mendapati bayang-bayang bergerak dari arah pintu tangga. Orlen mengarahkan senter.
Nollan. Pemuda itu mengernyit ketika silau senter memantul pada kedua matanya. Ia menaikkan tangan di atas alis. Wajahnya pucat dan pakaiannya mulai bebercak hujan. Di belakangnya, Vanya mengekor dalam diam.
"Di mana Joan?" Orlen tak bisa menyembunyikan histeria. "Kau apakan ia?"
"Kenapa memedulikan yang sudah tiada?" suara Nollan lebih lesu daripada ekspektasi. Orlen kira pemuda itu bakal marah atau semacamnya, sebab Orlen benar-benar mengacungkan pisau. Jelas sudah. Ia mengibarkan bendera perang sementara kematian ranum dipetik satu per satu di penginapan terpencil itu.
"Sekarang mau apa kau, Orlen?" tanya Nollan lagi. "Memperparah situasi?"
Orlen melihat Vanya seperti berbisik sesuatu dari balik punggung Nollan. Sang pemuda menelengkan kepalanya sedikit, mengernyit, lantas membuang napas samar.
Ubun-ubun Orlen memanas melihatnya. "Kau tahu kau seharusnya tidak ikut campur lebih jauh, Nollan," pekiknya. "Kau membuat segala hal menjadi lebih runyam!"
Sekarang atau tidak sama sekali.
Dengan seruan itu, Orlen merangsek. Nollan menatapnya dengan ekspresi keras. Tangannya mengepal. Ketika gadis itu tiba di hadapannya, ia berputar. Orlen terkesiap ketika kakinya terpeleset lantai atap yang licin.
Segalanya terjadi begitu cepat. Nollan menyentak tangannya dan memiting dengan kencang.
Selang tak lama kemudian, jeritan pecah memenuhi langit.
* * *
Rave bersandar pada punggung sofa dengan lemas. Matanya menerawang ke arah jendela di belakang sofa yang diduduki Nan, sementara jarinya memainkan kancing pemberian mendiang Erika. Badai memang mulai mereda, tetapi hujan masih mengguyur, suara ketukannya pada jendela terpantul pada dinding-dinding ruang duduk. Kegelapannya tak lagi tertolong.
Seperti hubungan keluarganya dengan Kasha. Tak tertolong. Berhari-hari lalu, ia masih punya harapan. Ia ingat saat ia dan Kasha sarapan bersama untuk terakhir kali. Rave bilang akan liburan bersama Nan. Kasha tidak menjawab, seperti biasa, kecuali kernyitan samar di kening. Bertahun-tahun lalu, Kasha akan merespons dengan cemoohan, berkata bahwa anak kesayangan Dad dan Mom bebas melakukan apa saja.
Namun, Rave masih mencoba. Sebelum berangkat, ia memenuhi isi kulkas dengan sayur mayur dan daging segar. Ia juga menyapu dan mengepel rumah, yang membuat Nan sempat protes karena merasa Rave terlalu berlebihan. Apa pun itu agar bisa meringankan perasaan Kasha saat Rave pergi. Agar tak ada cemoohan lagi, walau hanya tersebut di dalam hati.
Jarinya masih memainkan kancing, tetapi kali ini dengan remasan lembut. Tepi bulat kancing menekan telapak tangannya.
Ia semula berencana membeli beberapa oleh-oleh untuk Kasha, tetapi dengan situasi ini, apakah sekadar cerita pembunuhan bisa membuat kakaknya terhibur?
Mungkin? Itu pun kalau dia bisa keluar dari ancaman kematian, baik dari entah-siapa-itu maupun badai. Rasanya ia seperti terperangkap di gua penuh jaring laba-laba. Gelap. Berperangkap. Traumatis.
"Kau tidak sedang memikirkan rencana bodoh, kan?"
Rave tersentak saat Nan tahu-tahu mencondongkan tubuh di depannya, merentangkan tangan dan bersandar pada punggung sofa. Pandangan Rave kian gelap dan terbatas, hanya beraroma tubuh Nan dan wajah sang gadis yang samar. Namun, dalam keremangan ini, Rave masih mampu mengenal jelas kilat emosi di kedua mata pirus kekasihnya.
"Apa maksudmu?" suara Rave lebih tercekat daripada dugaannya.
Nan meremas tangan Rave yang memainkan kancing. "Kau berpikir untuk melakukan rencana bodoh."
Rave menelan ludah. Ia tidak merencanakan apa pun. Sungguh. Ia hanya memikirkan kakaknya, tetapi jika Nan tahu, gadis itu akan marah. Bagaimana bisa kau selalu memikirkan orang lain di saat seperti ini, ketika bisa saja nyawamu yang akan terenggut selanjutnya?
"Bagaimana ... bagaimana bisa kau menduga begitu?"
"Karena kau melamun, Rave. Aku terus-menerus memerhatikanmu tetapi matamu sama sekali tidak beranjak dari jendela."
Rave mendesah. Apa mereka akan berdebat lagi? Ia memilih untuk diam saja, dan mengedarkan pandangan untuk mengecek situasi. Ia menangkap sosok Adriana mendekat. Ekspresinya kaku, tetapi menyimpan sejumlah keraguan.
"Adriana," sapa Rave, cukup lega karena ada pengalih perhatian. "Di mana yang lain?"
"Aku tidak melihat Orlen," jawab Adriana dengan dahi berkerut. "Dan ... yang lain juga."
Rave dan Nan spontan bertukar tatap. Tanpa mengatakan apa pun, mereka sudah mengerti arti dari tatapan penuh isyarat itu. Sama sekali tak ada kata-kata walau sekadar bisikan. Mereka telah lama terbiasa seperti ini, apalagi ketika ada orang asing di dekat mereka.
Kebiasaan lama mereka di dunia bawah tanah telah menumbuhkan kebiasaan baru.
"Kita mesti mencari mereka." Rave beranjak, sementara Nan merogoh saku. Rave yakin gadis itu sedang memastikan posisi pisau lipatnya. "Kita tidak bisa berpencar lagi di saat seperti ini."
Mereka meninggalkan ruang duduk menuju lorong. Rave menyalakan senter yang ia bawa, berharap bahwa tenaga baterainya takkan habis. Segala ketakutan mendadak menyerbu, tetapi Rave kembali berpijak pada kenyataan. Jari-jari kakinya menapak kuat, merasakan dinginnya hawa yang terekam pada tiap inci lantai. Kemudian, saat tangannya menyentuh dinding untuk memantapkan diri, ia merasakan getaran pelan.
Langkahnya melambat.
"Ada apa?" bisik Nan di belakangnya. Gadis itu membersamai Adrian.
"Kau dengar sesuatu?" tanya Rave, berusaha mempertajam pendengaran di antara ketukan hujan pada jendela-jendela sepanjang lorong.
Nan ikut menekan tangan pada dinding. Rave yakin Nan paham bahwa mengandalkan pendengaran akan menyia-nyiakan waktu. Adriana sendiri mempertanyakan tindakan mereka, tetapi Rave terlanjur tenggelam pada upaya.
Kemudian terdengar suara benturan pelan, konstan, dan secercah erangan.
"Ada ruangan apa di depan?" bisik Nan.
"Toilet pria." Rave tanpa sadar membuang napas berat. Ia mempercepat langkah dan berusaha membuka pintu toilet. Namun pintunya bergeming. Rave melongok dan menyorot senter, memastikan tak ada kunci terpasang, tetapi mendapati bahwa ada selongsong besi yang mengganjal.
"Sial," geramnya. "Hei!" Ia menggedor pintu. "Siapa di dalam?"
"Rave?" Ia mendengar suara tak asing. Joan! "Rave! Bukakan pintunya untukku! Aku nyaris mati!"
Rave menyerahkan senter kepada Nan yang terkesiap. Di belakangnya, Adrian merapatkan diri. Sementara itu Rave memasang kuda-kuda.
"Mundur, Joan!"
Baiklah, ia pernah mendobrak pintu yang dikunci oleh selongsong besi. Tak masalah. Ia tahu caranya, meski agak menyakitkan bahu—
Rave mendobrak dan dinding di sekitar mereka bergetar keras. Debuman pintu menggaung di seluruh penjuru lorong, terpantul pada ruang duduk, dan meredam pantulan hujan. Suara besi terpental pada dinding menyusul.
Rave masuk, diikuti Nan dan Adrian. Sorot cahaya senter Nan mencari-cari sosok Joan hingga menemukannya di sudut samping pintu.
"Oh, sial—syukurlah." Joan mendesis. "Kupikir aku akan selamanya terperangkap di sini."
"Apa yang terjadi?"
Joan menatap Rave lekat-lekat dengan emosi membara. "Dengarkan aku," ujarnya. "Vanya adalah pelakunya."
Alis Rave berkedut, sementara Nan menghela napas dengan tajam di belakang punggungnya. Seolah-olah mengatakan, "Nah?" yang begitu tajam dan menyesakkan.
Rave menarik napas dalam-dalam. "Apa buktinya?"
Joan lantas bercerita. Ia menceritakan apa yang disaksikannya sejak beberapa saat lalu—ketika ia menyadari bahwa kecurigaan tak semestinya terletak pada Orlen. Kemudian upayanya menyusup di kamar sang gadis, hingga Vanya muncul.
Rave menelan ludah. Ia merasakan keberadaan kancing pemberian mendiang Erika yang kini berada di dalam saku celana jinsnya.
Joan menepuk pundak Rave dan meremasnya. "Kau harus—"
Jeritan melengking memecah kesunyian. Mereka spontan mendongak, ke arah asal suara yang begitu keras dan menyayat hati.
Jantung Rave berdentam-dentam kencang.
"Itu suara Orlen," bisiknya.
Ia pun melesat keluar toilet.
"Rave!" Nan berteriak. "Tunggu!"
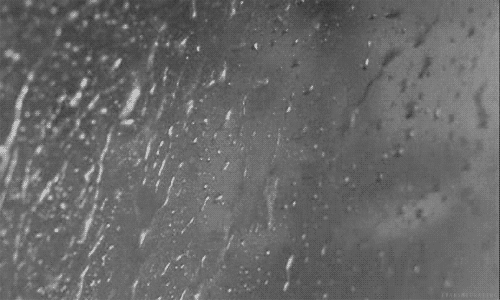
Part ini ditulis oleh andywylan dalam sudut pandang karakter Raven Danvers
____________________________
Raven Danvers

Umur: 21tahun
Profesi: Mahasiswa, mantan kriminal
____________________________
Di dalam rumah penginapan yang dilingkupi badai dan kematian ini, siapakah yang akan bertahan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro