⁕ Mimpi yang Terjual dan Buruh Pabrik ⁕
CW: bahasa vulgar, mohon dibaca dengan bijak, ya!
+ + +
Manisah merasakan lekat bau besi berkarat dan minyak mesin yang terjebak di udara. Begitulah kesehariannya tinggal di gubuk yang berimpitan dengan pagar besi pabrik. Sudah berisik, tercecap pula di lidahnya sekejap bangun tidur. Di antara derak alat-alat berat yang tak pernah berhenti berdengung, suara lembut tapi asing menyelinap ke telinganya.
"Anisa, masa bisa lelap tho tidurmu dengar suara mesin keras-keras? Aku ndak bisa. Mereka belum bayar upahku, Anisa." Lagi-lagi hal yang sama mengusiknya. Manisah sebal kenapa suara asing itu kerap memanggilnya dengan nama lain, dengan penekanan pada huruf n. Namun, ia juga merasa kasihan. Tampaknya ini suara memedi yang sebelumnya menghuni gubuk Manisah dan suaminya. Mungkin Anisa juga nama mendiang istri pemilik suara itu. Konon, kata suaminya, pemilik gubuk sebelum ini memang meninggal dengan mengenaskan karena kecelakaan kerja.
Namun, masa Manisah yang harus dihantui! Harusnya, ya, mesin-mesin yang menggiling dia saja! Atau, minimal mandornya!
Manisah menggerutu dalam tidur. Biasanya cukup dengan diusir, suara asing tersebut bakal hilang, dan ganti terdengar dengkur suaminya. Namun, suara asing itu kali ini tetap bertahan. Tiap penekanan huruf n pada nama ngawurnya semakin jelas dan Manisah bisa merasakan kesedihan si memedi.
"Ayo, tho, Anisa. Hidupku ndak bisa tenang. Cuma kamu yang bisa."
"Janji, ndak bakal neror aku di mimpi lagi?" Manisah menjawab dengan gusar dalam tidurnya, menatap ke arah sosok berkabut hitam yang melayang-layang di benak. Ia tidak bisa melihat wajah orang itu. Mungkin memang benar, dia roh penghuni lama gubuk yang belum pernah Manisah temui. Biasanya, ia bermimpi soal suaminya yang gemar minum, tetangganya yang suka teriak-teriak tengah malam, atau buruh-buruh pabrik yang tidak pernah pulang lagi.
Suara asing itu menjawab dengan sendu. "Janji, Anisa."
"Namaku Manisah!"
"Tetap Anisa bagi saya," balas si suara asing dengan kukuh. Ia menghilang setelahnya, begitu saja, tetapi Manisah justru terbangun dari tidur. Alih-alih suara asing, terdengar dengkur suaminya yang riuh. Saat Manisah bergerak, Pijo—nama suaminya—refleks meraih tangan Manisah dan meremasnya kuat.
"Jangan pergi, Maniii!"
Manisah terkikik geli. Suaminya lucu sekali kalau sedang mengigau. Makin menggemaskan di matanya sebab Pijo sangat manja pada sang istri. Tidak ada hari tanpa mereka bercinta, dan Pijo panik kalau Manisah pergi tanpa kabar, padahal cuma mau beli sayur di gerbang pabrik saat sore, tempat pedagang-pedagang mangkal di jam pulang kerja staf-staf kantor pabrik.
Meski begitu, Manisah juga jengkel karena Pijo selalu memanggilnya Mani. Sudah beberapa kali Manisah mencoba membicarakannya kepada Pijo, seperti dua jam kemudian, setelah Pijo bangun dan mereka sedang sarapan.
Jawaban sang suami selalu sama. "Lha, memang kenapa? Itu kan juga nama kamu!"
"Ndak enak kalau didengerin, Mas! Mani kayak barang intim aja," kata Manisah sambil bersemu.
Pijo menyeringai, memamerkan sederet gigi kuning beraroma tembakau campur miras. "Ya gak apa-apa, tho! Tanpa air mani juga kita gak bisa jadi manusia. Itu tuh cikal-bakal kehidupan! Udah dikasih Tuhan kok malu diakui. Kamu harusnya bangga. Tanpa kamu, kita gak bisa punya anak. Tanpa air mani, manusia gak bakal ada!"
Manisah hanya bisa senyum-senyum getir dan malu. Benar juga apa kata Pijo. Kadang-kadang dia kagum dengan kemampuan Pijo membuat hal-hal memalukan terdengar keren. Meski suaminya itu suka mabuk dan menjambak saat di ranjang, setidaknya Pijo itu pintar. Mungkin itulah kenapa Manisah muda bisa menikahinya.
Sayang, Manisah tidak ingat, sebab kenangan-kenangan lama habis dijual. Kata Pijo, mereka sempat terlilit utang, sehingga Manisah terpaksa menjual kenangan-kenangan lama. Lagi pula, apa yang bisa diingat dari kenangan kala menjadi gelandangan? Ia sudah berbahagia dengan seorang suami dan punya tempat tinggal. Tak perlu ia mengingat-ingat masa saat melajang dan melarat.
Pijo adalah suami yang sangat baik bagi Manisah, dan bagi tetangga-tetangganya. Pijo dan rekan-rekan yayasan sosial menyelamatkan mereka dari status gelandangan dan memberi mereka rumah, walau sekadar gubuk-gubuk di belakang pabrik besar itu.
Hanya Manisah yang beruntung untuk dinikahi Pijo, sebab Pijo satu-satunya yang tidak menjadi buruh pabrik seperti para lelaki gelandangan—alias suami-suami dari para wanita tetangga. Pasalnya, seiring waktu, Manisah selalu mendapat kabar duka dari wanita-wanita malang itu. Suaminya meninggal karena kelelahan bekerja, atau karena tergiling mesin, atau karena jatuh ke kolam minyak panas. Mau bagaimana lagi, gelandangan yang dadakan jadi buruh itu kurang paham soal keamanan.
Namun, Pijo dan rekan-rekan yayasan sosial selalu hadir. Kadang-kadang, Pijo tidak tidur di gubuk Manisah karena harus menenangkan wanita-wanita yang menjerit tiap tengah malam. Hanya dengan Pijo dan rekan-rekannya, tangisan pilu itu berubah jadi kesenyapan dan tawa-tawa puas para pria yayasan. Mungkin mereka senang dan lega karena bisa membantu menenangkan para wanita tetangga.
Sayangnya, Manisah juga iba kepada ibu-ibu itu. Hampir semua baru ketahuan hamil setelah suaminya meninggal. Entah kutukan atau berkah macam apa ini. Ia malah tidak kunjung hamil. Pijo pernah bilang, salah satu alasan lain kenapa ia dipanggil Mani adalah doa Pijo agar Manisah bisa segera hamil, karena saking seringnya menampung air mani Pijo. Bukankah nama adalah doa?
+ + +
Ketika Pijo pergi menemui rekan-rekan yayasan sosial, Manisah kembali digusarkan oleh mimpi tadi pagi. Ia tidak berani cerita kepada Pijo, khawatir kalau suaminya bakal ambil alih peran Manisah untuk mengunjungi pabrik. Ia tidak mau kehilangan suami seperti wanita-wanita tetangga. Maka, ia sampaikan kegundahan itu pada Nik yang hamil delapan bulan, janda yang tinggal di sebelah gubuk.
"Sinting kamu, Nduk," kata Nik dengan tajam, meski tatapannya kosong. Jarinya menggaruk-garuk perutnya yang sudah besar, seolah-olah janinnya adalah gatal yang mengganggu. "Kalo kamu nekat ke pabrik, kamu nanti bisa mati kecemplung minyak panas. Biar Pijo aja. Dia lebih pantes ke pabrik."
Manisah marah. Ia mengira Nik ingin menyeretnya ke nasib yang sama biar semua jadi janda sekalian. Karena kesal, Manisah memutuskan untuk menyelinap ke pabrik saja saat sore.
Namun, setelah mencoba mempersiapkan diri, Manisah sadar dirinya butuh seragam dan identitas. Ia juga tak bisa meminta tolong kepada janda-janda lain, sebab mereka sudah menjual kenangan-kenangan akan para mendiang suami.
Satu-satunya cara adalah dengan membeli kembali kenangan Manisah yang ia jual. Walau hanya tamatan sekolah dasar, Manisah mampu menebak kalau kemungkinan memedi di mimpinya berhubungan dengan dirinya. Biasanya, memedi minta tolong pada orang yang dianggap mampu membantu, kan?
Mungkin, Manisah mengenal Anisa yang disebut-sebut si memedi. Barangkali Anisa, yang kemungkinan adalah mendiang istri si memedi, adalah sahabatnya di masa lampau. Manisah berpikir begitu karena tiap kali si memedi memanggilnya Anisa, ia bisa merasakan denyut kerinduan yang tak bisa digapai lagi. Kerinduan yang dipisahkan oleh kematian.
Dengan membeli kembali kenangan, Manisah dihadapkan risiko untuk mengingat perihnya ditinggal sahabat. Namun, ia akan melakukannya. Perih ditinggal sahabat tidak seberapa daripada kemungkinan ditinggal mati seorang suami.
Setelah meminjam beberapa lembar simpanan Pijo, Manisah bergegas menuju toko kaset. Sengaja ia mencari yang agak jauh biar tidak ketahuan Pijo. Butuh naik becak satu jam menuju kecamatan orang-orang kaya, melewati sawah-sawah dengan air bau limbah, hingga berganti gedung-gedung menjulang dan baliho-baliho yang menjanjikan kota nyaman tanpa gelandangan.
Manisah berharap beberapa lembar biru yang dibawanya cukup untuk menyewa secuplik kenangan yang paling penting. Atau beberapa cuplik juga lebih bagus. Konon toko kaset yang dikunjunginya ini menyewakan kenangan dengan harga murah, walau entah efek sampingnya apa.
Sesampainya di toko kaset dan menyebutkan ciri-ciri kenangan yang diinginkan, si pemilik toko menuding ke sudut rak bertulis 'BEST SELLER' dan 'DEWASA', bukan jenis seri yang disangka-sangka Manisah. Kenangan macam apa yang ia miliki sampai digemari para orang dewasa? Ia sempat curiga, apakah dirinya dahulu gelandangan yang dijamah para lelaki brengsek sebelum diselamatkan Pijo? Ia merinding membayangkan kenangannya jadi tontonan orang-orang kaya dengan otak geser.
Dengan kaset kenangan di tangan, langkah Manisah kian memberat saat menghampiri bilik menonton. Ia tarik tirai menutup, menenggelamkan diri pada sofa dengan kulit pecah-pecah, dan mulai menyetel.
Rasanya aneh menonton kenangan milik sendiri macam film di bioskop. Namun begitulah bagaimana dunia ini bekerja. Segala hal dijual oleh rakyat miskin kepada orang-orang kaya, mendulang berbagai nafsu mereka demi kelangsungan hidup.
Hal pertama yang Manisah tonton sesuai dugaannya. Ia pernah menjadi seorang gelandangan. Ia tidak heran soal ini, sebab masih ada ingatan samar-samar soal itu. Rupanya ia dan para janda adalah gelandangan, berikut suami-suami mereka, dan seorang pria yang belum pernah Manisah lihat.
"Anisa?" adalah kata pertama yang diucapkan si pria di layar kaca. Pada adegan itu, tersorot si pria sedang mendorong pintu gubuk yang dikenalnya. Sorotan filmnya agak kacau. Maklum, itu kenangan Manisah. Otomatis segala kenangan yang ditontonnya, adalah sudut pandang Manisah sendiri.
Pria itu memiliki suara yang sama dengan di mimpinya.
"Nis, akhirnya punya rumah kita." Si pria tersenyum cerah. Matanya yang lembut berkaca-kaca saat menatap penonton—kala menatap Manisah. Tangannya yang kapalan menggenggam tangan Manisah sambil mendorong pintu masuk. "Ndak lagi-lagi kita perlu ngemis. Besok, aku mulai kerja di pabrik!"
Otak Manisah mengosong. Ia hanya tamatan SD, ia tidak mampu berpikir mengapa pria itu memanggilnya Anisa, tetapi ada denyut yang begitu perih saat ia menatapnya melalui layar.
Siapa pria itu, kenapa menggenggamnya begitu erat, dan di mana Pijo?
Sekosong otak Manisah, layar menghitam sejenak, kemudian memunculkan adegan lain. Sepertinya hari-hari telah berlalu, sebab pria tadi menumbuhkan cambang sembarangan dan ada luka bakar di tangannya.
"Ngeri banget, Nis, di pabrik." Suara pria itu gemetaran saat Manisah membukakan pintunya. Ia buru-buru menutup pintu kembali. "Tapi ndak apa-apa. Demi kamu agar bisa bubuk di kasur, bukan di kerdus lagi, apa aja aku lakukan. Kamu masih bisa tidur lelap, tho, dengar suara mesin keras-keras?"
Manisah saat ini merasakan getaran di hati saat pria itu mencondongkan tubuh dan mencium dahinya. Pijo tak pernah mencium dahinya, dan ia mulai panik. Mengapa pria asing itu menciumnya? Semoga Pijo tak pernah melihat kaset ini. Apakah ini alasan mengapa kenangannya dilabeli dewasa? Karena Manisah diam-diam selingkuh?
Belum reda kepanikan Manisah, sorotannya berganti lagi. Pria itu tampak lebih ceking dan kantong matanya tebal. Langkahnya pincang. Kala sang pria membuka sepatu, tampak ada jari yang telah hilang. Tiba-tiba layarnya memburam, tetapi masih tampak jelas bahwa pria itu menghambur padanya.
"Jangan nangis, istriku. Ini ndak seberapa. Orang-orang yayasan udah bantu kita, ndak enak kalau aku mundur dari pabrik. Setelah ini akhir bulan, waktunya dapat gajian. Sabar, ya, Anisa. Nanti Mas bisa belikan kamu apa aja. Sumpal kuping juga."
Satu detak jantung lolos dari dada Manisah. Istri?
"Kamu pantes dapat yang baik-baik, Anisa, dan Mas ndak keberatan kerja berat kayak gini demi kamu. Kayak nama Mas untuk kamu—Anisa." Penekanan huruf 'n' sang pria begitu jelas setiap menyebut nama panggilan itu. "Karena kamu mulia di mata Mas, mirip nama surat di kitab suci itu. Kamu satu-satunya yang bikin Mas bertahan hidup. Kamu pantes dapat apapun karena udah menemani Mas sejauh ini."
Untuk pertama kalinya, saat layar meredup, Manisah beranjak. Tangannya menggapai televisi. Ia masih ingin melihat kenangan itu sekali lagi.
Namun, kenangan telah berganti. Kali ini yang muncul adalah sosok Pijo dan rekan-rekan yayasan sosial. Hati Manisah mencelos, tatkala menyadari bahwa tingkah lakunya di kenangan itu begitu gugup. Tak ada si Mas. Hanya ada Manisah di sebuah ruangan menghadap Pijo dan pria-pria pekerja sosial.
"Siapa yang suruh kamu ke sini?" tanya Pijo.
"Nik," jawab Manisah ragu-ragu. Ia mengambil posisi duduk usai dipersilakan.
"Butuh duit, tho?" tanya Pijo lagi, kali ini sambil menaruh botol miras. Pria itu bersendawa. "Berapa?"
"Berapa aja, Pak." Manisah terkejut dengan betapa santun suaranya di kenangan itu, seolah-olah ia dan Pijo bukan suami istri. "Yang penting suami saya bisa diobati. Jarinya hilang satu lagi. Udah tiga bulan dia kerja dan bayarannya ndak cair-cair!"
Pijo terkekeh. "Yo gitu itu risikonya kerja di pabrik, Dik! Karyawannya buanyak, tapi negara lagi sulit!"
Manisah di kenangan itu gemetar. Pandangannya buram lagi. "Saya ndak kuat lihat suami saya nahan sakit tiap malam, dia kira saya sudah tidur padahal saya dengar dia merintih!"
"Oalah, tiap malam kesakitan? Kasian kamu, dong, udah lama nggak dijatahin? Orang sakit mana bisa kasih jatah, ya, tho?" Pijo menatapnya dari ujung kaki ke kepala. "Sayang sekali, lho! Gini, deh, kami bantu obati suami kamu, tapi ada syaratnya. Kamu gak usah khawatir, Nik sama yang lain juga udah nyobain!"
Manisah mengangguk. "Apa aja, Pak! Demi Mas!"
Wanita itu merasakan sekujur tubuhnya merinding ketika layar menggelap lagi. Namun, ia takkan pernah disiapkan oleh apa yang ditonton selanjutnya.
"ANISA!" suara Mas menggelegar di layar. Ia sampai melonjak kaget di sofa. Di kenangan itu, Manisah tak bisa melihat apapun selain kegelapan remang-remang dan suara tangisan yang ditahan. Sementara teriakan Mas menggelegar jauh, seperti memanggil-manggilnya dari luar.
"Nik, kamu liat Anisa, ndak?" suara Mas terdengar lagi.
"Nggak tahu, aku! Belanja, mungkin!"
Jawaban Nik membuat Pijo terkekeh. Jantung Manisah berdentam kencang saat mendengar kekehan Pijo begitu dekat di telinganya, menyusul tangisan Manisah yang tertahan di kenangan itu.
"Memang pinter, Nik itu. Udah bakatnya bohong. Gak kayak kamu, yang harus dipaksa dulu. Padahal enak, tho? Gini aja kamu udah bisa bikin seneng semua orang. Gak usah khawatir, kamu jual aja kenangan-kenanganmu biar gak ingat lagi kalau pernah jual badan ke kami-kami! Bakal banyak, kan, duitmu?"
Sorotan di layar bergoyang keras. Padahal Manisah tidak mengatakan apa-apa di layar itu, tetapi Manisah yang sedang menonton meneteskan air mata dengan deras. Seiring suara Mas yang menjauh dan tenggelam di pengeras suara televisi, semakin keras degup jantung yang terdengar.
Layar kembali menggelap, bersamaan dengan munculnya pemberitahuan bahwa tersisa satu kenangan lagi yang akan diputar. Sedetik kemudian, muncul cuplikan terakhir di televisi.
Tampak orang-orang berkerumun di tepi jajaran gubuk, begitu pula Manisah. Mereka sedang menyaksikan beberapa petugas menggotong tandu keluar dari gerbang belakang pabrik yang menyambung pada jajaran gubuk mereka. Terbentang kain putih di atas tandu.
"Ibu Manisah? Ibu Manisah! Itu suami kamu!" entah petugas mana yang berbicara, suaranya begitu lantang di antara gegap gempita para mantan gelandangan. "Dia terpeleset dan terkena setrum!"
Seorang buruh lelaki di samping Manisah, suami Nik kala itu, berbisik ngeri. "Aku denger dia didorong orang, Nis! Lho, lho, eh—Nis! Bangun!"
Layar menggelap, berikut suara pip pip yang menandakan bahwa sesi menonton kenangannya sudah usai. Namun, Manisah masih bergeming. Yang bergerak hanya air mata yang kerap mengalir deras dan dadanya yang naik turun, berusaha mengatur napas yang sesak.
"Nis."
Manisah kira suara itu muncul dari televisi. Tidak. Mas memang baru saja hadir dan duduk di sebelahnya, berimpitan di dalam bilik menonton yang sesak tersebut. Meski begitu, Manisah tidak keberatan, walau paha Mas tampak melebur sebagian dengan pahanya.
"Masa bisa lelap tho tidurmu dengar suara mesin keras-keras?"
Tangisan Manisah membanjir. Suaranya gemetar saat menjawab, "Ndak bisa, Mas. Tiap malam aku ndak tidur. Pijo minta jatah terus."
Sekarang ia mau muntah tiap mengucapkan nama itu, dan dadanya demikian sesak saat menyebut 'Mas'.
Mas di sisinya terdiam sejenak. Suaranya sendu saat menjawab lagi, "Mereka ndak pernah bayar upah, Anisa. Mas dan yang lainnya cuma diperbudak di sana."
"Saya harus apa, Mas?"
""Ayo, tho, Anisa. Hidupku ndak bisa tenang. Cuma kamu yang bisa."
Manisah tidak tahu, apakah roh memang punya keterbatasan kata-kata, atau ini hanya kegilaannya saja. Tidak, ia tidak gila. Yang gila itu ya Nik. Dan Pijo. Dan pemerintah. Dan semua orang.
"Mas ...."
"Janji, Anisa."
Suara itu tegas dan juga lembut, seperti kata-kata yang ditelurkan setiap Mas sebelum berangkat pagi untuk menjanjikan keselamatannya, tetapi berakhir pulang dengan luka bakar atau jari yang hilang, atau semangat yang padam.
Tak mau mengulangi kesalahan yang sama, Manisah memantapkan keputusannya bulat-bulat. Kebetulan ia tidak punya sisa uang untuk ongkos pulang lagi. Pilihannya hanya berjalan kaki selama dua jam, tetapi untuk apa ia menempuh jarak sejauh itu demi sekumpulan pemerkosa dan lacur-lacur bajingan?
Maka, memanfaatkan seluruh akal cemerlangnya, Manisah memutuskan untuk pulang saja kepada suaminya.
Tepat di bawah baliho "Kota Nyaman Tanpa Gelandangan!", Manisah berlari sekencang mungkin di tepi jembatan, dan melompat bebas ke sungai keruh di bawahnya.
+ + +
Prompt: Buka chatgpt.com atau aplikasi ChatGPT. Mulai percakapan baru, ketikkan "Aku ingin menulis sebuah cerita pendek. Berikan aku sebuah prompt yang menarik!" Buatlah cerita dengan prompt yang diberikan.
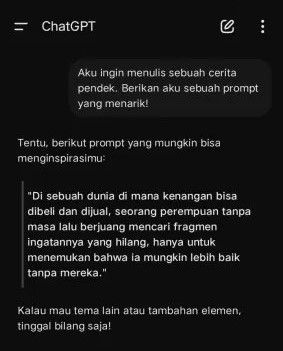
Note: Ini pertama kalinya aku menulis cerita dengan topik begini ... biasanya fantasi luar negeri dan sejenisnya, kan? Tapi, aku mau coba yang beda, dan ... aku mual. Jadi nulisnya nggak maksimal. :cry:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro