❄️ BAB 02: Apa dan Kenapa
Judul: Semusim Di Praha
Oleh: Sahlil Ge
Genre: Spritual, Slice Of Life
Alur: Maju-Mundur (Dulu dan Sekarang)
Diunggah pada: 5 Mei 2019 (BAB 2)
Bagian dari 'Antologi Semusim' (Winter).
Hak Cipta Diawasi Oleh Tuhan Yang Maha Esa.
***
Bab 02 - Apa dan Kenapa
***
Prague, Czech Republic - Winter
[Sekarang - Sultan El Firdausy]
...
"Aku sudah salah masuk kamar dia dan sekarang kamu malah rekomendasiin pada keluarga itu supaya aku jadi terapisnya?" aku sedikit bernada protes. Kami sudah pulang ke apartemen sekitar pukul sebelas malam. "Yang wajar aja dong, Nu. Mia Kathleen nggak salah paham sama aku saja itu sudah mendingan. Keluarganya nggak mikir yang aneh-aneh ke aku pun aku udah bersyukur. Dan biar aku tegasin sekali lagi, aku membaca buku untuk orang yang membayarku itu bukan terapi. Aku bukan terapis, oke?"
"Kamu tenang dulu deh. Biar aku jelasin," Wisnu mengambil posisi duduk di sofa seberang. "Persisnya aku nggak merekomendasikan kamu untuk jadi terapisnya. Tapi, Helga yang meminta."
"Helga siapa?"
"Kamu lihat kan perempuan yang memakai kursi roda satunya lagi? Yang keluar dari dapur membawa baki berisi kue. Yang makan bareng kita. Hum?"
"Kenapa memangnya," jawabku datar.
"Dia Helga. Kakaknya Mia dan Sergey. Asal kamu tahu Helga tidak masalah dengan kakinya."
"Lalu apa maksudnya kursi roda itu? Kamu pikir aku nggak ngerti fungsinya? Meskipun aku sudah setengah gila bukan berarti aku kehilangan pengetahuan dasarku tentang fungsi benda-benda, oke?"
"Kamu mulai tempramental," wajah dan tatapan itu selalu bisa membaca apa yang aku rasakan. Aku tidak bisa menampik ini. Wisnu dan Astrid sama-sama bisa mengerti emosi seseorang dengan baik. "Aku nggak bisa melanjutkan ini kecuali kamu mau mereda dulu emosinya," tambahnya.
Aku lalu membelesak pada sandaran sofa. Mengusap wajah dengan telapak tangan. Mengulang istigfar dalam hati. Semua ini sangat menyiksa saat kecemasan itu berimbas pada ketidakstabilan emosiku dalam merespons sesuatu. Sangat menyiksa.
"Aku sudah bersumpah pada Astrid dan kamu sendiri bahkan, kalau aku akan menanganimu dengan baik. Aku nggak akan mempermainkan kamu, Sul. Dan ini salah satu metode yang sering aku praktikkan."
"Tunggu, jangan ke sana dulu bicaranya. Aku perlu dijelasin kenapa Helga ... ya, kamu tahu."
"Jadi kamu sudah bisa diajak ngobrol sekarang?"
Aku mengangguk tak yakin.
"Karena kalau kamu masih membawa-bawa emosi dalam obrolan ini, aku lebih baik diam."
Aku menghening beberapa saat. Menarik napas dan mengeluarkannya melalui mulut beberapa kali. Diam lagi. Menunggu sampai detak jantungku normal kembali temponya. Lalu, "Oke, aku bisa."
"Bagus. Lakukan persis seperti itu kalau mulai panik. Kamu bisa melakukannya tanpa aku minta. Tidak sulit."
Aku mengangguk, "Jadi bagaimana?"
Wisnu tersenyum karena aku sudah bisa mengendalikan diri.
"Helga penjual bunga ketika siang, tapi penyanyi kafe ketika malam."
"Dan dia menyanyi di Coffee Cube," aku menebak.
"Ya," Wisnu mengangguk, "Dia temanku. Cuman aku baru benar-benar terlibat dengan keluarganya setelah mengurusi Sergey. Helga tahu aku psikiater. Hanya saja aku nggak buka tempat praktik secara serius. Jasaku gratis. Selama ini aku hanya meladeni pelangganku yang bermasalah. Maksudku mereka selain bisa jajan di tempatku juga bisa konsultasi sama aku. Itu kenapa Coffee Cube punya ikatan kuat dengan pelanggan."
Aku masih menyimak.
"Dimintalah aku buat nanganin adiknya yang nyaris nggak mau keluar rumah karena ada masalah besar sama pacarnya. Hampir bunuh diri intinya. Aku nggak bisa ceritakan apa masalah Sergey ke kamu karena itu asas rahasia yang harus aku jaga. Sama seperti aku yang nggak akan membicarakan PTSD-mu ke orang lain, kecuali Astrid. Aku serius soal ini, Sul."
"Kembali ke Helga," aku hanya tidak ingin Wisnu menyerempet pembahasan Post Traumatic Stress Disorder-ku.
"Nahasnya, setelah Sergey sembuh. Giliran Helga dan Mia yang celaka. Lalu-lintas. Kurang lebih itu di bulan Agustus. Mereka berdua sedang sister summer trip gitu ke Berlin. Dan kecelakaannya di sana. Mereka dipulangkan dengan pesawat sampai Ceko. Cuman, Helga sembuh. Dan Mia yang kena fatalnya. Paralyzed. Kisahnya berhenti di sana. Maksudku, Mia menghentikan kisah hidupnya dengan hanya mengurung diri di kamar. Dan tadi kenapa Helga masih pakai kursi roda padahal dia udah nggak perlu gituan, bahkan udah balik nyanyi di Coffee Cube lagi, itu karena beberapa hari ini adalah spesial untuk mereka. Maksudku, hei, ini Natal. Momentum keluarga berkumpul untuk suka cita bagi yang merayakan. Tapi Mia tidak memiliki gairah itu sama sekali untuk sekadar turun dan bergabung dengan keluarganya sendiri. Dia masih tidak bisa menerima kenyataan. Natal tidak turun di kamarnya. Sementara Helga tetap memakai kursi roda ke mana pun sejauh itu masih dalam jangkauan pandang Mia. Helga hanya ingin menghargai Mia dan membuat adiknya itu tidak merasa malu."
"Kamu serius?"
Wisnu mengangkat sebelah tangannya, "Udah habis-habisan materi mereka."
Aku mengangguk karena mulai mengerti. "Aku mau tanya, Nu. Satu hal."
Alis Wisnu terangkat.
"Apa sebelum celaka itu Mia punya semacam ... masalah? Aku cuma perlu tahu."
"Kalau itu aku kurang tahu. Helga nggak cerita banyak. Tapi aku menduganya. Karena gini, Sul. Aku sudah beberapa kali menangani orang dengan trauma kecelakaan lalu lintas yang bahkan sampai amputansi, hilang satu kaki, tapi dia masih bisa sangat menerima keadaan. Namun kali ini untuk kasusnya Mia, yang sama sekali tidak mau ditemui siapa pun, terutama ..." Wisnu membuat jeda.
"Apa?"
"Terutama dia tidak mau berinteraksi dengan laki-laki lagi. Siapa pun," sambung Wisnu, "Bahkan sangat tempramen dengan anggota keluarganya yang laki-laki. Di sana aku menaruh curiga kalau Mia sedang mempunyai masalah yang disembunyikan. Aku tidak tahu apakah keluarganya tahu. Helga tidak mengungkitnya. Kurasa mereka tahu cuman nggak mau menceritakan kepada orang asing. Tapi semua premis samar itu cukup mudah aku implikasikan ke arah satu dugaan," Wisnu memelankan cara bicaranya pada kalimat terakhir. Hampir seperti berbisik.
Aku tertegun. Sempat menahan napas.
"Jadi," Wisnu ragu-ragu. Mengusap punggung tangannya sendiri. "Aku ingin kamu bekerjasama denganku untuk terapimu sendiri. Caranya, coba beri terapi melalu bacaanmu untuk Mia."
"Nu, bentar," aku mengangkat sebelah tangan untuk interupsi, "Aku nggak ngerti apa maksudmu. Bagaimana bisa aku memperbaiki emosi seseorang dalam kondisi emosiku sendiri yang sedang tidak menentu. Di sini aku yang sedang mengandalkanmu."
"Kamu pembaca banyak buku, kan?"
"Ya, tapi apa hubungannya?"
"Zaryn Geraldi said, 'Demi siapa pun yang saat ini sedang berusaha membahagiakan kita, belajarlah untuk memberinya kesempatan. Sebab kita juga tidak tahu kapan kita akan membutuhkan kesempatan serupa. Mungkin nanti. Kalau kita mengharapkan sebuah kebahagiaan, mulailah dari membahagiakan orang lain. Mungkin kita adalah bahagainya yang selama ini ditunggu dan belum datang. Dan siapa yang tahu kita akan bahagia juga karena itu.'"
Aku tersenyum kecil, "Aku ingat buku itu. Tapi penggalan yang kamu sitir bukan dalam konteksku."
"Iya, aku paham. Tapi coba renungi itu. Ada satu bahagia milik kita yang terselip di antara kebahagiaan orang lain. Sebagai psikiater aku tidak boleh mengemukakan secara terang-terangan apa yang harus kamu lakukan dan bagaimana. Tapi aku mendorongmu, memberi pemicu, mengucurkan kisi-kisi, mengamati sebuah laju perkembangan psikis, menganalisa, lalu menunjukkan arah ke mana kamu harus mencari tanpa mengatakan apa yang harus kamu temukan. Karena kalau aku mengatakan semuanya secara gamblang ini-itu-nya, dikhawatirkan akan ada ketergantungan. Aku ingin setelah terapi ini selesai dan kamu kembali seperti sedia kala, kamu akan bisa mengolah psikismu tanpa aku atau siapa pun. Ya, maksudku Astrid seorang psikolog juga, dan kamu bisa dengannya setelah ini. Tapi tetap, sebuah ketergantungan selain kepada Allah bukanlah hal yang baik, kan? Kamu lebih tahu soal itu."
Wisnu orang yang cerdas.
"Beberapa kali aku sering menerapkan metode ini. Aku pernah menangani dua pelanggan Coffee Cube yang sedang mengikuti tahapan konsultasi denganku. Mereka punya masalah soal kehilangan. Apa yang aku minta untuk mereka lakukan? Kalau kamu menduga aku meminta mereka untuk saling bicara, cerita, memberi nasihat satu sama lain, itu benar. Dan hasilnya? Aku tidak banyak melakukan apa pun."
"Berhasil?"
"Of course. Mereka berteman dan terus berkomunikasi. Karena menasihati orang lain itu mudah, Sul. Dan nggak ada orang yang menasihati tanpa mengalami masalah itu sebelumnya. Berbicara dengan seseorang yang 'senasib' akan menghadirkan satu kebijaksanaan dari kontemplasi. Tukar pikir."
"Aku mengerti."
"Sebenarnya, setelah kupikir-pikir, aku nggak perlu banyak mengajari ini ke kamu. Aku tahu bahwa kamu tahu harus bagaimana. Maksudku, kamu lulusan Tassawuf Psikoterapi. That's your major. Ranahmu pada reparasi ruhani dan iman. Sementara aku nggak bisa banyak menyisipkan hal-hal religius dalam urusanku."
"Tapi, Nu. Oke, aku paham maksudmu. Cuman ... gimana ya," setiap membicarakan ini rasanya aku ingin menangis, "Apa yang aku alami justru membenturkan semua hal yang telah aku pelajari. Mereka tidak hilang dari alam akalku. Hanya saja aku merasa malu untuk menyentuhnya lagi. Aku malu mengakui semuanya. Aku kalau disertasi ini bisa ditunda, aku tunda deh, beneran. Mending aku balik ke Indonesia, ketemu anak dan istriku, juga keluargaku. Tapi kapan selesainya kalau aku tunda?"
Wisnu menatapku fokus. Pada saat seperti ini aku tahu otaknya sedang mencatat gerak-gerikku.
"Istriku ..." napasku mendesak di dada. Aku sebal kalau mulai cengeng seperti ini. Hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya, "Astrid bahkan ... dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku nggak cerita ke dia. Cuma kamu yang tahu. Dan Allah, yang mungkin sudah bosan mendengar ... melihat aku berkeluh kesah seperti ini."
"Allah nggak pernah bosan melihat kamu berkeluh kesah pada-Nya. Pun ketika kamu berkeluh kesah padaku atau Astrid, karena Dia lebih dari sekadar tahu kalau itu wujud dari usahamu."
"Lihat, aku bahkan mengatakan hal-hal yang sepayah itu," dengan cepat aku mengelap kedua ekor mataku.
"Aku rasa Astrid sangat perlu tahu."
"Sekali kamu berani cerita semuanya ke Astrid, bisa-bisa aku nggak akan pernah pulang, Nu."
Wisnu seperti tidak bisa konsisten lagi dengan diri psikiaternya, "Oke, sekarang aku ingin berbicara sebagai teman dan bukan sebagai psikiater. Karena aku sudah ingin mengorek ini lebih dalam. Sul, Astrid harus tahu."
"Kamu pikir itu hal yang bisa dia hadapi setelahnya? Aku, Nu," aku emosional mengarahkan telunjuk ke dadaku sendiri, "Menghadapi ini sendiri saja rasanya udah seperti otomatis calon penghuni neraka! Apa lagi kalau sampai Astrid tahu. Dia harus tetap bahagia! Dan bagaimana pun caranya dia nggak boleh tahu. Cukup dia tahu kalau aku sedang bermasalah dan perlu berurusan dengan psikiater. Dia nggak boleh tahu kalau ..." detak jantungku memburu. Napasku sengal berat. Dan apa yang kutahan-tahan di depan Wisnu selama ini akhirnya pecah. Air mataku meleleh. "Astrid nggak boleh tahu kalau suaminya yang sangat dia sayangi ... panutannya ... payung hujannya ... ayah dari anaknya ... pernah dilecehkan secara brutal oleh sekelompok cewek jalang pendendam di Istanbul!"
Wisnu tertegun dengan semua kosa aksara yang terbungkam.
Aku mulai berkeringat, "Astrid nggak boleh tahu atau membayangkan ... bagaimana suaminya secara kejam ditelanjangi dan diikat pada satu kursi! Dipermainkan. Dicambuk punggungnya pakai ikat pinggang sampai membekas hingga sekarang. Dan ditinggalkan di sana seperti sampah. Sebuah pembalasan tak adil untuk satu perbuatan yang kupikir itu bukan sesuatu yang salah. ... Astrid nggak boleh tahu," susah payah aku menelan ludahku sendiri.
Aku parah seperti apa nangisnya di sofa itu. Kedua tanganku tremor kuat sekali. Tapi terasa puas karena meluapkan itu.
"Anakku ... dan keluarga pesantren," hancur sekali perasaanku mengakui ini di depan Wisnu, "Mereka nggak boleh tahu."
Wajah Wisnu ketar-ketir menatapku.
"Ini aib besar, Nu. Dan aku nggak bisa membawa pulang ini ke pesantren. Atau ke pelukan Astrid. Apalagi pada anakku. Aku sudah lenyap. Sultan yang dulu sudah nggak ada. Calon penerus pesantren yang digadang-gadang itu sudah nggak ada. Aku seperti sudah mati di mataku sendiri!"
Aku menutupi wajah dengan kedua tangan sampai membungkuk. Terisak. Keringat yang mengalir di punggung masih bisa membuat sisa luka di punggung terasa panas. Masih ada bekas lecet. Kejadiannya memang baru awal Oktober lalu.
"Maaf, Sul. A-aku nggak tahu sampai separah itu," Wisnu gagap, "Terakhir kamu cerita hanya pelecehan dan stres penelitian. Kamu nggak menyebut soal ... ditelanjangi ... atau cambuk."
Aku baru sadar telah mengatakan detil kejadiannya pada Wisnu. Dan sangat menyesalinya.
"Tolong jangan beritahu Astrid, Nu. Tolong," kataku dengan suara yang tak jelas.
"Tapi semua ini bukan salahmu. Kamu korban. Dan pengeroyokan cewek-cewek jalang itu hanya karena kamu menggagalkan satu cewek yang mau dijual, kan? Seperti yang terakhir kamu ceritakan. Komplotan jalang itu marah dan ..." Wisnu membuat jeda, "Kamu melaporkan ini ke pihak yang berwenang?"
Awalnya aku nggak ingin menceritakan ini kepada Wisnu lebih lanjut. Tapi ini terlanjur aku buka dan mau seperti apa disembunyikan lagi dia akan tetap tahu. "Aku nggak bisa melakukan itu. Kalau aku membuat laporan, aku takut namaku akan mencuat pada berita di media-media. Apa jadinya kalau berita itu sampai ke pihak kampus? Sampai ke tanah air? Sampai ke pesantren? Dan sampai ke Astrid?"
"Maaf," dia masih segan, "Aku perlu tahu ini. Um, apa mereka merekamnya?"
Aku menggeleng, "Tidak ada, sejauh yang aku ingat."
"Apa kejadiannya di ruang ber-CCTV?"
Tidak kujawab begitu saja, "Tidak yakin."
"Mereka perempuan semua? Atau ... kamu nggak melihat salah satu di antaranya yang laki-laki ... atau ... b-bagaimana kamu bisa dibawa mereka?"
Aku nggak sanggup menjawabnya lagi. Hanya bisa membungkuk dan terisak tanpa membuat suara rengekan sedikit pun.
Pada situasi seperti ini aku berterimakasih karena Wisnu pengertian untuk tidak mengajukan pertanyaan lagi atau mengorek lebih dalam. Kami sesama laki-laki tak pandai memberi penenang untuk satu sama lain. Di hadapkan pada situasi ini jarang ada laki-laki yang mendekati salah satu yang sedang menangis untuk memberi pelukan untuk menenangkan. Berbeda dengan perempuan yang cenderung lebih mudah terbawa suasana dan tak segan untuk memberi pelukan untuk sesama perempuan. Tetapi lain untuk Wisnu yang pada dasarnya memang memiliki empati luar biasa kepada seseorang. Sejauh yang aku kenal. Dia beringsut mengambil posisi duduk di sebelahku. Lalu meletakkan satu tangannya di punggungku. Pelan sekali. Kurasa dia khawatir kalau-kalau sentuhannya bisa menyenggol luka lecetku yang baru dia tahu aku memilikinya. Iya ini memang sudah lebih dari dua bulan. Tapi bekasnya masih ada.
"It's okay," ucapnya pelan, "Aku sudah ngerti sekarang. Aku sudah paham kenapa kamu tidak ingin Astrid tahu. Aku sudah tahu dari mana sumber traumamu berasal. You're gonna be fine. Tumpahkan saja kalau kamu memang perlu menangis. Take your time. Aku ... aku ... um, terima kasih sudah cerita. Itu perlu nyali besar."
"Maaf," aku malu di depan Wisnu.
"No, Sul. Aku justru lega kamu berani cerita ke aku yang sebenarnya. Aku jadi lebih tahu harus seperti apa menangani kamunya. Maksudnya kita sudah nyaris sebulan kenal. Ya sejak Astrid mempercayakan kamu untuk tinggal di sini, dan memintaku untuk coba menanganimu karena katanya kamu perlu psikiater untuk konsultasi," ungkap Wisnu, "Astrid waktu itu bilang kamu mungkin cuma stres karena disertasi doang dan perlu tempat tinggal sementara selama di Praha."
"Aku pengin dia tetep tahunya aku stres karena itu, Nu. Bisa kan kamu bantu?"
"Aku bisa."
Kami menjeda percakapan cukup lama. Yang terdengar hanya suara isakan lirihku dan hidung berisik. Aku tidak mengira akan menceritakan semuanya pada Wisnu. Tapi aku percaya dia bisa diandalkan. Dia teman akrabnya Astrid selama kuliah dulu, katanya.
Lalu Wisnu berdiri dan melenggang pergi ke kamarnya. Dan kembali dengan sebuah kotak bening.
"Masih ada luka, nggak, Sul? Ini ada obat oles."
Aku mengangkat satu tangan. "Aku punya obat olesku sendiri."
"Oh. Tapi ini boleh kamu simpan. Jangan sungkan-sungkan sama aku. Istrimu itu teman baikku. Aku berhutang banyak budi padanya."
Aku berusaha tersenyum meski getir. Kuterima kotak itu hanya agar Wisnu merasa diakui olehku. Dia memang orang yang sangat baik. "Astrid tidak bohong ketika dia menyebut kamu orang baik."
Wisnu tersenyum kecil.
"Nu," ucapku sambil berdiri hendak ke kamar.
"Ya?"
"Jangan beritahu dia soal ini. Atau siapa pun."
Wisnu mengangguk.

***
Indonesia, Musim Hujan
(Sekarang - Astrid Pramesti)
...
SMAIT sedang memasuki jam istirahat pertama saat aku kembali ke kantor staf dan mendapati ada satu pesan WhatsApp dari Wisnu. Singkat namun berhasil membuat aku ketar-ketir setelah membacanya.
"Trid, telepon aku kalau luang. Aku udah tahu Sultan kenapa. Ini penting. Banget."
to be continued ...
***
***
Tunggu, sekarang coba jawab ini sebelum keluar jendela baca. Kita diskusikan bersama. Saya perlu tahu tanggapan dari pembaca-pembaca yang Budiman 🤫
1. Menurut kalian perlu tidak Astrid tahu masalah Sultan yang sebenarnya? (Komentar di sini)
Duh, yang jelas kalau sampai dia tahu pasti bakal berubah jadi super garang ngalahin Captain Marvel, atau marahnya Wanda ke Om Thanos yang udah merenggut Mas Vision. Astrid tipikal cewek yang nggak-akan-tinggal-diam. Bukan ke Sultan tentunya.
2. Sultan sedang kacau. Sangat terpuruk. Boleh beri kalimat penyemangat atau penenang untuknya? Jangan hakimi dia. Please be nice to him 🙂 (Komentar di sini)
3. Dari apa yang Sultan akui. Menurut kalian masih perlu nggak masalah itu dilaporkan ke pihak berwenang? Kan Sultan mengkhawatirkan banyak hal kalau sampai masalahnya naik ke publik. 😕 (Komentar di sini)
Hm, mending diserahkan ke pihak yang berwenang atau serahkan ke Bang Ge aja, ya? 🤔
4. Haruskah Sultan menerima saran Wisnu untuk memberi terapi bacaan pada Mia Kathleen? Yang mana itu bagus untuk kebaikan Sultan. Ya, ada metode seperti itu. (Komentar di sini)
5. One last question. Bab berikutnya sudah masuk Ramadan ketika diunggah. 🎉🎉🎉 Enaknya update jam berapa nih?
Abis sahur/Abis zuhur/Jam-jam ngabuburit/Abis buka/Abis tarawih?
(Komentar di sini)
***
Terimakasih untuk kawan-kawan yang sudah membaca, berkomentar dan memberi bintang. Kalian orang baik.
***
PS: Jangan salah paham ke Wisnu. Dia memang temannya Astrid. Akan diceritakan nanti. He's really a nice man.
PPS: Sudah lihat postingan terbaru di instagramnya @sultan.isme? Itu kaitannya dengan bab ini.
[Sampai jumpa di hari Kamis]
***
***
Pojok Pengetahuan:
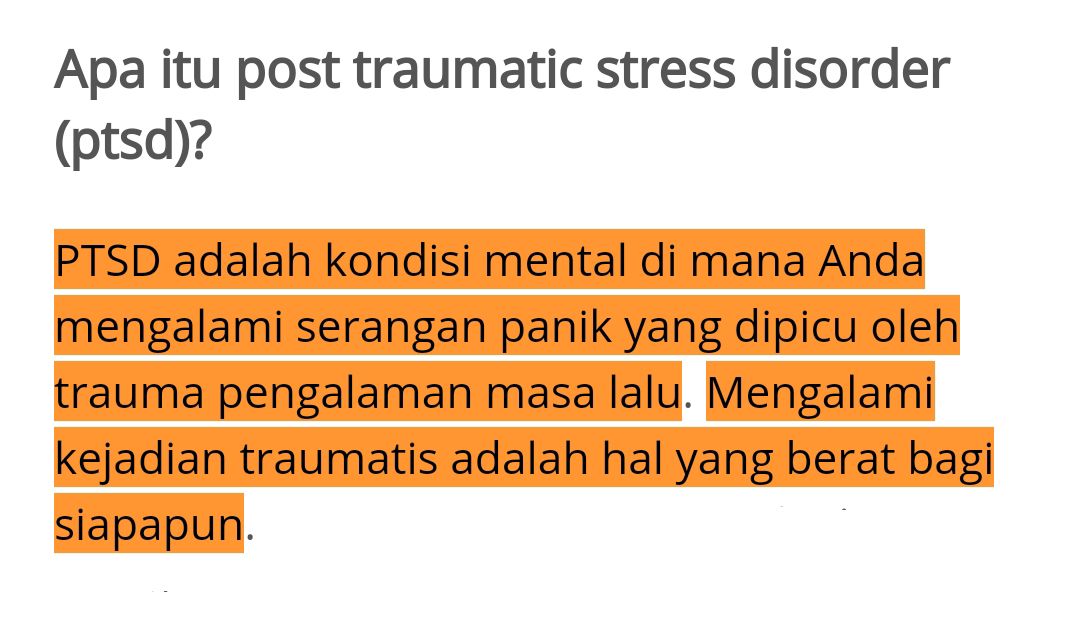
Sumber: hellosehat.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro