Bab 8
Please jangan nangis,
Jangan ikutan marah....
Please banget... Agam kayak gitu krn membela keluarganya...
----------------------
Kupikir tangis bisa menghapus beban luka yang terasa, namun nyatanya tangis hanya menambah luka bagi orang lain yang melihatnya.
Jam 8 pagi, dengan menggunakan penerbangan terpagi pada hari ini, Agam, dan Barra akhirnya sampai di bandar udara Abdul Rachman Saleh. Ketika sampai di bandara, keduanya langsung bergegas ke tempat di mana para keluarga penumpang sedang harap-harap cemas menunggu kabar terupdate.
"Gile rame juga," ucap Barra ketika pandangannya sudah berhasil menjangkau tempat yang dikhususkan untuk keluarga penumpang.
Agam mengangguk setuju. Sebelum melihatnya sendiri, Agam menganggap kondisinya tidak akan seramai ini. Akan tetapi, setelah datang langsung ke sini, dia baru sadar, bukan hanya keluarga Al Kahfi yang sedang menunggu kabar terupdate, namun banyak keluarga lainnya yang juga bernasib sama.
"Astaghfirullah al'adzim," ucap Agam. "Semoga hari ini ada kabar baik," sambungnya menepuk bahu Barra, sembari melangkah kembali.
Ketika hanya sisa beberapa langkah menuju tempat tersebut, dua orang laki-laki mendekati Agam. Beliau-beliau ini adalah orang yang diminta Agam untuk membantu menemani anak-anak mereka di sini.
"Selamat pagi, Pak!"
"Pagi. Bagaimana?"
"Hingga tadi malam, hanya ada kabar barang-barang penumpang yang ditemukan. Tidak ada kabar lanjutan. Namun masalahnya, salah satu barang yang ditemukan adalah ...."
"Iya, saya tahu," sahut Agam cepat. "Kalian bisa beristirahat dulu. Dan terima kasih atas bantuannya."
"Sama-sama, Pak. Siap laksanakan. Nanti kami akan coba mencari tahu ke lokasi jatuhnya pesawat tersebut."
"Baik. Terima kasih."
Mengakhiri kalimatnya, kedua laki-laki sigap itu pergi meninggalkan area ini. Mereka benar-benar siap membantu Agam sebagai partner kerja dulu, sewaktu Agam ada menangani kasus di Malang.
"Siapa mereka, Gam?"
"Dulu gue ada kerjaan di Malang. Dan mereka berdua yang bantu gue selama di sini. Setelah kerjaan gue kelar, ternyata bagusnya komunikasi kami masih terjalin. Dan menurut gue ini sebuah keberuntungan dalam menjaga silaturahim."
Barra tersenyum bangga kepada Agam. Sejak mengenalnya di Jerman dulu, Agam benar-benar sudah berubah.
"Kita harus bener-bener nemuin Wahid. Secara dia guru hijrah kita. Bener enggak?"
Agam menatap Barra, sahabatnya, kemudian kepalanya mengangguk setuju. "Yang terbaik untuk sahabat kita."
"Yang terbaik buat sahabat kita, si oli samping, ya balik lah. Gue yakin dia baik-baik aja."
"Hei, lo masih panggil dia oli samping. Bar, kita bukan lagi di Jerman."
"Alah, lo. Dulu lo panggil dia anak SMP kan. Mendingan gue, oli samping. Udah, pokoknya doain yang terbaik. Dan harus balik pokoknya, enggak mau tau gue!!"
"Ya, ya, ya. Kita cari anak-anak dulu," ajak Agam merangkul bahu Barra, sahabatnya. Sekalipun usia mereka sudah tidak muda lagi, namun persahabatan mereka terasa kekal abadi.
***
"Ayah ...." Zhafir memanggil seseorang yang terlihat seperti ayahnya berjalan di depannya menuju ke area para keluarga penumpang pesawat nahas tersebut.
"Yah, Ayah."
Hampir 3 kali Zhafir memanggilnya, barulah Agam merespon. Dia melepas rangkulan pada bahu Barra, kemudian tersenyum ke arah Zhafir yang berada tak jauh di belakangnya.
"Assalamu'alaikum, Yah. kenapa enggak bilang kalau datangnya akan pagi?"
"Wa'alaikumsalam. Semalam ayah belum berani bilang, karena yah kamu tahu sendiri, ibumu sulit untuk ditinggal. Jadinya baru subuh tadi om Barra mendapatkan tiket untuk berangkat pagi ini."
Setelah mencium punggung tangan Agam dan juga Barra, Zhafir mengangguk paham atas penjelasan ayahnya. Dia bisa merasakan betapa keras kepalanya sang ibu ketika dalam kondisi seperti ini.
"Abi mana, Fir?"
"Tuh, mas Abi. Abis subuh, kayaknya dia capek banget. Ketiduran di kursi."
Barra berbalik, melihat ke arah yang Zhafir tunjuk. Ternyata benar, anaknya itu sedang meringkuk di salah satu kursi, dengan kedua tangan memeluk erat tubuhnya sendiri.
"Ya Allah, anak gue," ungkap Barra sedih. "Gimana gue mau update kondisi Abi ke Syahla. Yang ada Syahla langsung nyusul ke sini kalau lihat Abi begini."
"Dari kemarin emang mas Abi kayak enggak mau hubungi mba Syahla. Katanya semakin sering menghubungi, semakin dia akan khawatir. Dan hebatnya, mas Abi ngomong gini ke Zhafir. Sebelum kami menikah, kami sudah terbiasa terpisah. Harusnya Syahla kuat untuk menunggu di rumah, sekalipun tanpa kabar dariku."
"Keterlaluan banget emang deh si Abi mah. Mirip bundanya banget!!" gerutu Barra kesal.
"Bar, lo tega banget. Giliran yang jelek dari sikap anak, lo kasih ke istri. Terus bagian lo emang yang bagus doang? Lupa soal masa lalu?"
"Serius, Gam. Lo ngeselin."
Tertawa, menghibur hati bersama. Zhafir melihat ayahnya dan omnya, sama-sama saling menghibur atas perasaan tidak karuan yang terasa kini. Padahal sesungguhnya, jika diperbolehkan semenit saja untuk mengungkapkan perasaan, Zhafir yakin mereka akan menangis karena tidak kuat menahan segala rasa.
"Yuk ke sana," ajak Zhafir.
Dia memimpin di depan. Berjalan mendekati posisi Abi yang masih meringkuk, seperti orang kedinginan. Sekalipun kondisi tempat menunggu ini sangat ramai, namun rata-rata dari pihak keluarga terlihat masih tertidur lelah, karena menunggu kabar yang belum ada perkembangan.
"Mas Abi ... Bi, bangun, Mas."
"Hm ...."
"Bangun, pindah ke hotel sana. Istirahat dulu. Nanti ke sini lagi," ucap Barra pada putra pertamanya itu.
Dengan pandangan yang masih belum jelas, Abi mengusap kedua matanya, melihat siapa yang membangunkannya dengan suara begitu familiar.
"Ayah ...."
"Iya, ayah. Udah sana bangun dulu, istirahat di hotel bareng Zhafir. Biar ayah sama om Agam yang di sini. Kita gantian jaganya."
Semakin tersadar, Abi merenggangkan otot-ototnya sejenak. Sebelum mengangguk patuh kepada perintahnya.
"Yuk, mas Abi."
Zhafir mengajaknya. Kali ini dia ingin kembali ke hotel, karena butuh membersihkan diri agar lebih segar setelah semalam begadang berdua Abi.
Namun sayangnya, baru beberapa langkah mereka menjauh dari ayah mereka, suara-suara keributan terdengar. Kali ini diikuti jeritan dari orang-orang yang mengikuti langkah petugas menuju kemari.
"Tunggu dulu, Mas. Ada kabar apa lagi, ya?"
Zhafir menahan tangan Abi. Kedua sama-sama melihat para petugas masuk ke dalam tempat menunggu ini dengan beberapa orang penting, seperti dokter dan pihak berwajib.
"Selamat pagi semuanya!!" Salam dari para petugas.
Anggota keluarga lainnya satu persatu mulai terbangun. Mereka cukup kaget melihat para petugas datang membawakan kabar terupdate sepagi ini. Apalagi beberapa pihak keluarga yang mungkin sudah mengetahui kabar apa yang akan diinformasikan, terlihat teriak-teriak dalam tangisannya.
"Feeling gue enggak enak," kata Abi mendadak. Kantuknya lenyap. Sakit punggungnya, efek semalaman duduk di kursi, mendadak hilang. Yang terasa kini hanya debaran jantung semakin kencang. Tanpa bisa ia tahan.
"Bismillah," gumam Zhafir.
"Innalillahi wa'inna ilahi rojiun ... innalillahi wa'inna ilahi rojiun ... innalillahi wa'inna ilahi rojiun. Pagi ini kami mendapatkan kabar terburuk yang rasanya tidak ingin kami sampaikan kepada semuanya. Para tim bertugas yang mencari lokasi jatuhnya pesawat semalam, akhirnya berhasil menemukan lokasi pastinya. Namun sayang, hasilnya teramat sangat tidak kami harapkan. Beberapa potongan tubuh, serta kulit yang menempel pada beberapa pakaian, berhasil ditemukan oleh tim petugas. Lalu tengah malam tadi sudah berusaha dicek berdasarkan sample dari keluarga penumpang yang hari kemarin sudah kami ambil datanya."
Terlihat menarik napas dalam, lalu mengembuskan perlahan. Tatapan mata petugas itu terlihat sedih ketika ingin menyampaikan nama-nama dari para korban.
"Para petugas yang sudah bekerja sama dengan sangat baik, akhirnya berhasil mengidentifikasi 10 korban dari beberapa potongan tubuh serta kulit yang masih menempel pada beberapa helai pakaian. Dan berikut nama-namanya."
Dengan harap-harap cemas, satu persatu petugas menyebutkan nama-nama korban yang berhasil diidentifikasi. Setiap sebuah nama disebut oleh petugas tersebut, ada saja sahutan jerit tangis dari keluarga korban setelah mendengar kabar duka ini. Sampai pada nama ke 10, atau yang terakhir, nama yang tidak ingin didengar oleh keluarga Al Kahfi, terutama Agam, dan Barra, tiba-tiba saja disebutkan oleh petugas.
"Untuk yang terakhir, dari potongan jari yang ditemukan berhasil diidentifikasi dengan nama bapak Rasyiqul Wahid. Usia yang terdaftar pada list penumpang, yakni 54 tahun."
"AYAH !!!!!" Jeritan kencang dari posisi di belakang, menarik fokus semua orang, termasuk Agam dan Barra yang berada di bagian terdepan.
Barra yang tidak bisa menahan tangisnya, berjalan mendekati Aesha dengan penuh isak. Sekalipun kedua kakinya lemas, tangannya gemetar, dia ingin merangkul putri dari sahabat terbaiknya. Wahid.
"AYAH JANGAN TINGGALIN AESHA!!!"
Gadis itu mengamuk. Melepaskan rangkulan Adskhan yang berada di sampingnya. Sekalipun nama ayahnya sudah disebut oleh petugas, Aesha seperti tidak percaya akan takdirnya ini.
Seharusnya hari ini mereka liburan di kampung halaman ibunya. Harusnya hari ini mereka berbahagia dengan kondisi bisa berkumpul bersama-sama. Mencocokan waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga adalah kendala terbesar bagi mereka. Lalu kini, ketika mereka berhasil memiliki waktu, nyatanya itulah waktu terakhir yang Tuhan berikan untuk mereka.
"Tolong bilang semua itu bohong. Ayahku belum meninggal. Ayahku tidak akan meninggal secepat ini."
Tepat langkah Barra sampai di depan Aesha, kedua tangannya langsung merangkul tubuh gadis itu dengan sangat erat. Seolah melepaskan rindunya pada Wahid.
"Tenang, Nak. Sabar."
"Orang itu bohong, Om. Ayahku belum meninggal. Ayahku masih ada. Mereka saja yang tidak bisa menemukannya."
"Ayahmu akan tetap hidup dalam kenangan, Nak. Percayalah."
Memejamkan kedua matanya, kilas balik ketika pertama kali bertemu dengan Wahid dulu di Jerman, seolah berputar kembali. Dia yang berada pada posisi aib ketika itu, bisa-bisanya mengajak Wahid yang belum dirinya kenal untuk terbawa arus buruk.
"Aku menyesal, Om. Aku menyesal mengajak keluargaku liburan. Aku menyesal."
Masih dalam pelukan erat Barra, wartawan yang mulai menyadari bila salah satu nama korban adalah sosok penting dalam dunia bisnis, langsung mengarahkan kameranya ke posisi Aesha dan juga Barra.
Tidak ragu-ragu, mereka saling dorong untuk mendapatkan gambaran terbaik. Walau dalam posisi ini, suasana duka yang tercipta, tapi sayangnya tidak ada satupun wartawan memahami kondisi ini.
Sampai akhirnya, Agam memukul salah satu wartawan yang hampir menjatuhkan Barra dan juga Aesha karena dorongan.
"SIALAN!! MENJAUH KALIAN SEMUA!!!"
Dalam memori ini kini kau tinggal.
Berbias menghilang akibat terkikis oleh waktu.
Kadang kupertanyakan, mengapa aku masih merasa terluka
Sekalipun kondisi ini cepat atau lambat pasti akan kurasa.
Pamit meninggalkan, hanyalah lelucon yang terakhir kau katakan.
Dirimu juga berkata agar aku tidak merindukan
Padahal jelas sekali kini rindu adalah sahabat terbaik yang kurasakan.
Terpikir untuk menyerah, tapi hati ini ingin sekali mengikhlaskan.
Meski air mata tidak kunjung reda
Namun bibir ini berusaha untuk mengatakan kesanggupan atas duka yang terasa
Terima kasih, Sahabat.
Berkawan denganmu adalah kehidupan terbaikku.
Kini kau bahagia di sana, sekalipun aku akan ... kesepian di sini.


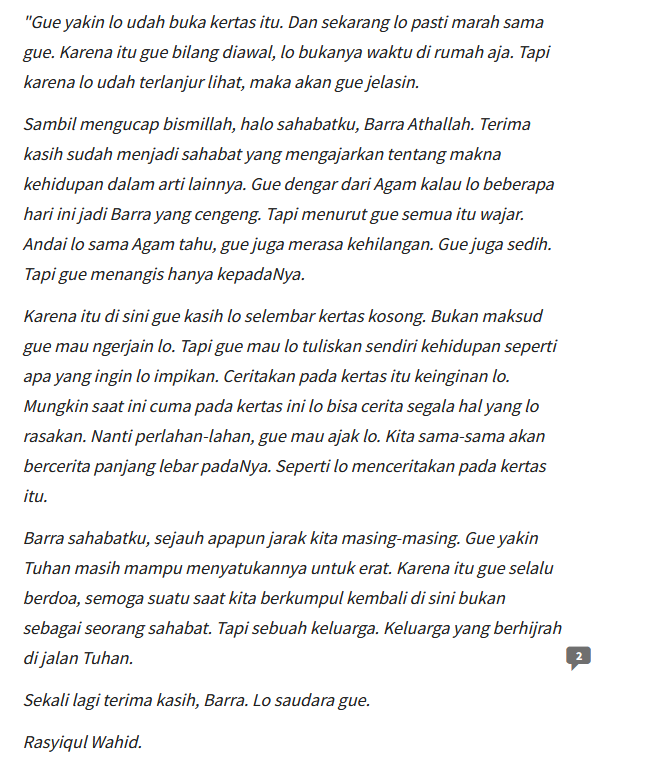
Sumpah demi apapun, gak tega bangeeetttt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro