#i. geger pecinan [prolog]
" hidup enggan, mati pun tak mau "
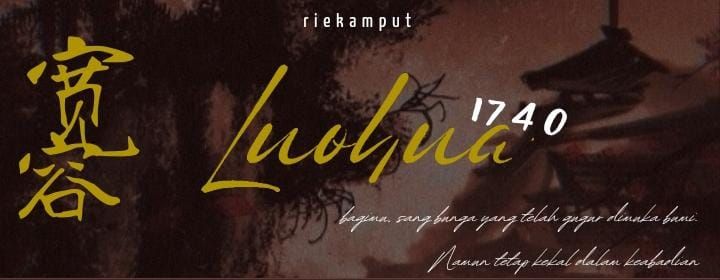
Apakah kalian tahu Geger Pecinan?
Pada periode awal kolonialisasi Hindia Belanda oleh Belanda, banyak orang keturunan Tionghoa dijadikan tukang dalam pembangunan kota Batavia di pesisir barat laut pulau Jawa.
Mereka juga bertugas sebagai pedagang, buruh di pabrik gula, serta pemilik toko.
Perdagangan antara Hindia Belanda dan Tiongkok, yang berpusat di Batavia, menguatkan ekonomi dan meningkatkan imigrasi orang Tionghoa ke Jawa.
Jumlah orang Tionghoa di Batavia meningkat pesat, sehingga pada tahun 1740 ada lebih dari 10.000 orang. Ribuan lagi tinggal di luar batas kota.
Pemerintah kolonial Belanda mewajibkan mereka membawa surat identifikasi, dan orang yang tidak mempunyai surat tersebut dipulangkan ke Tiongkok.
Kebijakan deportasi ini diketatkan pada dasawarsa 1730-an, setelah pecahnya epidemik malaria yang membunuh ribuan orang, termasuk Gubernur Jenderal Dirk van Cloon.
Menurut sejarawan Indonesia Benny G. Setiono, epidemik Geger Pecinan ini diikuti oleh meningkatnya rasa curiga dan dendam terhadap etnis Tionghoa, yang jumlahnya semakin banyak dan kekayaan yang semakin menonjol.
Akibatnya, Komisaris Urusan Orang Pribumi Roy Ferdinand, di bawah perintah Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier, memutuskan pada tanggal 25 Juli 1740 bahwa warga keturunan Tionghoa yang mencurigakan akan dideportasi ke Zeylan (kini Sri Lanka) dan dipaksa menjadi petani kayu manis.
Warga keturunan Tionghoa yang kaya diperas penguasa Belanda, yang mengancam mereka dengan deportasi.
"Jika tidak membayar pajak, kalian akan dapat dideportasi ke Zeylan!" Ujar petugas asli Belanda.
"Tetapi harga ini begitu tinggi, sangat tidak masuk akal!" jawab salah seorang pengusaha asal Tionghoa, yang kini tinggal di Batavia.
Stamford Raffles, seorang penjelajah asal Inggris dan ahli sejarah pulau Jawa, mencatat bahwa orang Belanda diberi tahu Kapitan Cina (pemimpin etnis Tionghoa yang ditentukan Belanda) untuk Batavia, Ni Hoe-Kong, agar mendeportasikan semua orang Tionghoa berpakaian hitam atau biru, sebab merekalah yang miskin.
Ada pula desas-desus bahwa orang yang dikirimkan ke Zeylan tidak pernah sampai ke sana, tetapi justru dibuang ke laut lepas, atau mereka mati saat membuat kerusuhan di kapal, juga sebuah kecelakaan.
Ancaman deportasi ini membuat orang Tionghoa resah, dan banyak buruh Tionghoa meninggalkan pekerjaan mereka.
Sementara, penduduk pribumi di Batavia, termasuk orang-orang Betawi, menjadi semakin curiga terhadap orang Tionghoa.
Seperti yang telah dikatakan tadi: masalah ekonomi ikut berperan, sebagian besar penduduk pribumi miskin, dan beranggapan bahwa orang Tionghoa tinggal di daerah-daerah terkemuka dan sejahtera.
"Lihat orang-orang Cina disana! mereka hidup dengan enak, sedangkan warga kita disini kelaparan! Sebenarnya siapa pendatang disini?" Ujar seorang penduduk pribumi yang bermaksud meracuni pikiran masyarakat lain.
Biarpun sejarawan Belanda A.N. Paasman mencatat bahwa orang Tionghoa menjadi "bak orang Yahudi untuk Asia", keadaan sebenarnya lebih rumit.
Banyak orang Tionghoa miskin yang tinggal di sekitar Batavia merupakan buruh di pabrik gula, yang merasa dimanfaatkan para pembesar Belanda juga Tionghoa.
Orang Tionghoa yang kaya memiliki pabrik dan menjadi semakin kaya dengan mengurus perdagangan, mereka mendapatkan penghasilan dari pembuatan dan distribusi arak (sebuah minuman keras yang dibuat dari molase dan beras).
Namun, penguasa Belanda yang menentukan harga gula, ini juga menyebabkan keresahan.
Sebagai akibat penurunan harga gula di pasar dunia, yang disebabkan kenaikan jumlah ekspor ke Eropa, industri gula di Hindia Belanda merugi.
Hingga tahun 1740, harga gula di pasar global sudah separuh dari harga pada tahun 1720. Karena gula menjadi salah satu ekspor utama Hindia Belanda, negara jajahan itu mengalami kesulitan finansial.
Pada awalnya, beberapa anggota Dewan Hindia (Raad van Indië) beranggapan bahwa orang Tionghoa tidak mungkin menyerang Batavia, dan kebijakan yang lebih tegas mengatur orang Tionghoa ditentang oleh fraksi yang dipimpin mantan gubernur Zeylan Gustaaf Willem baron van Imhoff, yang kembali ke Batavia pada tahun 1738.
Namun, orang keturunan Tionghoa tiba di luar batas kota Batavia dari berbagai kampung, dan pada tanggal 26 September Valckenier memanggil para anggota dewan untuk pertemuan darurat.
Pada pertemuan tersebut Valckenier berkata "Kita adakan pertemuan darurat, kita harus memikirkan cara agar kerusuhan yang dipicu orang Tionghoa ditanggapi degan kekuatan yang memastikan!"
Namun, kebijakan ini terus ditentang oleh fraksi van Imhoff.
Vermeulen berpendapat bahwa "ketegangan antara kedua fraksi politik ini ikut berperan dalam pembantaian"
Pada tanggal 1 Oktober malam, Valckenier menerima laporan mengejutkan.
"Lapor Pak! ribuan orang Tionghoa telah berkumpul dan menyerbu gerbang kota Batavia! amukan mereka diduga dipicu oleh pernyataan dewan pada lima hari sebelumnya!" Lapor salah seorang dari anggota mereka.
"Apa! mana mungkin!" teriak Valckenier, dan anggota Dewan Hindia lain tidak percaya hal tersebut.
Namun, setelah orang Tionghoa membunuh seorang sersan keturunan Bali di luar batas kota, dewan memutuskan untuk melakukan tindakan serta menambah jumlah pasukan yang menjaga kota.
Dua kelompok yang terdiri dari 50 orang Eropa dan beberapa kuli pribumi, dikirim ke pos penjagaan di sebelah selatan dan timur Batavia, dan rencana penyerangan pun dibuat.
Setelah berbagai kelompok buruh pabrik gula keturunan Tionghoa memberontak, dengan menggunakan senjata yang dibuat sendiri untuk menjarah dan membakar pabrik, ratusan orang Tionghoa, yang diduga dipimpin Kapitan Cina Ni Hoe-Kong, membunuh 50 pasukan Belanda di Meester Cornelis (kini Jatinegara) dan Tanah Abang pada tanggal 7 Oktober.
Untuk menanggapi serangan ini, pemimpin Belanda mengirim 1.800 pasukan tetap yang ditemani schutterij (milisi) dan sebelas batalyon wajib militer untuk menghentikan pemberontakan, mereka melaksanakan jam malam dan membatalkan perayaan Tionghoa yang sudah dijadwalkan.
Karena takut bahwa orang Tionghoa akan berkomplot pada malam hari, yang tinggal di dalam batas kota dilarang menyalakan lilin dan disuruh menyerahkan semua barang, hingga pisau paling kecil sekalipun.
Pada hari berikutnya, pasukan Belanda berhasil menangkis suatu serangan dari hampir 10.000 orang Tionghoa, yang dipimpin oleh kelompok dari Tangerang dan Bekasi, di tembok kota.
Raffles mencatat sebanyak 1.789 warga keturunan Tionghoa meninggal dalam serangan ini. Untuk menanggapi serangan ini, Valckenier kembali mengadakan pertemuan Dewan Hindia pada tanggal 9 Oktober.
Sementara, gosip tak mengenakan mulai tersebar dalam kelompok etnis lain, termasuk budak dari Bali dan Sulawesi serta pasukan Bugis dan Bali.
"Orang-orang Cina itu berencana akan membunuh dan memerkosa gadis kita! mereka pula akan menjadikan kita sebagai budak!! Apakah kita akan berdiam diri saja?!" Pria perut buncit dengan kumis Jampangnya itu berkata dengan penuh ketegasan didepan puluhan masyarakat pribumi lainnya, ia memprovokasi dan mencoba menghasut dan mencuci otak para masyarakat lainnya.
Untuk mencegah hal tersebut, kelompok-kelompok ini mulai membakar rumah-rumah milik orang Tionghoa di sepanjang Kali Besar. Ini disusul oleh serangan Belanda terhadap tempat tinggal orang Tionghoa di Batavia.
Politikus Belanda yang anti-kolonis W.R. van Hoëvell menulis bahwa "wanita hamil dan yang sedang menyusui, anak kecil, dan para pria gaek jatuh dalam serangan. Tahanan dibantai seperti domba".
Pasukan di bawah pimpinan Letnan Hermanus van Suchtelen dan Kapten Jan van Oosten, seorang serdadu Belanda yang selamat dari serangan di Tanah Abang, mengambil posisi di daerah pecinan.
Suchtelen dan pasukannya menempatkan diri di pasar burung, sementara pasukan van Oosten mendapatkan pos dekat kanal.
Sekitar pukul 5.00 sore, serdadu Belanda mulai menembakkan meriam ke arah rumah orang Tionghoa, sehingga rumah-rumah tersebut terbakar.
Suara mesin silih bersautan dengan teriakan ketakutan juga darah yang bertumpahan.
Beberapa orang Tionghoa tewas di rumah mereka, sementara yang lainnya ditembak saat keluar dari rumah atau melakukan bunuh diri.
Yang berhasil mencapai kanal dibunuh oleh pasukan Belanda yang menunggu di perahu kecil, sementara pasukan Belanda lainnya mondar-mandir di antara rumah-rumah yang sedang terbakar, mencari dan membunuh orang Tionghoa yang masih hidup.
Tindakan ini kemudian tersebar di seluruh kota Batavia. Menurut Vermeulen, sebagian besar pelaku merupakan pelaut dan unsur masyarakat lain yang "tidak tetap ataupun baik." Dalam periode ini ada banyak penjarahan dan penyitaan properti.
Pada hari berikutnya kekerasan ini terus menyebar, dan pasien Tionghoa dalam sebuah rumah sakit dibawa ke luar dan dibunuh. Usaha untuk memadamkan kebakaran di daerah Kali Besar belum membawa hasil, kebakaran itu malam semakin ganas, dan baru padam pada tanggal 12 Oktober.
Sementara, sebuah kelompok yang terdiri dari 800 pasukan Belanda dan 2.000 orang pribumi menyerbu Kampung Gading Melati, di mana terdapat orang Tionghoa yang bersembunyi di bawah pimpinan Khe Pandjang.
Biarpun warga Tionghoa mengungsi ke daerah Paninggaran, mereka diusir lagi oleh pasukan Belanda. Terdapat sekitar 450 orang Belanda dan 800 orang Tionghoa yang menjadi korban dalam kedua serangan tersebut.
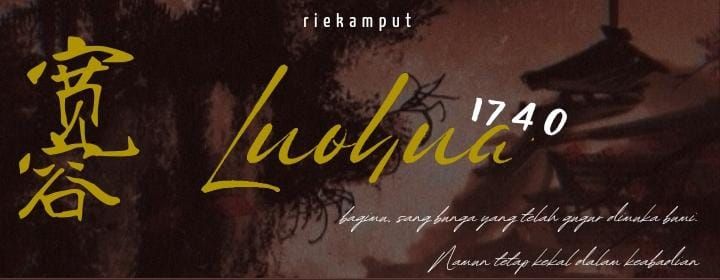
Kekerasan lanjutan.
Pada tanggal 11 Oktober, Valckenier menyuruh para opsir Belanda untuk menghentikan penjarahan, tetapi tidak berhasil.
Dua hari kemudian Dewan Hindia menentukan bahwa setiap orang yang membawa kepala orang Tionghoa akan dihargai dengan dua dukat, hal ini digunakan untuk memancing suku lain agar mereka ikut membantai orang Tionghoa.
"Siapapun yang membawa kepala warga Tiongkok! akan diberi imbalan dua dukat per kepala!" Pemberitahuan dari Dewan Hindia langsung menyebar begitu saja, dan tentu menarik hati semua orang yang mendengarnya.
Akibatnya, orang Tionghoa yang selamat dari serangan pertama mulai diburu bandit yang menginginkan hadiah itu.
Penguasa Belanda bekerja sama dengan kelompok pribumi di berbagai daerah di Batavia, grenadir Bugis dan Bali dikirim untuk memperkuat pasukan Belanda pada tanggal 14 Oktober.
Pada tanggal 22 Oktober, Valckenier memerintahkan agar semua pembunuhan dihentikan.
Dalam sehelai surat panjang yang berisi bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan orang Tionghoa saat kerusuhan di Batavia, dia mengajak orang Tionghoa untuk berdamai, kecuali pemimpin pemberontakan, dia mengajukan penghargaan sebanyak 500 rijksdaalder untuk setiap pemimpin yang dibunuh.
Di luar batas kota terus terjadi pertempuran kecil antara pemberontak Tionghoa dan pasukan Belanda.
Pada tanggal 25 Oktober, setelah hampir dua minggu adanya pertempuran kecil, 500 orang Tionghoa bersenjata berangkat menuju Cadouwang (kini Angke), tetapi dihalau oleh kavaleri di bawah pimpinan Ridmeester Christoffel Moll serta Kornet Daniel Chits dan Pieter Donker.
Pada hari berikutnya kavaleri itu, yang terdiri dari 1.594 pasukan Belanda dan pribumi, mendekati markas orang Tionghoa di Pabrik Gula Salapadjang.
Di sana mereka berkumpul di hutan, lalu membakar pabrik yang masih penuh dengan pemberontak Tionghoa, satu pabrik lain di Boedjong Renje dimusnahkan oleh pasukan Belanda lain.
Karena takut pada pasukan Belanda, orang-orang Tionghoa mengungsi ke pabrik gula lainnya di Kampung Melayu, yang berjarak empat jam dari Salapadjang, markas ini dimusnahkan oleh pasukan di bawah pimpinan Kapten Jan George Crummel.
Setelah mengalahkan orang Tionghoa, pasukan Belanda kembali ke Batavia.
Sementara, orang Tionghoa, yang mulai dikurung 3.000 prajurit dari Kesultanan Banten, melarikan diri ke arah timur mengikuti pesisir utara pulau Jawa.
Pada 30 Oktober dilaporkan bahwa orang Tionghoa tersebut sudah melewati Tangerang.
Perintah untuk gencatan senjata diterima Crummel pada tanggal 2 November. Dia dan pasukannya kembali ke Batavia setelah menempatkan 50 penjaga di Cadouwang.
Ketika Crummel tiba di Batavia, sudah tidak ada lagi pemberontak Tionghoa di luar tembok kota. Penjarahan berlangsung sampai tanggal 28 November, dan pasukan pribumi terakhir dibebastugaskan pada akhir bulan itu.
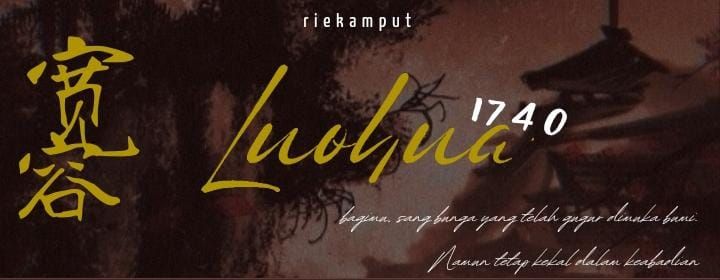
Vermeulen menyebut pembantaian ini sebagai "salah satu peristiwa dalam kolonialisme [Belanda] pada abad ke-18 yang paling menonjol".
Dalam disertasinya, W. W. Dharmowijono menyatakan bahwa pogrom ini mempunyai peran besar dalam sastra Belanda. Sastra ini muncul dengan cepat.
Dharmowijono mencatat adanya sebuah puisi oleh Willem van Haren yang mengkritik pembantaian ini (dari tahun 1742) dan sebuah puisi anonim, dari periode yang sama, yang mengkritik orang Tionghoanya.
Raffles menulis pada tahun 1830 bahwa catatan historis Belanda "jauh dari lengkap atau memuaskan".
Sejarawan asal Belanda Leonard Blussé menulis bahwa Geger Pacinan secara tidak langsung membuat Kota Batavia berkembang pesat, tetapi membuat dikotomi antara etnis Tionghoa dan pribumi yang masih terasa hingga akhir abad ke-20.
Pada abad yang sama, pembunuhan massal ini dicatat juga dalam Bahasa Banjar oleh Abdur Rahman di syairnya, Syair Hemop.
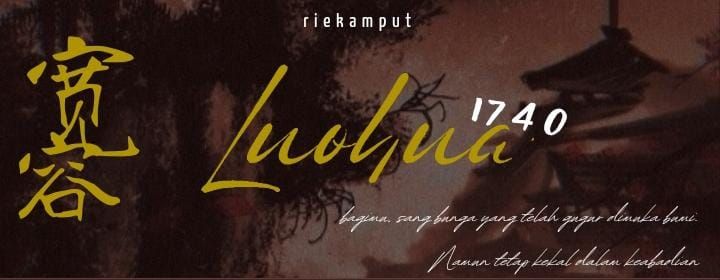
Usai kejadian dahsyat tersebut adakah diantara kalian yang memikirkan nasib kami (yang selamat dari maut)?
Kami tidak mati, kami pula tidak hidup. Apa artinya semua nafas jikalau tiada teman yang menemani?
Hidup enggan, mati pun tak mau.
*sebuah pribahasa yang berarti: seseorang yang tidak bisa berbuat apa-apa
Mungkin itulah kata-kata yang cocok untuk menggambarkan perasaan diri.
Kami tak bisa berbuat apa-apa.
Ketakutan, kebencian, seolah-olah telah menjadi makanan sehari-hari.
Walau rasanya hendak menjatuhkan diri ke jurang. Tetapi yang namanya hidup harus tetap dijalani, kita bukan pecundang, kita adalah pejuang.
TBC..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro