15 Januari 2014
Warning:
Cerita ini diikutsertakan event MWM oleh NPC2301
Dengan target tamat dalam sebulan
Akan ada banyak typo, plot hole, dan segala macam anu
karena dikerjakan tanpa proses semedi lebih dulu
Mohon maap jika hasilnya kurang memuaskan ;-;
Jika ingin bantu razia typo dan anu-anu, silakan komentar
I'd really appreciate it

"Jadi, siapa yang mengambil ini?"
Olive duduk dengan kaki bersimpuh, tangan di lutut, kepala menunduk, mulut tertutup rapat. Di depannya, tasnya telentang, terbuka lebar-lebar, memuntahkan beberapa barang keluar.
Karena tak kunjung ada jawaban, aku mengulangi, "Siapa yang ambil ini—kau atau Wilis?"
Kaki hantuku menyenggol—atau menembus, tepatnya—buku album foto keluarga yang seharusnya berada di loteng. Sudah menguning, halaman demi halamannya lengket, dan jilidannya masih penuh debu serta sarang laba-laba. Sekarang, benda itu berada di lantai kamar Olive—dibawa olehnya dan kakaknya, jauh-jauh dari rumahku.
Aku menunggu, tetapi gadis itu masih bungkam. Kali ini, dengan nada tidak sabar dan betul-betul marah, aku mendesak, "Olive—"
"Aku ..." jawabnya kemudian dengan suara pelan. Kedua tangannya saling remas. "Aku yang ambil."
Kutelan rasa iba dan tidak tega melihat wajahnya. Kulanjutkan dengan menunjuk selembar jaket yang menggumpal, setengah menyembul keluar dari tasnya. "Dan siapa yang mengambil ini?"
"Aku juga." Gadis itu menjawab, kali ini mengangkat kepalanya. "Soalnya masih kelihatan bagus ... aku tidak paham kenapa kau menyimpan ini di loteng—"
"Karena ini bukan punyaku," kataku sambil menekan suara. Gigiku menggertak. Aku berjongkok di depannya, barang-barang yang diambilnya dari loteng rumahku membentang di antara kami. "Ini punya mendiang ayahku."
Olive buru-buru menundukkan pandangannya lagi. "Ma-maaf ...."
"Bagaimana dengan yang ada di dalam tas Wilis?"
"A-ada album foto satu lagi yang lebih kecil." Olive menjabarkan. "Terus ada HP jadul—menurut Wilis, itu punyamu yang sudah lama ... dia bilang, mungkin ada sesuatu di dalam yang kau sembunyikan, walau sebetulnya aku juga sadar kalau dia cuma kepo. Soalnya aku juga begitu—kami berdua kepo. Juga ... Wilis mengambil dompet kecil merah muda—kayaknya itu punya kakakmu. T-tidak ada uang di dalamnya, kok. Wilis bilang, di dalam dompet itu ada fotomu sama kakakmu."
Aku tahu dompet yang dimaksudnya. Desember 2012 yang lalu, waktu Kak Nila ulang tahun yang ke-23—hanya 5 bulan sebelum dirinya hilang—aku memberinya dompet itu sebagai hadiah. Aku memilih warnanya secara khusus karena Kak Nila benci warna merah muda. Namun, kudapati dia tetap membawa-bawanya meski tidak pernah memasukkan selembar uang pun ke dalamnya—itu pun karena kakakku punya kebiasaan menjejalkan uang sembarangan ke dalam tas begitu saja.
"Kami bakal mengembalikan semuanya, kok." Olive berjanji. Matanya memerah. "Kau, 'kan, kemarin bilang agar aku mengalihkan perhatian Wilis supaya dia tidak berpikir untuk menghubungi ibumu ... dan cuma ini yang bisa kulakukan—selain menakut-nakutinya bahwa dia bakal digelandang polisi kalau ketahuan menghilangkanmu. Kau juga harus mengerti, Grey, Wilis cemas—dia ketakutan. Menurutnya, kau hilang. Dia tidak tahu sekarang kau di sini, jadi hantu. Dan dia merasa harus melakukan sesuatu—bahkan meski itu artinya mengambili barang-barang dari loteng rumahmu. Kalau aku jadi dia, aku pasti bakal kalap juga."
"Tapi, yang kalian lakukan ini mencuri!" Aku meninggikan suara tanpa sadar sampai gadis itu terperanjat. "Ada alasannya kami menyimpan benda-benda ini di loteng; tapi kalian, yang bukan siapa-siapa dan tidak tahu apa-apa, membawanya keluar begitu saja. Jelas saja aku marah! Dan jelas sekali Kak Zamrud benar karena mencurigai kalian kemarin!"
Olive gemetaran di tempatnya. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada yang diucapkannya.
Berdecak, aku duduk di depannya, menunjuk barang-barang yang diambilnya. "Masukkan lagi—aku mau kalian mengembalikan ini secepatnya."
Olive menurut tanpa banyak bicara. Sambil memberdirikan tasnya dan melipat jaket mendiang Ayah, gadis itu menyedot hidung. Matanya berkaca-kaca.
"Jangan salah sangka—aku tidak bermaksud terlalu memarahimu. Kalau Wilis bisa mendengar atau melihatku atau menyentuhku, aku bakal melakukan yang lebih buruk."
Alih-alih memperbaiki suasana, ucapanku justru membuat gerakan tangan Olive berhenti. Air mata mulai berjatuhan di wajahnya, menetes ke lututnya, bibirnya ditekan menjadi garis lurus. Sebelum aku sempat bereaksi, gadis itu sudah terisak-isak. Punggung tangannya mengusap hidung.
Beberapa detik pertama, aku cuma terpelongo. Banyak yang berkecamuk dalam pikiranku, menggantikan rasa marah: aku mesti apa? Wilis tidak pernah menangis di hadapanku, dan kalau pun dia melakukan itu, hampir pasti aku bakal menghinanya sampai dia berhenti menangis. Mama pernah menangis di depanku, dan aku memeluknya—tetapi Olive bukan mamaku. Kalau Kak Nila menangis, hal paling baik yang kulakukan adalah memberinya tisu supaya ingusnya tidak memeper padaku.
Kejadian yang paling mendekati saat ini paling-paling adalah saat aku kelas 1 SD, saat anak perempuan yang duduk di depanku menangis gara-gara aku dan teman sebangkuku main bola di dalam kelas dan tidak sengaja menggetok kepalanya pakai bola sepak. Apa tindakanku waktu itu buat menghiburnya?
Ah ... ya, kami lari. Sampai anak perempuan itu ditenangkan teman-temannya, kami jajan di belakang dan bersikap seolah tidak ada apa-apa.
Mana bisa aku menerapkan itu ke Olive?!
"Wah, wah, wah." Dari balik kaca jendela dan pintu balkon, Kinantan melongokkan kepalanya ke dalam. "Drama apa pagi-pagi begini? Aku boleh menonton?"
Aku memelototinya dari sudut mata.
"Kau tidak perlu menangis ..." kataku dengan suara melunak. "Aku tidak marah lagi, Olive."
"Tadi, kau marah!"
"Sekarang sudah tidak." Aku meyakinkannya.
"Aku malu, tahu?" ujarnya sesenggukan. "Aku tahu, kok, kami salah—kami kayak maling, masuk ke rumahmu, mengambili barang-barang ...."
Aku mengangguk-angguk. "Betul."
Tangisannya bertambah keras, membuatku jadi kepingin menepuk mulut sendiri. Barangkali aku memang berlebihan ....
Bagaimana pun Wilis dan Olive memang bermaksud membantu. Tindakan mereka kelewatan, tetapi mereka memang berniat menolongku. Aku tidak bisa marah pada niat itu. Dan malam ini adalah acara reuni SMA—Olive bakal menemui Kak Safir, menjadi penghubungku dengannya. Aku tidak boleh mengacaukannya dengan mengamuk.
Yah, memang amukan macam apa juga yang bisa kulakukan sebagai hantu? Menembus benda-benda dengan brutal?
Di depan pintu balkon, kini sepenuhnya berada di dalam kamar, Kinantan berdiri dengan kedua lengan terlipar di depan dada. Kepalanya menggeleng-geleng menghakimiku, tetapi bibirnya menyunggingkan senyum gembira.
Barangkali Olive menangis selama satu atau dua menit, dan selama itu aku cuma duduk di sana dengan kaki bersila, memelototi jari kakiku sendiri. Tangisannya baru mereda ketika Denim, yang sejak tadi hanya berbaring di atas bantal, akhirnya melompat turun dan mengendus-endus jaket mendiang Ayah.
"Sori," kataku setelah Olive mengangkat Denim kembali ke atas bantalnya. "Aku berlebihan. Aku tidak bermaksud membentakmu."
Gadis itu mengambil tisu dan menotol-notol wajahnya. Hidungnya merah. "Kami memang salah ...."
"Tidak, aku juga salah. Aku jadi membebani kalian."
"Oh, ini tidak seru lagi." Kinantan mendengus dan melengos pergi. Dari luar, si gadis hantu berseru, "Teriaklah kalau kalian bertengkar lagi!"
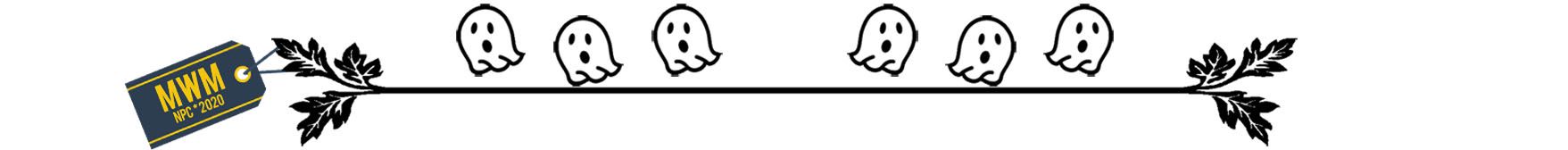
Malam itu, seperti yang diharapkan, resto keluarga itu penuh dengan muda-mudi alumni SMA kami—jumlah mereka sekitar 27 atau 29 orang, minus beberapa yang dipastikan tidak datang, terlambat, dan batal hadir.
Resto keluarga Wilis dan Olive tidak besar, tetapi juga tidak bisa dibilang kecil. Menggunakan ruko sewaan setinggi dua lantai, resto itu murah meriah, tampak ramai dan benderang di malam hari, dengan meja-meja dan kursi panjang di tiap sisi dan meja-kursi untuk empat orang di tengah-tengah. Nasi-nasi lalapan di antarkan ke meja-meja, berpiring-piring mi yang baru digoreng tersaji di atas nampan, bergelas-gelas minuman dingin dan hangat berdatangan, dan terdapat antrean yang lumayan panjang di meja kasirnya. Di lantai dua sedikit lebih sepi; hanya tersedia tempat lesehan, dan di sinilah reuni itu berlangsung.
Sesuai rencana, Kak Safir ada di sana. Yang di luar rencana ... Kak Zamrud juga ada.
"Itu kakak yang kemarin!" Olive mendesis-desis, tangannya terangkat menutupi sisi wajahnya. "Kenapa kau tidak bilang kakak itu juga sekelas dengan Kak Safir?!"
"Mereka tidak sekelas!" Aku menukas. "Kak Safir dan kakakku kelas IPS, Kak Zamrud kelas IPA ... kecuali reuni ini memang dihadiri lebih dari satu kelas dari angkatan mereka!"
Olive mengeluarkan ponselnya dan mengecek akun sosial media milik Kak Safir. Dia segera mencari semua post yang berhubungan dengan reuni dan menggulir layar pada komentar-komentarnya. "Ada sekitar ratusan obrolan mereka di sini! Bagaimana bisa aku menemukan—oh ... oh, ini dia. Iya ... ada tiga kelas yang ikut reuni malam ini."
Aku menepuk muka.
"Aku tidak bisa ke sana!" Olive mendesis lagi. "Kakak itu bakal mengenali wajahku! Bisa-bisa dia mengadu ke ibuku!"
"Tapi, kau mesti mendekati Kak Safir! Cuma ini kesempatan kita!"
"Tidak bisakah kau menumpahkan minum atau bikin tisu melayang-layang di depan Kak Zamrud biar dia pergi?"
"Aku tidak bisa menyentuh benda!"
Olive menjentikkan jari. "Kalau begitu, aku akan menunggu Kak Safir kalau dia memisahkan diri! Misal ... kalau dia ke toilet!"
Aku mengerjap. "Yah, ide bagus, sih ... tapi kalau dia ke toilet, bukannya dia bakal masuk ke toilet cowok?"
Olive merengut. Kakinya menghentak-hentak. "Aku mencoba cari solusi di sini—berhentilah cari-cari masalah dari solusiku!"
Aku menatap gelisah ke meja mereka. Kak Safir sedang berdiri, memberi gestur ke teman di sebelahnya kalau dia hendak salat. Ketika aku akan memberi tahu Olive momen itu, Kak Zamrud malah ikut berdiri bersama beberapa anak cowok lain di sebelahnya. Bersama-sama, mereka melewati kami menuju musala yang berseberangan dengan toilet. Olive buru-buru berpaling dan melongokkan kepalanya keluar jendela yang terbuka.
"Dia melihatku?" tanyanya tegang.
"Kurasa, tidak." Mataku mengawasi sementara mereka menghilang ke arah koridor. "Coba minta ke ayah atau ibumu, suruh mereka memanggil Kak Safir ke meja kasir atau apalah."
"Nanti ayah dan ibuku tanya-tanya buat apa!" Olive memelotot. "Kalau begitu, kita tunggu saja mereka keluar. Mungkin mereka keluar sendiri-sendiri ...."
Kami menunggu sampai sepuluh menit. Dua di antara para cowok tadi keluar dari musala, bersamaan dengan Wilis yang naik sambil membawa dua nampan sisa pesanan. Pemuda itu memelototi Olive dari kejauhan, menyuruhnya membantu ke bawah melalui gerakan bibir dan gestur tangan, yang dibalas Olive dengan juluran lidah. Keduanya bertukar ejekan dengan jari tangan sebelum akhirnya Wilis menuruni tangga.
Beberapa orang lagi keluar dari musala; Olive seperti hendak melompat dari jendela karena mengkhawatirkan Kak Zamrud, sedangkan aku menegakkan tubuh karena menunggu Kak Safir. Namun, itu bukan mereka.
Lima menit kemudian, Kak Zamrud keluar, Kak Safir di sebelahnya. Aku mendesak Olive, tetapi gadis itu ngotot tidak mau menghampiri mereka.
Untunglah—betul-betul keberuntungan dan timing yang tepat—Kak Safir terdiam dan meraba saku samping celananya. Dia mengeluarkan ponsel, yang tampaknya berbunyi, lalu memberi gestur pada Kak Zamrud untuk berjalan duluan. Kak Safir menyingkiri ke pojok dekat tanaman hias, berdiri di samping jendela, mengangkat telepon seseorang.
Kak Zamrud lewat agak terlalu dekat. Olive kembali menyandar ke jendela, kali ini dengan lebih natural, bahkan kakinya tersilang santai, seolah-olah dia hanya melihat pemandangan—padahal hanya ada atap-atap seng kumuh di antara temaram lampu jalan sejauh mata memandang. Kak Zamrud sempat melirik ke arah Olive yang membelakanginya, tetapi hanya sambil lalu, seperti tatapan tak sengaja, lalu lanjut berjalan ke meja teman-temannya, kembali ke kursinya.
"Tadi dia melirikmu." Aku memberi tahu Olive.
"Ya, sudah biasa, punggungku saja sudah menarik perhatian," kata gadis itu. Tangannya merapikan rambut yang baru saja tersaput angin. "Kau mesti gerak cepat sebelum aku diambil orang, Grey."
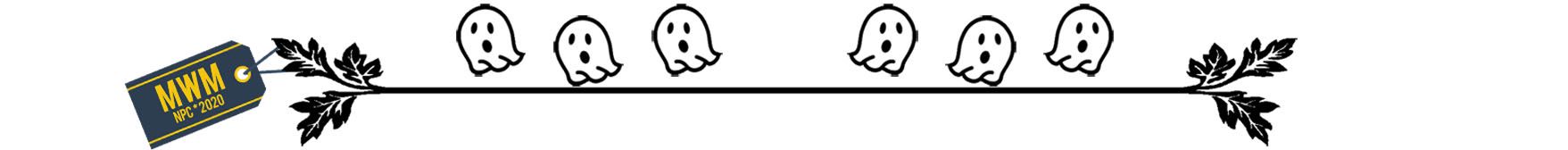
Olive menunggu tepat di belakang Kak Safir yang memunggunginya sampai pemuda itu selesai menelepon.
Kak Safir baru saja menjauhkan ponsel dari telinga dan belum lagi berbalik saat Olive menyambar kesempatan.
"Hai, Kak!" Gadis itu menyapa dengan nada ceria. Kedua tangan tersimpan ke belakang, senyum mengembang.
Kak Safir menelaah Olive sebentar. Sambil mengernyit, dia membalas senyum Olive. "Halo? Kita pernah bertemu?"
"Pernah." Gadis itu mengangguk. "Sekitar dua detik yang lalu waktu aku bilang hai."
Kak Safir tertawa sopan. Parasnya menunggu Olive mengucapkan keperluan.
"Begini." Olive memulai, membuatku berdebar-debar penuh rasa antisipasi. "Aku mengirim pesan ke medsos kakak beberapa hari yang lalu ... hmm, namaku Olive."
Olive memberi tahu nama akunnya. Senyum Kak Safir turun sedikit walau tidak lenyap sepenuhnya. Keramahan memudar dari matanya. Tangannya terangkat untuk mengusap tengkuk dengan canggung. "Ah, iya ... maaf, kukira itu pesan iseng, jadi tidak kubuka. Jadi, ada apa?"
Debar jantungku makin kencang, dan pada titik itulah aku menyadari ....
Bagaimana bisa aku merasakan sesuatu menggedor dadaku di saat jantungku tidak ada di sini?
Aku hanya sewujud kesadaran di sini—ruh, arwah, manifestasi penuh, tetapi bukan jasad. Secara fisik, aku tidak di sini. Jantungku juga. Jadi ... dari mana munculnya detak di balik rongga dadaku ini?
"Aku temannya Grey—adiknya Kak Nila," kata Olive lagi. Pada titik ini, wajah Kak Safir berubah datar. Olive tampaknya menyadari itu juga karena suaranya jadi bergetar dan penuh keraguan. "A-aku butuh bantuan Kakak. Saat ini Grey sedang kesulitan. Hanya beberapa pertanyaan, kok."
Ujung-ujung jariku tergelitik. Sudah lama sekali aku tidak merasa seperti ini. Aku nyaris menyangka bisa mengangkat meja panjang di sampingku dan melemparkannya ke luar jendela. Aku merasakan semilir angin. Aku membaui aroma makanan dari meja-meja. Aku merasa ... hidup sungguhan.
Sesaat berlalu, momen itu hilang, lalu muncul kembali, dan memudar sampai lenyap. Ia timbul tenggelam.
Ini berbeda dengan yang kurasakan saat berdekatan dengan Olive. Pikiranku mungkin lebih manusiawi dan wujudku terasa lebih utuh di dekat gadis itu karena kehadiranku kini terikat dengannya. Namun, sensasi yang ini benar-benar seperti harapan hidup. Seperti pintu yang terbuka lebar-lebar dan mempersilakanku masuk melewatinya agar aku bisa kembali ke kehidupan—menjadi bebas ke dalam bentuk tetap, bukannya terjebak di antara ada dan tiada yang mengombang-ambingkan wujudku.
Lalu, kusadari ini datangnya dari Kak Safir.
Aku tidak memerhatikan sebelum ini, tetapi dari dekat, Kak Safir seperti lebih terang. Bukan berarti badannya jadi menyala-nyala seolah dia habis menelan lampu atau apa. Maksudku, seperti ada aura yang menyelubunginya, membuatnya tampak mencolok. Lebih dari itu sekujur jasadnya adalah celah besar, terekspos, mengundang untuk dimasuki.
Aku menarik napas, lalu terkejut sendiri karena rasanya memang seperti sungguhan bernapas. Hanya sekejap, seakan-akan ada udara sungguhan masuk ke hidungku dan keluar lagi. Bayangkan kalau aku masuk ke tubuhnya ... aku bisa bernapas sungguhan. Aku bisa menyentuh barang-barang. Aku bisa berjalan. Aku bisa bicara dengan orang-orang. Kakiku akan menapak, tubuhku akan berbobot, isi kepalaku akan jadi jernih, dan segalanya bakal lebih jelas seterang siang bolong. Tidak akan ada lagi sensasi mengambang di permukaan air, diseret arus, sambil membeku dan kehilangan orientasi terhadap waktu.
Sebentar saja ....
"Grey!" Olive menyentakkanku.
Ketika aku sadar dari trans, kedua tanganku sudah terulur. Hanya sejengkal dari leher Kak Safir.
Aku buru-buru menurunkan tangan, melawan hasrat dan memadamkan harapan yang mencekik. Di belakangku, Olive tampak tegang dan ketakutan.
"Grey?" tanya Kak Safir. Matanya melirik ke sana kemari. "Apa aku tidak salah dengar—tadi kau memanggilku Grey?"
"Bukan!" Olive menggeleng kuar-kuat. "M-maksudku, ada Grey di sini."
"Ya? Di mana dia?"
Wajah Olive mengerut, kakinya berganti tumpuan dengan kikuk. Di belakangnya, di puncak tangga sana, Wilis naik dengan celemek berantakan dan kerah baju yang bernoda kecap. Matanya mencari-cari, lalu berhenti di Olive.
"Grey tepat di depan Kakak." Olive menuturkan sambil memainkan jari-jari tangannya. Kepalanya menunduk, jadi dia tidak menyadariku yang membelalak karena saat ini tengah terjadi dua hal:
Satu, Wilis berderap ke arahnya.
Dua, Kak Zamrud melihat Wilis dan mengenalinya, lalu mengendap mengikutinya.
"Beberapa hari yang lalu, Grey masuk ke salah satu rumah yang ... anu, ada penunggunya. Aku yakin Kakak paham maksudku. Jadi, sejak itu, Grey hilang. Tapi, ternyata dia tidak hilang—jangan menyela Grey." Gadis itu mengangkat satu tangannya saat aku memanggil namanya dan menyela. "Ya, seperti yang Kakak lihat sekarang, aku mungkin kelihatan bicara sendiri, tapi aku tidak bicara sendiri. Ada Grey di sini. Dia ... jadi hantu. Tapi, dia bilang dia masih hidup. Jasadnya entah ketinggalan atau apa di rumah itu."
"Apa?" Pertanyaan ini bukan meluncur keluar dari mulut Kak Safir, melainkan Kak Zamrud yang berdiri persis di belakang Olive. "Ulangi perkataanmu tadi."
Di samping Kak Zamrud, Wilis tampak membatu. Matanya menatap kosong ke punggung adiknya.
Bola mata Olive bergulir panik dan bolak-balik antara Kak Zamrud dan Wilis. Bibirnya dilipat ke dalam, lalu mengulas senyum canggung.
"Grey jadi hantu," kata Olive, tampak pasrah sepenuhnya di balik senyum ceria yang dipaksakan. "Barusan dia mencoba merasuki Kak Safir."
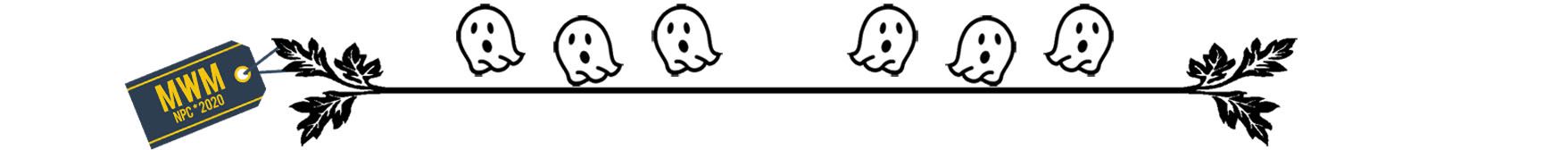
Meja-meja di pojok sana riuh oleh reuni. Di pojok sini, suasananya mencekam, canggung, dingin, menyeramkan, dan penuh kepanikan.
Olive bercerita kronologinya dari awal, agak makan waktu karena penjelasan gadis itu berputar-putar diwarnai kegugupan. Sesekali aku menambahkan penjelasannya, yang dikutip sama persis oleh gadis itu dan dia akan berkata, "Begitu kata Grey barusan."
Wilis masih diam, matanya menatap ke kakinya sendiri kali ini. Kak Zamrud menyimak dengan kening mengerut dan sesekali mengajukan pertanyaan. Kak Safir ... aku tidak bisa menebak ekspresi wajahnya sama sekali; dia sama diamnya dengan Wilis, tetapi matanya memerhatikan Olive, tampak menyimak sekaligus tidak, punggung ditegakkan seolah tidak sabar hendak meloncat keluar lewat jendela di sampingnya.
"Aku paham kalau Kak Safir sudah tidak ingin terlibat lebih jauh dengan perkara astral, terutama setelah apa yang terjadi pada kakakku, dan aku meminta maaf untuk yang terjadi hari itu."—Olive mengulangi ucapanku. "Begitu kata Grey."
Wajah Kak Safir mengeras. "Aku ditahan polisi 24 jam, Grey."—Lalu, alisnya mengerut sedikit. Jarinya menunjuk. "Tunggu, dia di sini? Atau di sini?"
Olive meraih telunjuk Kak Safir, mengarahkannya ke depan hidungku.
"Oke." Kak Safir menarik kembali tangannya dan mengulangi, kali ini menatap tepat ke arahku walau kurasa dia tidak bisa melihatku. "Aku ditahan 24 jam. Penerbanganku ke Jawa ditunda dan aku hampir batal dapat pekerjaan gara-gara kasus itu masuk berita. Abu bahkan tidak bisa keluar dari kantor polisi sampai 48 jam karena semua orang menyangkutpautkan masalah personalnya dengan Nila di masa lalu. Belum lagi karena dialah orang terakhir yang melihat Nila."
Kak Safir melambai ke meja yang ramai oleh teman-temannya. "Lihat? Tidak ada Abu. Dia memutuskan kontak sama sekali sejak kasus itu. Terakhir kudengar, dia ikut bekerja dengan kerabatnya sekarang, dan sama sekali tidak mau berhubungan dengan satu pun dari kami—sama sekali."
"Tapi, itu bukan salah Grey," kata Olive. "Dan sekarang Grey betul-betul butuh bantuan."
"Aku tidak bisa melakukan apa-apa." Kak Safir menekuri jari tangannya di atas meja. "Aku sudah tidak pernah lagi melakukan proyeksi astral sejak bertahun-tahun, dan kuharap tetap begitu."
"Bagaimana dengan beberapa pertanyaan?" mohon Olive. "Grey hanya mau bertanya apakah Kakak pernah ... apa tadi Grey?"
"Memengaruhi lintasan waktu—mencampuri masa lalu atau masa depan."
Olive menyampaikan ucapanku, membuat ekspresi Kak Safir hampir sama murkanya jika gadis itu langsung saja mencoloknya di mata.
"Aku tidak mau terlibat dengan apa pun yang Grey inginkan saat ini." Suara Kak Safir agak meninggi. Tangannya memukul meja. "Aku tidak mau mengingat lagi bagaimana rasanya atau apa saja yang terjadi saat masih mampu melakukan proyeksi astral. Katakan pada Grey, jika dia bisa langsung menemukan tubuhnya, lakukan saja apa yang sudah seharusnya dilakukan, jangan terlalu banyak tingkah—kecuali dia mau berakhir seperti kakaknya!"
Setelah mengatakan itu, Kak Safir bangkit dari meja dan berderap meninggalkan kami yang terdiam. Dia ke meja seberang, mengambil jaketnya, tampaknya berpamitan dengan teman-temannya di reuni. Wajahnya pucat, berkilau karena keringat, dan senyumnya redup.
Tanpa menoleh, pemuda itu menuruni tangga terburu-buru.

ヾ(*゚ー゚*)ノ Thanks for reading
Secuil jejak Anda means a lot
Vote, comment, kritik & saran = support = penulis semangat = cerita lancar berjalan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro