XIII - Stoik
Cinta yang hanya bertahan sesaat, tidak memiliki arti.
Aku ingin berteriak dan menangis, sambil tenggelam dalam cinta yang tak berujug.
Tak bisa menghindar, sampai terombang-ambing, dan hancur berkeping-keping.
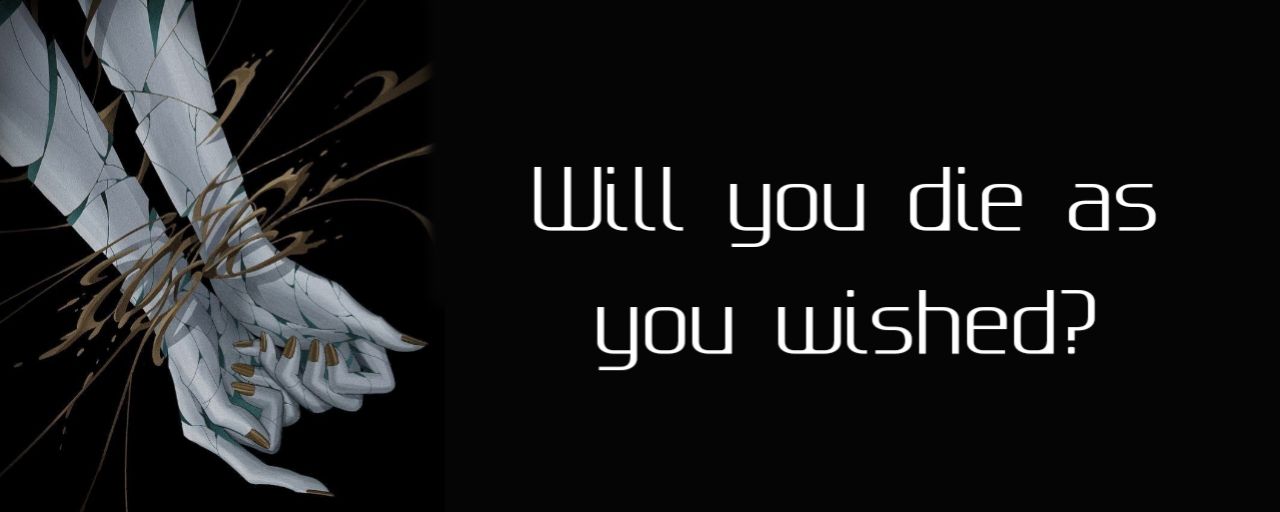
Aku sedang tertarik dengan cara berpikir Stoisisme, di mana mereka percaya bahwa ada dua hal penting yang perlu kita sadari; hal yang bisa dikendalikan dan hal yang di luar kendali. Hal yang bisa dikendalikan seperti emosi, cara pandang kepada suatu masalah, dan reaksi kita untuk menghadapinya. Sedangkan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan seperti jalan pikir orang lain, perasaan mereka, semua hal yang akan terjadi di luar kemampuan manusia seperti cuaca, rezeki, musibah, dan masih banyak lagi.
Karena itulah orang-orang yang paham akan stoik akan percaya bahwa kebahagian bukan berasal dari luar, tapi dari dalam, dari diri kita sendiri.
Buku bersampul hitam ini terlihat tidak berbeda dengan buku tebal yang berjejer di rak display. Namun kalau dilihat saksama, akan terlihat bahwa buku itu dibalut ukiran simbol yang rumit di tiap sisinya. Seperti mantra yang sengaja disembunyikan. Judulnya dibumbuhi tinta warna silver yang estetik; Cara Berdamai dengan Dunia--judul yang segera mencuri perhatianku.
"Itu buku langka," ujar pegawai dari toko bekas yang sedang kukunjungi. "Saran saya, kalau tidak segera dibeli, nanti keburu ada orang lain yang membelinya." Entah apa yang dia katakan hanyalah buaian manis dari seorang pembisnis atau itu memang adalah fakta yang belum kuketahui, tapi aku mencengram buku itu dengan penuh harap.
Pegawai itu mempersilakanku untuk membalikkan halamannya dan membaca jika aku ingin memastikan apakah sesuai dengan seleraku atau tidak. Tapi tidak peduli seberapa banyak halaman yang dibuka, isinya begitu memikat. Rasanya kalimat-kalimat yang tertulis di sana mengalir langsung ke dalam memoriku.
Pada akhirnya aku membeli buku yang ditulis oleh para filsuf terkenal itu. Benda itu sudah seperti harta karun yang harus kubawa ke mana saja. Buku pusaka yang akan menuntunku ke arah yang benar.
Namun aku tidak pernah menyangka, salah satu ajaran mereka untuk selalu bersiap dengan skenario terburuk dalam kehidupan ternyata benar-benar terjadi padaku. Dan, sejujurnya, aku belum siap untuk menghadapinya.
Aku pulang ke rumah dalam keadaan lesu. Tidak sempat menyapa Ibu yang sedang menyiapkan makan malam. Tubuhku seakan berjalan sendiri menuju kamar, ambruk di atas kasur tanpa melepaskan pakaian yang sudah dipenuhi keringat dan pilu.
Sesaat aku memandang langit-langit kamar yang suram, aku langsung membayangkan kembali ruangan Pak Alvi yang terekam dalam ingatanku. Pria itu rupanya sudah tahu akan kedatangaku. Dia seolah bisa membaca tindakanku selanjutnya, percuma sembunyi maupun kabur darinya.
Waktu telah menunjukkan pukup tujuh malam, saat-saat di mana tubuhku sedang berada di puncak jenuhnya. Rasa lelah mulai muncul ke permukaan, tindakan apa pun terasa tidak bisa dilakukan. Matahari yang mulai meluncur ke balik bumi membuatku ingin segera memejamkan mata. Menutup lembaran kehidupan untuk hari ini dan bersiap dengan lembar kosong untuk hari esok.
"Rinda? Makan malam!" seru Ibu dari arah dapur. Sontak tubuhku bangkit dari kasur dan duduk dengan sangat terpaksa.
Dampak dari aksiku tadi sore sudah menandakan hari-hariku bakal menjadi serentetan hari terburuk sepanjang hidupku. Aku harus maju dalam menghadapi masalah yang akan terus menghantuiku ke mana saja. Maka aku harus bersiap dengan asupan energi dari sumber apapun. Tumbang sebelum bertarung bukanlah prinsip kehidupanku.
Setelah makan malam yang sederhana bersama Ibu, aku kembali ke dalam kamar dan menguncinya dari dalam. Kuraih tas ransel yang biasa kubawa ke kampus dan mengeluarkan buku sakral yang mungkin saja akan menjawab kegundahanku yang tidak mau menyingkir di dalam kepalaku.
Dan benar saja, aku langsung menemukan sebuah pencerahan.
'Dalam upaya itu, yang penting bukanlah anugerah keberuntungan, memiliki hak istimewa bawaan, dan menghindari hal-hal yang secara alamia tidak disukai. Tetapi menjadikan nalar sebagai prinsip yang menentukan segala hal. Tak peduli kita mengalami kemalangan atau kemujuran.'
Itu artinya, aku harus berpikir secara terbuka atas masalah yang sekarang kuhadapi. Meski lawanku lebih kuar, memiliki keistimewaan sejak lahir, dan berpengaruh di lingkungan kerjaku. Pasti ada celah, meski itu sangat kecil sekalipun.
Semua orang punya kelemahan--termasuk Pak Alvi. Segala hal yang berkaitan dengannya memang terlihat sempurna, tapi aku rasa dia mendekatiku bukan karena suka dalam artian 'cinta'.
Seingatku, saat aku menolaknya di kantin, tatapan ketakutan tampak jelas di netranya.
Apa dia takut dengan sebuah penolakan?
Ya, bisa jadi. Karena dia sudah terbiasa hidup serba ada dan semua keinginannya bisa dikabulkan dalam sekejap, maka dia akan syok jika ada orang yang tidak sepemikiran dengan dirinya.
Seperti bocah saja. Dasar anak manja.
Aku berjalan ke depan meja kerja dan mulai menulis prediksi di atas papan tulis kecil yang ada tanpa terburu-buru. Aroma spidol yang tercium di tanganku sejenak membuatku tenang. Decitan kecil yang membuat ngilu anehnya tidak mengangguku selama menulis. Mataku terfokuskan pada rentetan reaksi yang pernah kudapati saat menghadapi Pak Alvi.
Saat itu wajah Pak Alvi dipenuhi dengan ketakutan sekaligus ketetapan bahwa dia akan mengejar mangsanya sampai sepenuhnya menjadi miliknya. Suatu ekspresi yang tidak pernah aku ketahui sebelumnya. Entah mengapa aku merasa raut wajah pria yang berdiri di hadapanku saat itu, walaupun menakutkan, begitu menadambakan hingga membuatku merasa sesak. Jika orang lain yang dia hadapi, apakah pria itu akan menunjukkan raut wajah yang sama?
Pemandangan dari jendela kamarku yang tidak pernah berubah dan udara menyesakkan yang terbendung di dalam ruangan sempit ini, membuatku jauh lebih sedih. Jika dibandingkan dengan kenyataan bahwa aku tidak bisa lagi menjalankan hari seperti biasanya, aku lebih gelisah dengan kenyataan bahwa aku telah melakukan kesalahan fatal yang akan mempengaruhi orang-orang di sekitarku.
Saat aku hendak menyalakan laptop di meja, aku melihat sebuah pesan masuk di ponselku yang tergeletak tidak jauh dari situ.
Terlihat potongan pesan Eria di layar hitam itu; Rinda, gawat nih!
Tanpa berpikir panjang, aku membuka kunci ponsel dan membaca pesan itu secara utuh.
[Rinda, gawat nih! Aku melupakan dompetku di ruangan Pak Alvi! Aduh ... bodohnya diriku. Maafkan aku, tapi, bisakah kamu menemaniku ke sana? Aku tidak mau sampai orang lain yang mendapatkan dompet itu.]
Helaan napas lolos dari mulutku, tidak menyangka akan mendapati kebiasaan buruk Eria muncul di waktu yang tidak tepat. Aku mengetik balasan dalam diam.
[Tidak akan hilang itu. Bisa jadi Pak Alvi sudah mengamankannya. Memang kamu taruh di mana?]
[Di balik bantal sofa. Uhhh ... aku tidak bisa menunggu sampai besok. Sudah dapat dipastikan malam ini aku akan terjaga dengan berbagai skenario bahwa dompetku akan lenyap untuk selamanya.]
[Eria ... tenangkan dirimu. Baiklah, aku akan pergi menemanimu. Tapi kamu coba hubungi Pak Alvi, apakah dia melihat dompetmu atau tidak.]
[Siap! Terima kasih, BESTICUUUU!!!]
Malam ini pun aku akan sulit untuk beristirahat dengan tenang.

Kalian pasti pernah, kelupaan barang di suatu tempat sampai panik dan menyesal. Sampai pengen mengulang waktu agar kebodohan itu tidak terjadi.
Kalau aku pasti bakalan panik, kepikiran, nangis, habis itu pergi mencari seperti orang buta. Hiks.
Atau kalian tipe yang menerapkan stoik jadi kalau tertimpa hal seperti itu, berserah diri dan membiarkan keadaan yang menuntun sebaiknya seperti apa?
Jangan lupa bintangi, komentari, dan share. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro