V - Vila
Aku tersesat di dunia yang penuh kebohongan yang tak berharga.
Akan kutinggalkan hari esok dan terus menari dalam mimpi.
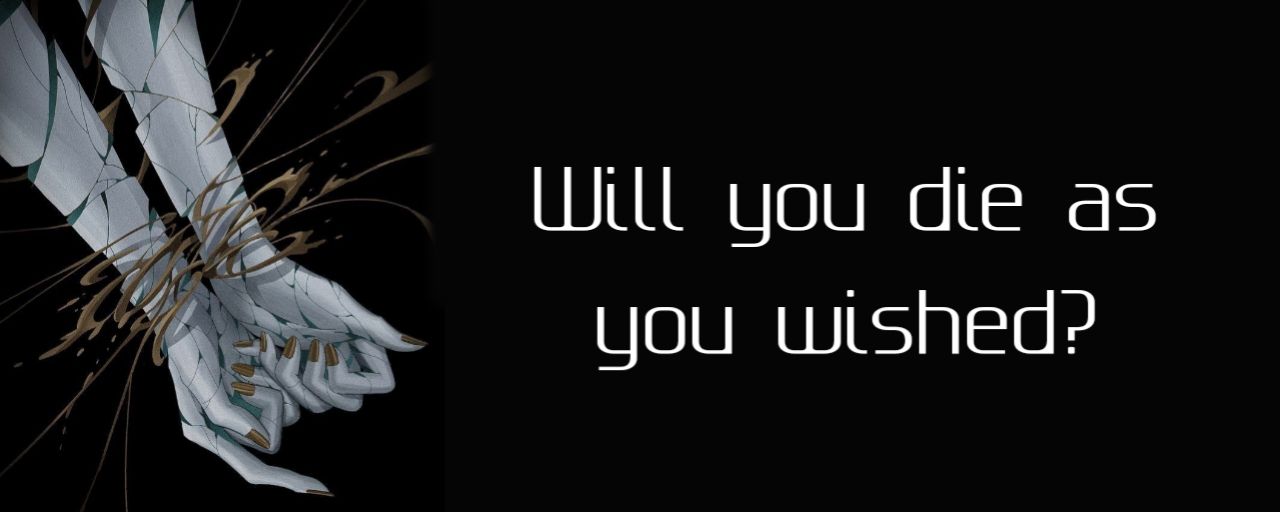
Kami pergi dari pagi buta.
Keluar dari kota yang rendah dan sempit, menuju dataran yang lebih tinggi, menuju jalan yang lebih lebar, dan langit yang lebih luas.
Aku tidak menyangka akan kembali menghirup aroma daun yang basah akibat embun pagi yang dingin nan sejuk. Merasakan kehangatan mentari terbit yang menyentuh kulit dengan lembut. Ditambah pohon-pohon rindang yang disulap menjadi payung alami di bahu jalan, membuat berkas-berkas cahaya yang berkilauan, seperti lampu sorot yang mengantarkan diriku ke sebuah vila yang tersembunyi di labirin hutan yang dalam.
Nuansa yang amat berbeda ketika berada dalam kota, di mana semuanya terasa serba cepat. Sesaat kamu membuka mata, di mana kamu masih ingin berleha-leha di atas kasur, pekerjaan ataupun kewajiban telah menyapamu lebih dulu. Terombang-ambing dalam masalah yang melelahkan dan tak ada hentinya.
Kamu ingin bisa menyelesaikan satu hari tanpa ada senggol bacok dengan pihak manapun. Bagaikan menumpulkan segala indera demi fokus dalam satu titik, melupakan segala hal kecil namun berarti di sekitar kita. Alam yang sedari tadi terus mengawasi tanpa meminta balasan, perlahan menghilang dan digantikan dengan benda mati yang menguasai tanah dan membubung tinggi ke angkasa.
Inilah alasan utama mengapa aku bersikeras ingin bergabung dalam kegiatan family gathering ini. Kami, para budak kampus, bisa membuka segala belenggu yang terus-menerus melekat setiap harinya. Mendengar suara alam yang harmonis, menghirup aroma kehidupan, merasakan angin yang terus mencoba memeluk dan menuntun kita pada kesyukuran tiada batas.
Untuk sejenak, aku bisa tenang. Menikmati keindahan yang terus kulukis dalam ingatan.
Saat aku mendongak ke atas, melihat barisan gunung yang tertutupi kepulan awan putih pekat, aku larut dalam kenangan yang sudah lama tidak tersentuh lagi. Kenangan tentang aku bersama Ayah dan Ibu pergi berkemah di dekat danau yang airnya seperti laut jernih nan tenang, di kelilingi barisan gunung yang tinggi. Ibu selalu menyebutnya Danau Lazulu--walau itu bukan nama danau yang sebenarnya--namun aku lebih suka nama pemberian Ibu.
Lebih menarik.
Ibu memasakkan makanan di atas api unggun. Ayah mengajakku mengambil air di danau menggunakan balon karet yang super elastis. Sesudah makan malam, kami bernyanyi di bawah langit hitam tak terbatas yang dipenuhi ratusan bintang yang berkelap-kelip. Lalu dibuat tertawa terpingkal-pingkal ketika Ibu menceritakan aib Ayah semasa SMA sesaat kami melihat bintang sebagai butiran ketombe. Dan tidak sadar sudah terlelap di dalam dekapan mereka.
Aku selalu berdoa sebelum tidur, berharap bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang panjang. Terbangun di dalam tenda, dan ketika aku keluar, Ayah dan Ibu masih saling membutuhkan satu sama lain.
"Rinda? Kamu tidak apa-apa? Daritadi murung terus," tanya seorang kolega yang cukup dekat denganku, Melly. Aku baru sadar selama ini menyusuri jalan setapak sembari melamun. "Apa kamu mabuk kendaraan?" lanjutnya.
"Ah, tidak. Maaf, aku terlalu menikmati pemandangan di sini." Aku tidak berbohong. Meski tidak sepenuhnya benar.
Melly tertawa kecil. Dia sedikit menutup mulutnya dengan telapak tangan. "Kamu seperti tuan putri yang baru keluar dari antah beranta. Sisa menunggu pangeran yang akan mengajakmu berkeliling." Wanita yang mengenakan topi merah jambu itu mengedipkan sebelah matanya kemudian berlari mendahuluiku, mengikuti teman-teman kantor yang sudah masuk lebih dulu ke dalam vila yang megah nan asri.
Seseorang menepuk pundakku sekali dan sesaat aku berbalik, seulas senyuman manis terpahat indah di wajahnya. Sinar mentari membuat segurat luka cukup dalam di dekat bibirnya tampak. "Halo. Kita ketemu lagi," ucap Pak Alvi ceria.
Padahal aku sudah tidak ambil pusing dengan kejadian memalukan di kantin. Kenapa lagi dia mendekatiku? Apa urat malunya sudah putus?
Hush! Rinda! Kendalikan dirimu. Berpikir positif. Bertindak positif.
Kubalas sapaannya dengan senyuman lebar. Senyuman itu sebenarnya tulus karena aku bukan memikirkan maksud terselubung si playboy satu ini, tapi karena perasaanku hari ini memang sedang bagus. "Selamat pagi, Pak Alvi. Ada yang bisa saya bantu?"
Pak Alvi mengusap dagunya yang tampak habis dicukur bersih tadi pagi. Masih terlihat sedikit rambut-rambut kecil nan tajam tertinggal di sana. "Waduh. Jangan terlalu kaku, Rin. Kita kan seumuran. Setidaknya kita bisa PDKT lebih mudah, gitu."
Astaga ... dia masih tidak menyerah juga? Apa dia masih waras?
"Maaf, Pak. Saya rasa, kita belum kenal dekat. Sebaiknya—"
"Sebaiknya kita kenalan dulu! Aku Alvi, semoga kita bisa lebih dekat lagi!" Bukannya menyodorkan tangan kepadaku, dia malah menarik tangan kananku dan kami berjabatan dengan cara yang aneh.
"I-iya ... maaf sebelumnya, Pak. Apa Bapak ... tidak lupa dengan kejadian yang lalu?"
"Hooo ... ingat sekali, lah. Kenapa? Kenapa?"
"Anu ... kan, saya sudah menolak Bapak. Jadi ...."
"Jadi?"
Duh, ini orang menyusahkan sekali. Pasti ada maunya.
"Jadi sebaiknya kita tidak terlalu dekat--"
"Hahahaha! Jangan bilang gitu, dong! Aku tahu kamu syok sekali. Okelah, akan kudekati dirimu dengan cara yang seharusnya dilakukan para pria serius."
Kalau saja, aku bisa kabur dari sini. Sudah kulakukan sedari tadi. Sayangnya aku teringat kisah Pak Alvi yang cukup membuatku 'sedikit' mengaguminya.
Kediaman yang akan menjadi persinggahan para peserta family gathering ternyata milik keluarga Pak Alvi. Vila yang memiliki belasan kamar plus kamar mandi pribadi, empat dapur, dua kolam pribadi, dan satu ruangan rekreasi bisa dibilang terlalu mewah untuk diriku yang sederhana ini.
Pak Alvi sebenarnya berasal dari keluarga pengelolah batu bara yang cukup terkenal di kalangannya. Namun, Pak Alvi berbeda dengan saudara-saudaranya yang lebih mengfokuskan pada bisnis keluarga. Dia lebih suka menjadi seorang pendidik daripada duduk bersama kliennya membahas kertas cek dengan digit lebih dari sembilan angka. Eria yang kadang menjadi anak buahnya dalam sebuah kegiatan kampus sering mendengar curhatannya yang sering diremehkan saudara-saudaranya. Tapi hebatnya, dia tidak semata membiarkan mereka menginjak-nginjak pekerjaan yang dia sukai.
"Aku kadang juga menyindir balik mereka. Kayak kenapa wajah mereka cepat keriput, kenapa sering kena penyakit aneh-aneh, sampai aku memperlihatkan diriku bisa bercengkraman bersama anak didikku. Mereka memang bisa pergi keluar negeri macam bolak-balik ke wc, tapi apa gunannya kalau tidak ada dinikmati, kan? Money isn't everything."
Saat aku mendengarkan cerita tersebut dari Eria, semenjak itu pula aku tahu bahwa Pak Alvi adalah orang yang sepertinya hidup dengan penuh kebebasan. Dia murah senyum, jarang sekali marah. Kalaupun terjadi, dia pasti akan segera meminta maaf kepada orang yang bersangkutan tanpa diminta. Dia adalah sosok dosen yang amat didambakan. Bagi teman-teman, mahasiswa, sampai petinggi sekalipun.
Pak Alvi adalah orang yang sempurna dan langka untuk ditemui. Serasa dia adalah spesies manusia yang terancam punah dan butuh perlindungan agar tidak menghilang secara tiba-tiba.
Sayangnya ... fakta bahwa dia adalah seorang pria pemikat wanita sudah cukup membuatku ingin mengurangi interaksi dengannya.
"Kenapa Bapak sampai serius begini? Ah, maksud saya ... kenapa Bapak mau mendekati saya?"
Pak Alvi tersenyum miring dan menjawab, "Karena semakin kamu menjauh, semakin menarik. Makin sulit, makin tertantang diriku."
Oh Tuhan, tolong lindungi hamba-Mu ini dari predator seperti Pak Alvi.
Belum sempat aku membalas gombalan mautnya, Pak Alvi sudah berjalan menjauh, menuju gerombolan teman kantor yang sedang memanjat ke salah satu pohon mangga yang sudah ranum buahnya. Pria itu mengawasi mereka dari bawah, sambil bercengkraman dengan yang lainnya. Tidak ada yang tidak dia ajak bicara. Semua diberi perlakukan sama.
Pak Alvi dikenal dekat dengan semua orang. Berbeda dengan dosen lainnya, dia seolah tidak memiliki batasan untuk berada di dekat siapapun, meski itu adalah rektor atau orang penting sekalipun. Dia seperti bisa memahami lawan bicaranya dengan mudah, menerima segala jenis tabiat dan watak para mahasiswa didiknya, mau sebandel apapun.
Dia pernah mendapati mahasiswa yang merokok di belakang wc perempuan. Bukannya dibantai habis-habisan dengan ceramah atau dilaporkan ke bidang kemahasiswaan, Pak Alvi menyuruh mereka untuk membersihkan tempat mereka merokok. Kedengaran biasa, tapi Pak Alvi tidak hanya melihat mereka saja. Dia juga ikut membantu sembari menggali hubungan dengan anak berandalan tadi.
Kalau saja semua dosen bisa mengikuti jejak Pak Alvi, mungkin kampus kami akan lebih tertib dari seharushnya.
Ah, tidak. Jangan.
Aku tidak mau kampus ini menjadi sarang buaya darat.

Kalau baca cerita di atas, apa kalian jadi bersimpati dengan Rinda atau gemes sama Pak Alvi?🤭
Btw, nulis bagian ini malah membuatku agak sedih. Liburan yang sudah direncanakan matang-matang, malah tidak jadi. Hiks!
Apa boleh buat, liburan di rumah sambil menulis kali ya?
Siap-siap bab selanjutnya malah terasa seperti curhat terselubung wkwkwwk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro