IV - Cemas
Aku ingin melupakannya.
Tapi aku selalu mengingat rasa sakitnya.

Perasaan gelisah terus-terusan menyelimutiku. Untung saja hari ini tidak ada jam mengajar. Kalau pun ada, aku akan meminta reschedule. Aku tidak mau menjadi bulan-bulanan di dalam kelas. Meskipun sekilas, saat di kantin tadi aku mengenal beberapa wajah mahasiswaku, menjadi saksi tindakan paling memalukan sepanjang hidupku.
Bukannya aku berburuk sangka, tapi tidak perlu dipertanyakan lagi, aku sangat mengenal kebiasaan para mahasiswa. Pasti mereka sedang membicarakan dosen jomblo tua yang luar biasa bodohnya. Ya, aku setuju kalau aku memang bodoh.
Sialan, Rinda. Jangan kembali ke dirimu yang dulu. Jangan.
Aku melihat jam tangan, ternyata masih ada waktu sampai jam kerjaku berakhir. Sebenarnya aku bisa pulang lebih cepat karena aku sudah mendapatkan kelonggaran jam kerja setelah menjadi dosen tetap di fakultas ini. Tapi tepat waktu adalah motoku.
Sambil membiarkan waktu terbuang sia-sia, aku membuka buku catatan dan memastikan kembali jadwal untuk esok hari. Aku tidak pernah meragukan ingatanku, namun memastikan jadwal kegiatanku dalam sehari terkadang bisa membuatku tenang. Semacam sebuah terapi agar aku bisa menata pikiran agar lebih fokus dalam menyelesaikan pekerjaan.
Kupastikan lagi catatan berisi jadwal yang isinya telah kuingat di dalam kepala. Setelahnya, aku merapikan meja, mencuci gelas kopi yang tadi pagi kuminum, dan mengecek jam tangan kembali.
Oke. Aku bisa pulang sekarang.
Masalah di kampus tidak boleh dibawa ikut bersamaku di rumah. Jadi aku memutuskan untuk meninggalkan fakultas melalui pintu belakang yang minim orang berlalu-lalang. Helaan napas penuh syukur melesat dari mulutku setelah berhasil masuk ke dalam mobil tanpa bertemu orang yang kukenal.
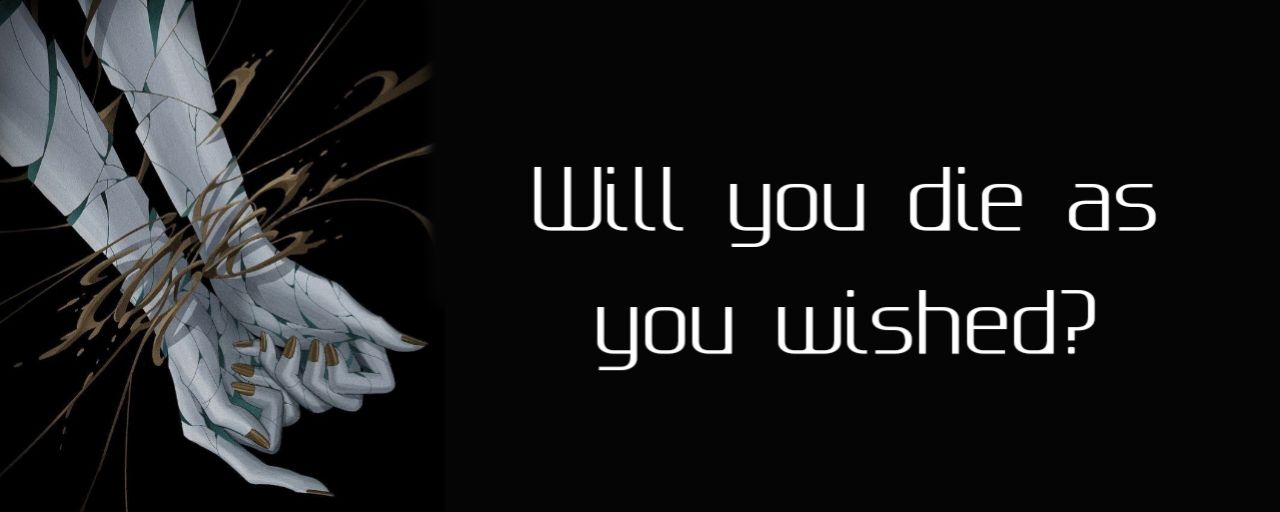
Aku tidak mau membuat ibuku khawatir. Aku tidak ingin menambah beban kepada pundaknya yang semakin membungkuk akibat usia, maupun kenangan pahit yang terbenam selamanya di dalam pusat memorinya. Terutama yang berkaitan dengan 'hubungan antara laki-laki dan perempuan'.
Luka lama yang masih membekas di dalam hatinya akan terbuka kembali. Luka yang terus mengendap di jiwa, membuatnya tak akan bisa berdamai hingga akhir hayatnya. Walaupun begitu, aku ingin ibuku sedikit lebih terbuka. Mengurangi tali pengekang yang dia selalu sebut sebagai kasih sayang.
Malam ini, aku akan mengatakannya.
"Ibu, jangan merepotkan Pak Rio terus. Orang-orang yang ikut family gathering itu teman-teman kantorku semua. Palingan mereka mengajak keluarga dekatnya. Tidak bakalan ada yang ganggu Rin, kok. Kemungkinan juga cuman menginap dua hari satu malam di sana. Villa juga sudah disewa dan pastinya bakal banyak orang di sana. Rinda janji langsung pulang setelah acara. Sekali ini saja ... Ibu percaya dengan Rinda."
Suara dentangan sendok besi yang tadi Ibu sikat dengan spons berbusa, melesat ke dalam lubang wastafel. Entah dia tidak senang dengan apa yang kukatakan atau sendok itu terlalu licin akibat sabun hingga benda itu lolos dari tangannya. Benda malang itu jatuh ke dalam lubang kotor yang dipenuhi sisa-sisa makan malam.
Aku sudah jarang mengeluh. Dulu memang pernah. Namun semenjak Ayah dan Ibu berpisah, aku mulai belajar dari kesalahan Ibu. Berusaha menekan kekecewaanku sebab apa yang kita katakan kadang akan menjadi kenyataan.
"Kenapa kamu harus ikut?" tanya Ibu masih dengan nada tenang. Meskipun begitu, terlihat jelas bahasa tubuhnya tidak selaras dengan cara bicaranya. Dia kembali mencuci alat makan secara tergesa-gesa, lalu melanjutkan, "Sudah berapa kali Ibu bilang, kamu boleh ikut acara apapun--tapi tidak boleh ada kegiatan sampai malam hari. Apalagi menginap. Lalu, acaranya di mana? Siapa saja yang ikut? Eri ikut, kan?"
Pertanyaan bertubi-tubi diberikan. Suara Ibu mulai meninggi. Aku bisa melihat tanda-tanda dia akan segera meledak.
Aku harus berhati-hati dalam memilih kata-kata.
"Di Malino. Semua dosen di fakultas biologi. Dan, ya, Eri pastinya ikut." Kemudian aku menarik napas dalam-dalam. Bersiap untuk memberikan pembelaan. "Rinda sudah beberapa kali tidak ikut kegiatan kampus di luar. Banyak yang mulai mempertanyakan diriku, Bu. Belum lagi sudah satu tahun aku menjadi dosen di sana. Tidak enak sama yang lain. Selain itu, Ibu ingatkan dulu kita pernah pergi ke Malino bareng Ayah--"
"Tidak usah ingatkan Ibu dengan masa lalu," potong Ibu sebelum aku menjelaskan lebih detail tentang kenangan keluarga kami.
Hobi Ayah yang suka pergi berwisata ke berbagai tempat adalah salah satu alasan dia bisa dekat dengan ibuku dan pada akhirnya menjadikannya sebuah kenangan berharga. Aku rindu melihat panaroma alam secara langsung. Bukannya melihat di sosmed, perjalan bahagai orang lain.
Aku juga berhak melakukan hal yang sama.
"Jadi ... Rin boleh pergi, Bu?"
Ibu menaruh spons berbusa ke mangkuk kecil, lalu menyalakan keran air, membilas satu per satu alat makan yang baru saja digunakan. "Apa ada yang tidak ikut?"
Mulai lagi dari awal. Rasanya aku juga ingin meledak.
"Kenapa Ibu bertanya seperti itu, sih?"
"Karena tidak ada gunannya kegiatan macam begitu."
"Artinya, Ibu melarangku pergi?"
Suara aliran air memenuhi seluruh ruangan. Dentingan kaca dan besi berbalas-balasan, membuatku gugup dan pusing karena Ibu masih belum mengeluarkan suaranya lagi.
"Ibu ... Rinda sudah 27 tahun. Bukan anak kecil lagi. Mau sampai kapan Rinda harus menutup diri? Ibu, percayalah. Sumpah, Rinda tidak akan melakukan hal-hal aneh yang sekarang Ibu pikirkan."
Cucian piring sudah selesai, namun Ibu belum beranjak dari posisinya. Dia mengelap kedua tangannya denga lap kering sembari berpikir keras. Kemudian berkata, "Berikan Ibu nomor temanmu yang lain. Sekalian atasanmu."
"Ibu! Sudah! Hentikan!" pekikku yang sudah tidak tahan.
Seketika dunia terasa senyap. Dadaku terasa sesak. Dari sudut dapur, aku memandang raut wajah Ibu yang kaget. Di satu sisi aku juga tersentak, sebab aku jarang sekali membentak dan kali ini aku menyesal karenanya. Mungkin inilah respon alami tubuh saat merasa tersudutkan. Di sisi lain aku sedikit merasa lega.
Aku paham perasaan seorang ibu yang takut hal-hal buruk akan menimpa putrinya. Apalagi tanpa pengawasan dari dirinya. Hanya saja aku tidak bisa terus-terusan mengikuti maunya. Mau sampai kapan aku harus menutup diri? Tidak bergaul dengan orang baru?
Rasanya seperti seekor burung yang dikurung dalam sangkar. Berteriak sekeras apapun, tidak akan pernah bisa terbang di langit yang tinggi dan luas.
Sudah sangat lama aku terkurung di dalam rumah ini. Di kota ini. Semenjak Ayah meninggalkan sisi Ibu, kebebasan adalah sesuatu yang mustahil untuk diriku.
Ibu memainkan kalung yang dikenakannya sembari menghela napas panjang. "Ya ... sesekali kamu ikut tidak apa-apa. Tapi ingat, setiap ada kesempatan, kamu harus menelepon Ibu. Melapor, oke?"
"Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Aku janji."
Aku bangkit dari kursi makan dan langsung memeluk Ibu erat-erat. Bau sabun cuci piring memenuhi badannya. Tubuh yang tingginya sudah hampir sama denganku ini, sudah melakukan pekerjaan yang berat setiap harinya. Menjadi singel mom, mencari nafkah saat aku kuliah, dan membesarkanku tanpa bantuan orang lain. Itulah sebabnya aku paham mengapa ibuku begitu posesif dengan keamananku. Karena aku satu-satunya harta karun yang tersisa untuknya.
Aku ingin hidupku dipenuhi kebahagaiaan, sehingga Ibu juga ikut bahagia. Meskipun aku belum bisa menyingkirkan kebiasaan buruknya dalam berburuk sangka. Setidaknya aku sudah mengubah pola pikirku untuk terus berpikir hal-hal yang baik dan tidak membiarkan pikiran negatif menghinggap di dalam benakku.
Meskipun begitu, kadang kala aku takut. Apa yang dikatakan Ibu benar-benar menjadi kenyataan.
Ucapan adalah doa.
Perceraian Ayah dan Ibu hanya disebabkan satu hal kecil, yang makin hari makin besar. Karena itulah aku tidak mau lagi mengeluh. Aku tidak mau lagi berburuk sangka. Apa yang kita ucapkan berulang-ulang bisa menjadi sebuah kenyataan dan aku tidak mau kata-kata itu berubah menjadi bumerang yang mematikan.
Aku berusaha membiasakan diri berbicara hal-hal baik saja.
Aku tidak perlu berpikir keras apa pendapat orang lain terhadap diriku. Jika mereka bilang aku jelek, bodoh, terlalu baik--aku akan mengambilnya sebagai sebuah kritik yang membangun. Itu artinya aku harus memperhatikan lagi penampilanku, belajar yang lebih rajin lagi, dan semakin memperbanyak melakukan perbuatan baik kepada orang lain.
Hidup dengan melihat dari sisi yang baik ternyata boleh juga.

Apakah ada yang dibesarkan di keluarga yang otoriter?
Setiap hal harus dilaporkan, diawasi, atau malah ditahan-tahan?
Sebenarnya tidak salah mencemaskan buah hati, apalagi perempuan. Cuman dampak jangka panjangnya cukup buruk untuk anak itu sendiri (karena aku salah satu contoh nyatanya hehehe).
Bayangkan aja, dulu aku dilarang main sama teman terlalu lama atau ke tempat yang jauh. Katanya takut diapa-apain. Okelah. Mencegah sebelum terjadi.
Tapi pas udah gede, malah ditanya gini, "Loh? Kamu tidak punya teman, kah? Atau pacar gitu? Mau sampai kapan sendirian terus? Nikah ..."
Pengenku berkata kasar~
Ada yang pernah mengalami hal yang sama?
Atau malah berbanding terbalik? Dampaknya buat kalian gimana?
Komen dungs. Perlihatkan eksitensi kalian, wahai silent reader wkwkwkw.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro