"Gia dan Ayah Naga" - BebekLucu
GIA DAN AYAH NAGA
A Short Story by BebekLucu
Seharusnya para ibu menasihati anak-anak mereka dengan lebih teliti, bahwa mengikuti orang asing dan makhluk astral itu berbahaya. Aku jelas enggak melanggar peringatan mama untuk menolak ajakan orang asing. Toh, yang aku ikuti adalah Nek Parsih, penunggu pohon alpukat dekat gerbang sekolah yang sering melambaikan tangan begitu melihatku. Kalau ada yang harus disalahkan, jelas ini salah para dedemit yang membuat kekepoanku meningkat karena selalu mendengar mereka memanggilku anak Rawindra Wajrapani.
Coba kutanya, siapa yang kenal Rawindra Wajrapani? Ayo ngacung!
Kemungkinan orang mengenalnya satu banding sejuta.
Dulu, aku pernah bertanya ke mama dan papa. Alih-alih memberikan jawaban, mereka malah memandangku ngeri setelah aku mengaku mendengar nama itu dari pocong di depan rumah Pak RT dan kuntilanak merah di pohon asem. Sejak itu aku mengambil kesimpulan kalau melihat pocong dan sebangsanya adalah ENGGAK NORMAL.
Aku mau menjalani kehidupan normal ala anak remaja yang memakai seragam putih abu-abu dong. Jadi, aku pura-pura enggak lihat wujud 'mereka'. Kadang aku pura-pura budek kalau diajak ngobrol sama 'mereka'. Pokoknya enggak boleh ada manusia yang tahu aku bisa melihat yang halus-halus.
Sayangnya usahaku gagal hari ini karena Nek Parsih yang biasanya hanya nyengir mendadak memanggil nama panjangku, "Bahagia Cempaka."
Namaku aneh banget dan aku enggak suka mendengarnya. Mama, tiga malam berturut-turut, bermimpi bertemu naga hitam yang memberikan nama Bahagia Cempaka pada bayi dalam gendongan mama. Papa pikir mimpi itu pertanda keberuntungan dan mengusulkan nama itu dipakai untukku. Yah, akhirnya gini deh. Aku punya nama yang bikin aku tampak aneh di saat aku mau tampak normal. Walau namaku aneh, mama dan papa mempermudah panggilanku dengan tiga huruf, GIA.
"Apakah kau mau bertemu ayahmu? Rawindra Wajrapani?" tanya Nek Parsih.
Kesalahanku dimulai dari situ. Aku penasaran pada si empunya nama. "Papaku di kantor dan namanya Rasyid Ilham, bukan Rawindra Wajrapani," sanggahku.
Nek Parsih menggeleng sekali, masih mempertahankan senyuman di bibir keriput yang menjepit sirih di sudut. "Ayahmu bukan manusia itu. Ikutlah denganku dan temukan kebenaranmu sendiri."
Itu ajakan paling enggak keren sepanjang masa. Harusnya aku ditawarkan menerima seperti emas permata yang cukup untuk merayakan ultah keenambelasku selama tujuh hari tujuh malam dengan tema Disney sampai Avengers di hotel bintang tujuh. Aku baru sadar kemudian, aku ternyata mudah tergiur dengan tawaran 'kebenaran'. Wow!
Nek Parsih mengucapkan sederet mantra aneh yang memanggil gelembung cahaya berwarna-warni. Gelembung-gelembung itu bersatu dan "POP!", berubah menjadi gapura batu dengan sebuah janur kuning di masing-masingnya.
Aku melewati gapura itu. Sekejap saja pemandangan di depan mataku berubah. Aku berada di hutan belantara. Hutan yang selama ini hanya kulihat di NatGeo. Hutan yang diisi pohon raksasa hingga langit sulit mengintip. Rahangku jatuh mengamati sekeliling. Bangunan SMA lenyap, berganti jajaran pohon yang enggak ada habisnya. Aspal pun diganti tanah yang dilapis daun kering dan ranting. Aku menyentuh salah satu akar pohon raksasa. Tekstur kasar kulit kayu terasa begitu nyata. Masih enggak percaya, aku pukul akar itu.
"ADOOOH!" jeritku kesakitan.
"Mengapa kau memukul pohon itu?" tanya Nek Parsih.
Tinggi Nek Parsih enggak sampai bahuku. Badannya kurus dibungkus kebaya ungu dan kain jarik. Rambutnya kelabu dicepol di belakang. Wajahnya tampak pucat dan tanpa riasan. Dengan seluruh deskripsi itu, mustahil Nek Parsih bisa membawaku ke tengah hutan. Tapi kita membicarakan Nek Parsih yang bukanlah manusia.
"Apa aku baru aja melewati wardrobe Narnia?" tanyaku sambil memegangi tangan kanan yang nyut-nyutan.
"Narnia?" Nek Parsih menelengkan kepalanya dan mengedip beberapa kali.
Aku mengibaskan tangan kiri. "Bukan apa-apa. Jadi, benda apa itu?" Aku menunjuk gapura batu yang masih ada setelah kami berpindah ke hutan.
"Itu gerbang antar dunia."
"Antar ... dunia?" aku mengamati gapura, hutan, dan Nek Parsih. Satu kesimpulan hadir. "DUNIA GAIB?!"
Nek Parsih terkikik. Suaranya mengingatkanku pada kecentilan kuntilanak. Aku mulai menduga Nek Parsih adalah salah satu versi dari kuntilanak.
"Tentu saja kita harus menyeberang ke dunia gaib agar kau bisa bertemu Rawindra," kata Nek Parsih, seolah seluruh orang tahu kecuali aku.
"Siapa Rawindra?" tanyaku agak mendesis.
"Kau akan segera mengenalnya, Nak. Itu jemputanmu. Naiklah."
Entah dari mana, tahu-tahu ada sebuah kereta kuda berwarna putih yang dilapis ukiran emas dan pada bagian belakangnya dibuat menyerupai sayap burung. Empat ekor kuda putih menarik kereta empat roda itu tanpa kusir, membuatku bertanya-tanya teknologi macam apa yang sudah dikembangkan dunia gaib.
"Naiklah," Nek Parsih berkata sambil menepuk bahuku.
"Kusirnya?"
"Kuda-kuda itu tahu ke mana harus mengantarmu."
Aku heran melihat Nek Parsih enggak menyusulku naik kereta. "Nek Parsih enggak naik?"
"Aku akan menunggumu di sini. Kembalilah bersama kabar baik."
Aku ingin membantah, lalu memaksa Nek Parsih naik kereta. Sebelum semua itu terlaksana, pintu kereta tertutup sendiri dan kereta itu bergerak. Bukan, bukan bergerak, melainkan terbang. Aku membelalak melihat kelincahan kuda-kuda itu melewati pepohonan hingga menembus dedaunan yang rimbun. Langit jingga menyambut indraku, mengantarkan ingatan kalau aku sudah melanggar perintah Mama untuk segera pulang setelah sekolah usai.
Enggak berapa lama, aku merasakan perubahan gerak kereta. Kami bergerak turun dalam pola melingkar. Aku menyandarkan badan sembari memegang tepian kursi yang bantalannya empuk banget. Aku berharap kuda-kuda itu benar-benar tahu caranya mendarat yang aman tanpa menimbulkan luka secuil pun. Ketika pintu kereta terbuka, aku tahu kami mendarat dengan sangaaaat baik.
"Selamat datang, Bahagia Cempaka." Seorang kakek menyambutku di depan kereta. Pakaian dan rambutnya yang dikonde di atas kepala serba putih, mirip pertapa.
"Kok tahu namaku?" tanyaku heran. Asal tahu saja, seragam sekolahku itu enggak memasang ban nama dan ini adalah pertemuan pertama kami. Kalau Nek Parsih lain cerita. Aku sudah melihatnya sejak baru masuk SMA setahun yang lalu.
"Nama yang elok untuk gadis yang tangguh, bagaimana aku tak mengetahuinya."
Aku menggaruk tengkuk, kehabisan kata menanggapi ucapan seperti itu dari kakek-kakek. Kalau yang bicara anak muda, aku pertimbangkan sebagai gombalan kurang edukasi.
"Rawindra sudah menunggumu. Mari masuk."
Aku mengikuti kakek yang mirip pertapa masuk ke dalam rumah besar dari bata merah. Sesaat aku menengok ke belakang. Kereta kuda mulai meninggalkan pelataran rumah menuju hutan.
"Kudanya pergi. Gimana aku pulang?" aku panik.
Kakek pertapa berhenti. "Kau sudah di rumah," katanya.
"Ini bukan rumahku. Rumahku itu ada di dunia manusia, bukan dunia gaib."
Kakek pertapa menggeleng dengan ekspresi letih. "Kau salah sangka, Nak."
"Salah sangka apa? Sebentar. Jelasin dulu, salah sangka apa? Aku mau pulang ke rumah, memangnya salah?"
"Rawindra." Si kakek menoleh ke salah satu lorong di dalam rumah.
Aku berhenti menuntut dan menatap penasaran lorong gelap itu. Perlahan aku mendengar suara derap langkah yang mantap, disusul bayangan yang bergerak mendekat. Aku memicingkan mata, berusaha menangkap sosok yang dipanggil Rawindra. Dari balik kegelapan, aku melihat sepasang kaki berotot. Aku meneguk ludah melihat ukuran kaki itu di atas ukuran kaki papa. Pandanganku naik ke atas. Seorang pria tinggi besar mendekati kami. Napasku tercekat menyadari ada sepasang tanduk di kepalanya. Tanduk bercabang.
"Apa itu raja genderuwo?" bisikku ke kakek.
Kakek pertapa berdehem. Dia kelihatan enggak menyukai pertanyaanku. Masalahnya hanya genderuwo yang aku tahu bentuknya tinggi besar. Walau pria yang di depan kami punya wajah rupawan yang enggak bisa disamakan genderuwo di kebun Engkong Mamat. Dan lagi, pria ini enggak berbulu ataupun melemparkan tatapan genit yang menjijikan.
"Dia adalah Rawindra," kakek melirik si Rawindra, lalu balik memandangku, "aku akan meninggalkan kalian. Berbicaralah dan temukan jawaban untuk segala kebingunganmu."
Si kakek pergi tanpa menunggu penolakanku. Langkahnya ringan dan cepat. Aku ragu memanggilnya karena belum mengetahui namanya. Lagipula ada orang lain di dekatku yang bisa saja enggak menyukai tamu yang berteriak di rumahnya.
"Kau sudah besar."
Aku sontak berpaling ke Rawindra. Suaranya dalam dan tegas sekaligus menenangkan. Ada perasaan rindu yang menggebrak dada sampai menyebabkan mataku memanas.
Sial, ketemu om setan saja aku baper!
Aku mengusap mata menggunakan lengan jaket hijau yang melapisi seragam. Harusnya jaket ini melindungiku saat menumpang abang ojol yang mengantarku pulang, bukannya dipakai mengelap air mata anak remaja baperan.
"Kamu kenal aku?" tanyaku takut-takut. Pengetahuanku seputar yang halus-halus itu terbatas pada pocong, genderuwo, kuntilanak, tuyul, dan banaspati. Semuanya yang sering aku temui di sekitar rumah dan sekolah. Yang lainnya kurang aku ketahui karena aku enggak mencoba mencari tahu. Aku takut pria ini punya semacam kelainan menghisap darah gadis perawan agar ketampanannya langgeng kayak drakula gitu.
Rawindra tersenyum. "Apa kau mau makan kue?"
Ditanya apa, malah balasnya apa. Bete sih, tapi aku juga lapar.
"Karena kamu maksa, aku coba sedikit aja," sahutku.
Rawindra enggak kesal menghadapi tingkah songongku. Dia malah tersenyum lebih lebar. Kalau mama dan papa, mereka pasti sudah ngomel melihat sikap sok jual mahalku.
Aku diajak masuk ke sebuah ruangan yang luas sekali. Ada meja kayu di tengah ruangan. Di bawahnya ada tikar. Kami duduk di tikar saling berhadapan. Meja dipenuhi panganan pasar dan satu kendi tanah liat serta dua gelas dari bambu.
"Makanlah yang kau suka." Rawindra menawarkan dengan ramah.
Aku mencomot sepotong kue hijau yang atasnya ada parutan kelapa. Isinya meleleh di mulutku. Aku kurang mengenal nama kue ini. karena enak kulahap saja.
Eh, aku melupakan urusanku ke sini.
"Itu..." Aku beranikan memandang Rawindra. "Om siapa, ya?"
"Aku adalah ayahmu," jawab Rawindra mantap.
Aku menggeleng kuat-kuat. Bercanda nih. "Aku punya papa di dunia manusia. Aku enggak mungkin anak Om. Aku itu manusia. Om kan makhluk gaib."
Rawindra memandang lama. Aku cemas dia akan mendebatku dan ngamuk. Tapi dia malah tersenyum maklum.
"Kau adalah anakku dan seorang manusia. Ya, kau manusia sekaligus siluman."
Petir langsung menyambar kepalaku. Amarahku mendidih. Aku menggebrak meja, lalu bangkit bersama perasaan enggak terima. "Bercanda itu ada batasnya, Om. Jangan bercanda deh. Om mau bilang mamaku selingkuh sama Om terus aku lahir? Ngaco banget! Mama dan papa saling cinta. Enggak mungkin mamaku melakukan perbuatan tercela kayak gitu," kataku berapi-api.
"Duduk, Bahagia Cempaka," perintah Rawindra.
Aku ingin menolak, tapi badanku spontan balik ke posisi semula. Aku menggeram enggak suka. Dia pasti pakai sihir, tuduhku dalam hati.
"Panggil aku Gia. Aku aneh dipanggil Bahagia Cempaka dari tadi," dumelku.
Rawindra masih mempertahankan senyum, meskipun dia menghela napas. "Baiklah, Gia. Berikan aku waktu untuk menjelaskan kisah hidupmu."
"Ya udah cerita aja," kataku nyolot.
"Kau adalah anak dari pernikahanku dan seorang dukun wanita. Sebelum kau lahir, terjadi kecelakaan yang memaksa dukun itu mengeluarkanmu beserta rahimnya. Kau dititipkan pada peri air. Butuh seribu tahun lebih untukmu berkembang sebagai janin dan lahir. Saat itu, Rasyid menemukanmu yang baru lahir di gua peri air. Dia membawamu. Dia dan istrinya pula yang membesarkanmu. Tapi waktumu untuk tinggal dan mewujud sebagai manusia sudah melewati batas. Kau tidak bisa mempertahankan wujudmu lebih lama lagi."
Aku menyimak ucapan Rawindra seperti bukan aku yang tengah dia bahas. Tentu saja bukan aku. Mana mungkin aku percaya. Aku itu manusia normal, enggak mungkin bisa dibodohi.
"Apa yang akan terjadi kalau aku tetap sebagai manusia?" tantangku.
"Kau akan menyantap jiwa orang tua manusiamu untuk bertahan hidup."
Aku ingin tertawa. Dipikirnya, aku bisa dikibuli. Sorry, aku itu bukan anak ayam yang bisa digiring masuk comberan.
"Kenapa aku harus menyantap jiwa papa dan mama kalau di depanku ada ayah siluman yang bisa aku makan?" ledekku dengan muka serius.
Rawindra enggak mengubah ekspresinya. Dia tetap tenang. "Kau tak bisa menyantap naga, Gia. Pada akhirnya, naluri bertahanmu akan memaksamu bertindak brutal."
"Naga? Om siluman naga?" aku suka nonton how to train your dragon. Kalau ada kesempatan melihat naga versi siluman, tentu menyenangkan.
"Kau pun siluman naga," balas Rawindra.
Mood-ku langsung anjlok. Enak saja aku dibilang naga. Aku berdiri. Main-mainnya sudah cukup. Aku harus pulang supaya mama enggak punya alasan memarahiku sepanjang makan malam.
"Aku mau pulang..." aku teringat ucapan kakek pertapa dan melanjutkan, "ke rumah orang tua manusiaku."
Rawindra enggak menolak permintaanku. Aku kembali ke hutan belantara diantar kereta kuda. Nek Parsih tampak sedih melihatku kayak dia tahu bagaimana akhir percakapanku dan Rawindra yang enggak mulus. Bukan salahku loh. Itu salah Rawindra yang berbagi cerita absurd.
Malam itu aku di kamar setelah mendengar omelan mama yang mengatakan pentingnya memberi tahu orang tua kalau mau pulang telat. Aku tiduran di kasur sembari memperhatikan lenganku.
"Masa lengan normal begini jadi lengan naga sih. Aneh banget," gumamku.
Aku terlelap enggak lama setelah itu. Kemudian mataku terbuka dalam kondisi paling gila. Aku duduk di atas badan mama yang sedang tertidur. Kedua tanganku mengeluarkan kuku tajam hewan buas dan siap mencekik leher mama. Aku melompat kaget. Mama dan papa masih pulas walau aku menimbulkan suara decitan kasur sewaktu melompat.
Gila!
Gila banget!
Aku berlari ke kamar, mengunci pintu, lalu duduk meringkuk di pojok terjauh dari pintu. Badanku menggigil membayangkan aku nyaris menjadi pembunuh. Aku menatap kuku tanganku. Sepuluh kuku itu balik sedia kala. Apa yang terjadi? Apa yang merasukiku?
Aku memutuskan enggak tidur lagi agar pengalaman gila itu enggak terulang. Aku enggak boleh menyakiti mama.
Esoknya, aku berangkat sekolah dengan hati gamang. Begitu melihat pohon alpukat di dekat gerbang sekolah, aku setengah berlari. Hanya ada satu orang. Ralat. Hanya ada satu siluman yang menyebabkan kegilaan semalam. Rawindra.
"Kau datang pagi sekali, Nak," sapa Nek Parsih.
"Antar aku ke Rawindra!" perintahku. Sudah hilang maluku diperhatikan murid-murid yang melintas karena berbicara pada pohon tua.
"Kau meminta lebih cepat dari dugaanku. Apa gejalanya sudah muncul?"
"Gejala?"
"Nalurimu untuk mempertahankan wujud." Nek Parsih tersenyum misterius. Aku enggak sempat bertanya maksudnya karena dia sudah merapal mantra. Gelembung warna-warni berkumpul. Gapura batu muncul dari balik letusan gelembung.
Aku enggak menyukai ide melintas antar dunia. Kali ini, aku melesakan ketakutanku demi keselamatan orang tuaku.
"Kalian terlambat." Kakek pertapa menyapa sinis begitu kami tiba di hutan belantara.
"Sabar sedikit, Mpu. Bahagia baru saja menunjukan gejala," sahut Nek Parsih.
Kakek melirikku penuh kecurigaan. Sikapnya berbeda dengan keramahan yang ditunjukan kemarin.
"Masih baik dia tak membuat pasangan manusia itu mati semalam. Ikut aku, Baha-"
"Tolong panggil aku Gia. Telingaku gatal karena kalian terus memanggil nama panjangku," potongku.
"Ya, ya, terserah saja," kata si kakek enggak sabaran.
"Dia tidak suka terlambat belajar." Nek Parsih meremas bahuku lembut. "Belajarlah dengan baik."
"Belajar apa? Aku mau ketemu Rawindra."
Nek Parsih tersenyum lebar hingga deretan giginya yang kuning akibat sering mengunyah sirih terlihat. "Kau akan bertemu Rawindra. Ikuti Mpu Batara."
Enggak punya pilihan lain, aku ikut si kakek naik ke kereta yang kemarin aku naiki. Yang berbeda adalah tujuan kami kali ini. Aku enggak diajak ke rumah bata merah, melainkan istana putih yang dikelilingi pohon melati hingga aroma wangi menyerbu hidung begitu kami turun.
"Kita enggak ke rumah Rawindra?" tanyaku.
"Kita ke sekolah," jawab kakek lebih kalem.
"Sekolah?" aku melafalkan kata itu dengan ganjil.
"Sekolah barumu. Sekolah kerajaan siluman."
"APAAA?!"
"Ada masalah apa, Mpu?"
Aku melompat ke belakang badan si kakek. Mataku membelalak pada sosok yang baru saja nimbrung percakapan kami. Seekor babi, eh, manusia. Apa sebutan untuk manusia setengah telanjang yang kepalanya babi hutan?
"Dia putri Rawindra, Bahagia Cempaka. Mulai hari ini dia masuk sekolah," kata si kakek tenang.
Manusia setengah babi itu menunduk untuk menjangkau tinggiku. Aku yakin siluman ini tingginya dua meter lebih.
"Dia masih mempertahankan wujud manusianya. Rawindra hebat sekali menyokong kebutuhan energi anak ini," kata si manusia babi.
"Dia masuk kelasmu pagi ini, Dwinata." Si kakek masih berbicara ke manusia babi.
"Aku harus bertemu Rawindra," selaku cepat.
Kakek dan manusia babi memandangku sejenak. Manusia babi memecah atmosfir tegang duluan. "Kurasa, Bahagia Cempaka mempunyai sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan dengan Rawindra."
Si kakek mendesah. "Kau hanya membuang waktu. Rawindra sedang semedi. Paling cepat lusa dia menyelesaikan urusannya."
"Heh? Buat apa siluman semedi segala?"
Kakek dan manusia babi sontak memberiku pandangan dingin. Aku mengulum bibirku rapat-rapat akibat suasana yang membuatku bak tersangka.
"Pergilah ke kelas Dwinata," suruh kakek pertapa.
Aku memperhatikan Dwinata si manusia babi. Kemudian mempertimbangkan keselamatanku. Babi suka makan orang, enggak?
"Aku tak akan memakan sesama siluman, Bahagia." Dwinata tiba-tiba menjawab kecemasan dalam kepalaku.
"Oh gitu, ya." Aku menggaruk tengkuk saking malunya.
"Ikuti aku, Bahagia!"
Aku membuntuti Dwinata. Langkahnya panjang dan cepat. Aku harus berlari untuk menyusulnya. Bukannya masuk ke bangunan istana yang kutebak sekolah siluman, Dwinata malah mengajakku menjauh melewati jalan setapak yang terbentuk dari batu koral warna telur asin. Itu loh yang biru tanggung gitu.
"Bisa enggak panggil aku Gia aja. Aku heran kalau dengar semua orang di sini memanggil nama panjangku gitu."
Dwinata berhenti tiba-tiba. Enggak sempat ngerem, aku menubruk badannya. Kaget bukan kepalang, aku melompat mundur. Dwinata itu enggak pakai baju dan hanya pakai celana pendek yang dilapis kain batik. Aku ngeri, kata mama harus hati-hati sama cowok, apalagi cowok yang enggak pakai baju. Walau badan Dwinata oke kebangetan.
"Kamu dipanggil Gia oleh orang tua manusiamu?" tanyanya seperti lupa ulahku yang baru saja menabraknya.
"Iya."
Aku mau menjerit ngeri melihat Dwinata tersenyum—kalau memang tarikan bibirnya bisa aku anggap senyum. Ya, ampun aneh banget melihat Dwinata dengan kepala babi hutannya tersenyum.
"Kau beruntung dirawat oleh manusia yang baik."
Seketika kejadian mengerikan semalam terbersit. Aku memandang Dwinata dengan sedih. "Apa yang terjadi sama aku kalau terus tinggal bareng mama dan papa?"
"Duduklah." Dwinata menunjuk batu besar yang bagian atasnya datar. Aku duduk di situ, sementara dia duduk di batu di hadapanku.
"Kita enggak ke kelas?" tanyaku ragu.
"Ini kelas kita."
"Hah?"
Dwinata terbahak. Suaranya besar dan menggelegar. Aku mengernyit ngeri. Kupikir guru paling kejam itu guru ekonomi dan matematika karena maksa aku berteman akrab dengan angka. Enggak tahunya, guru yang tertawa lebar sambil menunjukan taring dan gigi tajam lebih menggoyahkan nyali.
"Kita mulai kelas pertamamu dengan situasimu semalam," kata Dwinata.
Situasi semalam?
Rasanya aku belum cerita ke siapapun tentang kejadian yang aku alami deh. Gimana dia bisa tahu?
"Kau mulai menunjukan gejala dari keinginan mempertahankan wujud manusiamu," kata Dwinata sebelum aku sempat bertanya. "Kau mencoba menyakiti orang tua manusiamu sebagai pertukaran untuk mempertahankan wujud manusiamu."
"Kenapa aku mau nyakitin mama? Aku sayang sama mama," sanggahku. "Aku aneh gitu setelah ketemu Rawindra. Dia pasti tuh yang ngasih guna-guna."
"Rawindra yang selama ini menyokong kebutuhan energimu untuk bertahan dalam wujud manusia di dunia mereka. Sekarang, dia sudah tak mampu memberikanmu energi lagi. Kutanya, pernahkah kau lapar meskipun seharian tak makan?"
"Enggak pernah," jawabku segera.
"Karena makanan manusia itu bukan seleramu, Gia. Siluman naga menyerap energi alam untuk hidup. Kau pun begitu. Selama ini Rawindra yang memastikan kau tak kehabisan energi. Sayangnya, dia telah mencapai batas dan kau harus kembali ke duniamu yang sebenarnya."
Aku menggeleng. Masih susah dipercaya aku ini bukan manusia. Ada amarah yang menggebu ingin aku muntahkan. Kehidupan ini bukan keinginanku. Aku mau hidup biasa selayaknya anak remaja. Merasakan ribetnya ujian sekolah, mendaftar di OSIS, mempunyai pacar, kuliah, dan selamanya bersama mama dan papa. "Rawindra bilang aku setengah manusia dan siluman. Siapa ibuku?" aku bertanya dengan suara bergetar oleh emosi.
"Maksudmu Cempaka?"
"Ce... Cempaka?"
"Nama ibumu, dukun perempuan yang dinikahi Rawindra."
Aku melompat. "Pertemukan aku dengan ... Cempaka." Aku merasakan kegetiran saat menyebut nama perempuan yang katanya adalah ibuku.
"Itukah yang kau inginkan?" tanya Dwinata dengan penuh penekanan.
"Aku harus tahu apa alasan perempuan itu membuatku menjadi setengah siluman. Dia bahkan mengeluarkanku dari rahimnya sebelum aku lahir. Kenapa dia membawaku pada takdir mengerikan ini?" mataku memanas. "Aku hanya ingin hidup biasa. Aku ingin berteman, sekolah, tinggal bersama orang tua normal. Sejak aku tahu melihat hantu adalah keanehan, aku berusaha keras berpura-pura aku sama dengan yang lain. Tapi semua itu susah karena aku melihat hantu sama seperti aku melihat manusia. Mereka terlalu nyata untuk aku cuekin. Aku..."
Kekesalanku meluap semua. Kemarin pagi, aku masih manusia, lalu siangnya semua memberitahu aku adalah siluman. Siapa orang gila yang mau percaya? Harusnya aku enggak percaya, tapi kejadian semalam menggoyahkan keyakinanku. Aku enggak mau mengambil korban demi wujud manusia. Kalau ada yang ingin aku salahkah, enggak lain adalah orang yang menyebabkan aku hidup meradang. Cempaka.
"Aku ingin bertanya kenapa dia jahat banget," aku masih melanjutkan di sela tangisan yang memburamkan pandanganku. "Kalau dia enggak suka aku, kenapa dia bikin aku begini?"
"Aku akan mengantarkanmu pada Cempaka asal kau berjanji akan belajar di sekolah siluman," tawarnya.
"Tentu saja." Kita lihat nanti, lanjutku dalam hati.
Aku dibawa Dwinata ke sebuah gua yang di dalamnya terdapat danau. Airnya kehijauan dan tampak cemerlang. Sesaat aku takjub, lalu segalanya sirna saat perempuan setengah ular keluar dari sana.
"Apa yang kau butuhkan, Dwinata?" perempuan jelita itu tidak mengacuhkanku.
"Gia ingin bertemu Cempaka," jawab Dwinata.
Perempuan itu memberiku pandangan tertarik. "Jadi anak Rawindra telah kembali. Akan kuberikan waktu untuknya berkenalan dengan ibunya." Aku merasakan nada menyindir pada suaranya.
Enggak lama, seorang perempuan keluar dari tengah danau. Semula, aku enggak menyangka itu orang. Hanya bayangan hitam yang lama-kelamaan tampak sebagai rambut, lalu kepala, badan, dan kaki. Aku terus mengamati dengan jantung berdebar. Rasa penasaran membengkak seketika.
"Cempaka."
Mendengar nama itu disebut perempuan ular, aku langsung maju saking penasaran pada wajah ibu kandungku. Perempuan itu terlalu muda untuk kuanggap ibu. Umurnya mungkin masih di awal dua puluhan.
"Anakmu ingin bertemu denganmu. Temui dia sebentar," perintah si perempuan ular.
"Baik, Ni," jawab Cempaka.
Dia, Cempaka, maju. Senyum lembut melekat di wajahnya, tapi aku enggak akan termakan satu senyuman. Dia adalah penyebab kemalanganku.
"Mari bicara di luar, Gia," ajaknya. Aku hanya mengangguk dan mengikuti dia ke luar gua. Dwinata dan perempuan ular membiarkanku pergi berdua saja.
"Apa di sini nyaman, Nak?"
Aku memandang ke sekeliling. Ini adalah hutan yang enggak berbeda dengan hutan belantara tempatku dan Nek Parsih datangi. Akhirnya, aku mengangguk kecil. Aku memilih menjaga jarak. Kami enggak akrab dan aku enggak mau akrab dengannya.
"Aku benci kamu," kataku penuh kegetiran.
Cempaka tampak terpukul. Sekejap saja dia kembali mempertahankan wajah tenangnya. "Kalau diizinkan, beri tahu aku alasan kau membenciku," pintanya.
"Kamu bikin aku begini. Manusia bukan, malah jadi siluman. Apa sih alasanmu nikah sama siluman? Aku yang kena getahnya," omelku.
"Aku minta maaf, Nak. Waktu itu aku sedang meningkatkan ilmu dan tergiur kekuatan besar yang bisa aku peroleh seandainya menikahi siluman. Namun kegemparan terjadi di desa. Penduduk menganggap kehamilanku berbahaya. Mereka ingin mengejarku, juga janin yang kukandung. Akibat panik, aku melakukan penawaran pada Ni Sekar, dia perempuan yang kau temui di gua," cerita Cempaka begitu lancar.
"Penawaran apa?"
"Menjaga agar kau tetap hidup. Sebagai gantinya, aku menjadi pelayan Ni Sekar."
"Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu enggak minta tolong Rawindra?" sentakku penuh amarah.
"Rawindra sedang bertapa dan tak mungkin diganggu."
"Gimana bisa dia enggak nolong istri dan anaknya?" amarahku terasa mendidih. Kebodohan ini yang membuatku celaka. "Harusnya kamu biarin kita ditangkap penduduk desa. Harusnya kamu enggak buat aku harus tersiksa. Harusnya aku bukan anak siluman. Aku enggak mau jadi anak siluman. AAAAAAAKH!"
Aku merasakan ledakan tiba-tiba di dadaku. Segalanya menjadi gelap sesaat, lalu badanku melayang ke udara. Gelembung cahaya memerangkapku hingga pandanganku silau. Desakan demi desakan menggedor sekujur badan. Ada gelombang yang menarik dari kaki ke kepala. Ketika segalanya terasa membaik, aku tidak memijak tanah dan angin seolah berkumpul di kakiku.
"Gia! Bahagia, apa kau mendengarku?" Cempaka berteriak panik di bawah. Dwinata dan Ni Sekar berlari dari goa dan ikut panik.
Apa yang terjadi?
Aku menunduk, lalu terkejut mendapati tanganku seperti tangan buaya. Apa yang terjadi? Aku meliuk di udara menuju goa. Di tepi danau, aku melihat pantulan diriku. Bukan, itu bukan aku. Itu naga. Bagaimana bisa aku berubah menjadi naga?
Kemarahan berkumpul di hatiku. Semua ini kesalahan Cempaka, pikirku.
Aku terbang ke luar goa. Dalam gerak cepat, aku berusaha menyambar Cempaka. Ni Sekar bergerak lihai memukul badanku menggunakan ekor ularnya. Aku terpelanting hingga menabrak pohon.
"Gia!" Cempaka berusaha mendekat. Dwinata mencekal lengannya.
"Jangan ke sana. emosinya tak terkendali dan jiwanya sedang bimbang," Dwinata memeringati.
Aku mengangkat tangan, meminta pertolongan. Badanku sakit sekali terkena pukulan Ni Sekar dan menghantam pohon. Mataku berair dan itu cukup memengaruhi Cempaka. Dia menepis tangan Dwinata, lantas menyongsongku. Tidak menunggu lama, aku berdiri, menangkap bahu Cempaka, dan mendorongnya ke tanah.
"Semua salahmu," geramku.
"Gia, dia ibumu. Apa yang kau lakukan?" teriak Ni Sekar.
Aku menoleh penuh kebencian. "Dia yang membuatku begini. Dwinata bilang, aku butuh pertukaran untuk mempertahankan wujud manusiaku. Kenapa bukan ibu kandungku yang mengorbankan diri untukku?"
"Anak tak tahu diri!" Ni Sekar memaki.
Aku tidak peduli. Aku ingin kembali. Cempaka harusnya merasa pantas berkorban untukku. Aku memegang Cempaka semakin keras. Dia merintih kesakitan. Kenapa dia sakit? Aku yang terluka di sini. Aku dikhianati orang tuaku.
"Gia berhenti!" Dwinata berteriak.
Aku tidak memalingkan wajah. Hanya Cempaka yang kulihat. Dia kesakitan karena cakarku menusuk bahunya.
"Lakukan saja, Gia," kata Cempaka begitu lirih.
Keraguan merasuk melihatnya tersenyum di antara derai air mata. Aku enggak sanggup melakukan ini lagi, tapi aku mau pulang.
Sebuah suara meraung terdengar dari langit. Belum sempat aku mencari sumbernya, sebuah pukulan menyerangku. Badanku terlempar beberapa meter dan menabrak beberapa pohon sampai tumbang. Aku menjerit kesakitan. Rasanya puluhan kali lebih buruk dari serangan Ni Sekar.
Derap langkah sepasang kaki menghampiriku yang teronggok lemah. Seekor naga hitam yang puluhan kali lebih besar dari wujud nagaku berdiri. Ada murka yang menyala di mata kuningnya. Getir dan takut menyelimutiku.
"Naga tidak menyerang ibunya, Gia. Apa yang baru saja kau lakukan melanggar hukum alam," kata naga hitam itu. Suaranya menggelegar, tapi aku tetap mengenalinya adalah milik Rawindra. Dia wujud naga dari Rawindra.
"Aku benci di sini. Aku ingin menjadi manusia dan pulang. Aku tidak mau menjadi siluman," raungku sembari menangis.
Rawindra menggeleng. "Kau tak mungkin pulang dalam wujud silumanmu. Kau akan tetap di sini."
"Kembaliin aku ke wujud manusia," pintaku.
"Tak bisa. Kau sendiri yang harus memperoleh kekuatan untuk kembali ke wujud manusia," balas Rawindra tegas.
Aku menangis makin kencang. Badanku sakit, aku berubah menjadi kadal raksasa dengan sepasang sayap kelelawar, dan tidak bisa pulang. Apa lagi yang bisa lebih buruk dari hancurnya masa remajaku.
"Kita pulang." Rawindra tidak memberi kesempatan membantah. Dengan sihir, dia mengangkatku naik ke punggungnya. Rasa hangat melingkupiku. Sebelum Rawindra membawaku terbang, aku menoleh pada Cempaka yang susah payah berdiri dipapah Dwinata dan Ni Sekar. Rasa bersalah menghinggapi.
"Apa Cempaka baik-baik saja?" tanyaku.
"Setelah nyaris celaka, menurutmu dia baik-baik saja?" Rawindra membalasku ketus.
Kami pun diam sepanjang perjalanan pulang ke rumah Rawindra. Kakek pertapa dan Nek Parsih menunggu. Mereka membantuku beristirahat di kamar dengan kekuatan sihir. Sepanjang malam aku demam. Nek Parsih dan kakek bertapa bergantian memberikanku jamu yang rasanya buruk.
Esoknya, Rawindra masuk ke dalam kamarku dalam wujud manusianya bersama Cempaka. Aku mendengkus kesal melihat Rawindra bisa berubah kapan saja.
"Kau akan segera belajar di sekolah siluman," kata Rawindra.
"Aku enggak mau," tolakku.
"Kalau begitu, kau akan bertahan dalam wujud ini selamanya."
Aku melotot dan Rawindra malah buang muka. Cempaka bersikap sebaliknya, dia mendekat, lalu mengelus hidungku.
"Kau perlu belajar bersama Mpu Batara dan Dwinata jika kau ingin kembali ke wujud manusia. Ayahmu tidak bisa menyokong energimu lagi."
Aku merengut. "Kenapa aku tiba-tiba jadi naga?"
"Karena kau marah. Kekuatan silumanmu lepas tak terkendali. Tidak ada naga yang pernah gagal menahan amarah mereka," sahut Rawindra.
"Maaf," gumamku.
"Asal kau selamat, itu sudah cukup. Jika kau membiarkan dirimu termakan kekuatan sendiri, kau butuh bertapa seratus tahun untuk mengendalikan kekuatanmu," kata Cempaka.
"Aku enggak mau bertapa lama-lama. Aku..." aku melirik Rawindra. "Mau sekolah."
"Di sekolah siluman," lanjut Rawindra tegas.
"Iya, di sekolah siluman," ulangku.
"Kalau begitu, aku pergi. Tolong jaga Gia." Rawindra berbicara ke Cempaka.
Begitu Rawindra menghilang di balik pintu, aku bertanya ke Cempaka. "Dia mau kemana?"
"Ayahmu harus bertapa."
"Dia sudah bertapa kemarin."
"Tapanya terputus di tengah jalan. Dia harus mengulangnya lagi."
"Karena aku, ya?"
Cempaka enggak menjawab dan hanya tersenyum. Dia pun meninggalkanku. Aku diam di kamar, merenungi nasibku yang jungkir balik. Enggak ada jalan kembali kecuali melanjutkan kehidupanku di sini sembari belajar kembali ke wujud manusia.
VVV
Setengah tahun sudah lewat. Aku masih tinggal di dunia gaib. Wujudku sudah hampir sempurna seperti aku yang normal. Tinggal sepasang tanduk mungil yang belum bisa aku hilangkan. Cempaka tinggal bersamaku setiap Rawindra bertapa. Ni Sekar memberikan izin dengan alasan wujud nagaku yang hijau mirip seperti bangsa ular telah mencoreng martabat mereka. Aku ingin ganti warna sisik nagaku. Menurut Dwinata, itu enggak mungkin kalau alasannya enggak mau mirip siluman ular. Warna sisikku adalah anugerah yang patutnya disyukuri, katanya.
Sekolah siluman berisi anak-anak siluman yang usianya mirip denganku. Sekitar seribu tahun. Aku lumayan betah. Mereka juga suka bergosip. Kami cocok gitu.
Nek Parsih memberi kabar kehamilan mama. Akhirnya mama bisa hamil setelah menikah dua puluh tahun. Aku senang akan punya adik manusia. Nek Parsih menawarkan bertemu mama dan papa, tapi kutolak. Nanti saja saat bayinya lahir. Semoga saat itu tanduk nagaku sudah bisa kututupi.
Cempaka yang sekarang aku panggil ibu sering memasak. Makanannya lezat dan membuat kenyang. Bukan berarti masakan mama enggak enak. Hanya saja seleraku enggak sesuai dengan mama dan papa.
Rawindra akan pulang malam ini. Aku enggak sabar menunjukan kemampuanku berubah wujud.
"Ayah!" aku berseru senang melihat naga hitam mendarat di pekarangan rumah. Aku berlari menyambut ayah nagaku.
Sesuai kata kakek pertapa di pelajaran moral siluman seminggu yang lalu, kita enggak bisa memilih orang tua macam apa yang akan melahirkan kita. Yang bisa dilakukan setiap anak sepertiku adalah bersyukur dan mencoba melihat segalanya dalam sisi positif.
Kalau dilihat sisi positifnya punya ayah naga tentu saja aku tetap awet muda untuk beberapa ratus tahun ke depan. Sekedar info, siluman enggak butuh skincare dan perawatan salon untuk mempertahankan wajah glowing. Cukup rajin bertapa, menyerap energi alam, dan VOILA kami dapatkan badan bugar serta wajah rupawan. Kurasa, Nek Parsih dan kakek pertapa sengaja mempertahankan rupa tua mereka untuk gengsi. Kalau Dwinata, mungkin dia punya alasan tersendiri untuk kepala babinya.
Satu-satunya yang paling nyebelin ialah AKU HARUS BELAJAR DI SEKOLAH SILUMAN SELAMA SERATUS TAHUN.
Ada yang mau gantian sama aku?
TAMAT
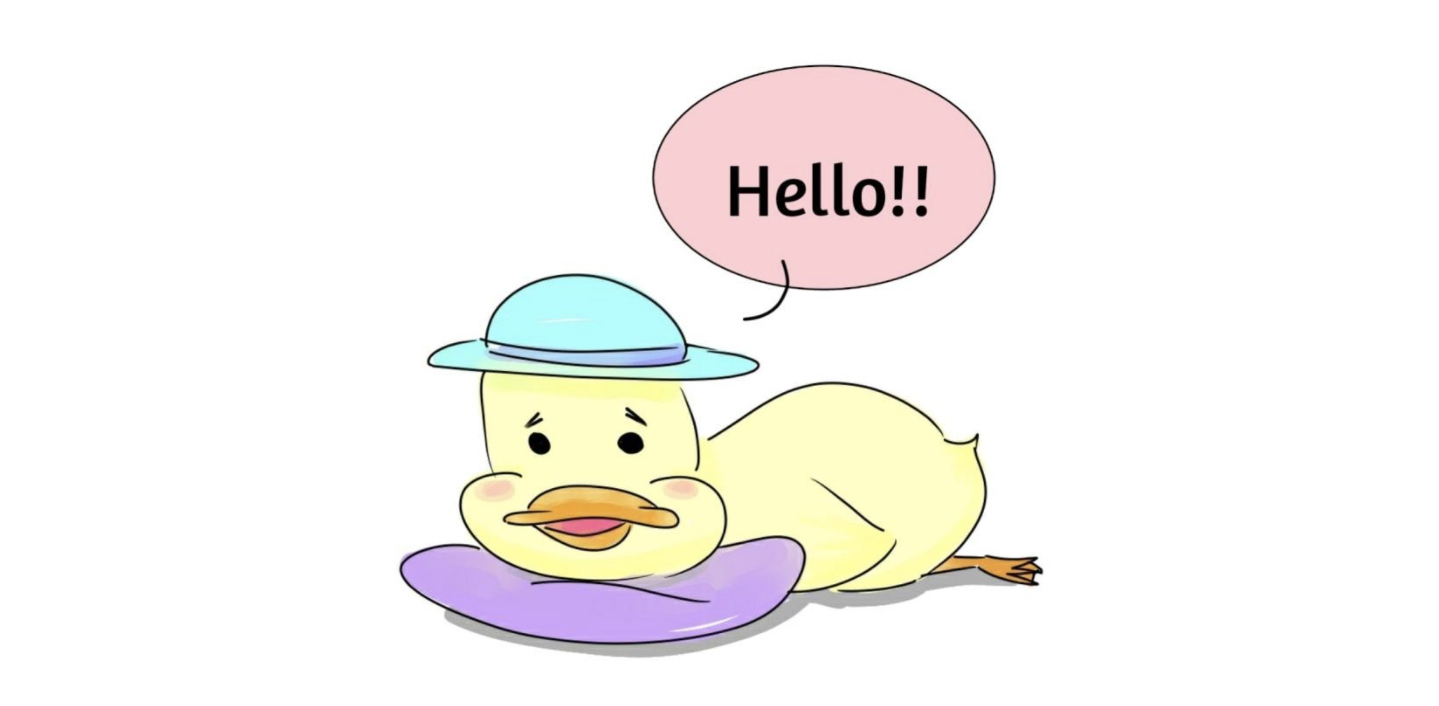
Halo, aku Bebeklucu atau yang sering kalian panggil Miss Bekcu. Aku penyuka ayam goreng, tapi nggak botak kayak Upin dan Ipin. Kartun kesukaanku Marsha and The Bear, walo umur nggak cocok banget sama tontonan.
Aku mulai gabung di Wattpad tahun 2016 dan mulai aktif berselancar bacaan di awal tahun 2017. Dari situ, aku mulai nulis cerita pertamaku. Alasanku nulis adalah memuaskan pembaca pertamaku, yaitu AKU SENDIRI. Aku buat cerita yang aku mau baca. Kalau ada yang terhibur dengan tulisanku, aku anggap itu bonus. Sampai saat ini aku masih dan akan terus belajar biar bisa bikin tulisan sekeren Jill Mansell dan Diana Gabaldon. Impian dan celeb crush-ku selalu berubah-ubah, tapi kesukaanku sama makanan manis nggak tergantikan. Aku selalu dibuat jatuh cinta sama kenikmatan Oreo cokelat dan Chatime. Ngobrol bareng teman dan ngetik cerita di kendaraan umum masih jadi andalan nyari inspirasi tulisan.
Buat kamu yang mau kenal dekat aku, yuk follow Instagram missbebeklucu! Jaga kesehatan dan jangan lupa bersyukur ^o^
Kecup becek, Miss Bebek yang suka susu pisang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro