Rimbana: Heroine's Neighbor
|| Rimbana | 1443 kata ||
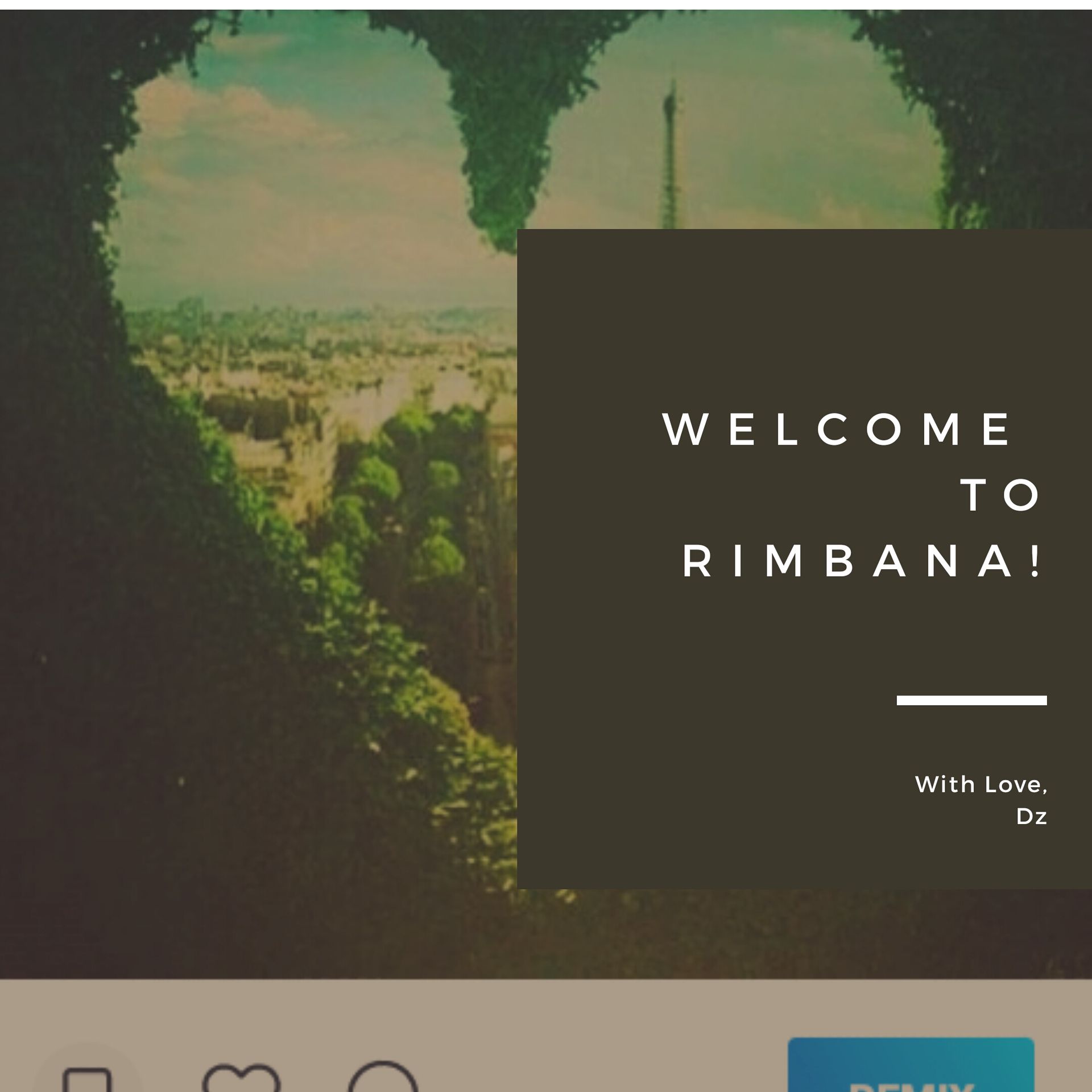
Aku pulang ke rumah tepat ketika matahari sudah melewati atas kepala. Sembari menenteng seikat rambutan pulang, aku bersenandung kecil. Sembari bersenandung, kupetik sebuah, kemudian menggigitnya dan mulai mengunyah. Yah, hitung-hitung camilan sampai aku mencapai rumah. Hehehe.
Masih melewati jalanan yang tadi kulewati. Tengah-tengah kampung. Perumahan penduduk. Warga yang beraktifitas meskipun panas menyengat, dan terakhir aku berhenti di depan rumah Kakek Sina. Melambai padanya yang tengah duduk di depan pintu rumahnya.
Memasang ancang-ancang, lalu kemudian aku melemparkan seikat rambutan yang tadi ku bawa ke arah si kakek. Beliau menyambutnya dengan tepat dan sigap. Lalu kemudian tersenyum sumringah.
"Terimakasih, Aruni. Aku akan segera menghabiskan semua rambutan manis ini," ucapnya dengan keras.
Aku tersenyum. "Ya, habiskan saja. Habiskan sampai kadar gula dalam darahmu meningkat. Aku tidak akan ikut gali tanah," balasku.
Kakek Sina tertawa. "Dasar bocah kurang ajar!" teriaknya kemudian melambai-lambai.
Aku pun melambai dan kemudian berlalu, kembali pulang ke rumah. Sudah waktunya makan siang, ngomong-ngomong.
***
"Ibu, aku pulang!" teriakku sembari membuka pintu. Mengedarkan pandangan mencari-cari Ibu. Rumah sangat sepi, dan tidak sengaja aku melihat kepulan asap dari pintu belakang.
Aku pun tersenyum sumringah, tahu bahwa Ibu sedang bergumul dengan masakannya. Segera saja aku melangkah ke sana. Melongokkan kepala keluar pintu. Dan benar saja, Ibu sedang meniup tungku batunya dengan salung bambu. Aku duduk di atas jenjang memperhatikan.
Eh, ngomong-ngomong aku belum bilang ya, kalau rumah penduduk Rimbana berupa rumah-rumah panggung setinggi dua meter. Tujuannya agar jika malam hari, dan hewan liar berkeliaran memasuki pemukiman, mereka tidak bisa langsung masuk ke rumah. Sementara dapurnya di bangun di luar.
"Jangan cuma melihat saja. Bantu Ibu mengangkat sagunya," dumel Ibu ketika melihatku duduk selonjoran di atas tangga dengan santai.
Ibuku wanita yang kuat. Meski usianya sudah lebih setengah abad, beliau masih sering keluar-masuk hutan untuk mencari kayu bakar. Atau menggarap ladang jagung milik kami yang dikerjakannya sendiri---tentu saja aku juga membantu. Atau memanen sagu dengan ibu-ibu lain ke hutan.
Aku memasang cengiran, kemudian turun ke bawah. Mengangkat adonan sagu mengepul yang diletakkannya di ember kecil tanah liat kemudian membawanya lagi ke atas. Meletakkan seember sagu itu di tengah ruangan. Tak lama Ibu menyusul dengan semangkok gulai ikan mas yang menguarkan bau harum.
Perutku langsung menabuh gendang ketika membaui aromanya.
Aku lekas-lekas duduk bersila. Mengambil piring tanah liatku dan mengulurkannya ke depan Ibu yang baru duduk.
Ibu mendelik dengan mulut menggerutu, sementara aku hanya memasang cengiran tidak berdosa. Namun, Ibu tetap mengambil piringku. Mengisi kuah gulai ke sana beserta sepotong ikan mas besarnya. "Kau sudah 17 tahun, Aruni. Coba belajar mengambil makananmu sendiri," gerutu Ibu yang mulai mengambil dua bilah bambu kecil yang diserut berbentuk silindris berukuran satu jengkal. Memegangnya satu di setiap tangan dan mulai menggulung-gulungnya di atas ember sagu. Membuat sagunya bergumpal sebesar ibu jari kaki kemudian menaruhnya ke piringku.
"Itu sungguh merepotkan tahu, Bu. Menggulung-gulung sagu dengan kayu begitu sungguh menguji kesabaran. Karena aku tidak sesabar Ibu, jadi aku minta tolong Ibu saja," jawabku sambil memasang raut sok menggemaskan.
"Mulutmu itu, ya. Pandai sekali merangkai kata," sungut Ibu. Kemudian mengulurkan piringku yang sudah penuh dengan gumpalan sagu—yang kuterima dengan mata berbinar tentu saja.
"Jangan makan dulu. Antarkan buat Paman Siak dulu sana," sela Ibu ketika aku belum sempat menyendok barang sesuap.
Aku berjengit dan bibirku berdecak ketika Ibu menyebut nama orang itu. "Tidak mau, ah. Nanti aku diomeli terus diludahi lagi. Tidak. Tidak. Ibu sajalah yang mengantarkannya pada orang tidak waras itu," tolakku langsung tanpa banyak alasan.
Paman Siak adalah tetangga kami yang rumahnya berjarak dua rumah dari sini. Dia adalah pria 60-an dengan rambut gondrong yang acak-acakan. Mukanya lusuh berminyak dan ditumbuhi banyak jambang yang tidak pernah dibersihkannya. Matanya bulat dan bibirnya hitam karena kebanyakan menghisap rokok pucuk anau. Dia tinggal sendiri sekarang semenjak istri dan anaknya meninggal akibat kerusuhan 8 tahun lalu. Kerusuhan yang juga merenggut ayahku dari sisi kami. Jika mengingat kerusuhan itu, hatiku terasa perih dan ngilu.
Rumah-rumah warga berkobar dengan api merah menyala-nyala. Teriakan minta tolong, jeritan, dan tangisan anak-anak menggema di mana-mana. Istri Paman Siak beserta satu anaknya tertimpa reruntuhan kayu rumahnya dan hangus terbakar. Sementara aku, Ibu berhasil membawaku keluar dan lari menjauhi perkampungan. Dan Ayahku, dia beserta lelaki Rimbana lain dan Pasukan Rimbana bertarung habis-habisan mengejar Suku Hitam, si pembelot, yang menyebabkan kerusuhan ini. Sebagian menyelamatkan warga dari rumahnya dan mengamankan mereka. Untung tak dapat di raih, malang tak dapat ditolak. Ayahku gugur ketika mengejar salah satu Suku Hitam ke dalam hutan. Tombak menembus perutnya, dan panah menancapi dadanya. Oh, aku ingin menangis jika mengingat bagaimana Ayahku ditemukan. Aku yang waktu itu masih berusia 9 tahun menangis histeris. Aku meraung-raung dan menendang apa saja disekitarku. Dadaku ngilu, nafasku sesak, dan dunia rasanya menyempit. Aku tidak bisa memikirkan apa pun dengan jernih. Rasanya tidak adil sekali Tuhan mengambil Ayahku yang baik hati dengan cara begini. Namun, Ibu menguatkanku, dan mengatakan bahwa Ayah adalah Pahlawan Rimbana. Walaupun begitu, aku tetap menyimpan dendam dan berjanji akan membalas Suku Hitam sialan itu.
Selain aku dan Paman Siak, penduduk lain juga banyak yang kehilangan keluarganya. Bahkan ada yang satu keluarga meninggal terbakar di dalam rumahnya sendiri. Dan ada yang jatuh dari rumahnya karena gemetar ketakutan kemudian tubuhnya mendarat pada bilah bambu pagar. Membuatnya tewas seketika sebelum akhirnya rumahnya yang terbakar runtuh dan menguburnya.
Namun, Paman Siak kurasa memang tidak waras setelah insiden itu. Kubilang dia tidak waras karena kerjanya setiap hari hanyalah mendumel sendiri di rumahnya yang reot karena tidak pernah dibenahi lagi. Mengumpati entah siapa itu. Selain berbicara sendiri dengan asap rokok mengepul, pria itu juga sering marah-marah tak jelas pada anak-anak seperti kami sambil mengumpat dan menyumpah serapah. Mulutnya kalau berbicara tidak pernah disaring. Dan kadang-kadang suka meludahi anak-anak yang lewat---itulah kenapa aku bilang tidak waras.
Namun, yah, Ibuku tetaplah Ibuku. Sebagai tetangga yang baik, dia tetap menyiapkan makanan untuk Paman Siak, mengabaikan kedongkolan anaknya yang sudah mencapai kepala dan ingin meledak saja rasanya.
"Coba kau bersikap lebih baik padanya, dia pasti lebih baik juga. Memangnya siapa yang tidak marah pada anak nakal yang suka mencuri buah lentimunnya?"
Aku tersipu mendengar ucapan Ibu. Tapi, kan, siapa suruh buah lentimunnya besar-besar dan terlihat ranum? Salah Paman Siak juga yang menanamnya di samping rumah. Mana pagarnya cuma setengah meter, dan itu pun jarang-jarang. Kami sudah meminta maaf---walau besoknya mencuri lagi---tetapi tetap saja, orang itu sering mengumpati kami kalau lewat di depan rumahnya, dan itu sama sekali bukan tindakan terpuji. "Pokoknya aku tidak sudi mengantarkan makanan ke rumahnya. Lagian, Bu---"
"Sudah, antarkan saja dengan cepat lalu kembali lagi ke sini."
Belum sempat aku mengeluarkan ultimatum penolakan, Ibu sudah menyelaku lagi. Dengan berat hati, kuambil piring yang diulurkan Ibu, yang sudah ditutupnya dengan daun pisang agar tidak kemasukan benda-benda aneh. Sebenarnya, kalau tidak mengingat Ibu tidak akan membiarkanku makan dan malah mengusirku dari rumah, aku berniat memasukkan barang satu atau dua ulat pohon ke dalam piringnya. Tetapi, yah, itu kan cuma niatku. Aku tidak berani melawan jika sepiring saguku dan sepotong ikan mas besarku jadi taruhan.
Aku berdiri dengan lesu, menuruni tangga dengan cemberut, dan menghentak-hentakkan kaki.
Aku membawa piring itu dengan malas, dan ketika melewati rumah tetangga kami yang di depannya ada pohon jambu biji dengan ulat hijau sebesar kelingking, rencana tadi terbersit lagi. Namun, aku lekas-lekas menggelengkan kepala dan berjalan cepat ke rumah Paman Siak.
Tujuanku saat ini cuma satu; antarkan dengan cepat, lalu pulang, dan santap makananku.
Aku memanggilnya dengan sopan sekitar tiga kali. Tetapi Paman Siak tidak kunjung membuka pintunya. Jadi kuputuskan untuk berteriak, "PAMAN! MAKANANMU DATANG DAN YANG MENGANTAR INGIN LEKAS PULANG! KALAU TIDAK KELUAR AKU BAWA PULANG SAJA LAGI!"
Tak berapa lama, Paman Siak muncul membuka pintunya dengan tatapan jengkel. Mukanya tetap lusuh dan berminyak. Rambut gondrongnya mengambang ke mana-mana seperti monster. "Mulutmu itu seperti sangkakala saja. Membuat telingaku pekak," rutuknya.
Aku hanya memasang tampang jengkel kemudian mengulurkan piringnya dari bawah.
Paman Siak meraihnya. Kemudian setelah itu dia menatapku merendahkan. "Bocah setan sepertimu ternyata bisa berbuat baik juga. Kukira kalian hanya bisa mencuri dan mencuri."
Aku berdecak kemudian memutar mata. Serius aku menyesal tidak mengambil ulat-ulat tadi dan memasukkannya ke piringnya. Lihatlah, alih-alih berterimakasih, dia malah mengataiku.
"Ya. Ya. Terserah Paman saja. Besok-besok aku tidak mau mengantarkan makanan pada monster tidak tahu terimakasih lagi," jawabku malas meladeni. Daripada menunggunya mengeluarkan umpatan yang pasti keluar sebentar lagi, aku berbalik dan berlari pulang.
Benar saja, Paman Siak mengumpat keras-keras sebelum akhirnya membanting pintu.
"Dasar monster tidak punya rasa terima kasih!" omelku lalu menyuap segumpal sagu setelah menceritakannya pada Ibu.
Sementara Ibu, jangan ditanya. Wanita itu mengabaikanku dan membiarkanku berbicara sendiri sambil menyuap makanannya dengan lahap. Argh! [ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro