Rimbana: Heroine's Friends
|| Rimbana | 1706 kata ||
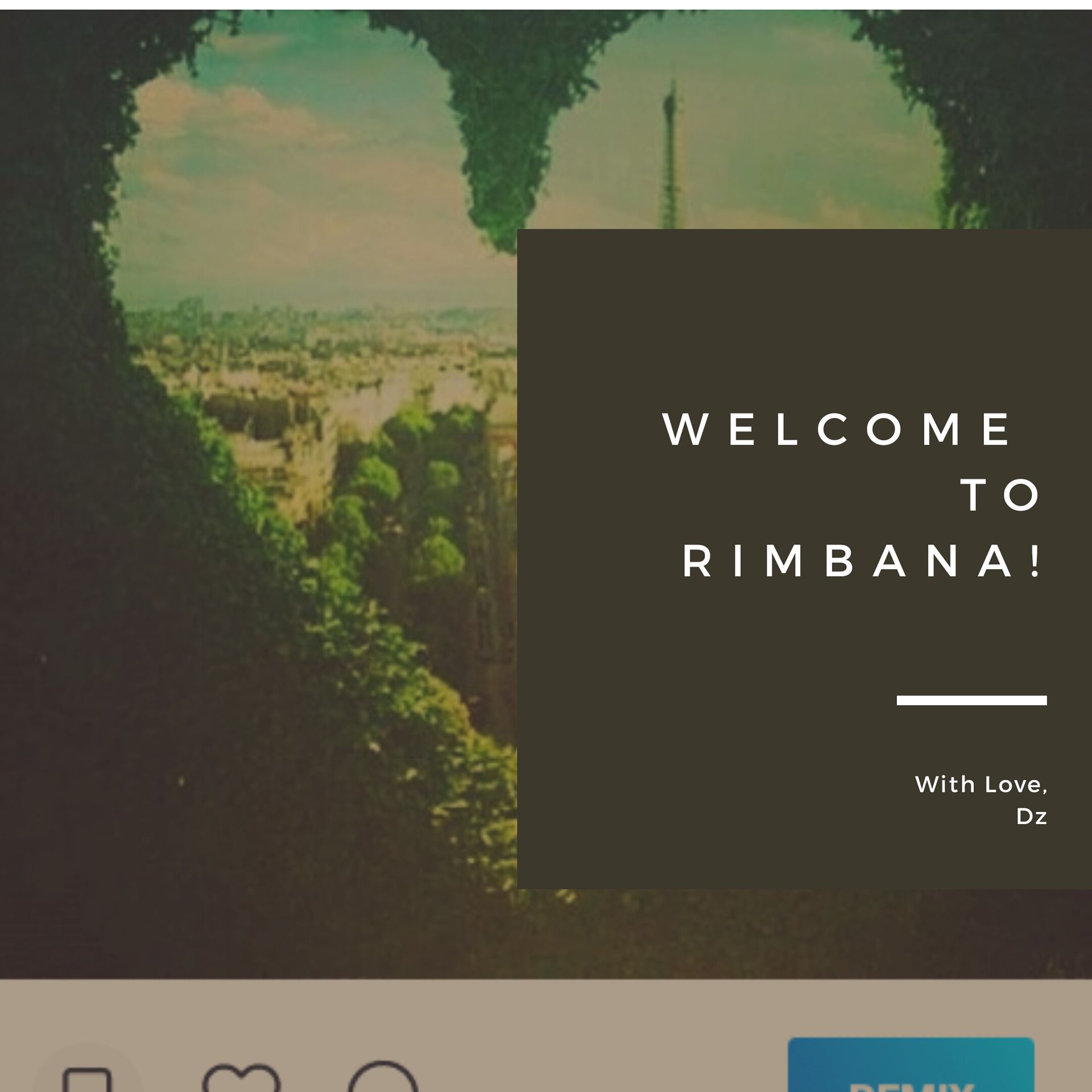
Matahari baru sepenggelan naik. Cahaya menelisik di antara sekat-sekat dedaunan sebelum akhirnya mencapai tanah coklat lembab yang ditumbuhi rerumputan hijau. Semalam hujan membasuh tanah Rimbana, jadi wajar jika pagi ini suasananya lebih tenang dan sejuk dengan sedikit kabut-kabut.
Aku berjalan dengan melompat-lompat kecil. Menunjukkan bahwa sendal kulit baruku yang dibuatkan Ibu begitu indah dan juga kuat. Buktinya sekeras apa pun aku menghentak tanah, sendalnya tidak robek dan hancur. Aku membiarkan rambut hitam kecoklatan sepunggungku yang agak bergelombang ujungnya itu tergerai, menyapu-nyapu baju seratku.
Perkampungan sudah mulai ada kehidupan. Penduduk mulai keluar rumah untuk melakukan rutinitas biasa mereka. Berkebun, beternak, berburu, atau hanya sekedar bercengkrama. Bahkan beberapa hanya mondar-mandir di depan rumah bambu mereka, entah sedang memikirkan apa.
"Di sebelah kiri masih belum rapat, Kek!" sorakku ketika melewati rumah Kakek Sina. Pria tua yang berusia nyaris satu abad dengan kulit coklat yang mulai mengeriput dan sebelah mata yang celek karena bergumul dengan babi hutan ketika ia berburu dahulu. Tentu saja Kakek Sina memenangkan pergumulan. Memangnya siapa yang mampu mengalahkan orang dengan stamina tidak wajar seperti Kakek Sina? Selain itu, Kakek Sina juga pemburu yang begitu disegani dahulu karena kemampuannya dalam berburu tidak ada tandingannya. Namun, itu dulu, sekarang pria itu sudah semakin menua dan mengaku lelah dengan dunia perburuan (walau dia pernah mengaku kalau berburu adalah hidupnya), kemudian pensiun. Semua orang tahu Kakek Sina hanya tidak ingin terlihat menyedihkan, padahal dia tidak berburu lagi karena memang kesehatannya memburuk dan tidak bisa berlama-lama di luar rumah, atau kalau dia memaksakan diri, maka bisa saja dia terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bangkit berhari-hari.
Kakek Sina mempunyai tatapan tajam dan wajah sangar, sehingga banyak anak-anak yang takut kepadanya. Apalagi ditambah sebelah matanya yang putih semua dengan jejak luka mengerikan. Membuat hidup pria sebatangkara itu semakin hampa saja. Hanya beberapa anak yang berani berbicara padanya. Itu tentu saja aku, dan beberapa temanku. Beliau sebenarnya orang yang ramah dan penyayang. Dia tidak pemarah dan semenyeramkan wajahnya. Buktinya sekarang pria itu dari atas atap ijuknya melambai-lambai padaku, mengacungkan ibu jari, dan berucap, "Terima kasih, Aruni! Mata orang tua ini memang sudah tidak seterang dulu!" kemudian bergeser ke arah yang kutunjuk dan mulai merapatkan atap ijuknya. Beliau sedang membenarkan atapnya yang sudah jarang atau mengganti yang lapuk dengan yang baru. Bukannya aku sudah bilang ya? Meskipun usianya nyaris satu abad, Kakek Sina masih mempunyai tenaga yang cukup hanya untuk sekedar memanjat dan membenarkan atap.
Aku balas tersenyum dan melambai-lambai. Kemudian berjalan lagi.
Menghirup udara panjang, membiarkannya berkumpul di paru-paruku baru kemudian melepaskannya perlahan. Aroma tanah Rimbana ketika habis disiram hujan, kemudian diserap oleh matahari itu begitu menenangkan.
Aku berbelok ke kiri, menelusuri jalan setapak yang lebih kecil lagi. Di sekelilingnya berdiri pohon-pohon besar yang tinggi dan beberapa semak belukar. Tidak menyeramkan sama sekali buatku, karena memang di sinilah kami tinggal. Tujuanku bukan tengah hutan, melainkan ke tepinya. Ke arah tebing-tebing tinggi yang di bawahnya lautan. Tempat favoritku sejak---eum---kira-kira 10 tahun lalu, waktu itu usiaku baru 7 tahun. Ketika Ayah mengajakku ke pinggiran hutan dan mengenalkan perairan luas (yang dulu kusebut sungai raksasa) bernama laut pertama kali. Aku begitu terkagum-kagum waktu itu dan rasa-rasanya aku ingin memindahkan laut ini ke halaman depan rumahku. Namun, Ayah mengatakan itu tidak mungkin bisa dilakukan, dan aku mendesah kecewa.
Aku duduk di bawah pohon rambutan tua yang batangnya sudah sangat besar dan dahannya melebar ke mana-mana dengan daun yang lebat---tempat favorit yang kumaksud. Merangkul lututku dan memandang lurus ke depan sana, ke antara ombak yang saling menggulung kemudian berdamai dan tenang kembali. Lalu mengulang kembali saling bergulung. Sementara angin laut mengembus-hembus rambutku, begitu menyejukkan.
Di sini begitu sunyi, tidak ada suara apa pun selain deburan ombak, burung-burung, dan desauan angin---alasan kenapa aku menjadikan tempat ini favorit. Aku bisa menyendiri dan mengenang hari-hari yang telah berlalu, termasuk Ayah. Ah, Ayah. Mengingatnya, aku mendadak ingin menangis tersedu-sedu saja. Tetapi tentu tidak kulakukan. Sekarang aku sudah besar dan tidak mungkin bergulingan di tanah seperti yang kulakukan 8 tahun lalu. Jadi, daripada menangis, aku memilih memejamkan mata dan membayangkan Ayah ada di sini, bersamaku.
"Pemandangannya lebih indah ya, jika matahari baru sepenggalan naik."
Aku menoleh, mendapati Kelana berdiri tiga meter dariku. Namanya Kelana Antara. Tubuhnya tegap kecoklatan dan rahangnya tegas, benar-benar seperti anggota Pasukan Rimbana pada umumnya. Pasukan Rimbana adalah semacam prajurit yang dilatih untuk melindungi Rimbana dari berbagai bahaya. Dan Kelana sudah memimpikan untuk bergabung dengan pasukan ini ketika kami masih anak-anak. Umurnya 19 tahun dan dia sudah bergabung dengan Pasukan Rimbana dua tahun lalu. Mewujudkan mimpi kecilnya. Matanya berwarna hitam kelam seolah-olah bisa menghisapku jika terus menatapnya. Namun senyumnya indah dan mendebarkan. Dia berjalan ke arahku. "Mau naik?" tanyanya sambil menggerakkan kepala ke atas pohon.
"Tentu!" balasku dengan senyum tak kalah cerahnya. Dia memanjat duluan, kemudian aku menyusul.
Kami memilih dahan besar yang mengarah ke bawah tebing. Duduk bersisian di sana menjuntaikan kaki. Mengayunkannya sesekali menepis-nepis udara.
"Kalau dari atas sini, semuanya terasa kecil," ucap Kelana memandangi lurus ke depan.
"Hm. Aku jadi merasa bisa melihat semuanya," anggukku mengiyakan.
"Menurutmu, apakah selain Rimbana, ada orang-orang seperti kita?" tanyanya.
Aku tentu saja langsung mengangguk antusias. "Tentu saja."
"Tetapi di seberang sana adalah Tanah Terkutuk dan isinya monster, dan kurasa mereka bukan orang-orang seperti kita."
"Iya juga sih. Tapi kan, di Rimbana juga ada monster. Mereka menghuni Hutan Hitam, dan kita hidup berdampingan asal saling menepati perjanjian untuk tidak memasuki wilayah masing-masing. Jadi kurasa di Tanah Terkutuk pun pasti ada yang seperti kita. Rasanya tidak masuk akal jika semuanya berisi monster. Bukankah di mana ada orang jahat, juga ada orang baik?"
"Uuuu." Kelana menatapku dengan sorot meledek kemudian menggeleng sambil berdecak. "Aruni, kau dan pikiranmu itu sungguh luar biasa," pujinya, yang malah terdengar seperti cemoohan bagiku.
Aku memutar mata. "Lagian, apa kau tidak penasaran dengan bayangan tinggi itu?"
Aku menunjuk ke seberang sana, ke arah deretan bayang-bayang putih yang menjulang tinggi. Yang selama ini selalu membuat berbagai pertanyaan bermunculan di kepalaku dan rasanya aku ingin menenggelamkan diri karena rasa penasaran ini terus menggerogotiku perlahan. "Apakah monster Tanah Terkutuk membangun menara setinggi itu?"
"Ya bisa jadi. Mungkin mereka membangun menara untuk mengawasi kita, kalau-kalau ada penduduk Rimbana yang menyeberang, dan mereka bisa mempersiapkan diri untuk menangkapnya ketika sampai."
Aku lagi-lagi menatap jengkel kemudian memutar mata ketika mendengar jawaban Kelana. Memilih mengabaikan dan meraih setangkai rambutan dari dahan yang menjuntai di dekatku. Mengupasnya dan mulai mengunyahnya asal-asalan. "Bagaimana mungkin seorang Pasukan Rimbana berpikir sesempit itu," celetukku sengit.
Kelana tertawa pelan, kemudian geleng-geleng kepala dan menatapku sebentar lalu menatap ke depan lagi. "Pasukan Rimbana kan bertugas melindungi Rimbana dan seisinya dari bahaya dan bertugas mendeteksi ancaman. Jadi wajar kalau aku mengatakan mereka membangun menara tinggi untuk mengintai. Dan juga agar kau tidak penasaran lagi dengan tanah seberang."
"Tetapi kenapa menaranya berdekatan bahkan terlihat berdempet-dempet begitu?!"
"Ya---"
"Oi!"
Seseorang bersorak dan kami serempak menatap ke bawah.
"Sudah kuduga kalian pasti ke sini. Kenapa tidak ajak aku sih? Aku kan mau ambil rambutan juga." Itu Nira, teman kecilku. Kami seumuran. Nira punya mata berwarna coklat, kulitnya langsat, dan rambutnya lurus seleher. Gadis itu lebih suka bertelanjang kaki daripada menggunakan sandalnya. Dan sekarang lihatlah, dia mulai menatap rambutan yang memerah di atas sana dengan tatapan harimau kelaparan yang baru menemukan mangsa. Melupakan ekspresi kesalnya beberapa saat lalu.
"Santai saja dong melihatnya, tidak akan hilang juga," celetukku, namun Nira sepertinya tidak mendengar. Nira termasuk anak yang bengal, walau pun ia perempuan, tetapi dia lebih suka berkeliaran ke hutan dan berburu. Buktinya ketika usianya baru 8 tahun, dia menyelinap ke dalam kelompok perburuan Rimbana dengan panah besar ayahnya. Dan coba tebak apa yang terjadi? Dia berhasil menangkap rusa yang ukurannya dua kali lipat dari tubuhnya. Walaupun setelah itu ibunya mengurungnya seharian dan memarahinya habis-habisan, tetapi dia tetap saja bengal dan keras kepala. Luka sayatan lebar akibat ranting di bahunya seolah-olah bukan apa-apa. Apalagi ayahnya yang juga seorang pemburu begitu mendukungnya dan malah mengajari Nira cara memegang panah yang benar alih-alih menyuruhnya mempelajari cara memintal bulu domba dan menganyam, dan sekarang lihatlah, gadis itu lebih seperti seorang monyet dari pada seorang manusia. Dalam waktu beberapa menit dia sudah sampai ke sisi dahan-dahan pohon rambutan yang lebat dan mulai memakannya dengan beringas.
"Kau ini benar-benar Nira atau monyet hutan sih?" Aku menatapnya yang berdiri di dahan di atas kami dengan mata menyipit.
"Eumm. Rambutan ini benar-benar manis. Pokoknya ya, semuanya milikku dan aku akan mengunjunginya tiap hari. Eummm." Nira terus mengupas dan memakan dengan mata terpejam dan tangan menaut di dada. Benar deh, dia itu kalau sudah bertemu makanan pasti langsung dihak milikkan olehnya. Semuanya punya dia.
"Ya, ya. Terserah kau saja. Mau kau habiskan dengan batangnya sekalian juga tak apa," ujarku sembari menggeleng-gelengkan kepala, membuka satu rambutan lagi yang tadi kuambil dan memakannya.
Kelana hanya terkekeh geli melihat Nira yang kesetanan dengan rambutan. Sudah tidak heran lagi, sih.
Kelana baru saja hendak menggigit satu rambutan ketika tiba-tiba Nira menginterupsi, "Hei! Itu punyaku! Selain aku dan Aruni, tidak ada yang boleh makan!"
Nira melempar kulit rambutannya ke kepala Kelana tanpa sempat pria itu hindari. Aku terbahak melihat ekspresi jengkelnya.
"Mana bisa begitu. Yang pertama diajak Aruni ke sini kan aku!" balasnya tidak terima kemudian melemparkan rambutan di tanganya pada Nira---tidak jadi dimakan---dan Nira langsung bergerak menghindar di atas.
"Tapi temannya Aruni itu aku!" cibir Nira dari atas.
"Aku juga temannya, hei!"
"Tapi aku lebih dulu berteman dengan Aruni, berarti selain Aruni, rambutannya punyaku!"
Aku semakin terbahak. Bisa-bisanya mereka masih bertengkar seperti anak kecil. Dan dari kecil, mereka memang selalu bertengkar. Tampaknya hingga sekarang pun tidak berubah. Dasar!
"Awas kau Nira!"
Kelana melempar lagi Nira dengan rambutan, yang kemudian disambut gadis itu, mengupasnya, memakannya, kemudian melemparkan kulitnya kembali pada Kelana. Kelana sendiri sudah semakin tersulut sejak tadi dan berinisiatif mengejar gadis itu ke dahan atas. Nira memanjat lebih tinggi, meloncat ke dahan pohon lain. Dan Kelana yang sudah lupa bahwa dia adalah Pasukan Rimbana yang harusnya berwibawa---harusnya---sudah ikut bergelayutan dari satu pohon ke pohon lain mengejar Nira. Dan aku hanya mampu tertawa terpingkal-pingkal sambil memegangi perut sebelum akhirnya mengikuti jejak mereka. [ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro