GhaiSyah - 36
Di usia yang terbilang muda—sepantaran Bang Veiro—Mas Faddyl sudah mengemban tugas perusahaan sebesar Papa. Kalau dibandingkan, entah Bang Veiro yang emang pemalas plus tidak berguna sebagai anak sekaligus kakak, atau pria berstatus suamiku ini yang kelewat rajin sampai bisa mendapatkan tugas seberat ini, dan anehnya, Mas Faddyl masih waras. Walau sedikit otaknya geser.
Disebabkan kesibukannya juga, Mas Faddyl memintaku sore ini datang ke rumah Mama Lia, membawa sebuah rantang stainless steel tiga tingkat. Pastinya, bukan mengemis makan malam. Seperti yang Mas Faddyl sampaikan kemarin, aku harus belajar memasak dari mama mertua. Nantinya, aku yang harus membawa makanan untuk Mas Faddyl, karena mungkin ia tidak akan bisa keluar dari kamarnya semalaman ini.
Padahal, ya, ternyata tugas kantornya itu berupa observasi kerja sama dengan perusahaan lain, yang bisa dikatakan, deadline-nya tiga bulan lagi. Namun, dasarnya Mas Faddyl yang kelewat mencintai akhir pekan—enggan waktu istirahatnya berkurang hanya demi pekerjaan yang tertinggal—jadilah ia mengerjakan semua pekerjaan lebih cepat dari seharusnya.
Entah aku harus memuji dia kelewat rajin, atau merutuk terlalu bloon; mau-maunya stres di usia muda hanya karena pekerjaan. Pantas, aku akui, dia kesulitan mengobservasi banyak perempuan di luar sana, dan berakhir dengan perjodohan seperti sekarang ini.
Menunggangi B’Twin Riverside 100 Matt hadiah dari Mas Faddyl ini, aku mulai keluar dari pekarangan rumah. Sebelum lanjut berbelok ke jalanan, rantang di bagian keranjang depan aku perbaiki sebentar.
Saatnya meluncur.
Cuaca saat menjelang matahari terbenam seperti sekarang ini, benar-benar nyaman. Sedikit ada rasa syukur dalam hati, karena Mas Faddyl membelikan sepeda. Aku jadi bisa menikmati pemandangan sekitar dengan santai, tetapi tetap mempermudah bepergian ke mana-mana.
Sesampainya di rumah Mama Lia, aku turun dari sepeda. Sedikit celingak-celinguk memerhatikan sekitar, memastikan bahwa Tiana tidak ada di sini sekarang, atau kehadirannya akan menjatuhkan mood-ku hingga dasar.
Aman! Tidak ada tanda-tanda keberadaan Tiana sekarang, seharusnya.
Sebab pernah tinggal di sini, dan sudah kuanggap sebagai rumah sendiri, aku langsung saja masuk ke dalam. Sembari mengucap salam tentunya. Aku menunggu respons, tetapi tidak ada jawaban. Jadilah, aku menyusuri rumah Mama Lia tanpa ada yang menuntun, hingga kakiku kini berpijak di lantai dapur.
Memang, ya. Anak sama mama—sama saja. Kalau fokus dengan sesuatu, pasti sekitarnya tidak diperhatikan. Salamku bahkan tidak dijawab Mama Lia tadi, saking sibuknya beliau di dapur.
"Assalamualaikum, Ma." Sekali lagi, aku menyapa. Membuat perempuan itu sedikit tersentak. "Maaf, Ma. Habisnya tadi, aku ngucap salam, nggak ada yang jawab." Aku meraih tangan Mama Lia untuk menyaliminya. Walaupun menyebalkan, tetap saja, faktanya bahwa Mama Lia adalah mama mertuaku. Harus hormat, walau di dalam hati sibuk memaki.
"Kenapa datang ke sini?" Pertanyaan Mama Lia terdengar begitu sinis. Untung aku tahan. Matanya melirik ke arah barang yang aku bawa, dan segera mengarahkan tatap merendahkannya padaku. "Kalau kamu mau minta makan buat suamimu di sini, jangan harap, ya, Chia." Mama Lia mendumel, kemudian berbalik membelakangiku karena sibuk mengaduk tumisan di wajan.
"Nggak, kok, Ma. Aku tipe manusia anti-mengemis." Untuk mengurangi canggung, aku mengeluarkan sedikit kekehan, sembari mendekat pada Mama Lia. "Aku nggak ngemis di sini, Ma. Cuman ... mau memohon supaya Mama mau ajarin aku masak. Boleh, Ma?"
"Tumben kamu?" Mama Lia mengangkat sebelah alisnya sebagai gelagat meremehkan, saat ia melirik padaku.
"Anu, Ma. Mau jawaban jujur, atau bohong?"
Decak Mama Lia terdengar, dan aku maklumi karena memang aku sedang mengganggunya. Mengundang amarah dari singa, memang selalu menjadi tantangan seru yang berbahaya. Salah-salah, aku yang dimutilasi Mama Lia di sini, dan dihidangkan untuk keluarganya. Namun, aku hanya ingin memperdekat hubungan, kok. Satu keluarga, tetapi saling tidak suka—itu terasa sangat tidak menyenangkan. Apalagi jika masih tinggal satu kompleks. Beuh, rasanya ... pahit banget.
"Bohong, sama jujur." Mama Lia menjawab, terdengar tidak acuh.
Aku tetap memenuhi permintaan Mama Lia.
"Kalau jawaban bohongnya, aku mau jadi istri Sholehah lagi baik, dan patuh, serta membuat Mas Faddyl nyaman sama aku, sehingga membuat pernikahan ini menjadi sakinah, mawaddah, warahmah." Aku buat cara penyampaianku seolah sedang mengucap puisi: penuh penghayatan. "Kalau jawaban jujurnya: memasak sendiri itu termasuk penghematan, Ma. Jadi, sisa uang belanja, bisa aku pake buat beli skincare SK II."
Sedetik berikutnya, keningku disentil. Tidak sakit, sih, tetapi ... INI KENAPA ANAK DAN MAMANYA HOBI SEKALI MENYAKITI MAKHLUK LEMAH SEPERTI DIRIKU?
"Awas kalau kamu bikin melarat tabungan anak saya! Saya ganti pake jualin organ tubuh kamu itu!" ancam Mama Lia.
"Ya ... kalau laku, Ma. Aku sendiri, hobi nonton sinetron di laptop non-stop sampai berjam-jam, sampe kayak mata udah sakit banget. Kemungkinan pembeli nggak suka mata yang bakalan rusak. Terus, aku suka minum Boba, tau sendiri, minuman manis-manis nggak bagus buat kesehatan dalam tubuh. Apalagi, katanya tepung kanji juga susah diproses di usus. Jadi ... beruntung banget kalau memang Mama bisa jual mahal badan aku."
Lagi, Mama Lia mengeluarkan desis kesal. E-he-he, ketemu lawan seimbang, 'kan, Mama mertua?
"Katanya kamu mau belajar masak? Sana, bantuin saya!"
"Ini juga bantuin, Ma," jawabku sembari memenuhi arah tunjuk Mama Lia untuk mengambil beberapa biji tomat untuk dibersihkan. "Aku bantu Mama menghilangkan kesepian. Itu udah berguna banget, loh."
"Berisik sekali kamu, Chia," balas Mama Lia. "Mana obrolannya seputar hal-hal yang nggak penting. Tiru Tiana, tuh! Kalau ngobrol, selalu hal yang berbobot."
"Bukannya bosanin, ya, Ma?" Aku balas ucapan Mama Lia. "Berisik-berisik gini, kalau aku nggak ngajak ngobrol Mama nantinya, Mama bisa kesepian, loh." Aku memotong-motong buah tomat seperti yang Mama Lia ajarkan biasanya. "Lagian, obrolan receh kayak tadi itu, bisa memperkuat hubungan, Ma. Daripada gosipin orang, pamer-pamerin sesuatu—yang Allah nggak suka, mending ngobrol hal remeh, yang bikin kedekatan terjalin, 'kan?"
Mama Lia melirik padaku, menampilkan ekspresi merendahkannya mulai luruh. Aku tersenyum pada Mama Lia, lalu mengedipkan sebelah tangan.
"Semprul!" balas Mama Lia, dan aku tertawa dalam diam.
***
Pulang hampir pukul delapan malam—aku tahu ini sangat terlambat dari yang seharusnya. Namun, aku bisa apa? Mama Lia sendiri kalau ajak aku bersilat lidah, seolah tidak ada hari esok. Kami terus mengobrol, sampai waktu isya datang. Karena kepepet waktu, akhirnya aku sholat bersama Mama Lia, sementara Papa Hikam ke masjid.
Ternyata ... belajar masak dari Mama Lia, sembari mengobrol non-stop, makan sampai perut penuh, dan mengendarai sepeda dengan ketakutan—cukup menguras tenaga. Aku sampai ngos-ngosan ketika memarkirkan sepeda di samping mobil Mas Faddyl di garasi.
Setibanya di rumah, aku tidak mendapati keberadaan Mas Faddyl. Bahkan dipanggil pun, ia tidak memberikan sahutan balasan. Aku sebagai sesama manusia, sontak langsung cemas. Segera mengecek kamar, dan pria ini ternyata masih sibuk dengan pekerjaan.
"Wa'alaikumussalam." Mas Faddyl baru menjawab salamku, bahkan tanpa mengalihkan pandangan dari layar monitor.
"Sorry, Mas. Aku telat pulangnya. Abisnya, Mama, sih ... nggak mau berhenti nasehatin aku."
"Iya."
Aku tidak tahu, dari nada bicaranya yang datar itu; Mas Faddyl marah atau sekadar tidak tertarik dengan penjelasanku. Namun, mengetahui bahwa ia tidak menunjukkan gelagat dingin berlebih, aku tidak mau peduli terlalu banyak mengenai dirinya. Mengambil sendok di dapur, aku meletakkan rantang di atas meja Mas Faddyl. Barulah, pria ini menoleh sedikit.
"Terima kasih," ucapnya dengan tanpa nada. Begitu tidak acuh, dan aku juga tidak mau ambil pusing.
Aku bersiap untuk tidur manja di kamarku-surgaku. Namun, kakiku malah tertahan ketika ujung mataku mendapati sebuah rak dekat pintu yang diisi oleh deretan buku-buku tebal. Bukan buku bersampul polos putih atau hitam yang menjadi objek pandanganku, tetapi lebih ke delapan novel yang didominasi oleh warna pastel di sana.
Aku mendekat untuk memastikan dan ... sial! Benar saja! Delapan novel ini adalah buku-buku Agrafa, dengan dua di antaranya adalah novel limited edition, sebab Agrafa malas mengurus penerbitan untuk dua buku ini.
Malas yang menguntungkan.
Karena dirinya, sekitar 130 eksemplar dari masing-masing buku, diincar oleh banyak orang. Mereka bahkan berani melelang hingga harga yang 5 kali lipat di atas harga asli, dan ... laku! Aku sendiri setelah mencari lama, tidak bisa menemukan dua buku ini. Fakta gilanya, bajakan dua buku ini saja tidak ada! Agrafa begitu tegas setiap pembajakan karyanya.
Pertanyaan utama di sini sekarang adalah ... kenapa pria dingin-anti roman picisan alay bin lebay ini malah mengoleksi buku Agrafa? Aku memicing sinis pada tengkuk Mas Faddyl, lalu mendekat.
"Mas?" panggilku, sembari duduk di tepian pembaringan Mas Faddyl. "Kok bisa, Mas punya novelnya Agrafa? Padahal, ini limited edition, loh. Dijual, bisa laku sampai sejutaan, tau!"
"Saya bisa menghasilkan tiga juta per hari, Chia."
Idih, sombongnya.
"Terserah. Kenapa Mas bisa punya? Kenapa aku nggak bisa nemu dua novel ini? Kenapa ... kenapa? Jelasin!"
"Memang kamu siapa sampai saya harus buang-buang waktu buat jelasin semuanya?"
Idih, idih. Lupa status?
Aku memukul pelan belakang kepala Mas Faddyl. Pelan, kok, hanya membuatnya maju sampai mendekati layar laptop. Pria ini segera menoleh kesal padaku.
"Sori, Mas. Aku kirain Mas amnesia."
"Orang amnesia, dipukul lagi, bisa makin amnesia, Chia!"
Ini obrolan, kenapa makin melebar?
"Bodo lah!" balasku sengit. "Mas jawab dulu pertanyaan aku."
"Saya pemilik saham kedua di penerbitan tempat penulis-siapa-itu menerbitkan buku." Mas Faddyl mulai menjelaskan, sembari fokus pada layar laptop, begitu khusyuk. "Makanya, saya dikasih buku-bukunya—yang katanya top best seller—itu. Huh, saya bahkan nggak minat baca, Chia. Ambil, atau jual kalau kamu mau."
"Nggak!" Giliranku menolak. "Aku ambil bukunya, ya? Aku nggak bakalan jual. Sesayang itu sama karyanya Agrafa."
"Sayang?" Mas Faddyl memicingkan mata, meremehkan.
"Mas nggak bakalan ngerti!" ucapku tidak acuh, kemudian merebahkan tubuh di atas kasur empuk. Malas keluar kamar, apalagi tadi aku sudah mengunci pintu utama. Niatnya, malam ini aku akan menghabiskan dua novel yang masing-masing berisi 328 dan 412 halaman ini.
Namun, keinginan hanya sekadar keinginan. Aku tidak tahu kapan pandanganku menggelap, dan malah menemukan hal yang mengerikan!
Mas Faddyl di atasku, mengungkung dengan kedua tangannya berada di samping kepalaku. Pria mesum ini mendekatkan wajahnya—sesuatu yang amat mengerikan, karena ia menampilkan senyum aneh. Aku bersiap menampar pria ini, jika seandainya mataku terlambat terbuka.
Bahkan, deru napasku berubah cepat hanya karena bayangan tadi, yang kuketahui adalah mimpi. Sekarang, kelegaan menguasaiku. Sehingga aku berniat tidur lagi. Ini pasti ... pasti lupa baca doa sampai Mas Faddyl menghantui hingga alam bawah sadar.
Seharusnya, aku kembali terlelap. Seharusnya. Namun, ketika aku mencari posisi nyaman, tidak sadar mengetahui ada dua hal aneh di sini.
Pertama, pergerakanku terbatas akibat ... sesuatu penghalang di belakang punggungku. Kedua ... ada tangan kekar yang melingkar di perutku, memeluk posesif dan nyaris tidak memberikan celah untukku bergerak.
Demi apa pun ... APAAN INI?
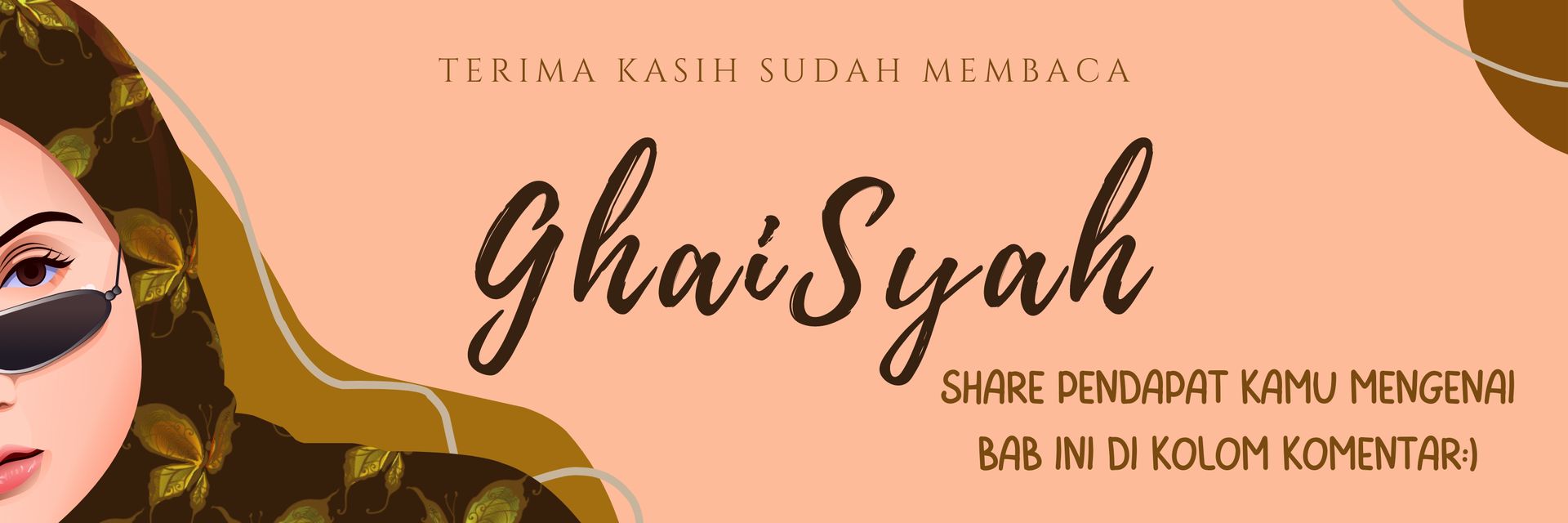
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro