33. Ilyas dan Cal
|| 33: Ilyas's pov | 5058 words ||

Gedung itu adalah tempat pertama kali Bu Miriam melihatku.
Salah satu universitas di Batavia mengadakan pameran kesenian dan acara melukis bersama dengan anak-anak panti asuhan di sana. Rumah Kasih yang diurus Bu Raiva menjadi salah satu panti asuhan yang diundang untuk berpartisipasi. Bu Miriam datang sebagai pengunjung bersama salah satu rekannya yang seorang dosen.
Tidak banyak yang kulakukan saat pameran. Aku hanya ikut melukis satu kali dan badanku langsung tidak enak. Aku hampir mewarnai kanvasku dengan muntahan, jadi Bu Raiva buru-buru mendudukkanku ke pojok bersama para panitia. Dia menjejalkan rubik yang dibawanya dari panti ke tanganku agar aku tidak rewel.
Para panitia itu masih muda—barangkali mereka mahasiswa yang mengadakan acara tersebut. Jadi, mereka mengajakku bicara sesekali. Mereka menanyakan nama, umur, rubik di tanganku, atau kegiatan lain yang kusukai. Sebuah usaha untuk membuatku tidak merasa terkucilkan di antara orang-orang yang umurnya terpaut terlalu jauh dariku, tetapi itu membuatku tambah ingin muntah.
Salah satu mahasiswa itu meminjam rubik di tanganku dan berusaha menyelesaikannya. Dia bilang, dia punya pengalaman memecahkan rubik kubus 5x5, tetapi belum pernah mencoba rubik ghost.
Sepuluh menit kemudian, teman-temannya mulai bosan dan mengerjakan hal lain.
"Benda ini mustahil," tukas si mahasiswa seraya meletakkan rubik itu ke meja.
Sementara mereka teralih dengan tugas-tugas panitia, aku meraih kembali rubik itu. Butuh hampir setengah hari buatku, tetapi akhirnya aku menyelesaikannya.
Saat si mahasiswa kembali lagi untuk memberiku camilan, matanya membelalak melihat rubik ghost yang sudah selesai.
"Boleh kupinjam lagi?" tanyanya dengan bersemangat.
Begitu aku mengangguk, pemuda itu langsung pergi ke teman-temannya, yang sedang duduk dengan para dosen dan pengunjung lain—ada Bu Miriam di sana.
Si mahasiswa memamerkan rubik itu seolah dia yang telah menyelesaikannya. Lima menit kemudian dia langsung mengaku sambil terbahak bahwa akulah yang memecahkan rubik itu, tetapi teman-temannya tidak ada yang percaya.
Sebulan kemudian, Pak Gun datang ke panti asuhan untuk mengadopsiku.
Untunglah saat itu aku merasa sakit hingga Bu Raiva membiarkanku duduk di sana dan Bu Miriam bisa melihatku.
Syukurlah aku menyelesaikan rubik tersebut tepat tengah hari sebelum Bu Miriam pulang.
Aku tidak menyesal membiarkan mahasiswa itu memamerkan rubik yang kuselesaikan meski biasanya aku tidak menyukai orang lain menyentuh apa pun yang harusnya kepunyaanku.
Aku bersyukur mengikuti Pak Gun hari itu.
Aku beruntung bisa ikut pulang ke rumahnya dan Bu Miriam.
Jika tidak, aku pasti masih di sana—di dalam panti asuhan itu, terjebak dengan Bu Raiva dan anak-anak tanpa orang tua lainnya yang akan terus berdatangan.
Selama ini aku memikirkan terlalu banyak hal, sebagian besarnya selalu buruk, hingga aku luput menyukuri hal-hal kecil seperti itu.
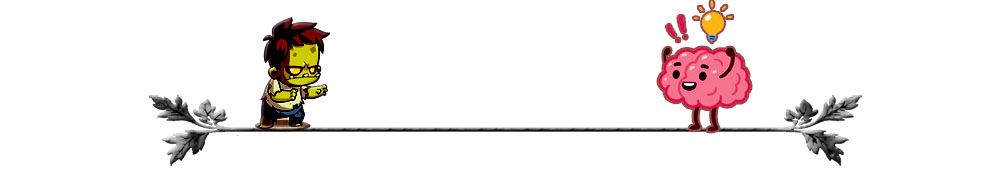
Mulanya, aku tidak bisa memproses apa yang terjadi sekeluarnya kami dari gedung tersebut. Aku hanya mengikuti Cal dan membiarkannya memegangiku. Kupeluk jaket kurirnya erat-erat meski bersimbah darah. Kupercayai dia sepenuhnya membawa Emma.
Dulu, aku mustahil membiarkannya sedekatnya ini. Jaket ini mungkin akan membuatku kejang. Pemikiran bahwa ada orang lain yang membawa adikku tanpa kuawasi bakal membuatku gila.
Aku mengerjap dan mendapati kami sudah duduk di dalam mobil MPV, dengan Joo dan Emma di belakang bersama semua barang-barang kami.
"Kau boleh tidur lagi, Ilyas."
Kurasakan tangan Cal di keningku. Barulah aku menyadari sekujur badanku basah oleh keringat dingin. Mataku panas.
Jaket kurirnya melorot dan untuk pertama kalinya aku melihat bekas luka gigitan itu.
Aku sudah merasakannya sejak awal, tetapi aku tidak berani melihat.
Aku merasakannya saat Khandra menggigitku. Kepanikan dan rasa takut justru membuatku mendorong wajahnya, memperdalam giginya di sana—di telapak tangan bagian jempol
Luka itu bahkan lebih dalam daripada luka gigitan di tangan Nenek Aya.
Tubuhku gemetaran tanpa bisa kukendalikan. Pandanganku mengabur. Bekas luka itu berdenyut hebat. Suara celotehan Emma di jok belakang berubah menjadi denging di telingaku.
Bagaimana ini?
Bagaimana dengan Emma?
Aku akan jadi apa?
Kenapa aku melakukannya?
Kenapa aku menolong Cal?
Apa untungnya aku melakukan ini semua?
Apa yang kupikirkan—melompat menyelamatkannya di saat risikonya sudah pasti?
Seharusnya tidak begini. Seharusnya aku diam saja. Seharusnya aku tetap bersama Emma. Seharusnya kami tidak ke sana. Seharusnya—
Lalu, Cal menaikkan kembali jaket kurirnya menutupi tanganku. Satu tangannya yang tidak memegangi roda setir terus menggenggam tanganku sampai gemetaranku berhenti.
Aku mengangkat wajah dan bersitatap dengan Joo lewat kaca spion tengah. Matanya yang pucat dan kosong tidak menampakkan tanda-tanda manusia hidup—hanya sesosok jasad yang kebetulan bergerak.
Kupejamkan mataku karena tidak sanggup melihatnya—bahwa beberapa jam lagi, aku akan menjadi seperti dirinya.
Kusandarkan kepalaku ke belakang dan seketika terpikir olehku ....
Barangkali ini akibat dari kebohonganku pada Cal.
Sudah berapa kali aku berdusta padanya? Berapa kali aku berusaha pergi meninggalkannya? Berapa kali aku menyusun rencana untuk memisahkan diri darinya? Berapa kali aku mengira diriku bisa bertahan sendirian tanpanya? Pada satu titik ... kurasa aku bahkan telah membuat rencana untuk berpura-pura kena infeksi zombie agar dia meninggalkanku.
Sekarang aku sungguhan terinfeksi, dan yang dilakukannya malah menggenggam tanganku makin erat.
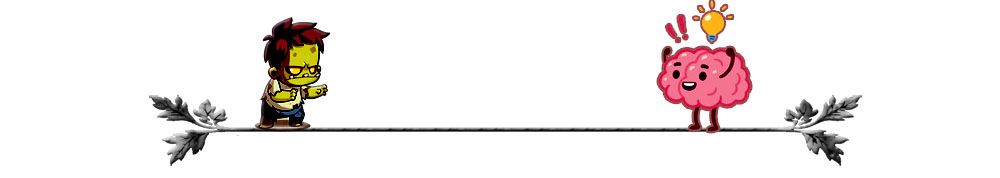
Pukul 3 sore. Sudah satu jam sejak aku tergigit. Kututupi tangan kiriku, terutama di area ibu jari, menggunakan perban dari kotak P3K pemberian Kamelia. Darahnya sudah berhenti keluar, tetapi nyerinya luar biasa.
"Kita makan dulu, yuk." Cal berbelok keluar jalur dan menerobos bentangan rumput, terus mengegas mobil menaiki tanah berbukit di sisi kanan jalan tol. Benar-benar tidak ada zombie di sisi ini karena hampir tidak ada bangunan sepanjang jalan. "Cuma Emma yang sempat makan sebelum kita pergi. Protein bar punya para polisi tadi juga rasanya aneh. Kita belum makan dengan benar dari pagi."
Dia membongkar bawaan kami dan mengeluarkan bekal yang dikemas Bu Raiva. Satu stoples penuh sayuran dan semur daging, dua stoples nasi, satu termos bubur ayam yang sudah dingin, dan satu wadah penuh sambal goreng kentang.
"Joo, kau bisa makan ini, tidak?" Cal memberikan seiris kentang ke telapak tangan si zombie.
Alih-alih memakannya, Joo malah menggenggam kentang itu di kedua tangannya seolah sedang menjaga permata.
"Kau boleh makan duluan, Ilyas." Cal meletakan jatah nasi dan laukku di pangkuanku, lalu membuka termos bubur.
Sesuai dugaanku, Emma mengeluarkan kembali bubur yang disuapnya karena sudah dingin dan keras. Di sendokan keempat, Emma memberontak dan memukul tangan Cal yang berusaha menyuapinya.
"Kau saja yang makan duluan, Cal."
Kusodorkan semua jatahku ke atas dasbor di depan gadis itu. Kuraih Emma dari jok belakang dan mendudukkannya di pangkuanku, lalu menyuapinya sesendok demi sesendok bubur yang kucampur dengan kuah semur dan sedikit daging atau sayur.
"Bagaimana kau tahu dia tidak akan memuntahkan itu?" tanya Cal seraya berpangku dagu.
"Kau harus memberi variasi rasa di setiap sendok dan sesuatu yang bertekstur untuk digigit. Asalkan tidak pedas dan tidak terlalu besar agar tidak tersangkut di tenggorokannya," kataku sambil sesekali menyeka bubur yang meleleh ke dagu Emma. Kulirik sendok di tangan Cal. "Kau tidak bisa menyuapinya dengan porsi suapanmu."
"Oke." Cal menyendoki nasi dan semurnya. Namun, alih-alih memakannya, dia justru mendorongnya ke arah mulutku. "Ayo, aa!"
Kurasakan wajahku memanas. Melihat ekspresi santai di mukanya membuatku tambah jengkel karena sepertinya cuma aku sendiri yang grogi menghadapinya. Aku berjengit menghindari sendoknya. "Tidak mau—"
"Eits! Pesawatnya masuk!" Dia mendorongnya langsung ke dalam mulutku. Sendoknya sampai membentur gigiku.
Aku tertunduk dengan mulut menempel ke bahuku sendiri agar makanannya tidak menyembur keluar. Rugi aku merasa canggung. Bagi Cal, mungkin ini tidak ada bedanya dengan menyuapi Emma atau menyodorkan kentang ke Joo.
Aku bahkan belum benar-benar menelannya saat Cal menyendok lagi. "Selanjutnya yang akan masuk: jet tempur."
"Kau mau membunuhku, ya?"
"Ya, sudah. Nih." Dia mengurangi nasi dan sayur di sendoknya. "Kapal jukung."
Cal menirukan suara mesin kapal dan menggerakkan sendok dengan lambat. Malah, dia sepertinya sengaja membelok-belokkan sendok itu ketika melihat Emma tertawa bersemangat dengan jari tangan meraih-raih ke atas.
"Apa? Emma, kau mau yang ini? Kalau begitu kapalnya untuk Emma dulu—"
Aku telanjur memajukan badan dan menyambar sendok itu dengan mulutku.
Cal terdiam cukup lama mengamatiku sambil menyunggingkan senyum geli sementara Emma merengek marah karena aku menelan kapal jukungnya.
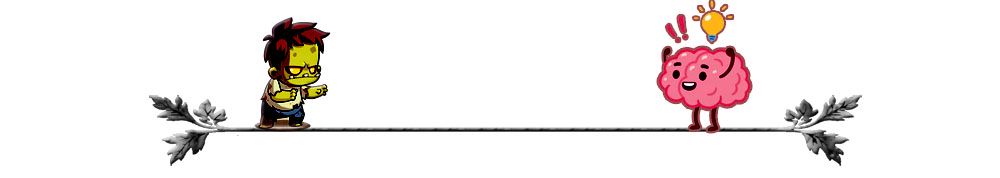
Pukul 4 sore. Dua jam sejak aku tergigit. Kurasa kami takkan sempat mencapai Kotatua sebelum hari gelap.
Cal sempat berbelok dan henda berhenti di sebuah rest area untuk mencari toilet, tetapi jalan lagi saat melihat beberapa zombie tipe 2 menghampiri mobil.
Di pemberhentian berikutnya, kami menemukan rest area yang lebih kecil. Hanya ada satu zombie di sana, tersangkut kabel listrik dari tiang yang rubuh menimpa pagar. Dari gerakannya yang menggeliat pelan, sepertinya ia masih tipe 1.
Cal memarkir mobilnya di samping toilet, lalu turun lebih dulu untuk mengecek keadaan. Dia kembali dan berkata tempat itu aman. Tidak ada zombie, hanya dua mayat yang tempurung kepalanya terbuka dan sudah kosong di dekat pom bensin.
Aku masuk ke toilet belakangan setelah Cal selesai dan memastikan Emma juga bersih. Aku mandi sekalian, mengguyur kepala sampai ujung kaki. Di balik pintu, Cal terus mengajakku bicara.
Kubungkus semua baju yang kupakai seharian ini dalam kantung plastik bersama perban yang kotor, lalu meninggalkannya begitu saja di bawah wastafel.
Aku baru selesai membalut tanganku dengan perban baru dan hendak memakai mantelku yang lain ketika Cal mendadak mendobrak pintu kamar mandiku. Kami sama-sama membeku dan membelalak menatap satu sama lain. Napasnya memburu dan suaranya bergetar ketika berkata, "S-sori. Habisnya kau tidak menjawab lagi saat kuajak bicara—"
"Cal," sengalku, "kau sadar, 'kan, aku bisa saja belum pakai apa-apa saat kau membuka pintunya?"
"Ehehe." Dia buru-buru menutup kembali pintunya, yang mana sia-sia karena kenop dan kuncinya sudah pretel. "Maaf, Ilyas!"
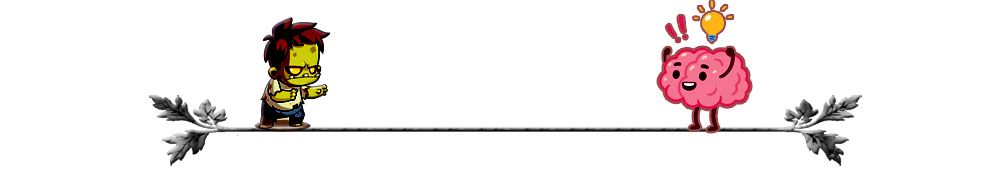
Pukul 5. Tiga jam setelah aku tergigit.
Ada toko camilan di samping pom bensin. Tidak ada penjaganya dan listriknya padam. Semua minuman dalam kulkas terasa hangat karena pintu kacanya menghadap keluar dan diterpa matahari sore. Cal memborong tiap camilan yang bisa dilihatnya, aku mengambilkan aksesoris-aksesoris yang ditunjuk oleh Emma pada rak pajangan di belakang meja kasir, sedangkan Joo bengong melihat etalase berisi roti jamuran.
Mataku kemudian menyapu rak berisi handuk-handuk dalam kotak. Aku mengambil tiga kotak.
"Ingat, tidak?" ujar Cal mendadak, membuatku terperanjat. Dia entah sejak kapan sudah berdiri di sebelahku sambil menenteng dua keranjang penuh camilan. "Dulu aku memakai handuk kesayanganmu buat mengelap darah dari pentunganku. Kau marah sekali dan kelihatannya hendak menendangku keluar."
Kupandangi kotak handuk di tanganku. "Benar juga."
Cal mengernyit. "Kukira, kau ingat, makanya kau mengambil handuk-handuk ini."
"Tidak, aku sudah lupa kejadian itu." Kukeluarkan salah satu handuk dari kotak, menggulungnya, dan memastikan tidak terlalu tebal. "Sepertinya ini pas di mulut."
"Hah?"
Aku menatapnya datar. "Kau tidak mungkin tidak memikirkannya, Cal. Cepat atau lambat, kau harus mengikat dan mengurungku di suatu tempat. Handuk-handuk ini bisa kugigit dan dililit kuat ke sekeliling kepalaku sebelum aku berubah agar aku tidak menggigit siapa-siapa."
Wajahnya berubah masam. Rahangnya mengencang dan mulutnya terkatup rapat. Cal langsung berbalik membawa semua keranjangnya dan masuk duluan ke mobil, lalu berdiam di sana sampai kami menyusulnya.
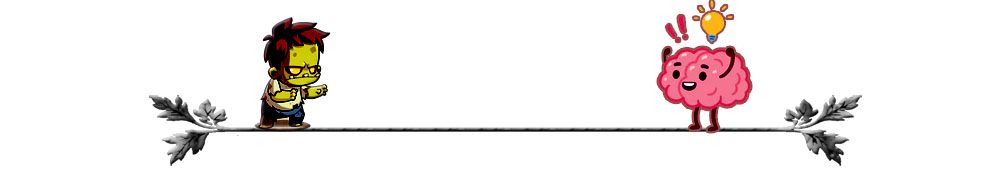
Pukul 6.30. Matahari sudah tidak terlihat dan cahaya samar-samarnya membuat langit tampak ungu kelam. Kira-kira 4 jam 30 menit berlalu sejak aku tergigit. Waktuku tinggal satu jam setengah.
"Cal," kataku sembari mengamati beberapa bangunan tua yang kami lewati dan zombie-zombie yang berlalu di bahu jalan. Cal begitu ngebutnya sampai-sampai Kotatua sudah di depan mata. "Kita harus berhenti sekarang. Kau bisa tinggalkan aku di salah satu bangunan itu."
Dia tidak menjawab.
"Akan ada petugas patroli di sekitar pagar dan blokade yang mereka pasang, Cal. Kau pasti juga tahu penjagaan di Kotatua salah satu yang paling ketat. Malah, mereka pasti lebih ketat daripada Batavia karena mereka memiliki tingkat infeksi yang tinggi dan masih bertahan—mereka hidup berdampingan dengan zombie, hampir seperti di Renjani. Mereka akan memeriksa kita dan menangkapku."
"Joo, kau harus pakai seragam kurirku lagi," ujar Cal seraya melihat spion tengah. "Rapikan maskermu dan jangan menatap siapa-siapa supaya tidak ada yang sadar kau zombie."
Dia pura-pura tidak mendengarku.
Kupejamkan mataku dan memikirkan bujukan macam apa lagi yang bisa meyakinkannya.
"Cal, apa kau tahu?" Aku memulai. "Zombie tidak bisa mengendalikan sebagian besar anggota tubuhnya. Saat aku berusaha menggigit seseorang dan orang itu menghindar, aku akan menggigit udara kosong ... atau lidahku sendiri. Aku akan merusak bagian dalam mulutku. Aku akan membenturkan wajahku ke mana-mana. Aku akan berjalan ke bawah gilasan mobil, atau baling-baling saluran udara yang menyala, atau jebakan zombie penuh duri yang terpasang di halaman rumah orang-orang. Aku tidak akan merasa sakit atau peduli pada apa yang terjadi ke tubuhku."
Gadis itu akhirnya menginjak rem.
Di depan kami, ada beberapa bangkai mobil yang dari kaca-kaca jendelanya bermunculan tubuh-tubuh mayat hidup, berusaha merangkak keluar, tetapi tersangkut sabuk pengaman. Dari kaca belakang mobil-mobil itu, aku bisa melihat beberapa zombie anak-anak.
"Kau harus mengikat tanganku ke depan." Aku memberi tahu Cal. "Karena ada kemungkinan aku mematahkan tanganku sendiri jika kau mengikatnya di belakang punggungku. Aku juga harus diikat dalam keadaan berdiri atau duduk. Jika aku berubah dalam keadaan berbaring, aku mungkin akan mencederai tulang belakangku saat berusaha bangun dengan paksa. Tinggalkan aku di ruangan yang kosong, terisolasi, jauh dari hal-hal yang membuat suara. Tutup mataku rapat-rapat. Tanpa distraksi suara dan penglihatan, aku mungkin akan bertahan dalam keadaan diam tanpa pergerakan sedikit pun."
Cal menarik napas dan akhirnya menjawab, "Oke."
Dia berbelok keluar dari jalur dan memotong jalan menuju sebuah bangunan tiga lantai yang berdiri tak jauh dari gerbang tol. Bangunan itu masih terletak di dalam area tol meski bagian depannya menghadap ke dalam kota. Pagar seng berpuncak kawat berduri dipasang di sekitarnya dengan garis polisi.
"Ini dulunya restoran bintang lima." Cal memberi tahu. "Sampai ada salah satu kokinya yang terinfeksi. Orang-orang yang panik membuat laporan dengan agak berlebihan meski si koki sudah dikarantina. Dan karena ini tempat makan, PN langsung mengasumsikan yang terburuk. Meski hanya ada satu korban infeksi, mereka memperlakukan seisi bangunan sebagai zona merah—seolah-olah seluruh orang yang ada di dalamnya sudah terinfeksi. Semua orang yang ada di dalamnya terjebak selama lebih dari 12 jam dan entah untuk alasan apa PN tidak bisa berkomunikasi dengan siapa pun yang ada di dalam. Begitu isolasi dibuka, mereka menemukan hanya ada dua korban selamat: seorang pria usia akhir 30-an dan si zombie koki yang masih terkurung dalam lemari pendingin."
"Orang-orang di dalamnya saling bantai karena mencurigai satu sama lain terinfeksi?" terkaku.
"Benar." Cal menerobos garis polisi dan menyetop mobilnya tepat di sisi pagar seng. "Anak-anak, kakek-nenek, remaja, orang tua, pegawai kantoran, kurir—semua yang tadinya datang untuk bersantai dan memesan makan saling bunuh. Begitu pula para pekerja restonya. Pemilik resto ini berusaha meneruskan usahanya setelah bangunan dibersihkan, tapi tidak ada yang mau datang ke tempat macam itu, 'kan? Akhirnya, resto ini gulung tikar. Bangunannya terbengkalai. Teman-teman kurirku biasanya memakai tempat ini buat persinggahan. Soalnya bangunan ini berdiri di tempat yang terpencil dari manusia, jadi para zombie sekali pun menjauhi lokasi ini dan lebih memilih berjalan ke sisi satunya yang lebih dekat dengan kota, di mana para manusia lalu lalang di balik pagar blokade."
Kami semua turun dari mobil. Cal menunjukkan jalan masuknya, di mana kami mesti merangkak melewati lubang di bagian bawah pagar seng. Joo tidak bisa melakukan itu. Lubang itu juga terlalu berbahaya buat dilalui Emma karena tepian sengnya yang tidak rata menghujam tajam.
Aku memeluk Emma untuk terakhir kali. Kudongakkan kepalaku, tidak membiarkan setetes air mata pun jatuh. Aku tidak mau dia menyadari kesedihanku.
Namun, Emma seolah memahaminya. Dia mendadak mencengkram bahu mantelku dan menolak lepas dari gendonganku.
"Emma ...." Suaraku bergetar saat aku berusaha mengangkat kepalanya dari bahuku. "Emma, tidak apa-apa. Kau akan aman dengan Joo dan Cal."
"Iya, ini cuma sementara, Emma." Cal berusaha menarik anak itu dariku. "Sebentar saja. Nanti kau akan ketemu Ilyas lagi setelah kakakmu membaik."
Emma bergelung makin rapat. Wajahnya tenggelam di lekuk leherku dan jari-jari tangannya menolak melepaskanku.
"Joo," kata Cal, "masuk mobil."
Si zombie duduk kembali di jok belakang, tetapi Cal membiarkan pintunya tetap terbuka lebar. Dia juga membiarkan mesin mobilnya tetap menyala beserta pendingin udaranya.
Gadis itu mendadak merenggut paksa Emma dari tanganku, sampai-sampai aku sendiri hampir mengulurkan tangan untuk merebutnya kembali. Tangisan Emma pecah, sedemikian nyaringnya, hingga kupikir aku akan mencekik Cal karena sudah melakukan ini. Aku sadar benar Cal melakukannya karena harus, tetapi kudapati diriku hampir menerjangnya untuk menggendong adikku lagi.
Cal dengan cepat mendudukkan adikku ke pangkuan Joo dan menutup pintu mobil, lalu menguncinya. Dia menarikku ke arah pagar seng, memaksaku bergerak. Aku mengikutinya dengan hati hancur dan air mata berlinangan.
Aku masih bisa mendengar Emma menangis menjerit-jeritkan namaku dari dalam mobil.

Cal menemaniku duduk di sana, di tengah-tengah ruang penyimpanan alat makan yang sudah dikosongkan. Dia menunggu sampai aku lebih tenang dan berhenti mengelu-elukan adikku. Kurasa, aku sudah membuang-buang 30 menit. Kurasa, hanya tersisa satu jam bagiku untuk berubah.
Dia mengambilkan sebuah matras simpanan milik teman-teman kurirnya untuk kududuki. Ada sebuah rak yang dibaut ke dinding di belakangku—tali yang mengikatku akan dihubungkan ke sana agar aku tidak berjalan keluar ruangan.
"Aku akan hubungi teman-temanku di Radenal dan mereka akan bergantian menjagamu di sini," ujarnya.
"Cal, itu tidak perlu—"
"Aku juga butuh bantuan mereka untuk masuk ke bank otak, tahu?" Cal berkacak pinggang menatapku. "Tenang saja. Mereka orang-orang baik. Nah, sebelum itu ...."
Tanganku sudah terikat ke depan dan tiba-tiba tangannya menyusup ke dalam saku mantelku. Aku terkesiap. Kurapatkan sebelah lenganku dan mengepit tangannya, berusaha menghentikannya, tetapi Cal keburu menarik keluar gunting kecil yang kusembunyikan di sana.
"Kau kira aku tidak menyadarinya saat kau mengambilkan mainan-mainan kecil itu untuk Emma di toko rest area tadi? Aku lihat kau mengambil ini diam-diam meski Emma tidak menginginkannya." Dia memutar-mutar gunting tersebut di jarinya. "Kau pikir aku bodoh sekali, ya, sampai tak tahu kalau tangan diikat ke depan atau belakang itu tidak akan ada bedanya untuk zombie tipe 1? Aku berhadapan dengan zombie lebih sering darimu, Ilyas. Aku menyaksikan orang-orang berubah dengan mata kepalaku sendiri. Aku tahu apa rencanamu. Memang benar, tangan diikat ke belakang punya risiko mematahkan lenganmu kalau kau mencoba menggerakkannya ke depan, tapi itu saat kau sudah berubah jadi tipe 2. Tipe 1 terlalu lemah dan mereka beruntung kalau bisa mengangkat tangannya sama sekali. Padahal ada cara yang lebih baik lagi: aku bisa mengikat rapat kedua tanganmu tetap di sisi tubuh, melilit badanmu sekalian. Aku bisa menggulungmu dalam matras atau selimut tebal dan kulakban. Pasti jauh lebih aman dan kau juga tahu itu. Tapi kau tidak mengatakannya karena kau tidak mau kuikat begitu. Kau butuh memakai tanganmu supaya kau bisa ... agar—setelah aku pergi, k-kau bisa ...."
Matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Dia menelan ludah berusaha bicara lagi, tetapi kemudian merapatkan mulutnya kembali.
"Argh!" Cal melemparkan gunting itu keluar sampai hilang di lorong gelap. Tangannya mengepal dan terangkat—sepertinya dia ingin menonjokku. Namun, Cal hanya menarik kerah mantelku dan mengguncang-guncangkan badanku. Dia menjerit di depan mukaku, "Kenapa, sih, orang-orang sepertimu mudah sekali berpikir buat mati?!"
Air matanya berjatuhan sampai dagu. Buru-buru kupalingkan wajahku karena, rasanya, aku takkan pernah terbiasa melihatnya menangis.
"Lihat aku, Ilyas gemblung!" Dia mengguncangku lagi dan kali ini mencengkram rahangku sampai menatapnya. "Lihat aku dan katakan—apa rasanya saat kau membayangkan dirimu mati? Lega? Masalahmu selesai? Masalahmu sebesar apa sampai-sampai kematian bisa jadi jalan keluar?! Apa yang kau pikirkan sepanjang jalan kita ke Batavia? Kau menertawakanku selama ini karena kau kira aku tidak sadar, 'kan? Kau sudah berencana pulang ke Renjani sejak awal, 'kan?! Kau mau mati di sana, 'kan? Kau ikut aku supaya Emma aman! Kau tidak peduli padanya kalau kakaknya hilang! Kau tidak peduli padaku kalau ... kalau—"
Cal melonggarkan cengkramannya dan langsung merosot, jatuh berlutut di depanku. Aku ikut terduduk karena tertarik oleh cengkramannya.
"Bukan ini yang mau kukatakan," isaknya dengan suara lemah. Kepalanya menggeleng-geleng. "Aku tidak bermaksud ... b-bukan ini yang harusnya kukatakan. Yang ingin kukatakan, Ilyas, adalah ... aku—minta—maaf."
Aku berdengap. Dengan tangan terikat, aku berusaha memegangi bahunya dan mengangkat wajahnya. "Cal, ini bukan salahmu—"
"Ini salahku!" jeritnya. "Semuanya salahku! Lubang di Tembok W, infeksi zombie yang menyebar ke dalam Nusa, tipe 4 datang ke rumahmu, jatuhnya kota Renjani—semuanya salahku! Seperti yang Ginna bilang, aku anak bawa sial! Kita juga hampir mati diserang preman-preman bayaran di distrik itu karena aku tidak mengikuti rencanamu! Segalanya selalu berjalan baik saat aku menuruti rencanamu—tapi aku selalu mengacau! Kau tergigit juga karena aku lengah—kau seharusnya tidak perlu menyelamatkanku! Kau masih punya Emma, kau juga mampu menangani Joo—berbeda denganku! Jika aku mati di sini, tidak akan ada yang menangisiku! Tidak ada yang tersisa untuk meratapi kepergianku! Seharusnya aku yang di sini, bukan kau! Seharusnya ...."
"Cal—"
"Aku menyesal karena dulu merundungmu ..." isaknya lagi. Tangannya mencengkram mantelku kian erat sampai buku-buku jarinya memutih. "Aku bahkan tidak pernah minta maaf sungguh-sungguh untuk itu. Saat kita bertemu lagi di rumahmu, kau sudah mengonfrontasiku, tapi aku menyepelekannya. Kupikir, aku hanya perlu menebusnya dengan mengeluarkanmu dari rumah itu dan melindungi kalian. Tapi itu bukan permintaan maaf yang layak karena aku melakukan itu hanya untuk mengangkat beban hatiku sendiri—agar aku terbebas dari rasa penyesalan tanpa memikirkan perasaanmu sedikit pun. Aku baru menyadarinya saat melihat bekas luka di badanmu, dan melihat panti asuhan itu ... aku benar-benar marah dan benci saat mendengar apa yang telah ibu asuhmu itu lakukan. Aku melihat teman-teman satu pantimu itu dan langsung merasa muak—mereka bahkan tidak menunjukkan penyesalan apa pun padamu. Aku ingin menghajar mereka semua, tapi kemudian aku sadar ... aku juga sama seperti mereka."
Aku tidak bisa berkata-kata dan hanya terduduk di sana mendengarkannya mengisak. Aku seharusnya mengatakan sesuatu, tetapi kerongkonganku tersumbat saat mendengarnya menangis sampai seperti itu.
"Kumohon, hiduplah." Cal melingkarkan lengannya di sekeliling leherku. Pelukan itu amat singkat sampai-sampai, saat dia melepaskanku, aku berharap dia bertahan sedikit lebih lama.
Cal menarik diri dan menyeka ingus yang meleleh ke atas bibirnya. Dia langsung berusaha mengeringkan air matanya dan menghindari tatapan mataku.
"Bertahanlah, Ilyas. Jangan mati. Jangan tinggalkan aku. Jika kau tidak mau melakukannya untukku atau dirimu sendiri, lakukan untuk Emma. Lakukan untuk mendiang Pak Gun dan Bu Miriam. Mereka meninggalkan Emma padamu. Jangan tinggalkan dia. Aku bersumpah akan menjaganya ... tapi aku tidak bisa melakukan ini sendiri tanpamu."
Cal mengencangkan ikatanku tanpa bersuara lagi. Dia menyumpalkan lilitan handuk ke mulutku dan mengeratkannya ke sekeliling kepalaku.
Terakhir, dia menutup mataku dengan kain tebal dan menahannya menggunakan perban.
"Bertahanlah, Ilyas." Kudengar suara Cal untuk terakhir kali. "Akan kupastikan kau bisa bersama adikmu lagi."
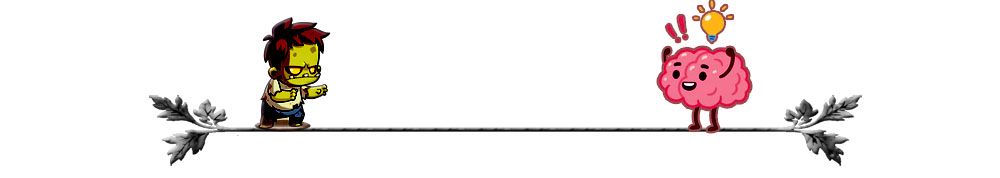
Aku tidak tahu sudah berapa lama aku terikat. Kurasa, aku sempat ketiduran selama beberapa saat, lalu terbangun lagi karena merasa tidak nyaman.
Ucapan Cal terngiang-ngiang dalam kepalaku. Rasanya aku masih bisa mendengarnya menangis. Ulu hatiku seperti dicengkram tangan tak kasat mata tiap kali teringat semua kata-katanya. Rasa sakitnya bertambah saat aku sadar bahwa aku seharusnya mengatakan sesuatu, tetapi tidak kulakukan.
Seharusnya aku mengatakannya—dia masih anak-anak saat menemukan lubang itu. Perbatasan tidak seharusnya dijadikan pemukiman. Pemerintah Nusa yang bodoh. Apa yang mereka harapkan saat warga—sebagian besar manula dan anak-anak—dibiarkan tinggal terlalu dekat dengan tembok?
Bahkan jikalau bukan Cal, akan ada anak-anak atau manula pikun lain yang melakukannya. Siapa pun bisa berada di posisi Cal saat itu.
Seharusnya aku mengatakannya—bukan hanya dia yang merundungku sejak kami kecil. Aku juga sama. Aku sering berbohong padanya. Aku sering memandangnya sebelah mata dan kadang terang-terangan mengejeknya untuk hal-hal yang sama sekali bukan kesalahannya—bahwa dia buta huruf, tinggal di perbatasan, dan tidak memahami materi-materi sepele yang diajarkan Bu Miriam.
Aku pernah menjebaknya saat kami main petak umpet. Kuarahkan dia sampai mencariku keluar rumah dan berkeliling kompleks sampai senja. Renjani bukan kota kecil. Seorang anak bisa hilang dengan mudah dan tak pulang lagi. Cal hanya beruntung dia tidak tersesat saat itu dan ditemukan orang-orang baik yang mengarahkannya kembali ke rumah Bu Miriam. Aku bisa saja membuat wajahnya berakhir dalam poster anak hilang.
Seberapa sering aku membentaknya? Seberapa banyak kata-kata menyakitkan yang kulempar ke wajahnya? Sudah tak terhitung hari-hari di mana aku melampiaskan rasa frustrasi dan depresiku sendiri padanya, menjadikannya seperti bak sampah untuk membuang perasaan-perasaan tidak enak yang menggunung di benakku. Bahkan setelah dia berhenti merundungku secara fisik, aku tidak pernah berhenti menyakitinya. Setelah semua yang dia lakukan untukku dan Emma ....
Sudahkah aku meminta maaf padanya untuk semua itu?
Cal juga menilai dirinya terlalu rendah, dan aku menyesal tidak mengatakan apa-apa untuk menentangnya.
Dia menyelamatkanku dan Emma dari zombie berkali-kali. Dia menyeretku keluar dari rumah—hal yang seharusnya kulakukan dengan kakiku sendiri sejak dulu. Dia menjaga kami. Dia mengemudi sepanjang waktu. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi adikku saat preman-preman bayaran itu berusaha membawanya. Dia tidak pernah meninggalkan kami, sejahat apa pun perlakuanku padanya.
Malah, andai Cal tidak secara impulsif menyelamatkan Rani dan Bahaduri—dua anak yang bergelantungan di langkan kamar apartemen, bersembunyi dari ibu zombie mereka ... andai dia tidak melakukan itu, kami takkan menemukan cara untuk melewati blokade.
Berkat dia juga aku akhirnya melengkapi informasi mengenai para zombie dan lubang di tembok.
Andai tidak ada Cal saat Joo pertama muncul ... Joo pasti sudah membawa Emma ke suatu tempat, dan tak ada yang bisa kulakukan.
Cal tahu apa yang terjadi pada Bu Miriam dan bagaimana Aryan membunuh ibu angkatku. Namun, Cal tidak pernah mengungkitnya. Seharusnya aku sadar, penyesalanku lantaran keluar dari kamar dan membuat Bu Miriam terbunuh, pasti sama parahnya seperti penyesalannya yang memperlebar lubang di tembok itu. Malah, beban hati Cal lebih besar, karena perbuatannya berakibat pada jatuhnya satu negara. Sambil membawa beban hati seperti itu, dia selalu berusaha menjaga perasaanku ....
Bisa-bisanya aku terus mengungkit perbuatannya saat masih anak-anak?!
Cal bertanya, kenapa mudah sekali bagiku berpikir untuk mati. Sejujurnya, kini aku mempertanyakan hal yang sama.
Saat mengambil gunting itu ... kurasa aku tidak serius. Ada banyak benda tajam lain yang lebih efisien untuk digunakan di sana. Aku malah mengambil benda menyedihkan itu.
Saat dia berencana merampok bank otak ... aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak berusaha menghentikannya. Satu-satunya yang terpikir olehku hanyalah betapa berbahaya itu untuknya. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku juga menyimpan harapan untuk kembali jadi manusia lagi. Untuk hidup lebih lama.
Untuk melihat Emma dan Cal lagi. Untuk menyaksikan Joo kembali sebagai manusia juga.
Seharusnya aku mengatakannya ....
Bahwa sejak aku bersamanya, aku tidak pernah berpikir ingin mati lagi.
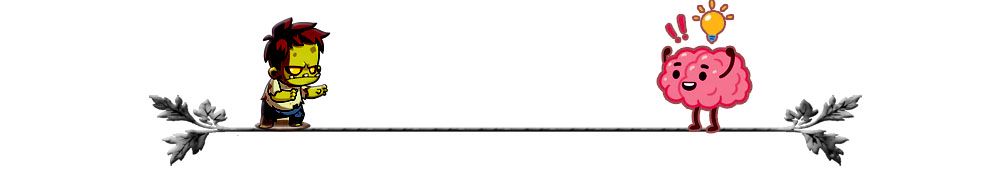
Ada suara seseorang. Ada yang masuk ke dalam ruangan tempatku berada. Langkahnya lambat.
Jam berapa ini?
Sudah berapa lama aku di posisi ini.
Aku lapar ....
Haus—
Mulutku sakit.
Tanganku sakit.
Sekujur tubuhku sakit.
Lalu, seseorang membuka penutup mataku. Aku terkesiap, terlebih saat penyumbat mulutku juga melonggar.
Butuh waktu lama untuk mataku menyesuaikan. Segalanya berkabut. Pandanganku dipenuhi bercak putih dan hitam.
Lalu, segalanya normal.
Ada Cal di hadapanku. Seorang pria paruh baya berseragam kurir berdiri menatap kami. Di sisinya, Joo menggendong Emma—
Adikku ....
Aku ingin adikku.
Lalu, mataku kembali memaut mata Cal.
Dia kelihatan tidak memercayai apa yang ditatapnya.
Apakah aku semengerikan itu? Apakah begini rasanya jadi zombie? Apakah aku bahkan sudah berubah?
Kemudian, Cal melepaskan semua ikatanku. Aku jatuh terduduk karena kaget, panik, marah, dan gelisah di saat bersamaan.
"Tidak ...." Aku terbata. "Apa yang kau lakukan! Aku bisa berubah sewaktu-waktu! Pergi dari sini, Cal! Pergi—"
Pria kurir di belakangnya mengacungkan tangannya yang mengenakan arloji.
Pukul 6.
Itu mustahil.
Kami masuk ke bangunan ini pukul 6.30!
Aku menoleh ke pintu. Lorong tidak sepenuhnya gelap. Ada jendela kecil di sana, tirainya terbuka, dan matahari pagi menyorot langsung hingga berkas cahaya samarnya jatuh ke lantai.
"Sudah 16 jam, Ilyas." Cal berkata. Matanya mengerjap-ngerjap penuh harap. "16 jam sejak kau tergigit ... dan kau tidak berubah."
Aku balas menatapnya. Aku tidak mengerti ....
Pria kurir itu berlutut di sampingnya dan meraih tanganku yang kena gigit. Dia menekan-nekannya dan mengernyit.
"Memang gigitan zombie." Dia mengusap bekas merah dan kebiruan di sekitar lukaku. "Ini memang bekas gigi zombie. Ini memang indikasi infeksi paling jelas."
"Prama ..." kata Cal tanpa mengalihkan matanya dariku. "Kau bilang ada beberapa orang yang dikarantina dan ditetapkan sebagai korban infeksi tiap tahun ... lalu diagnosis itu dinilai sebagai kesalahan, dan mereka dipaksa mendaftar masuk PN. Benarkah ... kau menyaksikannya sendiri, bahwa salah satu orang itu tergigit?"
"Aku yakin," jawab Prama. "Orang ini ... dia klienku dari Turan. Dia tergigit di depan wajahku. Tapi dia tidak pernah berubah. Pemeriksaan menunjukkan dia bersih. Sekarang dia seorang polisi. Semua orang bersikeras aku mengkhayalkannya. Mereka meyakinkanku aku pasti sudah gila."
"Ginna." Cal mencengkram kedua bahuku. "Ilyas ... Ginna memang terinfeksi. Aku tidak pernah melihat lukanya, tapi semua orang yang melihat luka itu mengatakan dia terinfeksi. Bahkan petugas evakuasi dan penanganan musibah zombie ... mereka semua orang yang berpengalaman. Mereka semua memutuskan untuk membawa Ginna agar dikarantina saat itu. Kurasa, Ginna bahkan tidak mengetahuinya ... bahwa dia termasuk orang-orang yang kebal."
"A—" Aku kehabisan kata-kata.
"Bicaralah pelan-pelan." Prama berdiri, lalu dia menepuk bahu Joo dan mengarahkannya serta adikku keluar. "Lepaskanlah dulu semua ikatan anak itu dan kasih dia air minum, Cal. Biarkan dia menenangkan dirinya. Kami tunggu di luar."
"Cal ...." Aku akhirnya mampu bersuara.
"Ilyas," sahutnya. Matanya berkaca-kaca. Dia segera mengeluarkan sebotol air mineral dari dalam tasnya, menuangkannya ke tangannya sendiri, dan membasahi bibirku yang terasa kering. "Ilyas, minumlah pelan-pelan."
Dia membantuku minum, lantas membantuku melepaskan semua sisa ikatan di badanku.
Dari dalam tasnya, dia mengeluarkan alat tes darah—sesuatu yang entah kenapa tidak kami lakukan dari awal. Mungkin karena aku terlalu takut melihat hasilnya.
Negatif.
Bersih.
Aku tidak terinfeksi.
Dengan ngeri, aku meraba gigiku sendiri dengan lidah, lalu dengan jari. Aku menampar kepalaku sendiri, berusaha meyakinkan diriku bahwa ini nyata.
Cal mengeluarkan pentungannya. "Mau kubantu?"
Lucunya, dia tulus mengatakan itu untuk membantu. Yang lebih lucu lagi, kudapati diriku tidak mempermasalahkan tawaran bodohnya. Malah ....
Aku senang.
Seumur hidup, tak pernah aku merasa sebahagia ini, ditawari untuk dipentung di kepala.
"Aku ..." kataku masih tak percaya, "bukan zombie ...?"
"Bukan zombie." Cal memastikan.
"Bukan zombie." Kuulangi kalimat itu. "Aku bukan zombie."
Setelah aku mengatakan itu, Cal langsung menghambur memelukku. Kali ini, aku mampu membalasnya. Kutarik dia lebih dekat sampai dia terduduk di atas kakiku. Kueratkan peganganku ke pinggangnya. Saat dia menangis, aku juga ikut menangis. Namun, kali ini kami juga sama-sama tertawa meski berlinangan air mata.
"Iyas!" Kudengar Emma berlari masuk sebelum merasakannya menabrak kami. Kuraup anak itu dalam pelukan juga. Pekikannya terganti jadi rengekan karena tergencet di antara aku dan Cal.
Di ambang pintu, Prama dan Joo berdiri bersisian. Bisa kulihat Prama menggaruk tengkuknya sendiri dengan canggung dan menatap Joo, lalu bertanya, "Jadi ... sudah berapa lama jadi zombie?"
Saat itulah aku baru menyadari masker Joo tidak terpasang. Matanya memandang kosong ke jendela. Bibirnya yang pucat agak terbuka.
"Tahu tidak," kata Cal sembari menarik diri, tetapi aku masih menolak melepaskannya. "Joo hampir bicara."
"Apa?"
"Saat kami akan masuk ke sini, dia berusaha bicara. Makanya aku melepaskan maskernya. Tapi, yah, dia tidak jadi bicara karena aku terlalu kaget saat melihatmu tidak berubah jadi zombie."
Joo masih memandangi jendela. Bibirnya terbuka sedikit.
"Joo," panggil Cal, "kau tadi mau bilang apa?"
Joo menarik napas. Bibirnya bergerak sedikit. Untuk sesaat, yang dilakukannya hanya bernapas lebih keras. Kemudian—
"Zo ..." lirihnya. Matanya masih menatap jendela. "Zom ... bie. Zombie. Di ... luar. Ada. Zombie ...."
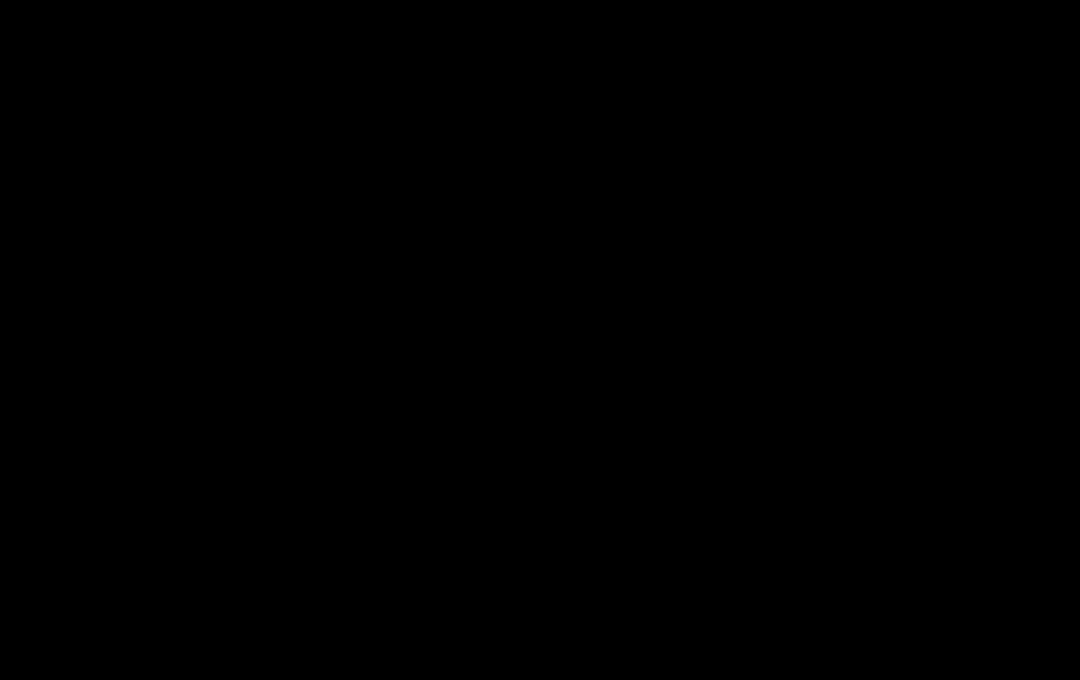
Chapter selanjutnya,
19 November 2024, 11.30 WITA
akan menjadi episode terakhir
Escapade: A Lone Wayfarer
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro