32. Cal dan Jalur Baru
|| 32: Cal's pov | 6997 words ||

"Luar biasa, kau masih hidup, wanita pemabuk!"
"Harusnya itu kata-kataku, kau bocah bawa sial!"
"Terakhir kuingat, kau terinfeksi!"
"Sudah kubilang itu luka lain dan bukan gigitan zombie, tapi berkat kalian bocah-bocah rewel aku dikarantina berminggu-minggu dan dipaksa mendaftar jadi PN!"
"Lucu sekali preman tukang mabuk jadi PN!"
"Maaf, ya, kalau tinggi badanku memenuhi syarat masuk PN sementara kau terjebak jadi kurir!"
"Kurir dua kali lipat lebih berguna daripada kalian para polisi!"
"Yeah, dan apa yang kalian dapat dari sana? Gaji dan tunjangan kalian hanya setengah dari pendapatanku per bulan!"
"Pendapatan yang langsung hilang setengahnya buat beli miras dan sisanya terpakai untuk membayar kurir yang mengerjakan tugas kalian, maksudmu?"
Dia menarik kerah seragam kurirku dan mencoba membantingku, jadi aku memeluk pinggulnya dengan kedua kakiku hingga perempuan itu merosot menghantam lantai lebih dulu. Batonku menghantam bawah dagunya dan ujung runcing gagang kayu yang dia pegangi menggoresku di atas alis kanan.
Sebelum kami sempat membunuh satu sama lain, Ilyas menarikku dari atas Ginna sementara Ahmed menarik perempuan itu menjauhi kami.
"Bisakah kau lihat situasi macam apa yang sedang kita hadapi sekarang?" bentak Ahmed seraya menggaplok kepala Ginna.
Aku mencoba menggeliat keluar dari kurungan tangan Ilyas, jadi pemuda itu menjentikku tepat di samping luka yang baru kudapat di jidat. "Cal, hentikan!"
Ginna menendang-nendang dan berusaha memberontak keluar juga dari pegangan Ahmed. Saat itulah aku melihat sebelah sepatunya tidak terpasang dengan benar, jadi aku menunduk tepat waktu saat alas kaki kanan Ginna terlepas dan meloncat ke arah wajahku.
Ilyas tidak menunduk.
Sepatu itu menghantam sisi kiri wajahnya, meninggalkan bekas kemerahan di bawah mata. Padahal dia habis kena serangan panik di dekat jalan tol, ditendangi di kepala oleh polisi yang membawa kami, dan sekarang kena tampol sepatu di muka.
Ilyas membeku syok, lalu rahangnya mengencang jengkel. Aku sendiri langsung terdiam, begitu pula Ginna. Ahmed hanya bisa membuka mulutnya hingga rokoknya jatuh ke lantai.
Lalu, Ilyas melepaskanku. Tangannya tertadah ke arah Ginna seperti mempersilakanku melakukan apa pun yang kumau.
"Tunggu—i, ini bukan saatnya ...." Ahmed tidak bisa menyelesaikan omong kosongnya karena aku keburu menyepak tongkat senjata Ginna sampai mental, lalu mengayun baton di tanganku. Ahmed tidak punya pilihan selain melepaskan Ginna kalau dia tidak mau kena.
Ginna bergerak menghindar, lalu meluncur ke arah tumpukan barang di pintu. Aku menjegal kakinya sebelum dia bisa mengambil senjata dari sana. Kami berdua jatuh sampai bergulingan. Saat dia berada di atasku, aku mengincar lututnya sampai dia kehilangan tumpuan. Alih-alih mendorongnya, aku berguling ke sisi, membiarkannya jatuh dengan wajah lebih dulu ke lantai. Jadi, saat aku berbalik untuk mendudukinya, Ginna berada dalam posisi tengkurap.
Di tengah usahaku mempertahankan posisi dan mengunci pergerakkan Ginna, Ahmed mencoba menyergapku dari belakang. Sebetulnya aku sudah siap—aku bisa menggetok giginya pakai baton dan mencekik Ginna pakai tangan satunya di saat bersamaan—tetapi Ilyas mengeluarkan senjata api laras pendek yang sebelum ini diambilnya dari persembunyian milik Ginna, dan mengarahkannya ke Ahmed.
"Mundur," kata pemuda itu seraya melangkah menyamping mendekatiku. Badannya masih menghadap Ahmed, begitu pula moncong senjatanya, tidak memberi si polisi pilihan selain mundur menjauhiku untuk keluar dari jarak tembak.
"Sudah kubilang ini bukan saatnya kalian bersikap tolol!"
"Kami dibawa ke sini untuk dimakan oleh polisi saja sudah tolol," tukas Ilyas. "Kau yang terborgol ke pilar dalam keadaan teler saat kami tiba. Kau tidak ada hak mengatai sikap kami tolol."
Ahmed berdengap tak habis pikir. "Kalian para bocah apakah tidak ada yang mengerti kita di sini sama-sama jadi stok pangan Pak Khandra yang entah kapan akan datang?"
Aku masih sibuk menahan Ginna di lantai sementara Ilyas dan Ahmed saling gertak, jadi kami terlambat sadar para polisi yang terborgol ke pilar sudah bangun. Salah satunya tampak benar-benar bingung dan menceletuk, "Kami ketinggalan apa?"
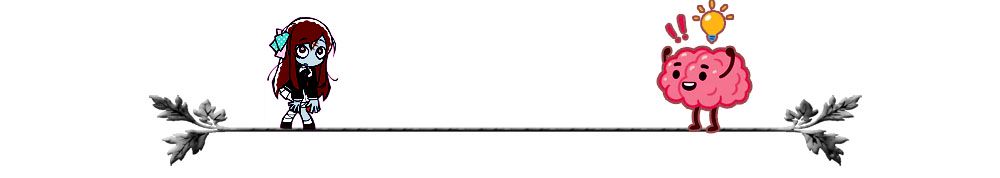
Ginna dan aku terpaksa menunda reuni kami. Semua orang berkompromi dengan menyimpan senjata api dan senjata tajam ke dalam satu loker, lalu mulai bekerja sama membuat barikade di pintu. Ilyas melepaskan borgol para polisi dengan jepit rambut ajaibnya. Ahmed membagikan protein bar dan air minum botolan secara merata ke semua orang.
Yah, tidak terlalu rata. Botol airnya cuma ada lima. Ahmed menyimpan dua botol untuk dibagi dengan sesama rekannya para polisi, padahal mereka semua bertujuh. Sedangkan dua botol lain diberikan untuk kami bertiga—aku, Ilyas, dan Emma. Satu botol disimpan untuk cadangan dalam loker. Tidak ada yang memprotes pembagian macam itu. Para PN sadar diri posisi mereka saat ini memalukan—disergap pemimpin operasi sendiri dan dibebaskan dari pilar oleh anak 16 tahun yang kepalanya berdarah kena sepak atasan mereka.
Sementara Ilyas membersihkan kepala dan rambutnya di keran wastafel toilet, aku menjaga Emma sambil memanggul baton di bahuku. Para polisi membiarkanku menyimpannya sementara mereka mempersenjatai diri dengan benda-benda tumpul lain dari loker cleaning service—sapu, tongkat pel, serok, dan tutup ember.
Begitu Ilyas selesai dari toilet, kami bertiga memutuskan duduk dekat pintu kaca yang mengarah ke lorong ruang ganti dan toilet, menjaga jarak dari para polisi yang mondar-mandir di tengah ruangan maupun dekat pintu keluar.
"Jadi, saat kau bilang kau kenal Ginna dari komunitas radio," kataku berbisik-bisik dengan Ilyas, "dan aku cerita tentang perempuan tukang mabuk dari rusun tempatku dan ibuku dulu tinggal ... kita membicarakan orang yang sama?"
Ilyas mengangguk. Dia bersandar ke tembok dengan rambut yang masih basah, tangannya menahan Emma yang sejak tadi tidak bisa diam, matanya melirik Ginna di seberang ruangan. "Kalau tidak salah, kau bilang dia terinfeksi?"
Aku menggeleng. "Sebenarnya aku juga tidak yakin. Saat itu ada dua anak lain yang bersama kami. Nayna dan Ulli—mereka beberapa tahun di atasku, tapi saat itu mereka juga masih anak-anak. Mereka yang pertama bilang ada bekas luka gigitan di badan Ginna. Waktu itu, wabah zombie baru pecah di rusun kami. Kurasa, Nayna dan Ulli panik saat melihat ada bekas luka di kakinya. Setelah kupikir lagi, cewek itu memang sering luka-luka karena dia bergaul dengan lingkungan yang tidak benar."
"Yah, kesalahan diagnosis korban infeksi memang tidak jarang terjadi," komentar Ilyas sambil bersedekap. "Kurasa, Ginna dipaksa masuk PN supaya dia tidak bisa menuntut atau buka mulut ke mana-mana ...."
Lalu, Ilyas mengernyit sendiri. Matanya memandangi lantai.
"Kenapa?" tanyaku seraya memajukan badan.
"Saat wabah zombie pertama pecah di wilayah rusun kalian ..." lirih Ilyas, "itu bertepatan dengan ulang tahun Nusa. Lingkungan rumahku di Renjani juga kena dampak penyebaran infeksinya. Saat itu, Kesatuan Militer Nusa belum dibubarkan paksa."
"Terus?"
"Yang bertanggung jawab atas semua kesalahan karantina itu Kesatuan Militer," kata Ilyas. "Kenapa wanita itu disuruh masuk PN? Kalau mereka mau membuatnya bungkam atau tidak bisa mengkritik orang-orang yang salah menuduhnya kena infeksi ... harusnya dia dipaksa masuk militer, bukan PN."
Aku mengerjap. "Barangkali kau terlalu berlebihan memikirkannya, Ilyas."
"Barangkali ..." keluhnya. Sebelah tangannya mengacak-acak rambutnya sendiri. "Kepalaku masih sakit gara-gara tendangan polisi tadi! Orang-orang pasti sudah dievakuasi dan kita malah terjebak di sini. Joo masih di jalan tol dan entah dia masih punya barang-barang yang kita titipkan atau tidak. Gedung ini juga lumayan jauh dari jalan tol, padahal kita tidak punya kendaraan lagi!"
"Kita bisa membajak mobil polisi yang membawa kita—"
"Lihat sekitarmu, Cal!" desis Ilyas dengan suara ditekan serendah mungkin. "Semua yang ada di ruangan ini polisi! Begitu Khandra dilumpuhkan atau berubah jadi zombie, merekalah yang akan mengambil mobilnya! Kita tidak mungkin minta tumpangan ke jalan tol—itu bakal memberi mereka alasan untuk menangkap kita di sini. Kalau kita bisa keluar dari sini hidup-hidup, kita akan dijejalkan ke dalam bus evakuasi."
"Selalu ada kendaraan yang ditinggalkan di suatu tempat, Ilyas," bujukku agar dia tenang. "Gedung ini dikepung ruko dan bangunan komersil lain. Biar pun sudah lama ditinggalkan, pasti ada sesuatu yang bisa kita pakai. Sepeda pun jadi." Aku menarik tangan Emma yang sejak tadi berjalan memutari badanku sampai anak itu terduduk ke pangkuanku. "Emma bisa kita taruh di keranjang. Kau di belakang. Kau tahu, 'kan, tidak ada yang bisa mengayuh sepeda secepat aku. Aku bisa membawa kita ke jalan tol dalam lima menit—"
"Bukan itu saja ...." Ilyas mengacak-acak rambutnya sendiri lebih keras sambil tertunduk. Siku bertumpu ke lutut. "Gelombang zombie, Cal—alasan lingkungan ini dievakuasi dan mengapa kita berangkat pagi-pagi buta! Karena para tipe 4 pasti sedang menuju kemari! Kita tidak ada waktu duduk-duduk di sini dan menunggu Khandra datang." Ilyas mengeluarkan suara gerungan kasar dari kerongkongannya. "Tapi kita juga tidak bisa keluar karena banyak zombie di depan pintu."
Aku garuk-garuk kepala karena kehabisan kata-kata. Emma di pangkuanku menggaruk sisi kepalaku yang satunya, barangkali mengira aku butuh bantuan untuk itu.
Kadang ada saat-saat tertentu, seperti sekarang ini contohnya, aku merasa menenangkan tantrum Emma lebih mudah daripada menenangkan Ilyas.
Aku bisa menutup mulut Emma pakai tangan jika dia menangis sambil berteriak, mengikat badannya ke badanku untuk kugendong keliling-keliling sampai rewelnya berhenti, atau kusumpal mulutnya dengan botol susu. Bahkan menunjuk-nunjuk jendela dan mengatakan padanya di sana ada gajah memanjat pohon pun pasti cukup untuk mengalihkan perhatian Emma. Ilyas tidak bisa ditenangkan seperti itu.
Sejak semalam, kukira ini hal bagus ketika Ilyas memutuskan dia tidak bisa memercayai Randall lagi. Soalnya, dia tidak bakal bisa balik ke Renjani. Namun, sejak itu pula Ilyas kelihatannya dua kali lipat lebih gelisah, lebih mudah panik, lebih cepat marah, dan perangainya gampang sekali berubah-ubah.
Pandangan mata dan sikap tubuhnya saat ini ... mengingatkanku pada sosoknya yang pernah kulihat di rumahnya dulu, berdiri di wastafel, membelakangiku, tidak lama setelah kami menguburkan nenek tetangganya—tepat sebelum Ilyas mendadak meraih pisau dapur dan mencoba mengiris lehernya sendiri.
Padahal kukira dia sudah jauh lebih baik sejak kami meninggalkan Renjani.
"Bagaimana kalau kau istirahat sebentar?" Kulepaskan jaket kurirku dan melipatnya, lalu kujejalkan di belakang kepalanya yang tersandar ke dinding. Rambutnya masih lembap. Meski bekas darah sudah dibersihkan sampai ke celah-celah rambutnya, ujung-ujung jariku bisa merasakan bekas luka baru pada kulit kepalanya. "Kau bisa tidur. Kalau ada apa-apa, kau pasti kubangunkan."
Ilyas tidak banyak menukas seperti biasanya. Malah, dia langsung merosot ke lantai dengan tangannya yang meraih jaket kurirku lalu dipeluknya sebagai bantalan di pipinya. Matanya dengan cepat tertutup dan Ilyas langsung bergelung di lantai, tidur seperti kucing.
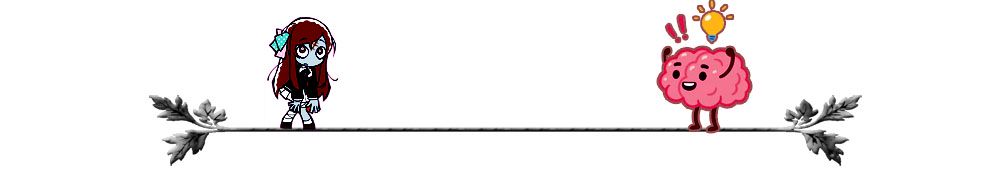
Pada satu jam pertama, aku duduk di samping Ilyas sambil menjaga Emma yang tidak mau berhenti mengelilingi badanku. Sedangkan para polisi tidak ada yang berdiam diri—mereka memperkuat barikade pintu, mengecek lorong-lorong, mengecek tiap jendela, dan memastikan ada atau tidaknya jalur alternatif yang bisa dipakai untuk keluar dari gedung ini.
Dua jam berlalu. Beberapa polisi yang mulanya cuma berbasa-basi mengajakku mengobrol akhirnya duduk-duduk di tengah ruangan dan membuka percakapan sungguhan.
Katanya, gedung ini sudah lama sekali tidak dipakai. Bahkan sebelum jalan tol ditutup, gedung ini sudah diisolasi lebih dulu karena beberapa staf pengurusnya terinfeksi dan berubah saat sedang bekerja. Jadi, mereka mengelas semua pintu samping dan belakang, lalu merantai pintu depan dan gerbangnya. Rantai-rantai itu dibuka beberapa bulan kemudian karena parahnya wabah di jalan ini, bertepatan dengan terinfeksinya jalan tol. Lahan parkirnya diubah jadi ladang ranjau dan jalan tol pun diblokade.
Tiga jam lewat begitu saja. Ahmed dan yang lainnya jadi makin santai. Mereka mulai menyusun rencana untuk nekat keluar dari sini dan mendorong para zombie di depan pintu menggunakan perisai yang dibuat dari pintu-pintu loker yang dicopot. Ide itu sebetulnya oke dan bisa saja berhasil kalau kami fokus bertahan, tetapi lain cerita jika polisi yang terinfeksi tadi datang di tengah pertempuran. Padahal Khandra membawa semua senjata kami dan dia sama sekali tak perlu khawatir kena gigitan lagi.
"Bisa saja dia sudah berubah sekarang," kata salah satu polisi itu. Kedua tangannya menepuk-nepuk gemas, mengajak bercanda Emma yang duduk bersila tepat di depannya. "Bisa saja Pak Khandra tergigit beberapa jam sebelum menyerang kita. Mungkin sudah lewat 6 jam? Kalian bilang, Pak Khandra tadi cari makan keluar? Yah, bayangkan itu. Berubah jadi zombie saat tangannya menenteng-nenteng plastik kresek berisi nasi bungkus."
Para polisi mulai terbahak-bahak pada pemikiran tersebut, kecuali Ginna.
"Tidak," tukas gadis itu dingin. "Dia menyerang kita tepat sesudah dia tergigit. Aku melihatnya. Tidak ada jeda. Artinya ini baru tiga jam sejak dia terinfeksi."
"Tapi bisa saja dia sudah tergigit sebelum itu tanpa dia tahu," celetuk polisi lainnya.
Aku tercenung ke kakiku sendiri. "Kalau begitu, bagaimana kita bisa tahu, di antara kita tak ada yang terinfeksi saat ini?"
Semuanya jadi terdiam.
"Ayo buat kesepakatan." Ginna memutar-mutar tongkat pel di tangannya, lalu menuding kami bergantian dengan ujung tongkatnya. "Siapa pun di antara kita, kalau melihat ada yang tergigit, harus segera menghabisi yang terinfeksi tanpa banyak bicara."
Ahmed mendengkus. "Ide bagus, tuh, keluar dari mulutmu. Kenapa tidak kau lakukan saat pertama melihat Pak Khandra terinfeksi?"
"Justru karena aku mengalaminya aku bisa bicara begini." Ginna menghentakkan tongkat pelnya ke lantai. Wajahnya murung. "Kalau dipikir lagi, harusnya saat itu aku langsung menghabisinya. Tapi aku syok. Aku malah terbata-bata dan memberitahunya dia digigit seperti orang tolol, padahal Pak Khandra sudah tahu dia tergigit. Makanya—" Ginna mengangkat dagunya dan memandangi kami semua satu per satu. "Ini berlaku buatku juga. Kalau ada yang melihatku tergigit, tembak aku dari belakang. Tidak usah ada adegan dramatis. Jangan berkata apa-apa. Jangan beri tahu aku. Jangan beri aku peringatan. Kalau bisa, akhiri dengan cepat. Jangan beri aku kesempatan buat lari. Soalnya, kalau ada dari kalian yang ragu-ragu sedikit saja ... aku pasti bakal lari."
Polisi yang duduk di sebelahnya menggosok tengkuk dengan canggung. "Yah, aku juga sama. Kalau aku tergigit, aku berharap kalian langsung menghabisiku dengan cepat. Jujur saja, kalau aku di posisi Pak Khandra ... aku mungkin akan melakukan hal yang sama. Jadi, jangan beri aku kesempatan buat berbuat bodoh seperti itu."
Mereka menyetujui itu, entah dengan anggukan atau tatapan mafhum. Jadi, aku angkat bicara.
"Kalau aku ... aku tidak mau. Kalau aku sampai tergigit, aku ingin sedikit lagi waktu. Aku tidak mau langsung dibunuh dari belakang." Saat kurasakan tatapan Ginna memicing ke arahku, aku buru-buru menambahkan, "Soalnya kalau aku mati di sini, Ilyas dan Emma bagaimana?"
Ahmed mendengkus. "Kami bisa mengevakuasi mereka ke kamp seperti yang lainnya."
"Masa?" tanyaku. "Kau tahu Kepala Polisi yang kau sembah itu ingin bertemu Ilyas untuk tujuan tertentu. Kau yakin dia akan membiarkan Ilyas dan Emma pergi untuk dievakuasi?"
Ahmed memicingkan matanya. "Pak Randall hanya berusaha mengungsikan anak itu keluar dari sini. Malah, sejauh yang kuketahui, lelaki itu duluan yang meminta tolong pada Pak Randall. Kenapa dia berubah pikiran—"
"Kau tahu, tidak, Ilyas dibesarkan di panti asuhan yang semalam?" Kugertakkan gigiku kesal. "Kau tahu, tidak, Kepala Polisi itu yang menaruh Ilyas ke sana saat dia masih bayi?"
Ahmed diam sebentar. Lalu, dia mengangkat bahunya. Tangannya meraih sebatang rokok yang tidak menyala dan menaruhnya ke mulut, lebih seperti gerakan refleks saja untuk menenangkan diri, bukan untuk merokok sungguhan, karena dia tidak punya apa-apa untuk menyalakan rokoknya saat ini.
"Aku tidak tahu masalahnya apa, tapi itu bukan urusanku." Ahmed menuding Ilyas yang masih lelap. "Aku hanya ditugasi menjemputnya tadi malam. Bukan posisiku untuk mempertanyakan perintah. Lagi pula, Pak Randall bisa saja melakukan ini semua karena merasa bersalah sudah meninggalkan anak ini di panti asuhan."
Aku meragukan itu. Dari pembicaraan kami tadi malam, aku tidak merasakan secuil pun penyesalan dari Randall. Dari yang kulihat, Randall malah seperti menuntut agar Ilyas diberikan padanya. Sikap seperti itu bukan bentuk kepedulian, tetapi lebih seperti ... dia menginginkan sesuatu dari Ilyas.
"Pokoknya aku tidak bisa membiarkan Ilyas dan Emma bertemu lagi dengan si Kepala Polisi. Kau jangan lupa, kalau tidak ada Ilyas, kau masih teler dengan muka menempel ke pilar. Jadi ...."
Aku menarik napas berat dan membayangkan kalau aku sampai terinfeksi di sini. Jika aku tergigit, para polisi ini pasti takkan ragu-ragu menghabisiku. Mereka menang jumlah dan kondisinya tidak memungkinkanku untuk melawan. Jadi, aku harus mengatakan ini.
"Aku yang membawa Ilyas dan Emma keluar dari rumah mereka. Ini tanggung jawabku jika mereka terjebak di sini. Kalau aku tergigit, biarkan aku memulangkan mereka kembali atau setidaknya beri aku waktu untuk mengantar mereka ke kota yang lebih aman. Siapa pun dari kalian boleh mengikutiku. Setelah Ilyas dan Emma aman ... silakan saja."
Ginna bersedekap. Matanya melirik Ilyas dan Emma bergantian. "Bagaimana kalau salah satu dari mereka yang tergigit?"
Kuraih Emma dan kududukkan anak itu ke pangkuanku.
"Tidak akan." Sebelah tanganku terulur ke arah Ilyas. Jari-jari tanganku menyusup ke rambutnya yang sudah mengering. "Akan kujaga mereka dengan nyawaku."

Sudah lewat lima jam. Sudah lewat tengah hari. Khandra tidak muncul-muncul dan, dari suaranya, jumlah zombie bertambah di depan pintu.
Kubiarkan dua orang polisi menjaga Emma—mereka sama-sama punya anak di rumahnya masing-masing dan kelihatan lebih berpengalaman mengajak balita bicara. Emma terus mengoceh tidak jelas dengan mereka, dan keduanya bertingkah seolah-olah mereka paham.
Tiga polisi lainnya mencopoti pintu loker dari engselnya. Aku, Ahmed, dan Ginna merakit perisai dari pintu-pintu itu dengan menyambungkannya menggunakan kawat pembersih saluran. Sesekali mataku mengawasi Emma di tengah ruangan dan Ilyas yang masih tidur dekat pintu kaca.
Kemudian, kudengar suara Ilyas yang menggumam samar-samar, "Emma ... Cal ...?"
Masih menggigiti rokoknya, Ahmed, berkata, "Mama Cal, si pangeran bangun."
Mengabaikan ejekannya, aku buru-buru menghampiri Ilyas. Pemuda itu sudah duduk meski matanya masih setengah memejam. Satu tangannya mencengkram jaketku dan tangan yang satu lagi mengepal mengetuk-ngetuk bagian depan kepalanya sendiri.
"Kepalaku lebih pusing dari sebelumnya."
Aku memegangi tangannya agar berhenti menggedor-gedor jidat seperti itu, lalu merasakannnya berkeringat dingin. Dahinya agak hangat.
Salah seorang polisi yang menggandeng Emma berjongkok di sisiku. Kudengar rekannya sebelum ini memanggilnya Bang Tria karena nama aslinya Satria dan mustahil dia mau dipanggil Bang Sat. Polisi itu ikut memeriksa Ilyas.
"Lihat aku, sini. Kau ingat kita di mana?"
Ilyas butuh beberapa detik untuk menjawabnya. "Gedung ... Rajasa."
"Kau merasa mual?"
"Tidak." Lalu dia membuat suara seperti akan muntah.
"Telingamu berdenging? Apa matamu terasa kabur?"
Ilyas meringis lemah. "Kabur ke mana?"
Sebenarnya seberapa keras pria tolol itu menendangi kepala Ilyas?!
"Dia baik-baik saja tadi," kataku heran.
"Aku pernah gegar otak di masa-masa awalku bertugas," kata Bang Tria, "kena pukulan nyasar saat melerai kericuhan suatu siang. Aku baru merasakan gejalanya di malam hari saat akan tidur."
Bang Tria mengambil botol air mineral cadangan yang kami kumpulkan di dalam loker, lalu memberikannya ke Ilyas. Dia kemudian mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan membasahi kain itu untuk mengompres kepala Ilyas.
"Lebih baik kau diam di dalam lorong ini bersama adikmu." Polisi itu memegangi pintu kaca. "Jangan keluar sampai kami menyingkirkan zombie yang tersisa."
Ginna yang mendengar itu langsung menegakkan punggungnya. "Sebentar, Bang Tria. Bukankah rencana awalnya adalah mendorong semua zombie di depan pintu dan berlari keluar secepat mungkin?"
Bang Tria berkacak pinggang. "Rencana siapa itu?"
Ginna menuding Ahmed dengan ibu jarinya, bersamaan dengan Ahmed yang menunjuk Ginna dari belakang. Keduanya berpandangan, lalu Ahmed mengangkat tangannya sendiri. "Iya, deh, rencanaku."
"Kau pikir anak ini kelihatannya bisa lari bersisian denganmu?" tanya Bang Tria seraya menunjuk Emma.
"Dia bisa kau gendong, Sat." Ahmed melambaikan tangannya seperti menepis lalat. "Kau bisa lari duluan dan kami melindungimu di belakang."
Bang Tria menunjukku dan Ilyas. "Dan mereka?"
"Kau tidak lihat cewek itu larinya secepat apa. Ingat maling televisi yang waktu itu kita kejar sampai subuh? Ya, dia secepat itu. Dan dia tidak kesulitan menghadapi zombie. Anak laki-laki itu ... yah, dia harus berusaha agar tidak ketinggalan kalau mau bertahan hidup."
"Aku tidak peduli meski mereka bisa terbang di atas kepala zombie-zombie sekali pun, mereka tetap prioritas untuk dievakuasi." Bang Tria mendudukkan Emma di samping kakakknya dan menghampiri Ahmed. "Apa kau tidak malu? Kita polisi yang tengah bertugas, dan kita ditemukan semaput, terborgol ke pilar, oleh anak-anak ini. Atasan kita menendangi anak laki-laki itu dan berencana memakan otak mereka juga, lalu sekarang kau ingin meninggalkan kewajibanmu mengutamakan evakuasi sipil demi bisa menyelamatkan diri sendiri. Aku tanya sekali lagi, kau tidak malu?"
Ahmed mengeluarkan rokoknya dari apitan gigi, lalu menyimpannya lagi ke saku. "Malu tidak bikin kita selamat, Sat. Kau juga punya anak dan istri yang menunggumu di rumah—anak keduamu baru lahir, 'kan? Kau kira mereka bakal senang kalau mendengar ayahnya tidak bisa pulang karena terlalu memikirkan anak orang lain? Lagipula, bocah-bocah ini melenceng dari jalur evakuasi. Kalau mereka tidak keliaran di sekitar sini, mustahil Pak Khandra menangkap mereka."
"Tunggu dulu ...." Ilyas meringis lagi seraya mencopot kain kompres di kepalanya. Emma mengambil sapu tangan yang basah itu dan menempelkannya ke matanya sendiri seperti kacamata. "Apa tadi—kalian berencana mendorong para zombie dan lari? Itu mustahil. Pasti akan ada yang tergigit."
Sebelum Ginna menukas, Ilyas mendahuluinya seraya menunjuk pintu-pintu loker yang bersusun sebagai perisai. "Dan jangan harap itu cukup. Tembok W keropos karena digerogoti zombie dari luar. Rahang dan gigi zombie-zombie itu mampu membuat retak tengkorak manusia. Pintu-pintu loker itu plastik! Kemungkinan terbaiknya, hanya setengah dari kita yang bisa keluar dalam keadaan utuh dari sini."
"Tentu saja kami memikirkan itu." Ahmed memutar bola matanya. "Sudah kubilang dari awal, satu-satunya cara bertahan hidup saat ini hanya berusaha untuk tidak ketinggalan dan jaga diri masing-masing."
Mudah baginya bicara begitu. Dia polisi. Dia terlatih untuk ini. Kemungkinan untuknya selamat dari ini lebih tinggi daripada Ilyas dan Emma.
"Ada cara lain," cetus Bang Tria, dan dia bicara bersamaan dengan Ilyas yang berdiri sempoyongan, menawarkan rencana yang persis sama: "Biarkan para zombie itu masuk dan kita sembunyi sampai menemukan celah untuk keluar dari sini."
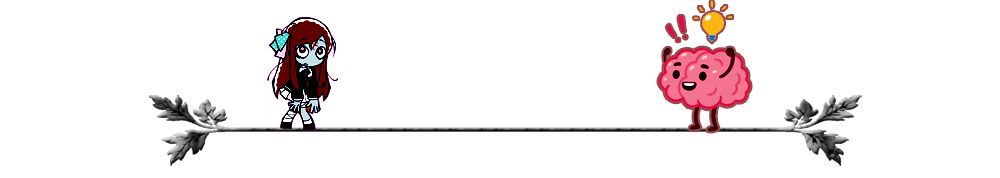
Aku mengerti kenapa rencana sembunyi ini tidak dicetuskan dari awal. Soalnya, harus ada salah satu dari kami yang membukakan pintu. Sisanya harus diam sediam-diamnya di balik tumpukan barang bekas barikade yang digeser. Ada kemungkinan Emma membunuh kami semua kalau mendadak dia kepingin mengeluarkan suara, dan membekap mulut anak itu hanya akan membuatnya menangis makin keras. Lalu, ada kemungkinan kami ketahuan juga. Jika begitu, kami akan terjebak dengan para zombie di sini.
Jadi, Ilyas dan Emma bersembunyi dalam ruang ganti yang tersekat lorong dan pintu kaca. Rencananya, setelah semua orang keluar, kami bakal membuat suara-suara di sekitar ladang ranjau untuk menggiring para zombie memasuki lahan parkir lagi. Barulah Ilyas dan Emma keluar setelah semuanya aman.
Mulanya, aku menawarkan diri untuk membuka pintu. Semua orang hampir setuju, kecuali Bang Tria dan salah satu rekannya yang masih muda, hanya beberapa tahun di atasku dan Ilyas—aku tidak tahu namanya. Bang Tria menawarkan dirinya dan memelototiku untuk tidak menentang, jadi aku balas memelototinya.
"Bah, sudahlah!" Ahmed berjalan sendiri ke balik pintu dan tangannya langsung siap di kenop. "Aku saja. Kuhitung sampai sepuluh. Satu dua tiga empat—"
Ahmed menghitung dengan kecepatan yang membuat kami kocar-kacir. Namun, aku mengerti, Ahmed melakukannya agar tidak ada yang bisa menentangnya atau memperpanjang masalah lagi.
Setelah memastikan Ilyas dan Emma aman di dalam ruang ganti, aku kembali ke ruang aula. Aku memilih bersembunyi di balik pilar seperti Bang Tria yang memunggungi pilar lain. Bagiku, ini akan mempermudah pergerakanku dan mengurangi risiko terjebak dalam persembunyian sendiri.
Rasanya aku seperti bisa mendengar suara Serge lagi di masa lalu: "Dengar, ya, anak barongsai. Ada dua jenis tempat paling ideal untuk bersembunyi dari zombie. Pertama, tempat paling kentara dan terbuka—di balik tirai sekali pun bisa. Kedua, tempat paling tertutup dan paling tersembunyi sekalian—ruang terkunci tanpa ventilasi, mobil dengan kaca gelap, atau kurung dirimu dalam brankas baja. Jangan pilih tempat persembunyian yang berada di tengah-tengah dua jenis itu. Tempat pertama fungsinya untuk memudahkanmu bergerak ke tempat persembunyian lain. Para mayat itu rabun dan kaki mereka tidak terkoordinasi dengan benar. Kau akan punya keuntungan jika kau bisa bergerak lebih bebas dari mereka. Tempat kedua fungsinya untuk mengurung dirimu dalam jangka waktu lama dan kau harus yakin kau tidak akan butuh keluar dari sana. Pastikan para zombie tidak bisa mengendus, mendengar, atau melihatmu sama sekali."
Saat ini, tempat Ilyas dan Emma bersembunyi adalah jenis yang kedua. Kamar itu tertutup pintu dan tirai, tidak punya jendela atau ventilasi, disekat lorong dan beberapa ruang lain, lalu dihalangi pintu kaca lagi. Para zombie takkan pergi ke sana karena mereka akan merasakan jumlah manusia paling banyak ada di aula.
Bang Tria, entah dia memahaminya juga atau hanya kebetulan memilih berdiri merapat di pilar karena tidak sempat mencari tempat aman lagi. Di balik tumpukan barikade sudah ada Ginna dan dua orang polisi lainnya. Dua lagi—personel PN yang kelihatannya paling muda—membungkuk di belakang perisai pintu loker yang sebelum ini kami susun di samping pintu.
Dulu, aku mungkin akan mengira tempat macam itu juga yang paling aman. Sekian lama punya pengalaman bergelut dengan Serge dan zombie, aku jadi paham bahwa pemikiran macam itu sama seperti pola pikir Emma yang menutup kedua matanya pakai tangan dan berjongkok menciutkan diri, mengira dirinya tidak bisa dilihat hanya karena dia sendiri tidak bisa melihat keadaan sekitar.
Begitu pintu dibuka dan para zombie membanjir masuk, kedua polisi di balik perisai pintu loker itu akan sama rentannya dengan Ahmed. Hanya karena mereka merasa terlindungi oleh lebarnya permukaan perisai, bukan berarti mereka takkan ketahuan. Para zombie yang kakinya kurang terkoordinasi itu mungkin akan menabrak pintu-pintu loker tersebut. Bahkan satu gerakan oleng saja berisiko membuat para zombie tanpa sengaja memutarinya hingga mereka bisa melihat apa yang ada di baliknya.
Begitu ketahuan, perisai pintu loker itu juga yang akan jadi penghalang bagi keduanya untuk kabur.
Namun, aku tidak sempat memberi mereka peringatan.
Ahmed bahkan belum selesai berhitung saat pintu menjeblak terbuka. Benar-benar terbanting ke dalam dan menggencet Ahmed ke dinding sampai suaranya menghilang.
Para zombie membanjir masuk, sebagian besarnya tipe 1, dan salah satunya adalah Khandra. Namun, di tengah-tengah pintu yang telah terbuka lebar, berdiri seorang lelaki asing yang tidak mungkin lebih tua dariku.
Lelaki itu masih utuh, berbentuk manusia sempurna tanpa kurang apa pun. Bajunya pun kelihatan masih baru. Namun, para zombie yang berbondong-bondong masuk mengabaikannya sama sekali. Gigi dan mulutnya yang menyunggingkan cengiran itu penuh darah. Matanya agak kecil dengan pupil yang menyempit. Mirip mata Joo. Kulitnya agak kehijauan dan keriput berbintik-bintik. Persis kulit zombie yang dulu mengekoriku sampai rumah Ilyas. Tersadarlah aku ....
Kami menghadapi zombie tipe 4.
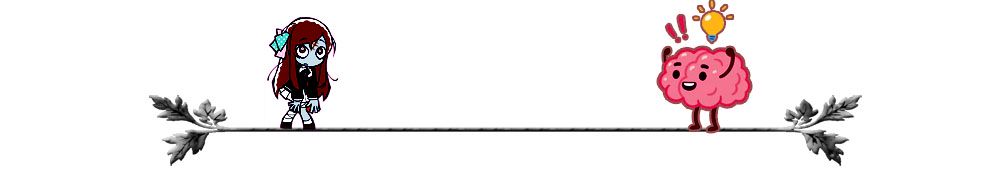
Keadaan berubah kacau dan benar-benar di luar kendali dalam sekejap.
Dua polisi di balik perisai pintu loker, persis seperti dugaanku, langsung ditemukan gerombolan zombie yang masuk. Salah satunya Pak Khandra. Mereka tidak terjebak di sana dan aku hanya bisa mendengar jeritan mereka dari tempatku berdiri.
Ahmed agak beruntung. Daun pintu rubuh menimpanya. Bisa kulihat pria itu tengkurap ke lantai dengan daun pintu menutupi tubuhnya. Gerombolan zombie yang masuk mengabaikannya atau lewat begitu saja dengan menginjak daun pintu beserta Ahmed di bawahnya.
Si tipe 4 berderap masuk begitu saja dan langsung menuju tumpukan barikade, lalu tangannya yang membentuk cakar mencaplok ubun-ubun salah satu polisi di samping Ginna. Ia menariknya, mencopot kepala si polisi semudah mencabut sumbat botol. Ginna dan polisi satunya yang selamat segera melompat keluar dari persembunyian mereka dan lari tunggang-langgang.
Tipe 4 itu hanya sedikit lebih tinggi dariku. Wajahnya jelas masih remaja. Aku yakin umur kami sama atau setidaknya ia lebih muda setahun. Aku terpaku melihatnya membentur-benturkan kepala yang baru dicopotnya ke lantai, seperti hewan yang berusaha membuat retak buah kelapa. Lalu, ia duduk dengan kedua tangannya menekan kepala itu, yang ia jepit di antara kedua kakinya, persis cara manusia membelah buah durian.
Aku berpaling saat si tipe 4 berhasil membuka batok kepala itu. Mataku berkedut hebat mendengarnya mengunyah karena dia duduk tepat di belakang pilar tempatku bersembunyi.
Mataku bertemu pandang dengan Bang Tria. Pria itu terlihat lebih syok lagi. Mulutnya menganga, rahang bergetar, mata membelalak lebar-lebar menyaksikan si tipe 4 makan di belakangku.
Kurasa, tidak ada pelatihan polisi seperti apa pun yang menyiapkannya untuk pemandangan ini. Bahkan aku sendiri tidak siap menghadapi ini, di sini, sekarang.
Senjataku hanya baton polisi milik Ginna. Ini hanya bekerja buat tipe 1 dan 2. Kami menyimpan semua senjata tajam dan senjata api dalam loker di ujung ruangan, berseberangan dengan tempatku berdiri, karena semua benda itu hanya akan merugikan kami jika digunakan melawan tipe 1 dan 2. Namun, senjata-senjata itulah yang saat ini bisa menjadi satu-satunya harapan untuk melawan makhluk di belakangku.
Aku mengintip lagi ke balik pilar dan terkejut saat melihat si tipe 4 menendang sisa makanannya sampai berguling ke kawanan zombie di tengah ruangan. Ia tersenyum, dengan sisa-sisa merah muda masih menyelip di giginya, memerhatikan kawanannya mengeroyok otak yang tersisa.
Tipe 4 itu kemudian berjalan ke pintu kaca.
Aku kehilangan akalku dan langsung bergerak maju, tetapi Bang Tria seketika menarik kerah bajuku, menghentikanku di tempat.
Sekujur badanku gemetar saat melihat tipe 4 itu menarik pintu kaca sampai terbuka. Ia berdiri santai di ambangnya, menyengir pada sesuatu di lantai, lalu ia melebarkan bukaan pintu kaca tersebut. Tipe 4 itu bersandar ke belakang, lalu membentur-bentukan kepalanya sendiri ke kaca, membuat bunyi gaduh yang mengundang beberapa zombie di tengah ruangan untuk menghampirinya.
Zombie-zombie itu lamban. Kalau aku bergerak sekarang, pasti sempat. Namun, Bang Tria menolak melepaskanku. Dia mengerangkeng kedua lenganku dengan kedua tangannya dan mati-matian menarikku menjauhi pintu kaca.
Lalu, si tipe 4 melihat ke arah kami.
Senyumnya melebar.
Matanya membelalak kian besar seperti anak kecil melihat mainan.
Ia berjalan ke arah kami.
Aku dan Bang Tria mundur menjauhinya. Punggungku menempel dengan punggung Bang Tria. Dia bergerak maju sementara aku bergerak mundur sambil terus berpandangan dengan si tipe 4. Tangan kami bergerak putus asa menebas zombie-zombie lain yang bergerak mengepung.
Perlahan tapi pasti, kami memutari ruangan dan mencapai loker yang menyimpan senjata. Bang Tria membuka pintu loker dan saat itu juga si tipe 4 mempercepat langkahnya. Kurasa si tipe 4 sejak tadi hanya bermain-main dengan kami. Ia baru menerjang dengan kecepatan penuh saat melihat semua senjata di dalam loker.
Tepat saat si tipe 4 melompat ke arahku, tanganku menggerapai ke dalam dan mendapatkan tongkat pel yang tadi dipatahkan Ginna. Ujung runcingnya kuhujamkan ke atas, menembus satu titik di leher bawah, tepat di tengah-tengah di antara tulang selangka si tipe 4.
Tipe 4 itu terhenti saat giginya tinggal berjarak dua jari dari tanganku yang memegangi tongkat pel.
Bang Tria di belakangku mencabut sepucuk pistol dan mengisi magasinnya. Zombie cerdik itu langsung tahu apa yang akan terjadi—ia mengaum dan memberontak, berusaha lepas dari hujaman tongkat pel.
Aku bisa mempertahankan peganganku, tetapi tidak bisa menghentikan tongkat pel yang patah ketika si tipe 4 melepaskan dirinya. Si zombie segera berlari menjauhi kami dan pergi ke luar sebelum Bang Tria bisa membidiknya.
"Tidak!" Aku menjerit. Tanganku mencari-cari senjata api lain di dalam loker. "Jangan biarkan makhluk itu lolos! Kita tidak bisa membiarkannya hidup!"
Makhluk ini, meski sama seperti Joo, ia juga sama sekali berbeda. Tipe 4 yang ini benar-benar cerdas ... dan sadar akan apa yang dilakukannya.
Dan ia terlihat menikmatinya.
Aku berusaha mengejarnya, tetapi terlambat. Para zombie yang lebih lamban telanjur mengepung kami.
Dengan putus asa, aku dan Bang Tria mencampakkan semua senjata. Bersama-sama, kami mengangkat loker paling besar di belakangku, lalu melemparkannya ke depan sampai menimpa sebarisan zombie untuk membuka jalan.
Di saat bersamaan, terdengar suara ledakan beruntun dari luar. Sepertinya ... dari arah lahan parkir. Ladang ranjau itu.
Baru kusadari, Ahmed sudah tidak ada di bawah daun pintunya. Aku hanya bisa berharap dia, Ginna, dan polisi yang satu lagi berhasil sampai ke ladang ranjau.
Bang Tria dengan sigap menarikku ke samping loker senjata. Bunyi-bunyian ledakan itu membingungkan para zombie di sekitar kami untuk sesaat. Begitu aku dan Bang Tria menghilang dari jarak pandang mereka, semua zombie itu menganga dan merenungi udara kosong di depan wajah masing-masing, benar-benar lupa pada kehadiran kami berdua.
Rentang perhatian zombie tipe 1 lebih pendek dari anak TK, kudengar suara Serge lagi saat dia mengajariku berhadapan langsung dengan tipe 1. Bahkan anak yang berat otaknya cuma dua gram sepertimu jauh lebih pintar dan fokus daripada mereka.
Suara ledakan terdengar lagi, kali ini berupa rentetan panjang tiada henti sampai hampir 30 detik lamanya. Untuk waktu yang cukup untuk para zombie memutuskan berbalik keluar dan mengejar sumber suara.
Tersisa kira-kira enam atau tujuh zombie di ruang aula, tetapi semuanya bergerak terlampau lamban. Dan alasan mereka tidak keluar adalah karena telinga dan mata mereka yang mengucurkan darah.
Namun, ada satu zombie yang kelihatannya masih memiliki sebelah matanya. Dia berjalan pincang dari arah barikade ke pintu kaca yang masih terbuka lebar. Lalu, aku melihat alasannya menuju ke sana: Emma.
Anak itu berdiri terlalu dekat dengan pintu.
Zombie yang melihatnya bergerak ke arahnya.
Tidak.
Tidak akan sempat.
Jarak kami terlalu jauh dan zombie itu sudah berdiri tepat di hadapan kaca pintu.
Namun, aku tetap berlari ke sana.
Lalu, tepat ketika Emma berjalan maju, si zombie juga bergerak maju. Pintu kaca itu terbuka ke arah luar. Seluruh badan si zombie, kebetulan sekali, mendorong kaca pintu dan membuatnya mengayun tertutup kembali tepat di depan wajah Emma.
Emma terduduk ke belakang, lalu mengerjap-ngerjap, sedangkan zombie di hadapannya masih berusaha bergerak maju meski terhalang kaca pintu. Anak itu berdiri susah payah, tangannya menepuk-nepuk kaca pintu sementara zombie di hadapannya masih jalan di tempat.
Lalu, Ilyas muncul, merangkak gemetaran dan banjir keringat. Tampaknya dia langsung kehilangan tenaga pada lututnya ketika menyaksikan tipe 4 tadi yang menyambanginya di ambang pintu. Sedangkan Emma yang baru bisa berjalan tidak punya masalah melangkah ke arah zombie—meninggalkan kakaknya di belakang dengan kecepatan penuh.
Ilyas buru-buru menarik Emma ke pelukannya dan merangkak pergi lagi, menjauhi pintu dengan susah payah.
"Cal, ayo!" panggil Bang Tria yang sudah berdiri di ambang pintu dengan persenjataan lengkap. "Kalau kau mau mereka aman, kita harus keluarkan zombie-zombie ini dari sini."
Aku mengekorinya dan membuat suara-suara agar para zombie yang tersisa dalam aula bergerak keluar. Mereka super lamban, super lemot. Aku dan Bang Tria harus melangkah pelan dan memastikan para zombie ini membuntuti kami sampai lahan parkir.
Sesampainya di sana, bisa kulihat tanah retak-retak penuh rumput gosong dan berasap hitam pekat. Para zombie berkumpul di ujung, menggapai-gapai ke atas, mengepung sebuah bangunan tembok bata setinggi satu lantai. Di puncaknya, ada Ahmed, duduk sambil merokok. Rokoknya menyala.
Di tepian pagar, Ginna dan polisi satunya mengendap-endap ke arah kami. Mereka menempel erat ke tembok, berusaha tidak menginjak rumput sama sekali dan tetap melangkah di garis semen yang tersisa.
Aku memanjati pagar dekat gerbang yang terbuka, begitu pula Bang Tria. Para zombie yang mengekori kami masuk dengan patuh begitu melihat kawanan mereka berkumpul seperti sekte pemujaan Ahmed yang merokok.
"Yak, terus. Yang tertib." Kudorong beberapa zombie itu pakai baton agar masuk lebih cepat. "Awas, ranjau—"
Salah satu zombie yang baru masuk tampaknya salah melangkah. Ledakan menyembur dari bawah kakinya, menghamburkan badannya sampai terpotong-potong. Tiap irisannya berkedut dan tetap berusaha bergerak menuju kawanannya yang lain.
"Baru kubilang, awas ranjau."
Ketika Ginna dan polisi satunya sampai di bawahku, kutarik mereka ke atas agar mereka tidak perlu menginjak rumput dekat gerbang.
"Trims," gumam Ginna singkat.
Aku menepuk punggungnya keras. "Aku yang makasih. Kalau kalian tidak membuat suara di sini, kami yang di dalam aula tinggal nama dan cacahan jasad."
Aku dan Bang Tria turun lebih dulu, disusul Ginna dan teman polisinya. Dengan kelegaan luar biasa, kami menutup gerbang. Kueratkan kembali rantainya, sementara Bang Tria langsung memeluk kedua rekannya dengan mata berkaca-kaca. Pria itu kedengarannya menangis sedikit.
Melihat gerbang sudah tertutup, Ahmed berdiri dari tempat nongkrongnya. Pria itu berjalan menyusuri puncak tembok yang sempit, kedua tangan masuk ke saku celana, gigi masih mengapit rokok, mengabaikan kawanan zombie yang bergerak searah dengannya. Begitu Ahmed melompat turun, dia langsung berangkulan dengan Bang Tria seolah mereka ada di acara kumpul reuni, bukan di depan ladang ranjau penuh zombie.
"Kacau sekali hari ini," komentar Ahmed seraya menjentikkan abu rokoknya ke tanah saat kami berjalan kembali ke arah aula. "Banyak hal-hal tidak masuk akal yang kulihat. Aku hampir yakin seharian ini hanya halusinasiku. Ginna, kau harus kurangi konsumsi miras."
"Kenapa jadi aku?!"
"Kalian lihat juga yang tadi, 'kan?" tanya Bang Tria memastikan. "Bukan hanya aku, 'kan? Itu tadi zombie, 'kan? Bukan aku yang gila sendirian?"
"Tipe 4." Aku memberi tahu mereka. Para polisi itu langsung bungkam sambil terus menatapku yang jalan di depan mereka. "Anggap saja begitu. Tipe 1 yang baru berubah jadi zombie. Tipe 2 yang baru makan dua atau tiga otak utuh. Tipe 3 yang sudah mampu belari—barangkali sudah memakan lima otak. Tipe 4 ... yang seperti tadi. Memakan sekitar tujuh otak utuh dan berubah jadi sesuatu yang dideskripsikan Khandra sebelum ini—dia bilang atasannya yang berubah jadi zombie itu membebaskan diri dari rantai setelah makan cukup banyak otak, 'kan?"
"Kau tahu banyak, ya." Ahmed mengangkat sebelah alisnya. "Pantas saja anak laki-laki itu tidak tampak kaget saat mendengar Pak Khandra mencoba memakan otak kita. Apa kau dan anak itu mengetahui sesuatu yang tidak kami ketahui selama ini?"
Aku mengabaikannya dan berlari lebih cepat meninggalkan mereka. Aku langsung melompat ke dalam aula dan dengan riang memanggil, "Ilyas! Ayo, keluar! Zombienya sudah bubar—"
Lalu, Khandra muncul dari samping.
Giginya yang penuh darah berusaha mengatup ke wajahku. Seluruh bobotnya mendorong perisai pintu loker yang menjadi penghalang di antara kami sampai roboh menimpaku.
Aku terjepit.
Responsku lambat.
Batonku. Mana baton keparat itu? Apa aku melepaskannya?
Tidak. Jangan panik.
Namun, aku telanjur membeku dan merasakan kepanikan mulai merayap naik ke kepalaku.
Sela giginya penuh sesuatu yang aku tidak mau tahu itu apa.
Darahnya menetes-netes ke wajahku.
Aku menahan napas, tetapi tetap membaui kebusukannya.
Tanganku secara spontan bergerak untuk menghalangi wajahnya dari wajahku.
Di detik-detik terakhir sebelum telapak tanganku mencapai mulutnya, suara Serge menggema dalam kepalaku, seolah menembus keluar dari gendang telingaku: "JANGAN. SENTUH. WAJAH. MEREKA! Kau dengar aku, Anak Kalong? Hentikan tanganmu tepat di dada mereka. Tahan posisi tanganmu sejajar bahunya. Bahkan bawah dagu pun berbahaya. Inilah kesalahan paling dasar para korban infeksi—mereka selalu mengangkat tangannya untuk melindungi diri dan berakibat pada gigitan."
Tanganku langsung turun menahan pintu loker. Wajah Khandra turun dan hampir mencapaiku, tetapi dia sepertinya tersangkut dan tidak bisa maju lagi. Kakiku jadi dingin, perutku sakit, dan tanganku mulai gemetar. Seumur hidup sejak Serge melatihku, aku tidak pernah selengah ini.
Aku terjebak.
Segalanya jadi bergerak begitu lambat di mataku. Seolah-olah otakku mendadak memproses keadaan dengan begitu cepat, tetapi seluruh anggota tubuhku tidak mampu mengikutinya dan malah membeku di tempat.
Kudengar Bang Tria meneriakkan namaku. Ginna berlari ke arahku setelah memungut batonnya. Ahmed mengeluarkan pistolnya, tetapi terhenti saat menyadari bahwa yang dia bawa-bawa itu pistol bius—tidak mempan sama sekali untuk zombie.
"Cal!" Bang Tria memekik lagi. Kurasakan Khandra mulai membebaskan diri di atasku dan menggeliat lebih dekat ke arahku. "CAL—"
Kemudian, sekelebat sosok lain menyambar dari sisiku yang satu lagi, menabrak Khandra sampai mereka bergulingan. Momen itu menjadi tamparan yang membuatku sadar.
"ILYAS!" Aku bangkit secepat kilat dan mencengkram punggung Khandra yang berada di atas Ilyas. Aku melemparkan makhluk jahanam itu ke hadapan Ginna, yang langsung menghantamnya dengan baton.
"Sini!" Si polisi yang masih tak kuketahui namanya itu menepuk-nepukkan tangannya, berusaha menggiring mantan atasannya untuk mengekor ke arah ladang ranjau, diikuti oleh Ginna yang masih mengayunkan baton berkali-kali ke punggung si zombie.
"Ilyas! Ilyas!" Aku berlutut di hadapannya, merasa lebih panik daripada saat si zombie berada di atasku. "Ilyas!"
Pemuda itu terduduk, kedua tangannya memegangi jaket kurirku yang tadi kuberikan padanya sebagai bantal. Jaket itu koyak dan bersimbah darah, barangkali bekas mulut kotor Khandra.
Ilyas tidak bisa bicara sama sekali. Dadanya naik turun mencoba bernapas. Wajahnya basah oleh keringat.
"Dia tergigit—"
"TIDAK!" Aku mengeluarkan pistol yang sebelum ini kuambil dari loker dan mengarahkannya ke wajah Bang Tria, yang kebetulan sekali juga memegang senjata model sama, terarah ke Ilyas. "Jangan berani-berani—"
"Kalau begitu, coba kita cek di balik jaket itu—"
"JANGAN MENDEKAT!" teriakku. Kugeser kamar peluru pistolku dan kuletakkan jariku pada pelatuk. "DIA TIDAK APA-APA! ILYAS TIDAK TERINFEKSI! MENJAUH DARI KAMI!"
"KALAU BEGITU, PERLIHATKAN APA YANG ADA DI BALIK JAKET BERDARAH ITU!" balas Bang Tria membentak. Dia juga menggeser kamar peluru senjatanya.
Emma muncul dari dalam aula. Dia tampak ketakutan kali ini, barangkali karena teriakan-teriakan kami, dan langsung berlari ke arahku. Kemunculan anak itu membuat Bang Tria lengah untuk sesaat dan terlambat menyadari Ahmed mengendap, membiusnya dari belakang. Ketika Bang Tria melemas, lalu jatuh dengan mata berputar ke atas, aku mengganti arah moncong senjataku ke Ahmed.
Kupegangi Emma di sisiku dan kupastikan Ilyas tetap di belakangku, tidak terekspos ke jarak tembak siapa pun.
Namun, Ahmed menjauhkan jarinya dari pelatuk. Dia mengangkat kedua tangannya sejajar kepala, menandakan senjata biusnya tidak mengancamku.
Ginna dan polisi satunya kembali. Mulanya mereka kaget melihat kami berposisi begini. Kemudian, Ginna melihat Ilyas di belakangku, memeluk seragam kurirku yang bersimbang darah.
Gadis itu mendadak mengeluarkan kunci dari balik seragam polisinya dan melemparkannya ke hadapanku. Dia juga menggelindingkan sebuah tongkat ....
Tongkat milik mendiang Pak Radi yang sebelum ini dibawa Khandra.
"Ada toko alat olahraga di samping gedung ini," ujar Ginna. "Mobilku terparkir di depan pintu tokonya."
Kenapa?
Kupandangi polisi yang satu lagi dan kuarahku moncong senjataku padanya. Dia berkedut sedikit, tetapi kemudian berpaling. Seolah-olah tidak melihatku, dia berkata, "Mobil Pak Khandra masih terparkir di depan. Ayo, kita harus ke kamp dan membuat laporan."
Kenapa?
Namun, rasanya aku tidak peduli lagi. Buru-buru kuraih kunci mobil Ginna dan tongkat Pak Radi. kugendong Emma dan kuangkat Ilyas sampai berdiri. Kubiarkan pemuda itu menumpukan bobot tubuhnya ke bahuku.
Saat kami sampai di jalan, Ginna berteriak lagi.
"Cal!" panggilnya, membuatku menoleh. Dia berhenti sejenak, seperti ragu-ragu hendak mengatakan sesuatu. Namun, akhirnya dia melanjurkan. "Kotatua. Bank otak terbesar ada di sana."
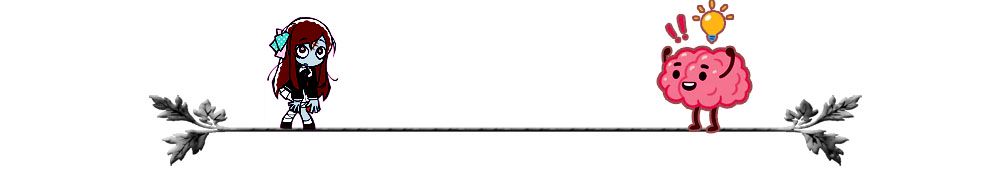
Barang-barang kami yang sebelum ini dibuang oleh Khandra ke bahu jalan masih ada di sana. Kubawa semuanya tanpa pikir panjang.
Tanpa pikir panjang pula, aku menyingkirkan barikade yang menghalangi satu jalur di plaza tol. Jalur itu kosong. Kurasa suara ledakan dari ladang ranjau mencapai lokasi ini dan membuat para zombie berkumpul di sisi lain jalan.
Kukemudikan mobil Ginna masuk ke jalan tol, lalu berhenti lagi untuk menggeser kembali barikade sampai menutup.
"Kabar baiknya, kita tidak perlu cari-cari mobil atau memikirkan ganti aki," kataku dengan suara seriang mungkin. Kurebut jaket kurirku yang penuh darah dari pelukannya, lalu kubuang di jalan. Kuberikan padanya jaket kurir cadanganku dari dalam tas, masih wangi dan bersih.
Aku lanjut mengemudi.
Percaya tidak? Joo masih di sana, memencet bebek.
Ketika aku menurunkan kaca, Joo langsung masuk ke belakang dengan patuh bersama semua bawaan kami. Zombie-zombie lain yang mengerubunginya sebelum ini menempel ke kaca mobil, berusaha menebeng.
Begitu Joo berhasil memasang sabuk pengamannya, aku langsung tancap gas.
"Joo," desahku sambil mengamati muka datarnya dari spion. "Aku tak percaya bakal mengatakan ini, tapi aku kangen sekali padamu."
"Jo jombi," celoteh Emma seraya merangkak ke kursi belakang.
Joo merentangkan tangannya, seperti hendak menyambut pelukan Emma. Namun, anak itu, sambil tertungging-tungging, rupanya cuma mencari bebek karetnya yang jatuh ke bawah kaki Joo.
Emma berguling dan duduk manis di sisi Joo sambil memegangi si bebek. Joo masih membeku dengan posisi menyambut pelukan.
Kuamati keduanya dari spion, lalu mataku melirik Ilyas.
"Kau boleh tidur lagi, Ilyas," kataku lembut. Sebelah tanganku yang tidak memegang setir menyeka rambutnya yang menempel di kening karena peluh.
Lalu, sekujur badannya gemetar hebat. Jaket kurirku yang dipeluknya melorot dari tangannya. Kunaikkan lagi jaketku. Kugenggam tangannya kuat-kuat sampai gemetarannya berhenti.
Sepanjang jalan, sebelah tanganku terus memegangi tangannya seperti itu, berpura-pura tidak ada bekas gigitan di sana.
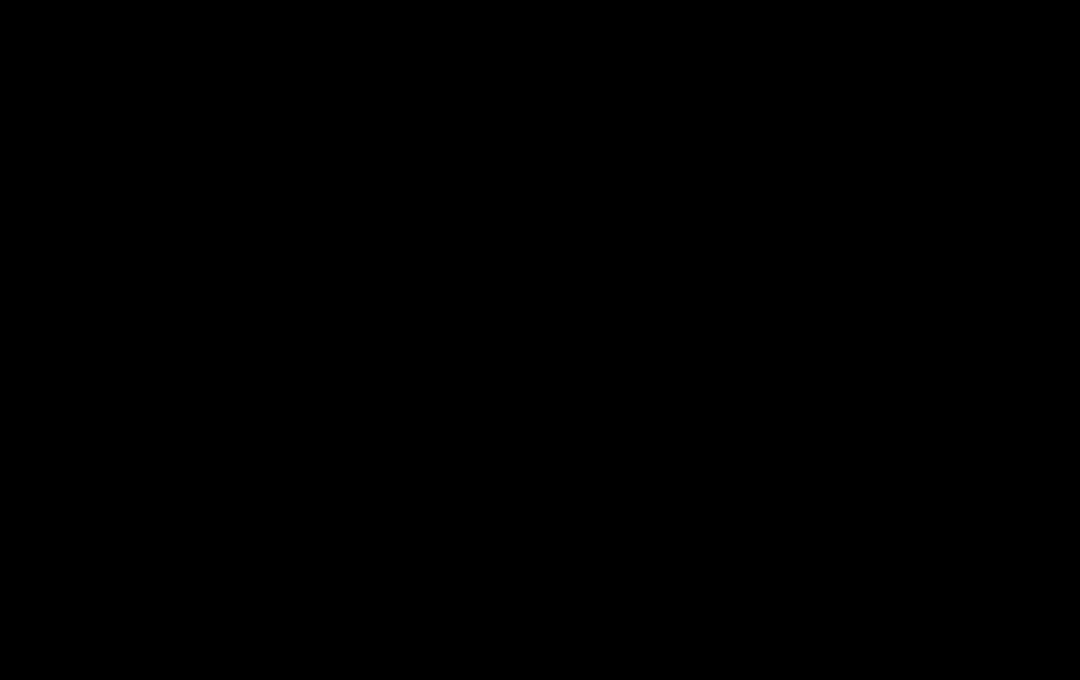
Selamat tidur man teman (*¯︶¯*)
Mimpi indah yaaaa (っ˘з(˘⌣˘ ) ♡
Oiya, habis ini satu chapter terakhir ya. Baru epilog. Habis itu kita cus ke buku dua '-')V
Oiya lagi, saya kepikiran nyari tempat gentayangan lain selain wattpad. Ada yang punya saran? Di wattpad masih kok, cuma mau nyoba-nyoba tempat bertapa lain aja. Cuma mau meluaskan eksistensi dan menebar lokasi gentayangan E-Jazzy. Soalnya di wattpad juga pesan privat udah ilang, 'kan, nda enak banget kalo mau menggibah diam-diam sama kalian jadi susah.
Dah itu aja. Met bobo guys ( ' ▽ ' ).。o♡
ヾ(*゚ー゚*)ノ Thanks for reading
Secuil jejak Anda means a lot
Vote, comment, kritik & saran = support = penulis semangat = cerita lancar berjalan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro