31. Ilyas dan Jalan Buntu
|| 31: Ilyas's pov | 6170 words ||

Jantungku seperti mental ke mana-mana. Tiap decit ban, tiap belokan, tiap bantingan setir—aku hanya bisa merasakan degup jantungku sendiri. Ujung-ujung jariku mendingin. Aku tidak bisa merasakan kakiku sendiri di bawah sana.
Parameter jalan sudah dipasang. Beberapa polisi masih sibuk mengarahkan penduduk yang tersisa untuk memasuki bus-bus evakuasi. Cal datang menabrak pembatas jalan, menghindari orang-orang yang teriakannya terdengar sampai ke dalam mobil kami, dan untuk sesaat yang singkat ban depan di sisiku tersasar naik ke atas emperan rumah seseorang.
Badanku menempel ke sandaran jok, lalu ke kaca, lalu mukaku hampir menghantam dasbor. Sabuk pengaman mengencang di lenganku yang menamengi Emma. Napasku berhenti dan melaju silih berganti. Aku melirik speedometer dan melihat jarumnya bergetar di angka 80 ... 100 ... 120 ....
Ada bundaran dengan tugu monumen di tengah-tengahnya, berdiri di antara perempatan jalan. Cal membawa kami berbelok melewati bundaran sampai seisi mobil condong ke satu sisi. Suaraku tidak bisa keluar. Nyawaku tertinggal di jalan satunya.
Di pangkuanku, Emma menjerit girang, "Ngueeeeeng!" menirukan deru mesin mobil. Mendengarnya membuatku bertanya-tanya apakah kegilaan Cal telah menular ke adikku. Perilakunya jelas sekali bukan turunan dari Pak Gun maupun Bu Miriam. Aku juga tidak ingat pernah mengajarinya bersorak menyambut kematian.
Cal tidak bercanda saat dia berkata kami bisa berada di jalan tol dalam lima menit. Dengan kecepatan orang waras, jarak panti asuhan ke jalan tol ini harusnya ditempuh dalam 15 menit lebih.
Kami berhenti tepat di hadapan pagar seng yang menghalangi area pemukiman dan jalan tol. Jalanan sepi di belakang. Tidak tampak anggota PN yang mengejar. Parameter jalan juga tidak ada. Bangunan-bangunan di sini sudah terbengkalai, ditinggalkan oleh para pemiliknya yang tidak mau tinggal berbatasan dengan jalan tol.
"Nah, sampai—" Cal membelalak saat menoleh ke belakang. "Astaga! Joo, maaf!"
Aku ikut menengok. Di jok belakang, si zombie sudah dalam keadaan tertungging, terjepit antara jok Cal dan dudukannya sendiri. Sebelah kakinya ditimpa kotak aki, kaki yang satu lagi mengangkangi jeriken minyak.
Cal segera keluar dari mobil dan membuka pintu belakang untuk membantu Joo bangun. Gadis itu lantas memanggul ransel di satu bahu, menenteng kotak aki di kepitan lengan satunya, dan menjinjing kedua jeriken bensin di masing-masing tangannya.
"Tunggu." Aku menarik napas gemetaran. Kubuka kaca jendelaku untuk mencari udara. "Lututku ... mati rasa."
Cal mengerjap lugu. "Kau pasti kelamaan mandi tadi."
"Atau karena seseorang mengemudi seperti minta mati."
Gadis itu menutup pintu belakang, lalu memutari mobil untuk mencapai sisi pintuku. Tanpa melepas pegangannya pada jeriken bensin, Cal mengait handle dengan jari kelingkingnya dan membuka pintuku.
"Lewat sini, Yang Mulia Pangeran."
Aku tidak punya tenaga untuk membalasnya.
Ketika aku melepas sabuk pengaman, Emma mengulurkan kedua tangannya ke arah Cal sambil berucap, "Ndong!"
"Sekarang saat tanganku penuh, baru kau minta digendong. Kemarin-kemarin ketika kugendong, kau bertingkah seperti dibawa sindikat penculikan anak."
"Ndong!" Emma bersikeras.
Barangkali karena aku gemetaran dan sekujur tubuhku bermandikan keringat dingin, Emma merasakan kegelisahanku. Dia tahu digendong olehku saat ini sama saja seperti didudukkan di atas gelondongan kayu yang terseret ombak laut.
Cal mengalihkan ranselnya dari punggung ke depan. Dia membalikkan badannya dan membungkuk dengan punggung menghadapku. "Ikat adikmu ke punggungku sini. Pastikan dia tidak bisa lepas seperti waktu di pos polisi di Renjani."
"Tapi ...."
"Sudahlah, tidak apa-apa. Ayo cepat."
"Maaf, Cal ... terima kasih."
Aku membuka ransel dan mengambil kain selimut yang diberikan Bu Raiva sebelum ini, melilitkannya ke sekeliling bahu dan perut Cal, memasukkan kaki dan pantat Emma ke dalam lilitannya, lalu mengencangkan ikatannya dengan shoulder holster yang dipakai gadis itu.
"Biar aku yang bawa aki dan jeriken minyaknya," kataku seraya mengambil alih kedua jeriken minyak di tangannya, tetapi Cal menolak melepaskan aki di bawah kepitan lengannya.
"Kau awasi Joo saja." Cal menunjuk si zombie. Gadis itu kemudian menarik keluar pentungannya. "Bisa gawat kalau aku salah menyerangnya semisal ada zombie di depan kita."
"Jalan ini langsung ditutup begitu infeksi menyebar, Cal, dan hampir tidak ada pemukiman di sana. Jadi, zombie-zombie ini tidak memakan otak sehat sejak mereka berubah. Artinya, semuanya tipe 1 atau tipe 2. Tipe 1 tidak bisa dibunuh sama sekali, 'kan?"
Yah, sebenarnya bisa. Namun, satu-satunya cara membunuh tipe 1 hanya dengan membakar mereka sampai jadi abu. Artinya menjejalkan mereka ke dalam tungku kremasi di krematorium.
"Betul juga." Cal menyimpan kembali pentungannya. "Berarti, satu-satunya pilihan kita hanya lari dan jangan sampai terjebak dalam kepungan zombie. Soalnya, tipe 1 paling mematikan kalau mereka bergerombol."
"Sebentar, Cal." Aku mencegatnya.
Kuletakkan jeriken bensin dan membongkar tas Cal. Kukeluarkan semua tali-temali, kain, dan sabuk bawaan kami. Kubuat bakul-bakulan untuk menampung aki dan kedua jeriken minyak, kusambungkan dengan ransel besar berisi pakaian. Kupasang semuanya ke badan Joo. Kalau pun si zombie tersinggung dijadikan gantungan tas, dia tak menunjukkannya.
"Ide bagus." Cal berdecak lega setelah bawaannya jadi lebih ringan. "Dia tidak akan diincar zombie, dan selama ikatannya kuat, semua barang ini akan terus menempel ke badannya."
Kusandang ranselku sendiri dan tas selempang yang berisi kotak P3K. Kukuatkan diriku dan berusaha untuk tidak memikirkan rasa dingin di kaki. Aku gugup, takut, cemas, pikiranku ke mana-mana, dan rasanya makin sulit bernapas. Udara berbau amis dan busuk karena orang-orang di area ini membuang sampah mereka dekat batas jalan tol.
Andai bisa, aku ingin kembali ke dalam mobil sedan dan mendekam di sana selamanya. Namun, aku tidak bisa membebani Cal lebih dari ini.
Cal berjalan di depan, aku mengikutinya, Joo paling belakang. Emma di punggung Cal terus menatap ke arahku.
"Dindin?" tanya Emma seraya menunjuk sedan yang kami tinggalkan di belakang.
"Dindin?" tanya Cal.
"Mungkin dia menamai mobil sedan itu." Kuusap pipi Emma dengan jari-jari tanganku. "Mobilnya capek, Emma. Biarkan dia istirahat di sana."
"Kita akan cari Dindin baru yang lebih besar dan keren," bujuk Cal. "Kalau ada Jeep atau SUV, bakal bagus sekali."
"MPV bakal lebih bagus untuk bawaan banyak, Cal." Mataku mengerling bawaan Joo. "Aki yang diberikan Kamelia tadi arusnya berapa?"
"Aki kering, bertegangan 1.260 Volt dan kapasitas 35 Ah."
"Kau bisa pasang aki sendiri?"
"Kalau tidak bisa pasang aki, ganti ban, dan menyedot bensin kendaraan lain, aku tidak bisa jadi kurir saat kiamat zombie."
Di sisi pagar seng, Cal menggeser bak sampah dan barang-barang buangan dari tumpukan rongsokan—televisi yang layarnya pecah, alat pemanggang yang pretel, dan kulkas tanpa pintu. Gadis itu memanjat lebih dulu.
Dadaku sakit karena gelisah. Detak jantungku tidak mau memelan. Kami sudah jauh dari ladang ranjau dan belum ada PN yang menyusul, tetapi memikirkan kami akan masuk ke area yang terinfeksi membuat asam lambungku naik.
Lalu, seolah ingin menambah pikiranku, di puncak tumpukan itu Cal mendadak terdiam.
"Cal? Kenapa?"
"Zombienya banyak sekali."
"Tentu saja." Aku mengusap muka dengan frustrasi.
Orang-orang membuang sampah ke sini tiap hari. Para zombie akan berkumpul paling banyak di seberangnya karena tertarik pada suara-suara yang mereka buat.
"Aku akan turun dulu," kata gadis itu enteng. "Dan menarik perhatian mereka ... tunggu. Tapi, adikmu di punggungku ...."
Sekali ini, syukurlah Emma menempel padanya, jadi Cal harus berpikir dua kali kalau mau bertindak bodoh.
Aku menaikkan satu kaki ke atas badan kulkas rongsokan dan menarik lengannya. "Bisa kau lihat plaza tol dari sana?"
"Iya. Hanya ada beberapa zombie di salah satu jalurnya. Jalur yang lain kosong. Tapi kalau mau lewat sana, kita harus memutar sedikit agak jauh, Ilyas. Lagi pula, tidak ada jaminan jalurnya akan kosong dari zombie begitu kita mencoba masuk."
"Kalau begitu, biarkan Joo yang turun lebih dulu lewat sini." Kutarik si zombie untuk mendekat ke tumpukan barang. "Dia bisa berdiri diam dekat pagar dan menarik perhatian para zombie. Jadi, kita bisa masuk lewat plaza tol."
Kukeluarkan mainan bebek karet yang pernah diambil Emma di minimarket, lalu memaksa Joo menggenggamnya kuat. Cal melompat turun dan memperhatikanku yang berusaha mengajari Joo memencet bebek karet.
"Bagaimana kalau nanti dia berhenti memencetnya?" tanya Cal. "Ajari saja di memukul pagar seng."
"Dia mendobrak pintu sedan sampai rusak, Cal. Aku tidak mau ambil risiko kalau tipe 4 ini tanpa sengaja merubuhkan pagar seng. Lagi pula ini bagus untuk melatih motoriknya. Kalau dia akan menggendong Emma untuk seterusnya, dia harus belajar menggunakan fungsi spesifik otot-ototnya."
Joo sebenarnya mampu mencengkram, tetapi membuatnya memencet secara terus-menerus adalah hal lain. Aku menekan jari-jarinya pada bebek karet itu, memperlihatkan padanya apa yang harus dia lakukan. Begitu aku membiarkannya mencoba sendiri, alih-alih memencet, dia malah membuka jari-jarinya dan membuat mainan itu jatuh.
"Pegang yang benar!" Kukembalikan bebek karet ke tangannya. Kupencet jari-jarinya lagi sampai si bebek berbunyi.
Kulepas tangannya perlahan, dan Joo berhasil memencet sendiri dua kali sebelum kemudian jari-jarinya menegang, membiarkan si bebek meluncur lagi ke tanah.
"Joo!"
"Sabar, Ilyas." Cal memungut si bebek lagi, meletakkannya ke tangan Joo, lantas berusaha membuat si zombie meremasnya dengan seluruh jari dan telapak tangan. Itu justru membuat si bebek meloncat keluar sampai Cal naik pitam. "Zombie pe'a!"
Bebek karet itu masuk ke dalam kain bedongan Emma. Adikku mengambilnya dan memencetnya dengan ganas. Gigi-gigi mungilnya menggertak kecil karena gemas pada si bebek. Bunyi beruntunnya membuat pagar seng berkeletuk karena para zombie di baliknya berusaha menerobos kemari.
"Lihat?" Ibu jari Cal menuding Emma di punggungnya. "Lakukan seperti Emma!"
Cal mengembalikan bebek itu ke tangan Joo, yang mendadak mampu memencetnya dengan tiga jari tangannya. Jari manis dan kelingkingnya terangkat.
"Bagus, tetap pencet begitu."
Cal melepaskan tas-tas bawaannya. lalu buru-buru menyeret Joo ke atas tumpukan barang. Aku ikut memanjat naik dan berusaha mengangga Joo dari bawah. Kubiarkan dia menginjak punggungku, sedangkan Cal mengangkat tubuh Joo dengan mengaitkan tangan ke bawah kedua ketiak si zombie.
"Cal, hati-hati." Kupegangi betis gadis itu agar dia tidak ikut meluncur turun melewati pagar seng. "Jatuhkan saja dia!"
"Nanti aki dan jeriken bensinnya ikut jatuh!" Cal mengerang. "Joo harus mendarat berdiri!"
Joo mungkin kurus kering, tetapi bobotnya ditambah oleh bawaan yang terikat ke badannya. Perut Cal pasti tertekan oleh puncak pagar seng karena diberati beban tersebut, tetapi gadis itu memastikan si zombie berdiri di atas kedua kakinya. Perlahan, dia berhasil menurunkan si zombie ke sisi seberang.
Aku ikut naik ke sisi Cal dan mengecek. Zombienya benar-benar banyak—Cal tidak bercanda. Di sisi pagar ini saja, jumlahnya pasti dua lusin.
Dari seberang jalan, ada lima zombie yang berusaha bergerak ke arah kami. Dari balik mobil-mobil yang terbengkalai, bermunculan zombie-zombie yang tidak berkaki, merangkak seperti siput dengan jejak darah sepanjang jalan yang mereka lewati. Zombie-zombie dari arah plaza tol dan arah sebaliknya pun mulai bergerak mengikuti suara bebek karet.
"Angkat tanganmu!" kataku pada Joo. Kuangkat sebelah tanganku sendiri untuk memberi contoh. "Jangan sampai bebek itu lepas—awas! Kenapa kau diam saja disenggol begitu!"
"Joo, tangan!" Cal ikut memerintah dengan gemas. "Angkat ke atas kepala!"
Joo malah mengangkat tangan yang tidak memegangi bebek karet.
"Angkat kedua tanganmu!" perintahku dengan tegang, tetapi Joo disenggol lagi oleh zombie lain sampai badannya terputar membelakangi kami. "Zombie tolol—lihat sini! Lihat kami!"
Kami menghabiskan sepuluh menit hanya untuk mengatur posisi Joo. Dia bahkan sempat berhenti memencet bebek karet itu. Cal sampai harus melempar kerikil ke kepala Joo untuk membuatnya memperhatikan dan kembali memencet si bebek.
Joo akhirnya mampu mempertahankan posisinya. Dia bahkan mengukuhkan tempatnya berdiri—zombie itu bergeming meski disenggol-senggol dan ditabrak kawanan sesama jenisnya.
Aku merosot terduduk di atas televisi rongsokan. Punggungku tersandar ke pagar seng. Lututku makin tidak keruan rasanya. Perutku kosong, tetapi aku ingin muntah. Kutekankan kedua telapak tanganku ke mata.
"Kita bahkan tidak tahu apakah masih ada mobil yang layak jalan di sana. Bagaimana juga caranya kita membebaskan Joo dari kepungan mayat-mayat itu ketika kita sampai di dalam?"
Cal berjongkok di sisiku. Tangannya menepuk-nepuk bahuku pelan. "Keringatmu banyak sekali, Ilyas. Sori, ya, nanti kucoba untuk menyetir lebih manusiawi."
Ingin kukatakan padanya bahwa bukan gaya menyetirnya yang jadi masalah. Yah, pengalaman ngebut tadi memang berkontribusi mengurangi umurku, tetapi saat ini yang paling memenuhi pikiranku adalah masalah gelombang zombie yang mengekori ke mana pun kami pergi. Tidak kusangka kata-kata tidak masuk akal Bu Raiva bakal memengaruhiku sebesar ini.
Belum lagi masalah Randall.
Tadi malam aku terlalu lelah untuk memikirkannya, tetapi kini semuanya mulai meresap. Kusadari, aku tidak punya tujuan lagi. Semua rencanaku berantakan. Aku tidak bisa mengamankan Emma ke keluarga lain yang dicarikan Randall—aku tidak memercayainya lagi.
Sekarang, kami akan memasuki area terinfeksi yang sudah diblokade, hanya karena jalan ini adalah satu-satunya pintu keluar dari Batavia yang paling aman. Sebelum ini, aku setuju karena kupikir kami akan pergi dalam kawalan PN.
Kondisi ini sejujurnya membuatku menyesal. Seharusnya kami tidak pergi keluar. Seharusnya kami tetap diam di dalam rumah. Seharusnya kami tinggal di Renjani. Rumah itu satu-satunya peninggalan Pak Gun dan Bu Miriam—bukti bahwa aku pernah punya keluarga. Semuanya hilang.
Sebagian diriku ingin sekali menyalahkan Cal atas ini semua.
Namun, kemudian aku merasakan tangannya di bahuku. Kehadirannya yang dengan sabar menunggu sampai aku tenang.
Begitu akal sehatku kembali, kusadari betapa tidak adilnya kalau aku menyalahkannya. Toh, hari itu Renjani sudah jatuh. Kami keluar atau tidak, para zombie telah berderap ke sana, dan kemungkinan besar akulah penyebabnya (jika perkataan Bu Raiva benar adanya).
Ketika Cal menyodoriku tisu, barulah aku sadar wajahku basah sampai dagu. Air mata, ingus, ludah pahit, dan keringat dingin menetes-netes tanpa bisa kukendalikan. Aku membungkuk ke samping tumpukan rongsokan dan batuk dengan keras, seolah kerongkonganku sedang berusaha memompa keluar organ dalamku. Namun, sekeras apapun aku berusaha muntah, tidak ada yang keluar selain lendir pahit.
"Di mana yang sakit?" tanya Cal lembut. Tangannya melekat di punggungku. "Kau mau minum dulu?"
Cal mengeluarkan air botolan dari tasnya, membasahi beberapa lembar tisu, dan menyeka keseluruhan area wajahku.
"Omong-omong, Ilyas," kata Cal hingga aku mengangkat wajah, "coba lihat apa yang dilakukan adikmu."
Emma tengah menatapku sambil membelalak, barangkali takut karena suara batuk dan sikapku barusan. Kedua tangannya memeluk kepala Cal dari belakang hingga menutupi pandangan gadis itu sepenuhnya.
"Aku tidak apa-apa, Emma," lirihku seraya mengurai tangannya dari wajah Cal.
Cal menggelengkan kepala untuk mengusir rambut yang menempel ke matanya. "Kau mau duduk dulu?"
"Tidak, kita sudah membuang terlalu banyak waktu." Kuraih beberapa lembar tisu lagi untuk membersihkan mulut dan hidungku yang terasa lembap.
Cal membuka mulutnya ragu-ragu, lalu menutupnya lagi. Namun, kemudian akhirnya bertanya juga, "Apa kau akan lebih tenang kalau minum obatmu sekarang?"
Ide itu menggodaku, tetapi aku menggeleng.
"Obat itu bakal bikin aku mengantuk, Cal."
Cal mengulurkan kedua tangannya dengan telapak menghadap ke atas. "Mau kugendong? Kedua tanganku bebas, nih. Tapi ranselku kau yang bawa."
Kupandangi kedua tangannya, lalu beralih ke wajahnya. Dia tampak serius. Ketulusan di matanya membuatku bingung harus tersinggung atau bersyukur punya teman seperti dirinya.
Kuangkat satu tanganku dan menepuk telapak tangannya yang tertadah.
"Aku tidak ngajak tos, Ilyas."
"Aku juga tidak." Kugenggam salah satu tangannya dan menariknya untuk bergegas. "Ayo, jalan saja."
"Ilyas, salah arah. Jalan masuknya ke sana."
Aku berbalik arah tanpa memandangnya sambil menelan rasa malu, sementara Cal cekikikan di belakangku.

"Keringatmu masih banyak," komentar Cal ketika plaza tol sudah terlihat. "Kau yakin kau tidak apa-apa?"
"Aku cuma capek."
"Suara napasmu mirip orang mau melahirkan ketimbang orang capek."
Aku hampir membentaknya karena jengkel dengan semua pertanyaannya, tetapi mataku menyapu salah satu jalur masuk di plaza tol dan langkahku terhenti. Cal menabrak punggungku karenanya.
"Polisi," gumamku.
"Pantas saja tidak ada yang mengejar atau meringkus kita dari tadi," ringis Cal. Tangannya mencengkramku di siku. "Rupanya ada yang menunggu di sini."
Kami berbalik arah, tetapi sang polisi keburu melihat kami dan akhirnya berlari mengejar. Cal dan aku tidak punya pilihan selain ambil langkah seribu.
Polisi itu sendirian dan jarak kami terpaut jauh, tetapi dia tetap saja polisi—kecepatannya dua kali lipat lariku yang tercepat. Badannya lebih besar dari Randall, lebih tinggi dari Ahmed, mungkin menyaingi mendiang Pak Gun juga. Cal bisa saja selamat, tetapi gadis itu menyamakan laju larinya denganku.
Kemudian, Cal mendadak jatuh. Kedua sikunya menghantam tanah saat melindungi diri dari hempasan. Emma merengek di punggungnya dengan tangan meraih helaian rambut Cal.
"Cal!" Aku bersimpuh di sisinya, berusaha membantunya berdiri. "Ada apa—"
Lalu, aku melihat betisnya.
"Kakiku tidak bisa bergerak!" jerit gadis frustrasi. "Apa yang bajingan itu lakukan?! Aku tidak bisa berdiri!"
Aku mencabut sesuatu yang menyembul dari betis belakangnya. Dilihat dari reaksi Cal, ini bukan penenang atau bius saraf. Mungkin relaksan otot.
Dari jarak sejauh itu ... dan targetnya sedang berlari.
Pemakaian senjata dengan peluru bius dilegalkan sejak runtuhnya Tembok W, tetapi penggunaannya dibatasi hanya untuk melumpuhkan orang yang terinfeksi dan mencoba kabur. Menggunakannya ke korban infeksi yang mematuhi perintah karantina atau warga sipil yang belum dikonfirmasi terinfeksi bisa berakibat pemecatan. Apakah Randall seputus asa ini hanya untuk menangkapku?
Kuangkat tubuh Cal susah payah dan berusaha menggendongnya di punggungku, tetapi si polisi keburu menyusul. Dia menodongkan senjata ke arahku.
Masih dalam posisi bersimpuh, kuangkat kedua tanganku sejajar kepala. Polisi ini tidak mungkin melepaskan peluru aktif di tengah situasi darurat zombie, tetapi tetap ada kemungkinan terburuk. Maka, aku bergeser menjauhi Cal agar, kalau polisi ini memutuskan melepas tembakan, dia tidak akan mengenai gadis itu maupun Emma.
Aku mengangkat sebelah alisku menyelidik saat melihat lambang di seragamnya. Satu melati emas—komisaris polisi. Di atas Inspektur Polisi Aryan. Dinilai dari wajahnya, dia lelah. Matanya merah dan jelas mengantuk.
Artinya, dia bukan petugas yang bertanggung jawab untuk evakuasi, melainkan yang menjaga ladang ranjau semalaman.
Barangkali dia dikirim kemari untuk meneruskan operasi di ladang ranjau begitu Randall dan Ahmed membereskan zombie di jalanan. Ada sedikit percikan darah di seragamnya—itu wajar jika dia sempat membereskan beberapa mayat hidup yang mencoba keluar dari ladang ranjau sebelum ini.
Namun, yang tidak masuk akal bagiku, untuk apa dia menghadang dan mengejar kami sendirian seperti ini?
Mana anak buahnya?
Ahmed pasti salah satu personel dalam pasukannya untuk mengamankan area di sekitar ladang ranjau. Pasti ada beberapa polisi lain juga karena terlalu dekat dengan pemukiman penduduk. Namun, orang ini sendirian di sini.
Aku berusaha mengulur waktu. "Kami tidak terinfeksi."
Barangkali relaksan otot yang mengenai Cal hanya bekerja beberapa menit. Namun, kalau dia lumpuh selama lima belas menit atau lebih, kami celaka. Aku tidak bisa lari membawanya dan Emma sambil dikejar polisi.
Kemungkinan terburuk ... aku harus cari cara menjebol pagar seng. Toh, tempat ini sudah tamat.
"Apakah Randall yang menyuruh Anda membawa kami seperti ini?" tanyaku.
Polisi itu mengeluarkan borgol. "Diam dan ikut saja."
"Kami bukan kriminal! Anda tidak bisa menangkap kami!" Kukibas tangannya yang berusaha menangkap lenganku. "Atas dasar hukum apa kami ditangkap?!"
Polisi itu tetap menekanku ke tanah dan berhasil memiting kedua tanganku ke belakang. Aku memberontak, menanyakan namanya, meminta surat penangkapannya, dan mendesak si polisi untuk memberiku kesempatan menghubungi kuasa hukumku—meski aku tidak punya kuasa hukum.
Putus asa, aku berguling telentang dan mendorongnya dengan kedua tangan, memancingnya untuk memborgolku di sana. Aku jelas tidak bisa menang main fisik dengan makhluk sebesar ini. Cepat atau lambat, dia pasti meringkusku. Jadi pilihan terbaik saat ini adalah membuatnya memborgol kedua tanganku di depan, bukan di belakang.
Setelah memborgolku, dia beralih ke Cal. Gadis itu merangkak sejak tadi dan sudah hampir mengait kaki si polisi, tetapi pria itu berhasil berkelit. Dia menekan tengkuk Cal ke tanah, lalu menyuntikkan sesuatu ke lehernya yang membuat gadis itu melemas.
Mata Cal berputar ke atas dan dia kehilangan kesadaran.
Si polisi melucuti bawaan kami dan melempar semua tas ke bahu jalan. Dia kemudian mengangkat Cal di bahunya, dengan Emma masih tergendong di punggung gadis itu. Lalu, tangan satunya menenteng tubuhku seperti mengangkat kucing di perut.
Tanpa mengacuhkan tangisan Emma, polisi itu berjalan menjauhi plaza tol, melompati trotoar dan memasuki jalan yang lebih kecil. Ada mobil polisi terparkir di sana, dan dia langsung menjejalkan kami ke jok belakang.
Kukira dia akan mengemudikan kami kembali ke jalur evakuasi atau di mana pun itu Randall berada. Namun, si polisi berhenti di pertengahan jalan, di depan gedung serbaguna yang lahan parkir di sampingnya telah berubah menjadi salah satu ladang ranjau untuk menjebak para zombie.
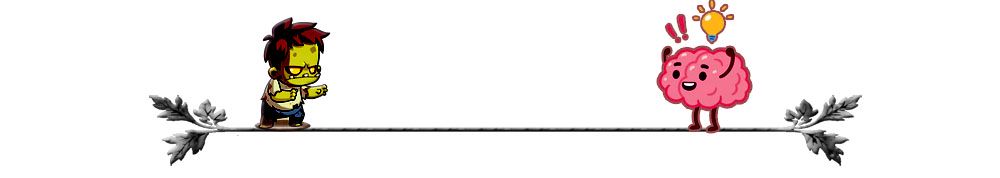
Gedung itu biasanya jadi tempat pameran atau acara amal saat anak-anak panti diundang. Ini juga tempat pertama kali Bu Miriam melihatku.
Meski sudah lama tak digunakan, tempat ini sepertinya masih dirawat. Dinding dan lantainya lumayan bersih, delapan pilar ruang aula masih berdiri kokoh, dan tak ada tanda-tanda keretakan cat atau debu di kaca sama sekali.
Di enam pilar lain, sudah ada enam polisi yang terborgol ke masing-masing pilar. Semuanya tampak teler—barangkali mendapat bius yang serupa dengan Cal.
Ada Ahmed juga di sana, duduk dengan mata terpejam. Kedua tangannya diborgol dengan posisi memeluk pilar.
Si polisi yang menangkapku melemparkan badanku sampai menabrak pilar ketujuh. Dia merogoh saku samping celananya, lalu terdiam.
"Ginna!" Pria itu berteriak ke samping. "Apa kau mengambil kunci borgolku?!"
Dari balik pintu kaca yang mengarah ke lorong toilet, seorang perempuan menjawab, "Sudah kubilang, tidak!"
Aku kenal suaranya.
Lalu, kusadari, aku juga kenal seseorang bernama Ginna.
Meski aku tahu dia anggota PN dan berbasis di Batavia, tetap saja kebetulan semacam ini mengejutkanku.
"Begitu caramu bicara pada atasanmu?!" bentak si polisi.
Ginna dari balik pintu kaca berdecak-decak. "Maaf, Pak Khandra. Tidak, Pak Khandra."
Si polisi—Khandra—kemudian mengambil alih Emma dari punggung Cal. Dilemparkannya Cal yang masih tak sadarkan diri ke arahku sampai dada dan perutku sakit saat berusaha menangkapnya.
"Jangan macam-macam," ancam Khandra seraya mengangkat Emma di kedua tangannya. "Kau mau anak ini hidup, 'kan?"
Tangisan Emma meledak. Hal itu membuat Ginna muncul dari balik pintu dan berderap ke arah kami.
"Yang benar saja!" teriak gadis itu. "Buat apa Anda menyekap bayi?!"
"Sejak kapan kau peduli?"
"Aku bukan peduli pada bayinya!" Gadis itu buru-buru lari ke pintu. Dia baru membukanya sedikit, lantas tampak seseorang berjalan mendekat dari luar. Ginna pun segera menutup pintu masuk dan menguncinya dari dalam. "Ini yang kutakutkan! Ladang ranjau di sebelah itu sudah kehabisan jebakan dan gara-gara Anda kunci pagarnya rusak! Sekarang kita terjebak!"
"Oh, para zombie itu? Mereka lamban dan bodoh." Khandra mengoper adikku ke tangan Ginna. "Tenangkan anak itu."
"Bagaimana denganku? Kau bilang, aku boleh pergi setelah membantumu mengawasi mereka!" Ginna melambai ke arah para polisi yang terborgol. Tangannya yang lain menepuk-nepuk punggung Emma. "Kau setenang ini karena sudah tergigit! Bajingan—hidupku masih panjang! Tidak sepertimu! Bangkotan, duda, orang kasim, digigit zombie—"
Khandra melayangkan bogem mentah ke wajah Ginna. Gadis itu terlempar ke lantai, lalu adikku merosot jatuh hingga tangisannya makin keras.
"Pilar ke delapan," desah Khandra seraya menarik Ginna di rambutnya, "kau yang akan mengisinya."
Sementara si polisi sibuk menahan Ginna ke pilar terakhir menggunakan borgol gadis itu sendiri, aku diam-diam membaringkan Cal, lalu meluncur ke arah Emma.
Aku belum sempat meraih adikku saat Khandra selesai memborgol Ginna dan berderap ke arahku. Si polisi menyepakku di kepala.
Bola mataku bergetar di rongganya. Untuk sesaat, pandanganku gelap. Kurasakan sepakan lain di rusukku, lalu di di perutku, lalu kepalaku lagi.
Saat aku membuka mata, darah dari pelipisku sudah menetes-netes ke lantai. Tangisan Emma kian menjadi.
Khandra menghelaku di kaki. Sambil terseret dalam keadaan telentang di lantai, kutatap langit-langit yang meliuk karena pandanganku mulai berkunang-kunang. Aku hampir kehilangan kesadaran saat Khandra menghempaskan badanku menghantam pilar. Punggungku mati rasa. Lalu, sakitnya datang kemudian, perlahan-lahan, membuatku kesulitan bernapas.
"Jangan banyak tingkah, atau kulempar anak ini keluar." Khandra menuding Emma yang masih menangis sendirian di tengah ruangan. Kugertakkan gigiku murka. Si polisi kembali menyepakku di kepala. "Jangan berani-berani menatapku. Atau kucongkel mata anak itu."
Khandra mengeluarkan sebatang rokok, lantas mendekati Ahmed, hendak mengambil mancis di saku bajunya. Saat itulah Ahmed mendadak membuka mata dan mengangkat sikunya sampai menghantam Khandra tepat di antara kedua matanya. Namun, posisinya tidak menguntungkan—Ahmed hanya membuat Khandra kaget, lalu kesal. Tidak ada luka atau cedera berarti di sana. Tindakannya hanya membuat Khandra geram dan menendangi Ahmed yang masih terborgol ke pilar.
Khandra akhirnya mengambil mancis Ahmed dan duduk bersila di tengah ruangan sambil menyalakan rokoknya. Tangan kotornya menarik Emma dan mendudukkan adikku di sisinya.
"Aku punya keponakan perempuan. Lebih kecil dari anak ini." Khandra mendadak berkata. Tangannya menepuk-nepuk kepala Emma sampai tangisan adikku memelan. "Kalau aku tidak pulang, dia dan ibunya bakal mati kelaparan. Kalian mengerti, 'kan? Jadi, anggap saja kalian menolong pria tua ini melanjutkan tanggung jawab untuk keluarganya."
"Baru sembilan orang," kata Ginna tiba-tiba. Dia meludahkan darah ke lantai lalu tertawa. "Kau bilang kau butuh setidaknya sepuluh orang. Sekarang kau tidak bisa keluar untuk mencari yang ke sepuluh."
"Enam." Khandra menunjuk para polisi yang terborgol di pilar-pilar, lalu menuding Ginna. "Tujuh." Secara berurutan, dia menunjuk Cal yang masih tak sadarkan diri, aku, dan Emma di sisinya. "Delapan, sembilan, sepuluh."
Ginna terdiam sebentar, lalu menggertakkan giginya dengan jijik. "Kau bercanda. Setelah berkata kau punya keponakan seumurannya, kau berencana membunuhnya?"
Khandra tertawa kecil. "Kau membantuku membawa para manusia sehat untuk kumakan otaknya. Tapi garis moralmu kau tarik di sana—karena aku berencana memakan anak kecil? Kau yang bercanda, Ginna. Pembunuhan tetap pembunuhan, entah korbannya tua atau muda."
"Anak itu—" Ahmed menunjukku dari balik pilar. "Kesayangan Pak Randall Duma. Anda pikir kenapa Kepala Polisi datang jauh-jauh ke sudut ibukota begini? Dia berusaha menjemput anak itu. Kalau dia mati—"
"Siapa yang akan memberi tahunya?" Khandra berucap acuh-tak-acuh, lantas mengembuskan asap rokok dari hidungnya. "Kau? Apa yang bisa kau lakukan saat tempurung kepalamu kosong nanti?"
Ahmed kelihatannya kehabisan kata-kata. Aku tidak menyalahkannya. Barangkali dia baru benar-benar menyadari apa yang tengah Khandra lakukan saat ini.
"Anda masih manusia," ujar Ahmed tak percaya. "Dan Anda sudah menyiapkan diri untuk makan otak orang lain?"
Khandra tertawa lagi. Dia menjentikkan abu rokoknya sampai jatuh ke lantai.
"Memakan otak adalah cara mengembalikan zombie jadi manusia." Ginna buka suara. Matanya mengamati Khandra tajam. "Sepertinya yang tahu ini hanya beberapa orang di kepolisian, para menteri, dan orang-orang tertentu yang terkait."
"Pak Presiden dan anggota lembaga riset juga tahu." Khandra memberi tahu sambil terkekeh-kekeh. "Sebetulnya aku tidak diberi tahu karena jabatanku. Aku tahu karena aku pernah ada di posisimu, Ginna. Aku melihat atasanku tergigit, lalu aku membantunya. Dia memberi tahu hal-hal yang hanya diketahui segelintir orang di Nusa sebelum berubah jadi zombie. Sebagai gantinya, aku bawakan dia otak manusia yang masih sehat. Tujuh otak utuh, dan mendadak dia bisa membebaskan diri dari belenggu besi yang merantainya selama dua puluh hari, seolah-olah dia mendapatkan kekuatan super entah dari mana. Meski kelihatannya dia hampir sembuh, dia masih zombie saat itu, dan dia mencoba menyerangku. Jadi, aku menghabisinya."
Aku mengernyit. Atasan yang dia bicarakan itu barangkali naik ke tipe 4 begitu memakan otak ketujuh, mungkin seperti zombie berkulit hijau yang dulu masuk ke rumahku saat mengikuti Cal. Bahkan Joo saja belum utuh sebagai manusia sehat, tetapi setidaknya Joo tidak lagi berinsting predator dan sudah berhenti memakan otak. Artinya tujuh otak utuh belum cukup untuk mengubah zombie jadi manusia. Karenanya Khandra mengumpulkan sepuluh orang, berharap itu cukup.
Khandra mengembuskan napas berasapnya, lalu tersenyum. "Kau sama saja, Ginna. Kalau sepuluh otak tidak cukup dan aku masih zombie, kau akan mengkhianatiku juga. Mending kau jadi makanan. Malah—" Khandra berjalan ke arah Ginna. "Aku tahu kau yang mencuri kunci borgolku. Aku tahu kau berencana membuka borgol yang lainnya begitu aku lengah. Kau menunggu teman-temanmu sadarkan diri agar mereka bisa mengeroyokku."
Khandra berjongkok di hadapan gadis itu dan melepaskan sepatu Ginna, di mana sesuatu berdenting keluar.
Kunci borgol.
"Kalian punya 5 jam lebih sebelum aku berubah," kata Khandra seraya menjentikkan abu rokoknya ke rambut Ginna. Dia mengambil kunci, semua borgol, sisa senjata yang disimpan oleh anak buahnya. "Gunakan sisa waktu itu untuk bersantai. Aku akan cari makan sebentar—mumpung lidahku masih menikmati makanan manusia."
Khandra mengeluarkan kunci mobil dan melenggang ke pintu. Dia membuka kuncinya, menarik daun pintu, dan memukul zombie pertama yang mencoba masuk.
"Mau apa kau?" Khandra menahan wajah si zombie dengan tangannya tanpa ragu karena dia sendiri sudah tergigit. "Mereka punyaku! Buru sendiri makananmu!"
Pria itu keluar dan menutup pintu kembali, meninggalkan kami terkurung di dalam sini.
Aku mengerjap-ngerjap dan berusaha untuk bangun, tetapi kepalaku seperti berputar. Aku mencoba duduk, tetapi seisi ruangan ikut berputar, membuatku jatuh lagi.
"Emma—"
Lalu, kusadari adikku tengah menyeberangi ruangan ... berjalan ke arahku.
Emma. Berjalan. Ke arahku.
Kakinya bergerak canggung, tetapi dia berdiri. Kedua tangannya terarah padaku. Wajahnya merah dan dagunya belepotan ingus. Bulu matanya basah. Sesekali dia cegukan dan terisak kecil, lalu jatuh di atas pantatnya. Namun, adikku bangun kembali dengan susah payah, dan lanjut berjalan.
Melihat itu semua, aku mampu mengabaikan rasa sakit luar biasa di kepala dan sekujur tubuhku. Kuangkat badanku ke posisi duduk. Kusandarkan badanku ke pilar agar aku tidak jatuh lagi. Kedua tanganku yang terborgol terulur dan menyambutnya saat Emma menjatuhkan diri ke pangkuanku. Jari-jari tangannya yang mungil mencengkram lengan mantelku.
Sudut bibirku terangkat dan suara cekikikan bahagia lolos dari mulutku.
"Apa tendangan tadi membuat otakmu bergeser agak terlalu ke kanan?" tanya Ahmed sinis. Namun, bodo amat.
Adikku akhirnya bisa berjalan.
Kukira hari ini tidak akan pernah datang. Sebenarnya aku sudah siap menerima kenyataan jika Emma takkan pernah bisa berjalan atau tidak lancar bicara. Sejak dokter kandungannya memberi tahu Bu Miriam bahwa dirinya terlalu tua untuk hamil dan persalinannya berisiko, lalu hilangnya Pak Gun menambah pukulan pada wanita itu di masa kehamilannya, juga betapa lemahnya tubuh Emma sejak dia lahir prematur ... aku benar-benar siap menerima kondisi Emma apa pun yang terjadi.
"Mungkin Cal benar," bisikku seraya membawa Emma ke pelukanku. Kuciumi puncak kepalanya bertubi-tubi. "Aku terlalu memanjakanmu—menggendongmu ke mana-mana. Harusnya aku membawamu jalan kaki sejak dulu."
Tidak pernah kusangka hanya dengan melihatnya berjalan seperti ini seketika melenyapkan rasa sakit di tubuhku. Kepalaku terasa lebih ringan sampai rasanya aku ingin melompat.
"Cal," panggilku, tetapi gadis itu masih tidur. Kutepuk-tepuk pipinya, memaksanya bangun. Dia harus melihat ini. "Cal. Cattleya. Cal—bangun."
"Hm, hmm ...." Cal menggumam, tetapi masih menolak membuka mata.
"Dia baru kena bius, berapa—20 menit?" Ahmed berujar lagi. "Tunggu 10 menit lagi. Yang dia dapat hanya dosis sisa, jadi harusnya dia akan sadar sebentar lagi."
"Kau punya air minum?" tanyaku seraya merogoh saku celana susah payah. "Atau sesuatu untuk mengeluarkan bius ini dari badan? Kalian membawa-bawa bius dan relaksan otot. Mustahil kalian tidak menyiapkan antidote-nya."
Lalu, aku menemukan yang kucari di saku mantelku. Aku masih menyimpan jepit rambut Rani—anak perempuan dari kompleks apartemen yang diselamatkan Cal—yang sebelum ini kugunakan untuk membongkar kunci apartemen lain.
"Semuanya di dalam mobil Pak Khandra ... apa yang kau lakukan?" Ahmed mengernyit saat aku menggigit ujung tumpul jepit rambut milik Rani dan membentuknya jadi huruf L bengkok. Alisnya terangkat saat melihatku memakai jepit rambut tersebut untuk membuka borgol di satu tanganku, lalu yang sebelah lagi.
"Ada antidote dan suntikan kafein yang kucuri dari mobilnya," kata Ginna mendadak. Kepalanya mengangguk ke arah pintu kaca menuju lorong toilet dan ruang ganti. "Kusembunyikan di sana. Tapi hanya cukup untuk tiga orang. Ahmed juga bakal membutuhkannya meski dia sudah bangun—dia harus dalam keadaan prima karena hanya dia yang badan bongsornya hampir setara dengan Pak Khandra."
"Oke," kataku seraya beranjak ke pintu itu, mengabaikan omelan Ahmed agar aku membukakan borgolnya lebih dulu.
Aku mengambil tas besar yang disembunyikan Ginna dalam bilik toilet perempuan. Di dalamnya tak hanya antidote dan suntikan kafein, tetapi juga satu pak peluru bius lain, beberapa ampul sedatif, 5 botol air minum kemasan, dan protein bar.
Kuambil pak amunisi dan pistolnya, kusimpan ke dalam saku mantelku. Untuk saat ini kami memang bekerja sama. Namun, kalau terjadi sesuatu yang membuat mereka berpaling melawan kami, Ginna atau polisi lainnya tidak boleh memiliki ini di tangan mereka.
Aku mengecek setiap sudut dan menyusuri loker-loker di ruang ganti. Salah satunya tidak terkunci. Di dalamnya, ada baton, pistol, belati, dan dua pak amunisi berisi peluru tajam. Ginna tidak berkata apa-apa tentang ini. Artinya dia berusaha menyembunyikannya dari kami. Aku pun mengambil semuanya.
Melihatku keluar dengan semua senjata rahasianya, Ginna tampak tercengang, tetapi tidak mengatakan apa. Namun, akhirnya dia dan Ahmed mengomel juga saat aku mendekati Cal lebih dulu dan menyuntikkan antidote ke gadis itu.
Ginna mendadak berucap, "Hei, apa aku mengenalmu? Suaramu ... kayaknya aku kenal."
Aku mengabaikannya dan mengangkat tubuh Cal, kemudian menyandarkannya ke dinding. Kepalanya terangguk-angguk. Dia masih butuh beberapa menit untuk sadar sepenuhnya. Kuletakkan baton dan senjata lainnya milik Ginna di sisi Cal. Dia akan membutuhkannya karena semua senjata miliknya sudah diambil oleh Khandra.
Sementara menunggu Cal bangun, aku mengunci pintu keluar, lalu membuat barikade dengan gagang pel dan ember-ember dari ruang cleaning service.
Emma mengekoriku seperti anak ayam karena, begitu mengambil langkah pertamanya barusan, sepertinya tak ada lagi yang diinginkannya selain jalan kaki seumur hidup. Sesekali dia terjatuh, membuatku nyaris panik, tetapi anak itu akhirnya bangun sendiri dan lanjut berjalan menyisir sisi ruangan, berpegangan ke dinding. Saat aku mendorong benda-benda untuk menambah barikade, Emma mendorong kakiku seperti hendak membantu.
"Buat apa kau menahan pintunya?" tanya Ginna. "Pak Khandra bisa mendobraknya dari luar dengan mudah."
"Dia tidak akan mau zombie-zombie di luar masuk dan merebut makanannya," kataku. "Terlebih, dia sendiri sepertinya belum yakin jumlah pasti otak yang harus dikonsumsi untuk berubah jadi manusia lagi. Dia akan berpikir dua kali untuk menjebol pintu ini karena itu artinya dia harus berkompetisi dengan para zombie di luar untuk memakan kita."
"Kalau begitu, dia tinggal membereskan para zombie di luar," tukas Ginna. "Dia sudah tergigit dan dia tidak takut apa pun saat ini. Jumlah zombie yang keluar dari ladang ranjau juga tidak sebanyak itu. Begitu dia menghabisi semuanya, dia bisa mendobrak pintu itu."
"Tapi itu akan memberi kita waktu, setidaknya sampai teman-teman kalian sadarkan diri," kataku. Kucari-cari ke sekitar ruangan sesuatu untuk menambah barikade. "Kalau beruntung, dia akan kehabisan lima jamnya di luar sana."
"Lepaskan borgolku," kata Ahmed, "dan kau duduk saja sementara aku menggeser loker-loker itu ke pintu."
Aku mengembus napas berat sambil berkacak pinggang mengamati barikade di pintu. Sejak tadi, aku hanya mendorong satu loker. Itu saja membuat otot-otot lenganku panas. Cal sudah membuka matanya, tetapi gadis itu masih lemas dan kelihatan belum nyambung. Yah, kurasa Ahmed bisa berguna.
"Bagaimana denganku?" tanya Ginna sementara aku membukakan borgol Ahmed. "Aku juga bisa membantu membuat barikade—"
"Jangan." Ahmed menggeleng sementara aku menyuntikan kafein padanya. "Wanita itu bisa mengkhianati kita lagi."
"Aku tadinya berusaha membebaskan kalian, tahu?" cecar Ginna. "Tapi aku harus menunggu kalian semua bangun! Karena sia-sia saja kalau kalian bebas dalam keadaan semaput dan Pak Khandra belum dilumpuhkan! Lagi pula, berkat aku kita punya antidote dan air minum!"
Sementara Ahmed menggeser loker-loker ke pintu sambil dibuntuti Emma, aku mendekati Ginna dan bersimpuh di depannya sambil menjaga jarak. "Kunci kendaraan yang kau simpan," kataku, "berikan padaku."
"Kunci apa—"
"Kau menyimpan kunci kendaraaan di suatu tempat di badanmu," kataku. "Berikan itu, dan akan kubuka borgolmu."
Ginna memutar bola matanya. "Aku tidak menyimpan yang seperti itu."
"Aku mendengar bunyinya saat kau dipukul Khandra. Polisi itu pasti sempat mendengarnya juga. Tapi saat dia membuka sepatumu, hanya ada satu kunci borgol. Polisi itu mungkin tidak sadar, tapi aku tahu bunyi dentingnya berbeda. Artinya ada kunci lain. Kau juga berencana kabur setelah membebaskan teman-temanmu, berharap mereka bisa mengatasi Khandra untukmu. Artinya kau sudah menyiapkan sesuatu untuk pergi dari sini."
Ginna tersenyum miring. "Hei, sekarang aku ingat. Kau Ilyas, ya? Yang dari komunitas radio—"
"Kunci." Aku bersikeras.
"Kau bohong, ya, tentang umurmu? Seingatku kau pura-pura jadi pria yang lebih tua dari ini, ternyata kau masih anak-anak. 16? 17?"
"Kau mau borgolmu kubuka atau tidak?"
Ginna menelengkan kepalanya. Masih tersenyum licik, dia memajukan badannya sedikit. "Ambil, nih, kalau berani. Di dalam bajuku."
Gigiku mengatup rapat. Mataku memandangi seragam atasannya dan sempat mempertimbangkan untuk benar-benar mengambilnya sendiri.
Lalu aku berdiri. Lebih baik aku tunggu Cal bangun, biar dia yang mengambilnya nanti.
"Eh, tunggu!" Ginna berteriak melihatku beranjak. "Aku bercanda! Bukakan borgolku, aku akan langsung memberimu kuncinya! Hei!"
Aku membukakan sebelah borgolnya. Setelah Ginna memberikan kunci mobilnya yang dia bilang tersembunyi di gang samping, aku membukakan borgolnya yang sebelah lagi.
Lalu, perempuan tolol itu menyerbu dan menduduki perutku. Satu tangannya memiting tanganku yang memegang kuncinya.
"Makasih," ucapnya seraya mengantongi kembali kunci mobilnya. "Kau bisa ambil senjata dan semua antidote bodoh itu. Tapi kau tidak bisa mengambil kendaraanku. Paham, Ilyas?"
Aku mendorongnya dari atasku, yang mana tidak perlu karena Ginna bangun sendiri sambil terbahak. Dia mengambil salah satu gagang pel, mematahkannya sampai ujungnya meruncing—dan begitulah Ginna mendapat senjata kembali meski aku mengambil semua pistol dan belatinya. Namun, dia tetap ikut membantu Ahmed mendorong loker-loker ke pintu.
Lalu, kusadari Ahmed sudah tidak mendorong loker dan malah merokok. Emma di sampingnya, sedang menepuk-nepuk salah satu loker dengan kedua tangannya. Ahmed berjongkok menatap adikku sambil berkata, "Dorong yang benar."
Kukeluarkan pistol bius dari dalam mantelku dan menempelkan moncongnya ke leher Ahmed. Tanganku yang lain memegangi borgolnya. "Kau mau kembali ke pilar?"
Ahmed memutar bola matanya, lalu kembali mendorong loker dengan rokok terapit di giginya.
Kuraih tangan Emma dan mengarahkannya ke sudut untuk menjauhi pintu. Aku mengecek jumlah peluru dan tengah mempertimbangkan mana yang harus kutembak duluan, Ginna Ahmed, tetapi suara Cal mengejutkanku.
"Ilyas!" jerit Cal. "Ilyas, adikmu berdiri!"
Aku menoleh dan melihat Cal sudah duduk tegak. Di depannya, Emma melepas pegangan dari pilar, lalu berdiri sempoyongan, dan melangkah ke arah gadis itu.
"Ilyas! Adikmu jalan!"
"Cal!" Aku berlari menghampirinya sambil menyengir. "Iya, Emma bisa jalan!"
Cal menatapku dan matanya membelalak. Barulah aku teringat dahi dan wajahku sempat berdarah setelah disepak Khandra sebelum ini.
"Ilyas, kau nyungsep di mana?"
Aku menceritakan secara singkat apa yang terjadi. Cal mendengarkanku sembari memeluk baton polisi yang tadi kutinggalkan di samping tubuhnya. Alisnya mengernyit dan dia tampak sedih luar biasa ketika mendengar pentungan miliknya diambil Khandra.
Ketika aku hampir selesai bercerita, kusadari Ginna mendekati kami. Alisnya mengernyit dan matanya memicing mengamati Cal. Perempuan itu pun membelalak. "Cal?"
Cal mengangkat wajahnya. Matanya disaput rasa tak percaya. "Ginna—itu kau?"
"Cal!" Ginna berjalan cepat ke arah Cal.
Cal langsung berdiri dan melakukan hal yang sama. "Ginna!"
Lalu, keduanya sama-sama mengayunkan senjata di tangan masing-masing—baton polisi milik Ginna di tangan Cal beradu dengan tongkat pel yang meruncing di tangan Ginna—dan mencoba melibas kepala satu sama lain.

Friendly reminder 1: Ginna pernah tinggal satu atap sama Cal dan ibunya Cal di rumah susun habis dievakuasi dari kampung mereka. Ginna juga pernah jadi temen ngomong Ilyas pas radio Ilyas masih ada.
Friendly reminder 2: selama kekacauan ini terjadi, Joo masih mencetin bebek karet di jalan tol.
ヾ(*゚ー゚*)ノ Thanks for reading
Secuil jejak Anda means a lot
Vote, comment, kritik & saran = support = penulis semangat = cerita lancar berjalan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro