Ch. 8: Bersama Mereka
N E W C H A P T E R
Wordcount: 1.427 words

Bel pulang sekolah berbunyi. Aku langsung menoleh ke samping, menatap Aiden yang masih sibuk membereskan barang-barang.
Kelopak mataku terasa berat. Kurang lebih hanya tiga jam aku tidur, membuat tubuhku seperti akan hancur berkeping-keping kalau disenggol. Namun, ketidaksabaran ini masih tersangkut dalam diriku.
Aku ingin membahas hal-hal yang berkaitan dengan rencana itu. Sayangnya dari tadi, baik Aiden maupun Erna, mereka terus menyuruhku untuk bersabar. Kurasa itu bukan hal yang bisa dibicarakan di sekolah.
Mau tidak mau aku harus menunggu. Sudah belasan cara kucoba agar Aiden memulai pembahasannya, tetapi tidak satu pun berhasil. Jangankan berhasil, membuatnya goyah sedikit saja tidak bisa. Kalau Erna, dia selalu menghindar tiap aku hendak bertanya.
"Julian masih harus bersih-bersih." Erna datang menghampiri, sudah memikul ransel. "Kalian tungguin, ya. Aku mau balik duluan. Dia gak punya HP buat nelpon atau nge-chat."
Belum sempat aku atau Aiden iyakan, cewek itu sudah menghilang. Ya sudahlah. Kami pun beranjak menunggu di depan kelas bobrok ini. Selain takut mengganggu mereka bersih-bersih, aku masih kurang nyaman berada di dekat Julian.
Aku dan Aiden tidak banyak mengobrol selagi menunggu. Masing-masing sibuk dengan ponsel. Bunyi meja digeser, kayu beradu, juga seruan yang kukenali adalah suara Julian menjadi musik tunggu.
Walau bosan dengan berbagai respons datar saat aku berusaha memulai pembicaraan, tetap kucoba lagi mumpung sekitar sudah sepi. Hanya petugas kebersihan di dalam kelas kami yang berisik.
"Jadi ... kita berangkatnya besok?"
Aiden masih sibuk dengan ponselnya. Dia hanya merespons dengan gumaman singkat. Itu kode kalau dia tidak mau membicarakan itu di sini. Semangat pantang menyerahku langsung lenyap.
Tidak lagi aku mencoba mengangkat topik itu, bahkan setelah Julian selesai dengan tugas piketnya. Dia keluar dengan atasan kaus oblong warna hitam. Bawahannya masih celana seragam abu-abu. Kemeja seragam putih tersampir di bahu bersama tali ransel.
Julian menatapku heran sebentar, kemudian beralih menatap Aiden dengan malas. "Erna mana? Kita balik jalan kaki?"
Tanpa menjawab pertanyaan Julian, Aiden menarikku berjalan menuju gerbang depan. Tadi dia bilang, kontrakan mereka lebih dekat kalau lewat gerbang depan. Artinya, anak ini bohong soal melihatku keluar dari lorong kemarin, juga soal rumah kami yang searah.
Meski sambil mengumpat, Julian mengekor. Tidak sulit baginya untuk menyusul dengan sepasang kaki panjang itu. Dia bahkan mendahului kami menuju gerbang, membuat jarak yang cukup lebar.
Setibanya kami di luar gerbang, aku melepas pegangan Aiden. "Apaan sih, pegang-pegang."
Aiden menatapku dengan kepala sedikit ditelengkan. "Kalau nggak suka, kenapa nggak lepas dari tadi?"
Aku tidak menjawab, justru membuang muka. Perjalanan menuju jalan raya diselimuti kecanggungan. Ingin mengobrol supaya canggungnya hilang, aku malu karena yang barusan. Ditambah dengan adanya Julian di sini. Aku sama sekali tidak menyukai cowok itu.
Setelah mengusir rasa malu dan memberanikan diri untuk buka mulut, perasaan buruk lain menghampiri. Isi perutku seperti terlilit dan napasku sempat tercekat.
Kami sedang menunggu waktu yang aman untuk menyeberangi jalan raya. Lama-lama berdiri di sini sambil menatap kendaraan berlalu mengingatkanku pada kejadian itu. Suara para petugas yang sibuk menjalankan tugas mereka serta bunyi sirine ambulans terputar dalam kepala.
Tidak kusadari, tanganku sudah terulur ke samping, mencengkeram lengan seragam Aiden. Selain isi perut terpelintir, kepalaku mulai pusing. Pandanganku juga mulai dipenuhi kunang-kunang.
Aiden dan Julian sontak menatapku heran. Lima detik berlalu, Julian tak kunjung peka. Untung Aiden berbanding terbalik dengannya. Ia segera menuntunku menjauhi jalan raya.
Setelah berada pada jarak aman, Aiden menyuruhku duduk di atas susunan bata pendek. Ia pun merogoh saku celana, lantas mengeluarkan ponsel. Sambil menekan-nekan layar dia berkata, "Sori, harusnya tadi aku langsung telpon Erna."
Julian yang masih tidak peka datang menghampiri dengan langkah santai. Ia mengamatiku dalam diam, berusaha memahami apa yang terjadi. Aku terlalu sibuk menjaga diri ini tetap bernapas untuk sekadar menegurnya.
Ponsel Aiden berbunyi. Dia hendak mengirimkan pesan suara. "Er, bisa jemput kami? Ini lagi di pinggir jalan besar, gak bisa nyebrang." Bunyi yang sama kembali terdengar, menandakan Aiden sudah selesai dengan pesan suaranya.
Tak sampai sepuluh detik, Erna muncul di hadapan kami. Dia menatapku cemas sebelum meraih tanganku dan Aiden. Beralih menatap Julian, ia berkata, "Aku baru bisa bawa dua orang sekarang. Kau pulang sendiri, ya."
Sejurus kemudian, Erna berteleportasi tanpa mengindahkan kata-kata mutiara dari Julian. Kami muncul di ruang tengah kontrakan mereka.
Erna menuntunku duduk di sofa. "Aiden, ambilin air anget sana." Setelah aku duduk dengan nyaman, ia melepas pegangan lalu berucap, "Aku mau jemput Julian dulu."
"Loh? Bukannya barusan disuruh pulang sendiri?" Dari dapur, Aiden menanyakan hal yang ingin kutanyakan.
"Canda doang tadi." Erna memasang senyum jenaka. "Lagian aku mau ke minimarket dekat situ. Sekalian aja." Setelah berkata demikian, Erna menghilang dari hadapanku.
Rasanya sudah sedikit membaik, tetapi badanku masih lemas. Kakiku juga masih gemetar. Berulang kali aku melafalkan mantra dalam hati.
Kami baik-baik aja. Nggak ada tabrakan. Nggak ada ambulans. Luka di badanku nggak bertambah.
Aiden kembali dari dapur membawa segelas air. Dia memberikannya padaku, lalu duduk di samping. "Sori lagi. Aku gak tahu kamu ... bisa sampai segitunya. Harusnya aku sadar lebih cepat."
Setelah meneguk air hangat yang diberinya sampai habis, aku malah merenung. Seburuk itukah kelihatannya? Ya, rasanya juga sangat buruk.
Aku malah tertawa kecil, memaksakannya. "Kupikir aku bakal mati karna habis napas tadi."
"Hei." Aiden mengambil alih gelas kosong di tanganku. "Jangan mati dulu. Adikmu masih nunggu buat diselametin."
"Aku tahu, cuma kadang rasanya gitu. Pengen mati aja." Aku terdiam sejenak. Begitu sadar ucapanmu mengundang kecanggungan, segera aku menambahkan, "Tapi gak beneran pengen kok."
Giliran Aiden yang tertawa kecil. "Emang gitu, kan? Aku juga pernah ngerasain," ucapnya terus beranjak ke dapur. Baru tiga langkah ke sana, ia berhenti sejenak dan menoleh. "Mau nambah air anget lagi?"
"Nggak." Aku menggeleng sementara dia lanjut melangkah.
Lumayan lama Erna pergi ke minimarket sekaligus menjemput Julian. Habis dari dapur, sempat-sempatnya Aiden memimpin tur rumah. Katanya, orang tua Julian yang membayar uang sewa dan segala macam tagihan. Mereka bertiga dapat uang jajan dari orang tua masing-masing.
Rumah yang disewa ini tidak begitu besar. Hanya rumah sederhana satu lantai dengan dua kamar, satu toilet sekaligus kamar mandi, ruang tamu, dan dapur. Karena hanya ada dua kamar, Aiden dan Julian harus berbagi sementara Erna mendapat kamar sendiri.
"Ngomong-ngomong, orang tua Erna nggak masalah dia tinggal bareng dua cowok?" tanyaku penasaran. Aku pernah menanyakan ini pada Erna, tetapi cewek itu punya seribu cara untuk menghindar.
Aiden terdiam sejenak, mengalihkan pandangannya dariku. "Erna itu anak yatim piatu," jawabnya dengan suara pelan seperti di telepon semalam. Menjeda sebentar, Aiden melanjutkan, "Orang tua Julian mengadopsinya sebelum para peneliti gila mengambil anak-anak Eccentric dari panti asuhan."
Seketika atmosfer ruangan menjadi berat. Aku enggan bicara. Aiden pun memilih untuk diam, barangkali merasa sudah bicara terlalu banyak.
Atmosfer ruangan tak kunjung membaik, justru memburuk karena kami mendengar pintu depan diketuk. Sontak aku dan Aiden saling tatap, sadar bahwa siapa pun yang mengetuk bukanlah Erna ataupun Julian.
Aiden sebagai tuan rumah bangkit berdiri. Aku ikut berdiri, tetapi Aiden segera mengulurkan tangan guna menghalangiku. Aku menurut saja. Kalau dia sudah siaga seperti ini, artinya ketukan di pintu depan rumah ini bukanlah hal baik.
Sesampainya di depan pintu, Aiden mengintip melalui lubang kecil. Kulihat otot tubuhnya melemas. Tanpa menunggu lama, pintu langsung ia buka. "Lain kali jangan ketuk doang. Manggil kek!"
Rupanya yang mengetuk pintu adalah Marlo yang menjabat sebagai ketua kelas. Pandangan kami bertemu setelah dia meminta maaf pada Aiden.
Napas lega kuembuskan. "Hai, Ketua Kelas," sapaku seraya mengambil langkah mendekati mereka. "Ngapain ke sini?" Aku tersenyum, tidak ingin ada lagi yang melihatku dalam keadaan menyedihkan.
Terlihat jelas Marlo salah tingkah. "Hei, ya ... kamu ngapain di sini? Eh, nggak. Aku udah dikasih tahu, kok."
Aku memasang wajah cemberut lantas mengungkapkan isi hati. "Canggung banget. Kita kan udah temenan."
Mendengar itu, Marlo justru gelagapan. Beberapa kali dia melirik ke belakang, barangkali berpikir lebih baik kalau dia pergi saja.
Aiden terkekeh melihat temannya itu. Hebat sekali dia bisa berubah ceria dalam sekejap. "Marlo memang suka salah tingkah kalau bicara sama cewek," ucapnya sambil mengibas-ngibaskan tangan.
Saat Aiden selaku tuan rumah mempersilakan Marlo masuk, dua orang yang kami tunggu-tunggu akhirnya muncul. Mereka muncul tepat di atas sofa. Erna memakai sandal, sedangkan Julian masih memakai sepatu.
"Ups, kayaknya aku sedikit meleset," ucap Erna terus melompat turun. Julian melakukan hal yang sama, kemudian beranjak membawa dua kantong plastik besar yang dipegangnya ke dapur. Melihat wajah kesalnya, kurasa dia sedang badmood.
"Ah, dia kan badmood setiap saat."
Tunggu. Aku keceplosan!
Di tengah kepanikanku, Aiden terbahak-bahak sementara Marlo menahan tawa.
Dari dapur Julian berteriak, "Ngapain kalian ketawa, hah?!"
Bukannya berhenti, tawa Aiden justru makin keras. Bahkan Marlo sampai kelepasan tertawa. Aku sebagai biang kerok hanya tertawa kecil sambil menutup pintu. Tidak mau ketinggalan, Erna ikut tertawa. Sepertinya dia senang mengejek Julian.
Suasana terus berubah dalam jangka waktu singkat tiap aku bersama mereka. Mungkin ini pertanda baik.
.
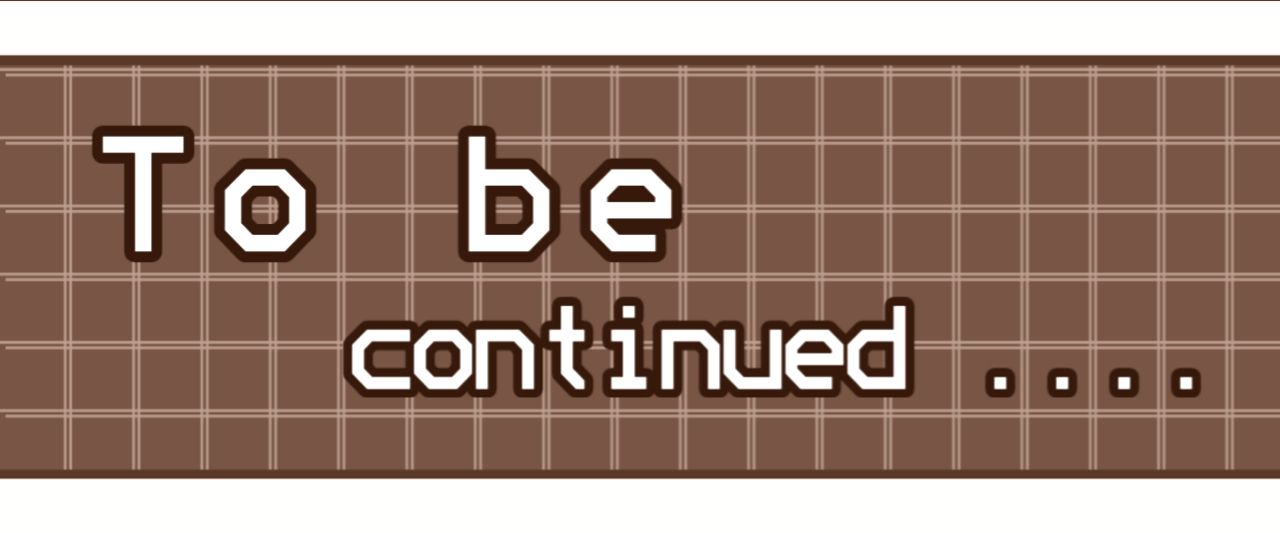
.
.
Clou's corner:
Gimana menurut kalian? Pertanda baik atau malah tanda datangnya tragedi?
Dua-duanya keknya asik deh
17-08-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro