Ch. 41: Kecamuk dalam Hati
Wordcount: 1.937 words

Sehari setelah hari yang gila itu, aku masih berleha-leha di kamar yang sekarang mereka sebut unit pemulihan. Orang-orang yang kumaksud adalah Natha dan Tia. Mereka cepat sekali akrab, padahal belum dua puluh empat jam Tia tinggal di sini.
Julian sudah kembali ke kamarnya sejak pagi tadi, sedangkan Aiden masih meringkuk di atas kasurnya. Kelihatannya suasana hati mereka berdua sedang buruk. Aku bahkan bisa merasakan aura suram menguar dari mereka. Pagi tadi kami sarapan di atas kasur dalam diam sebelum Julian pergi. Tidak ada yang memulai percakapan sampai detik ini.
Mari kesampingkan Julian yang memang tidak pernah kelihatan bersahabat. Aiden yang biasanya banyak bicara dan murah senyum kini bertingkah sebaliknya. Dia berbaring di kasurnya, membungkus diri dengan selimut, dan memunggungiku.
Awalnya aku sedikit kesal. Kalau dia tidak ingin berinteraksi atau bahkan melihatku, kenapa tidak keluar saja. Kalau tidak ingin kembali ke kamarnya di rumah utama, masih ada banyak tempat lain. Kantong dimensi ini luas bukan main sementara penghuninya hanya sedikit.
Mungkin aku saja yang pergi. Aku juga ingin mandi, tidak tahan dengan bau keringat. Awalnya malas karena kakiku masih sakit akibat dipaksa berlari terus kemarin, tetapi aku tidak tahan dengan kecanggungan di ruangan ini.
"Aku ... aku balik duluan, ya," ucapku setelah bangkit berdiri. Tidak ada jawaban dari Aiden. Kuanggap dia sedang tidak ingin diusik. Lebih baik kubiarkan sediri saja dulu.
Asumsiku terbukti benar sebab dia sama sekali tidak mencegah. Jangankan mencegah, bergerak saja tidak. Dia seperti patung di balik selimutnya.
"Oh, Feli. Selamat pagi," sapa Kak Will yang kebetulan hendak lewat di depan ruang unit pemulihan. "Udah baikan?"
"Pagi juga, Kak," balasku. Aku cengar-cengir tidak jelas sambil mengelus tengkuk. "Ya ... kakiku masih keram karna kemarin lari mulu. Tapi udah mendingan, kok."
Kak Will ber-oh ria. "Cepat sembuh, ya. Sama makasih buat yang kemarin," katanya dengan senyum yang dapat membuat anak-anak cewek di satu sekolah jatuh hati secara instan.
Alih-alih terpesona, aku justru merasa hatiku diremas. "Iya, Kak. Sama-sama," ucapku sambil mengusap permukaan pintu ruang unit pemulihan. Saat ini aku lebih ingin melihat senyum Aiden daripada milik siapa pun. "Aku pergi dulu, ya, Kak."
"Hmn, iya. Hati-hati."
Aku dan Kak Will sama-sama melanjutkan langkah. Arah kami berlawanan. Kurasa dia sempat menyadari perubahan suasana hatiku, tetapi untungnya dia memutuskan untuk membiarkanku sendiri.
Hati dan pikiran ini sungguh kacau. Semoga aku bisa lebih tenang setelah mandi. Namun, aku teringat, sebelum dan setelah itu aku harus naik-turun tangga. Siksaan yang teramat kejam bagi sepasang kakiku ini. Kenapa kamarku harus di lantai dua?
***
"Haaa ... segarnya," ucapku saat keluar dari kamar mandi usai berganti pakaian. Kali ini aku tidak menangis saat asyik berendam, jadi rasanya benar-benar segar dan ringan.
Tertatih-tatih aku naik ke kamar lagi untuk menaruh pakaian kotor di keranjang. Di kamar para cewek hanya ada Zenia yang sedang tidur di kasur tengah, barangkali masih lelah karena berkelahi dengan si cowok portal kemarin. Sebisa mungkin aku masuk dan keluar diam-diam, tidak ingin mengganggu istirahatnya.
Berjalan di lorong lantai dua, baru kusadari kalau tempat ini sepi bak padang gurun. Di lantai satu juga tidak ada siapa-siapa, setidaknya saat aku naik. Kala menuruni anak tangga sambil sesekali meringis, kudapati Riel sedang duduk di meja makan dengan segelas kopi.
Seperti bapak-bapak saja, pikirku. Tak berani kuucapkan karena cowok itu terkenal seram kalau ada yang menyebutnya tua dalam konteks meledek. Kami bertemu pandang tepat saat aku berpikir demikian, membuatku seketika merinding.
"Mau aku bikinin kopi?" tawar Riel seraya mengacungkan gelasnya.
Aku menggeleng, kembali sibuk memperhatikan langkah. "Nggak, makasih. Aku mau bikin teh manis aja kalau ada daun teh."
"Oh, ada. Duduk aja, biar aku yang bikinin." Riel meletakkan gelasnya yang masih mengepulkan uap, kemudian beranjak ke meja dapur.
Kalau sudah begini, tidak ada yang bisa menolak tawarannya. Aku pun duduk di meja makan, berseberangan dengan tempat Riel duduk barusan. Kuperhatikan cowok itu yang dengan santai menyiapkan teh manis. Tidak perlu memanaskan air karena kebetulan masih ada sisa di dalam termos.
Setelah lengang beberapa saat, Riel membuka topik pembicaraan. "Yang kemarin itu, waktu nyelametin Feo sama ... Aiden. Untung kamu sampai ke mereka tepat waktu."
Dia mau membahas hal yang sempat kubanggakan malam tadi. Aku tertawa kecil, tidak tahu harus membalas seperti apa. Orang ini benar-benar alergi memuji secara langsung. Bukannya aku percaya diri. Aku menyadarinya karena dia sering begitu ke semua orang.
"Echros kamu berhubungan sama nasib baik dan buruk, kan?" tanya Riel sambil memindahkan kantong daun teh dari gelas ke wadah kecil. Dia kemudian memasukkan satu setengah sendok gula dan mulai mengaduk. "OP banget."
Spontan aku memiringkan kepala. "OP ...?"
Selesai membuat teh manis, Riel berbalik menghampiriku sambil menjelaskan, "Overpower, sesuatu yang hebat banget." Dia menaruh segelas teh manis di hadapanku baru kembali duduk di kursinya.
"Makasih," ucapku yang dibalas dengan anggukan singkat sebelum Riel menyeruput kopinya. Aku termenung sebentar; tatapan terkunci pada gelasku yang mengepulkan uap panas. "Sebenernya aku nggak ngerti yang waktu itu apa, soalnya spontan make echros karna panik."
Riel menggoyang-goyangkan gelasnya sambil menatapku heran. "Bukannya itu kubah transparan yang sering kamu latih di bukit sendiri?"
Selama lima detik bengong baru aku tercerahkan., tetapi sedetik kemudian aku kembali galau. "Iya, ya ... yang itu. Tapi aku masih nggak ngerti cara kerjanya gimana. Mumet."
Riel mengendikkan bahu, lalu membalas, "Aku nggak pandai soal itu. Nanti ngomong sama Natha aja pas dia balik." Dia menyeruput kopinya lagi sampai tersisa setengah gelas. "Dia lagi belanja keperluan bareng Hana."
Aku mengangguk dan sunyi kembali hadir. Udara hanya diisi oleh suara kami menikmati minuman. Aku jadi terpikir akan sesuatu, melirik ke meja dapur. Dua stoples berisi gula dan kopi terletak di dekat termos, belum Riel bereskan.
Waktu tinggal di vila, aku sering melihat Aiden minum kopi yang dari kemasan saset. Mungkin suasana hati anak itu bisa membaik kalau aku membuatkannya segelas kopi.
"Hei," panggil Riel, membuatku terperanjat. "Anak itu, gimana keadaannya? Si Aiden. Tadi pagi Julian keliatan suram banget pas balik ke sini. Habis berantem mereka?"
Mendengar terkaannya, aku tersedak. "Nggak kok! Dari bangun tadi mereka emang lagi nggak mood aja."
"Oh. Gitu, ya." Masih ingin melanjutkan percakapan, Riel pun bertanya, "Kamu sama si Aiden itu keliatan deket. Kalian pacaran?"
Lagi-lagi aku tersedak---kali ini lebih brutal. Teh panas tersembur sedikit sebelum aku mulai batuk-batuk. Meletakkan gelas di meja, aku mengibas-ngibaskan tangan seperti orang yang sedang tenggelam. "Nggak!"
Menyaksikan reaksiku, Riel memasang senyum meledek yang amat langka. "Nggak 'pacaran', tapi 'jadian'. Gitu maksudnya?"
Dengan mata memelotot aku menepuk meja. Pelan saja karena tidak ingin membuat keributan yang tidak diperlukan. Setelah puas memelototinya, aku bersedekap dan berkata, "Asik bener, ya, ngeledek orang."
Masih dengan senyum meledeknya, Riel menyahut, "Habisnya, reaksimu lucu. Sampai keselek gitu." Dia tertawa kecil, barangkali sedang mereka ulang adegan barusan.
Aku mendengkus sebal, lantas meraih gelasku lagi. Pandangan kualihkan pada meja dapur yang sedikit berantakan. Wajahku sedikit memanas dan ini bukan karena teh yang sedang kuminum. "Pokoknya kami cuma temen deket. Nggak lebih."
"Belum lebih." Riel menegak kopinya. Sekarang tersisa seperempat gelas. "Kita liat aja nanti."
Kalau saja dia berada di dekatku, sudah kupukul bahu atau lengannya keras-keras. Awalnya saja dia kelihatan cuek. Kalau sudah cukup dekat, beginilah tingkahnya.
Sudah cukup berurusan dengan cowok pengendali batu itu. Dia juga tidak memulai percakapan lagi, lebih memilih untuk menikmati sisa kopinya. Aku menyesap teh hangatku, kembali menenangkan diri.
Riel pergi ke luar setelah minumannya habis; tak lupa untuk mencuci gelas yang dia gunakan. Kurasa dia tahu aku berniat menyeduh sesuatu, jadi meja dapur tidak dia rapikan.
Setelah mencuci gelas sendiri, aku beranjak ke meja dapur. Air panas dalam termos masih cukup untuk menyeduh kopi di gelas kecil. Kala menuang setengah sendok kopi hitam ke dalam gelas, gerakanku tercekat. Tiba-tiba aku terpikir, bagaimana kalau Aiden tidak suka kopi yang bukan dari saset?
Aku menggelengkan kepala guna mengusir pikiran itu. Kalau dia tidak suka, aku saja yang minum. Aku bukan ingin memaksa dia minum kopi supaya suasana hatinya membaik dan bisa segera tersenyum lagi saat bicara denganku.
"Astaga ... gara-gara si Riel!" Ucapannya tidak mau pergi dari kepalaku. Karena itu, aku membuat kopi dan mengantarkannya ke rumah dekat danau sambil setengah melamun. Untung tidak tumpah. Aku berhasil tiba di depan ruang unit pemulihan dengan selamat.
Sebelum masuk, tentu aku mengetuk pintu terlebih dahulu. Tidak ada jawaban dari dalam, jadi aku masuk begitu saja. Aiden masih meringkuk di kasurnya.
"Aiden, aku bawain kopi. Mau?" tawarku sementara berjalan menghampiri kasurnya.
Saat kupikir dia tidak akan menggubrisku, Aiden justru bangun dengan cepat. "Kopi apa?" tanya anak itu.
Aku duduk di tepi kasurnya. "Nggak tahu. Aku pake kopi yang di toples bekas sosis." Kuperhatikan dirinya sedang menimang-nimang, lalu aku menambahkan, "Gulanya lumayan banyak kok. Aku tahu kamu suka yang manis-manis."
Mendengar itu, Aiden menerimanya dan berterima kasih. Aku masih duduk di tepi kasurnya, menemani. Karena tidak ingin keadaan menjadi canggung, aku pun memberanikan diri untuk memulai percakapan.
"Ngomong-ngomong, lukamu semuanya udah disembuhin sama Tia?" tanyaku.
Aiden menatapku sebentar sambil menyesap minumannya. Mata bulatnya itu membuatku gemas. Dan sepertinya, kalau aku tidak salah lihat, netra cokelat itu sedikit lebih cerah dari biasa. Dia lalu menjawab, "Iya, udah sembuh. Tia itu si anak baru yang masih kecil?"
Aku mengangguk. Aiden hanya membalas dengan gumaman pelan. Canggung yang kuhindari malah datang. Aku tidak tahu harus bicara apa lagi dan sekarang pikiranku ke mana-mana.
Sebenarnya Aiden menganggapku apa? Sempat tergoda diriku untuk bertanya demikian. Untung saja tidak keceplosan. Itu akan memalukan.
"Fel," panggil Aiden tiba-tiba, membuatku terperanjat. "Kamu nggak kesel?"
Aku menoleh padanya. "Kesel? Kenapa harus kesel?" Tadi aku memang sempat kesal karena tidak digubris. Namun, ada sesuatu yang berbisik padaku, bahwa bukan itu yang Aiden maksud.
"Sama aku." Dia menurunkan gelas sampai ke pangkuan, menatap isinya lekat-lekat. "Selama ini aku lebih banyak bikin kamu repot, bikin kamu panik ... padahal pas kita baru ketemu, aku sok banget. Pengen ngehancurin BPE katanya," ujar Aiden yang kemudian mulai menertawai dirinya sendiri.
Kalau ditanya begitu, aku tidak tahu jawaban seperti apa yang harus kuberikan. Hal itu jarang sekali terlintas dalam kepalaku, kecuali saat ada yang mengungkitnya. Aku memang berpikir kalau ambisinya itu gila, tetapi aku tidak pernah menganggapnya mengesalkan.
Aiden tertunduk lebih dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya. Tanpa menunggu jawabanku atas pertanyaannya barusan, dia lanjut berkata, "Aku nyerah."
"Hah?"
"Soal aku yang pengen balas dendam sama BPE ... lupain aja."
Apa-apaan anak ini? Dan, kenapa aku merasa kesal---tidak. Perasaan ini lebih dari kesal; seolah-olah ada yang terbakar di dalam dadaku.
"Lupain aja!?" Sontak aku berdiri, hampir tergeliat saat berbalik menghadapnya. Aku meringis nyeri, lantas melanjutkan, "Setelah semua yang udah susah payah kita lewatin sampai sekarang ini, kamu mau nyerah? Jangan ngaco!"
Napasku tersengal-sengal; dadaku masih berkecamuk. Tak lama kemudian, barulah aku tersadar. Mata bulat Aiden membeliak, menatapku seakan-akan aku adalah hantu yang muncul untuk menakut-nakutinya.
"Eh---sori, aku ...." Tak ada lagi kata-kata yang ingin keluar dari mulut ini. Aku memalingkan wajah dalam diam seribu bahasa, menyadari bahwa ucapanku barusan sudah kelewatan.
Memangnya kenapa aku marah? Bukannya bagus kalau Aiden mengurungkan niatnya untuk balas dendam? Apa hak-ku sampai bisa memarahinya? Kehadiranku dalam hidupnya hanya secuil jika dibandingkan dengan Julian yang bahkan tidak dia dengarkan.
Aku ini hanya orang baru. Aku ini masihlah asing baginya. Aku ini bukan siapa-siapa.
Lebih baik aku keluar dari sini. Untuk terakhir kalinya sebelum beranjak pergi, aku meliriknya. Aiden masih menatapku, tampak terkejut dan bingung. Jujur saja, aku juga demikian. Maka dari itu, daripada kelepasan berteriak lagi, aku keluar tanpa berucap apa pun.
Secepat mungkin aku berjalan meski terpincang-pincang. Begitu tiba di luar, aku menutup pintu dan bersandar di dinding untuk sesaat. Aku menyadari ada yang mengintip dari ujung lorong di sebelah kiri, tempat ruang tamu berada. Entah siapa itu karena aku tidak sempat mendapati wajahnya.
Kutarik napas dalam-dalam terus mengembuskannya. Mendadak kepalaku berdenyut, sepertinya karena frustrasi. Niatku ingin membuat Aiden merasa lebih baik, tetapi aku justru marah-marah di depannya. Bodoh.
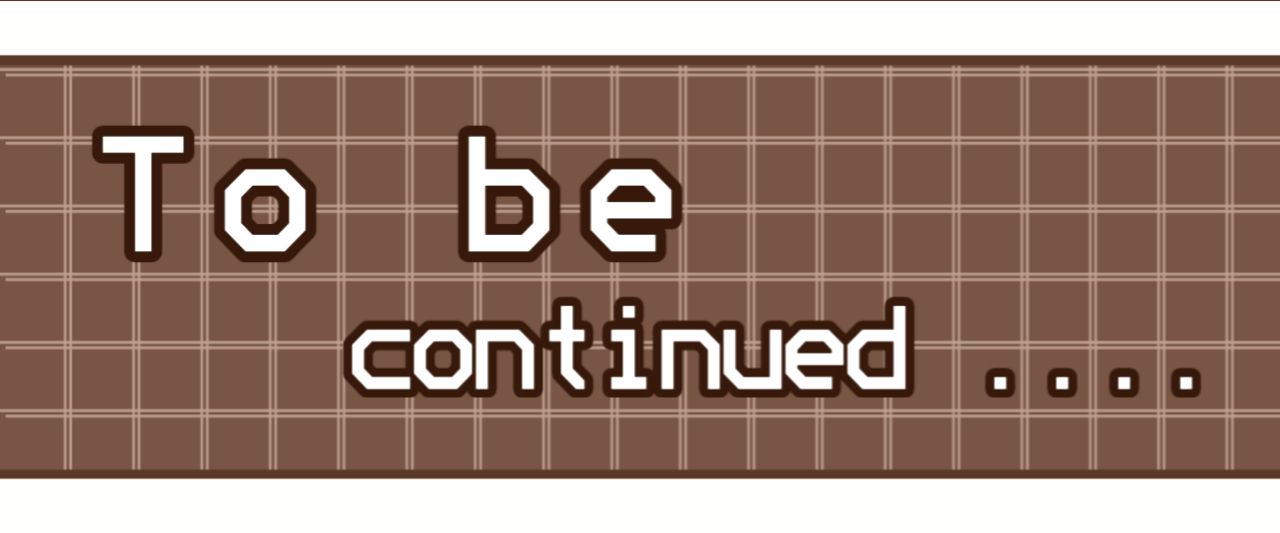
Clou's corner:
Filler dulu dikit. Kita nyantuy sebelum lanjut ke bagian akhir arc ini.
Kira-kira masih ada dua chapter lagi sebelum arc ini ditutup. Jangan lupakan bonus chapter tiap akhir arc! Kali ini pov siapa, ya?
Hari minggu depan aku UAS sehari lima matkul :(((( semoga nanti tetap waras biar bisa namatin ET yeeyy!
09-06-2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro