Ch. 10: Sudah Terlambat untuk Mundur
Wordcount: 1.392 words

Waktu menunjukkan tepat pukul empat subuh. Sudah waktunya aku menyelinap keluar. Berderap di bawah penerangan lampu jalan menuju gang di depan lorong yang biasa kulalui sepulang sekolah.
Suasana sebelum matahari terbit cukup mencekam. Sumber cahaya tidaklah banyak, hanya lampu jalan dan lampu depan beberapa rumah.
Setibanya di tempat tujuan, aku mengembuskan napas lega. Kulihat Erna sudah menunggu sambil memainkan ponsel. Aku tidak perlu berlama-lama menunggu seorang diri di gang menyeramkan ini.
Menyadari kehadiranku, Erna menoleh dengan senyum terukir di wajah. Ia berderap menghampiri, lantas meraih tanganku. Dalam sekejap kami berteleportasi ke depan Aiden dan Julian di tengah hutan.
Tidak ada yang berucap. Aiden menatap Erna terus mengangguk. Setelah membalas anggukan itu, Erna menghilang dari pandangan. Dia pergi ke tempat Marlo untuk mempersiapkan pelarian kami.
Mengamati sekeliling, tak banyak yang bisa kulihat selain pepohonan yang mengepung kami. Minimnya cahaya serta embusan angin malam nan dingin membuatku merinding.
Julian mencolek bahuku dengan kasar. Aku pun berbalik, siap menonjok. Tampak cowok pemarah itu mengarahkan senter ke depan, menerangi sebuah jalan setapak. Tangan satunya dikibas-kibaskan sebagai isyarat agar aku mengikuti mereka. Aiden sudah berjalan lebih dahulu. Dia berhenti sejenak karena jalan di depannya masih diselimuti kegelapan.
Tidak butuh waktu lama bagi Julian untuk menyusul. Aku yang susah di sini, harus buru-buru melangkah dengan kaki pendek kalau tidak mau tertinggal di tengah kegelapan.
Suasana yang benar-benar sunyi membuat gesekan alas kaki dengan permukaan tanah pun rumput terdengar jelas. Masih terlalu pagi bagi para burung untuk berkicau.
Tak ada waktu untuk tenggelam dalam pikiran. Banyak sekali batu, ranting, serta tanaman rambat yang menghambat perjalanan. Bisa-bisa aku terjatuh dan cedera sebelum masuk ke markas BPE. Kalah sebelum perang kalau begitu.
Aku mengembuskan napas kasar. Harus fokus.
Cukup lama berjalan, kami pun tiba di daerah lapang yang ditumbuhi rerumputan berbunga kuning nan mungil. Tidak begitu luas. Kira-kira luasnya hanya setengah dari kelas kami.
Julian menyerahkan senter yang sejak tadi dipegangnya pada Aiden. Segera Aiden maju seorang diri, mencari sesuatu di antara rerumputan. Samar-samar aku melihatnya tersenyum.
Aiden menyorot area yang rumputnya tidak berbunga. Secara bergantian ia menatapku dan Julian, lalu melangkah maju. Kami mengikutinya, tidak mau lama-lama berada jauh dari cahaya.
Aiden mengembalikan senter pada Julian terus berjongkok. Ia meraba-raba rerumputan, mendapati sesuatu yang menyerupai gagang pintu besi. Ditariknya gagang tersebut.
Pintu rahasia, terbuka diiringi bunyi derit karena engselnya sudah berkarat. Tanah serta rumput di atasnya menempel, tidak berhamburan seperti yang seharusnya.
Sebelum turun, Aiden berbalik. Ia menunjuk dirinya sendiri, aku, lalu Julian. Anak itu turun begitu kami mengangguk.
Julian mengamati sekeliling, memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Sementara itu aku terus mengamati Aiden yang tengah menuruni tangga, menunggu tanda darinya.
Aku ikut turun setelah menerima tanda berupa acungan jempol. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku tidak perlu meletakkan tangan di area tubuh tertentu untuk merasakannya.
Sumpah, aku pasti sudah gila. Nekat ambil bagian dalam rencana gila ini. Namun, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau aku terus berdiam diri di rumah Paman Val.
Keputusanku sudah benar, kan?
Setibanya di bawah, mataku harus beradaptasi dengan pencahayaan dalam lorong ini. Lampu kecil yang memancarkan sinar temaram terpasang pada dinding besi dengan jarak yang cukup lebar antara satu sama lain.
Kulihat ada beberapa ventilasi udara di langit-langit yang tentunya terbuat dari besi juga. Selain itu, ada pula lampu-lampu merah yang tidak dinyalakan, barangkali merupakan lampu alarm.
Kalau ada lampu alarm, pasti ada pemicunya. Aiden pasti memikirkan hal yang sama. Kami mengamati sekeliling dengan saksama, mencari benda yang mencurigakan.
Julian berbisik memanggilku, mengganggu konsentrasi. Dijatuhkannya senter ketika aku berbalik dan mendongak. Untung aku bisa menangkapnya dengan baik.
Perlahan ditutupnya pintu masuk sebelum bergabung dengan kami di bawah. "Hei," ucap Julian pelan, "bukannya ini terlalu lancar?"
Akhirnya ada yang berbicara setelah lama dikepung kesunyian nan mencekam. Sialnya, ucapan Julian memicu hal buruk.
Lampu merah yang tadinya mati kini hidup menggantikan lampu kecil yang segera padam. Alarm pun berbunyi sebab lampu merah yang tiba-tiba menyala tidaklah cukup.
"Kalian berdua! Salah satu dari kalian pasti nginjek perangkap!" tuduh Julian. Sorot matanya tajam dan rahangnya mengeras. Aku yang paling lama ditatap. Tandanya, dia berpikir ini semua salahku.
"Enak aja! Dari tadi kami diam di tempat, nggak keliaran!" sahutku jelas tidak terima. "Kau yang paling banyak gerak terakhir!"
Adu mulut tidak berfaedah kami diinterupsi oleh getaran serta bunyi baja beradu. Jeda beberapa detik, lantai kembali bergetar diiringi bunyi yang sama. Aku mendengar suara orang-orang yang tumpang-tindih
"Mereka datang." Aiden maju dua langkah terus merentangkan kedua tangan ke depan atas. Untuk sesaat telapak tangannya terbuka. Bahunya naik-turun, tanda ia sedang mengatur napas.
Sejurus kemudian, tangannya terkepal erat. Diayunkannya ke bawah seolah-olah sedang menarik rak kayu hingga patah. Di saat yang sama, sepetak langit-langit lorong runtuh. Lapisan baja terkelupas; beton hancur; tanah dan bebatuan berhamburan menutupi jalan.
Aku sempat berpikir Aiden telah melakukan hal bodoh: memerangkap kami di sini. Rupanya tidak. Dapat kudengar banyak orang berderap di sisi lain lorong, berseru pada satu sama lain. Dia menutup jalan agak orang-orang itu tidak kemari. Alarm keamanan pun berhenti berbunyi.
Julian berdecak. Raut wajahnya begitu kusut kala berderap menghampiri Aiden, kemudian menyambar lengan jaket anak itu. "Kita keluar. Sekarang!"
Aiden tidak berbalik ataupun menyahut. Ia justru terhuyung ke belakang, tersandar pada Julian yang tak kalah terkejut dariku.
Aku segera menghampiri seraya berseru, "Aiden!" Apa yang kudapati bukanlah hal bagus atau candaan belaka. Kulitnya pucat pasi, juga keringat dingin membanjiri wajah.
Mengikuti naluri, kuraih satu tangannya. "Ayo, kita mundur aja." Peganganku kian erat kala Aiden menggelengkan kepala dengan mata terpejam. Matanya kembali terbuka seiring tangan satunya terulur ke depan.
Sambil mengguncang bahu Aiden, Julian berseru, "Apa yang mau kaulakukan?!" Tindakannya tidak dapat menghalangi Aiden yang kurasa sudah bulat keputusannya.
Walau kelihatan sudah mau pingsan, Aiden masih bisa menggerakkan sebuah batu besar. Batu tersebut melayang mendekat, berhenti di hadapan kami, lalu melayang lebih tinggi lagi dan akhirnya jatuh menghantam lantai beton, mengikuti gerak tangan si pengguna telekinesis.
Aksi itu diulang beberapa kali hingga lantai beton yang terus dihantamnya hancur, membuka jalan masuk ke lorong yang lebih kecil. Tangan Aiden yang masih terkepal erat mulai bergetar. Getarannya kian mengkhawatirkan. Tidak ada yang menduga, batu besar yang dikendalikannya hancur menjadi kerikil.
Seketika Aiden kehilangan kendali atas tubuhnya. Kulihat wajahnya menjadi lebih pucat. Rambutnya pun basah karena keringat.
Peganganku melemah hingga akhirnya melepaskan tangan Aiden. Kedua tanganku lalu menggantung lemas di sisi tubuh.
Berbeda dariku yang bertingkah seperti orang bodoh, Julian mengangkat Aiden dengan sigap. Kuakui itu adalah tindakan yang tepat, tetapi ... memangnya tidak apa seorang manusia dipikul seperti karung beras?
"Lompat," perintah Julian terus melompat turun tanpa basa-basi. Dia mendarat tanpa kesulitan meski membawa beban tambahan. "Cepat turun. Jangan banyak alasan."
"Pandang enteng," ucapku ketus. Suaranya seakan-akan memberiku tenaga. Aku pun melompat turun dan mendarat dengan mulus. "Gini doang mah udah biasa."
Melompat turun begini memang biasa, tetapi rasa sakit di telapak kakiku ini luar biasa. Kumpulan kerikil yang kupijak cukup tajam meski tidak menembus sol sepatu, sakitnya saja yang tembus.
Julian tidak menghiraukanku. Dia melangkah maju bersama Aiden di pundaknya seperti aku tidak pernah datang bersama mereka.
Oke, lupakan cowok menjengkelkan itu. Aku beralih mengamati sekeliling dan tentunya lubang di atas. Lorong tadi rupanya dibangun di atas lorong lain yang lebih kecil.
Tidak seperti lorong di atas yang memberi kesan modern, lorong ini justru memberi kesan magis seperti dalam film fantasi. Tanah berkerikil dengan sedikit rumput sebagai pijakan; dinding yang terbentuk dari susunan batu bata, sudah retak dengan lumut tumbuh di sela-sela; tanaman rambat yang menutupi sebagian besar dinding lorong.
Aku menggeleng-gelengkan kepala dengan cepat, menyadarkan diri. Tak ada waktu untuk mengagumi betapa kerennya tempat ini. Harusnya aku mengkhawatirkan Aiden.
Langkah langsung kupercepat. "Hei, bisa nggak gendong yang bener? Dia itu orang, bukan karung beras," tegurku setelah berhasil menyusul.
Julian hanya melirikku sebentar sambil terus melangkah. Jalannya jadi sedikit lebih cepat. "Lebih gampang begini."
Geram dengan tingkahnya, aku mempercepat langkah. Kutarik bagian belakang jaketnya dengan kasar. Dia pun menoleh dengan alis tertekuk dalam dan kening berkerut. Kami melontarkan tatapan sinis pada satu sama lain sampai Julian menyerah dan mengembuskan napas kasar.
Dia menurunkan tubuh Aiden, mengopernya padaku, lalu berjongkok. "Biar kudukung aja. Puas?"
Setelah mengembuskan napas panjang, aku mengatur sedemikian rupa agar Julian dapat membopong Aiden dengan benar. Tampak kondisinya sudah membaik. Sedikit.
Kuberanikan diri untuk menyibak rambut di keningnya sekaligus menghapus sedikit keringatnya. Sedetik kemudian, Julian baru berdiri seakan-akan ia menungguku melakukan hal itu.
"Kita cari jalan keluar dari sini sekalian tempat istirahat." Julian melanjutkan langkahnya.
Aku kembali mengekor setelah mengangguk.
.
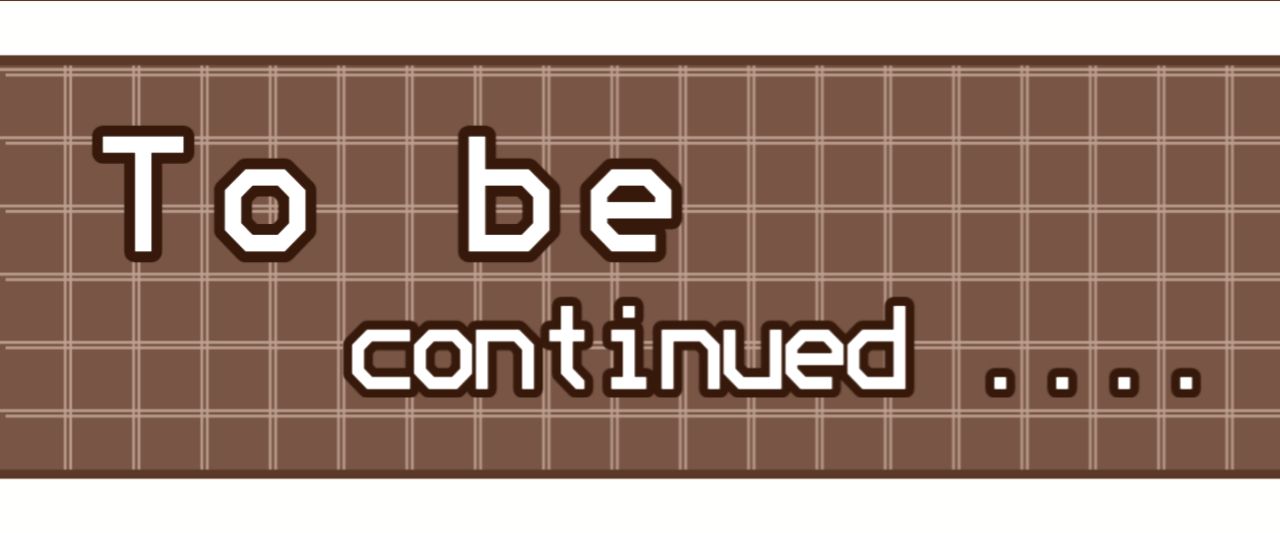
.
.
Clou's corner:
Belum ganti hari kan kalo WIB
Hehe
19-08-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro