interlude
TRIGGER WARNING.
IF YOU DON'T FEEL WELL MENTALLY, DON'T READ.
I AM NOT JOKING, PLEASE, BE BETTER FIRST AND BE OKAY FIRST BEFORE YOU READ THIS CHAPTER.
*
My father told me once that
the most important thing every man should know is
what he would die for.
—Tana Fench—
*

Ada beberapa hari dalam hidup seorang Ryona Keshamora yang tidak akan pernah bisa dia lupakan, bahkan meski dia mencoba untuk tidak pernah mengingatnya lagi. Satu adalah hari ketika dia membatalkan pernikahannya dengan seseorang secara sepihak. Satu adalah malam dimana dia bertemu dengan seseorang yang lain, yang berhasil menghancurkan hidupnya begitu rupa. Satu terakhir adalah saat dia melepaskan seseorang berikutnya dari dalam dekapannya. Seseorang yang baru punya sebatas tangis untuk berkomunikasi. Seseorang yang waktu dia tinggalkan, memejamkan mata dengan kelima jari mungil menggenggam jari telunjuknya—sebelum dia paksa tarik lepas.
Ryona ingat segalanya tentang satu yang terakhir. Langit mendung, seperti ikut berduka untuk perpisahan yang telah dia putuskan. Jalanan sepi ketika dia turun dari taksi, berjalan melewati halaman luas menuju teras rumah, bersamaan dengan seorang lelaki tinggi muncul dari dalam. Lelaki itu menyadari keberadaannya, langsung mematung di ambang pintu. Ryona terus saja melangkah, memandang nanar dan mata mereka saling terkunci.
"Ini anak kamu." ujarnya tanpa basa-basi setelah mereka cukup dekat.
"Ryona,"
"Jangan sebut nama saya. Kita nggak saling kenal. Dan seharusnya, memang nggak pernah bertemu."
"Selama beberapa bulan ini," Lelaki itu menelan ludah. "Selama beberapa bulan ini... kamu ke mana?"
"Ke suatu tempat yang nggak perlu kamu tahu."
"Dengarkan saya—"
"Nggak. Saya nggak mau dengar apapun dari kamu. Sekarang, kamu yang seharusnya mendengarkan saya." Ryona memotong dingin, tanpa ekspresi. Tatapan beralih turun, berpindah pada sosok kecil dalam dekapannya. Semakin dia melihatnya, semakin dia sadar bahwa hampir tidak ada jejaknya yang tertinggal pada sosok itu. Semua pada wajah sosok itu lebih mirip dengan lelaki yang kini berdiri di depannya. Lelaki yang jika dia bisa, ingin dia hapus eksistensinya dari dunia. "Ini anak kamu. Saya nggak mengakuinya. Saya mengembalikannya ke kamu."
Lelaki itu diam saja, tetapi dia menuruti keinginan Ryona, balik meraih sosok mungil dalam dekapan perempuan itu hingga berpindah dalam pelukannya. Ryona menatap wajahnya sejenak, tidak tahu kenapa tiba-tiba dia ingin menangis, padahal dia tidak seharusnya menangis. Sebab, dia tak mengasihi anak itu. Anak itu merenggut semua yang berharga dari hidupnya. Anak itu adalah pengingat untuk kebodohan-kebodohan yang tidak seharusnya terlaksana. Anak itu adalah perusak semua harap yang telah terencana, apa-apa yang Ryona inginkan mengisi masa depannya. Anak itu adalah monster paling nyata yang pernah dikenalnya.
Tetapi... apakah ada monster dengan wujud layaknya malaikat seperti anak itu?
Dia masih tertidur dengan tenang kala Ryona mengambil beberapa langkah mundur. Pipinya memerah. Satu-satunya kemiripan antara anak itu dengan ibunya hanya warna kulit yang pucat. Tidak ada yang lain lagi. Dia lebih mirip ayahnya.
"Boleh saya tahu... siapa namanya?"
"Dia anak kamu. Kamu yang akan memberinya nama." Ryona menggigit bibir, berusaha mati-matian untuk tidak menangis. "Saya harus pergi."
"Tunggu."
"Apa lagi?"
"Suatu hari nanti... dia bakal menyadari apa yang seharusnya dia punya, tapi nggak dia miliki. Kalau dia bertanya tentang kamu, saya harus bilang apa?"
"Apa pun. Kamu bisa mengarang cerita. Beritahu dia, saya sudah lama mati." Ryona melihat sekali lagi pada anak itu, kembali buang muka ketika dia merasa dadanya ditikam nyeri tak kasat mata. "Atau kamu bisa berterus-terang. Kasih tahu dia apa yang terjadi. Kasih tahu dia bagaimana buat saya, dia nggak pernah ada. Bagaimana saya nggak mengharapkan dia. Itu terserah kamu."
Di belakang lelaki itu, seorang perempuan setengah baya tersekat mendengarkan percakapan keduanya. Tangannya menutupi mulut. Matanya diliputi oleh keterkejutan bercampur rasa kasihan. Tak perlu waktu lama bagi tangisnya untuk pecah, jadi latar belakang yang tidak hanya dramatis, namun juga memilukan.
Ryona berbalik, melanjutkan langkah tanpa melihat lagi. Lelaki itu memanggilnya, tetapi dia tidak peduli. Dia berlalu pergi dengan kepala tegak, mengabaikan semua yang ada di sekitarnya. Hari itu, dia membuang seseorang dari hidupnya. Seseorang yang dia benci. Seseorang yang tidak ingin dia lihat lagi.
Seseorang yang kemudian menyandang nama Jevais Nareshwara.
Jika ditarik kembali ke masa silam, Ryona tidak pernah menduga bahwa delapan belas tahun kemudian, dia akan berlari menyeberang jalan tanpa berpikir sambil memekik panik, menghampiri seseorang yang hadirnya dalam hidup ini tidak pernah dia harapkan.
Ryona meraihnya dari atas aspal tanpa berpikir, membuat darah seketika turut menodai bagian pakaiannya sendiri. Nana belum sepenuhnya kehilangan kesadaran. Saat Ryona memekik histeris, memanggil siapapun untuk memberinya pertolongan, remaja itu mengangkat tangan untuk menggenggam jemari ibunya, seperti yang dia lakukan bertahun-tahun lalu, saat dia hanya bayi kecil yang cuma bisa berkomunikasi lewat tangisan. Tindakannya membuat Ryona mengalihkan pandang padanya. Mata perempuan itu penuh air mata, beberapa menetes ke pipi Nana.
Nana menatapnya lekat, dengan pandangan mata yang kabur. Dia ingin bilang pada Ryona agar jangan menangis, namun sayangnya, dia tidak punya cukup kekuatan untuk bisa bicara. Napasnya menderu dan tak berapa lama kemudian, dia terbatuk, mengeluarkan lebih banyak darah. Lebam bertebaran di wajahnya. Luka lecet menghiasi lengan dan kakinya. Ada darah merembesi bagian dada kausnya.
"Please... please... please..." Ryona menangis di tengah teriakannya memanggil orang-orang yang kini mulai banyak berkerumun di sekitar mereka. Tangannya menyentuh pipi Nana, mengusap kulit anak itu pelan. "Please... please... please..."
Ada banyak yang ingin Nana katakan, tetapi mulutnya terkunci. Ada sensasi aneh yang menyelubunginya, membuat kepalanya terasa ringan. Tapi dia menolak untuk kehilangan kesadaran. Dia tidak mau membiarkan kegelapan mengambil alih penglihatannya. Dia memaksa diri tetap terbangun, jadi dia bisa menatap wajah perempuan yang kini mengusap rambutnya seraya terus terisak sedikit lebih lama. Wajah milik perempuan yang keberadaannya selalu dia pertanyakan. Wajah seseorang yang telah dia rindukan bahkan tanpa pernah dia temui sebelumnya.
Dia punya ibu, dan ibunya ada di sini. Dia bertemu dengan ibunya, dan ibunya menyayanginya. Itu saja sudah cukup dan buat Nana, jika dia harus mati sekarang, dia akan pergi dengan senang hati.
Meski begitu... jika dia boleh serakah... dia ingin menghabiskan waktu beberapa lama dengan ibunya. Tidak perlu sampai berminggu-minggu, atau berhari-hari. Lima menit saja sudah cukup. Lima menit dimana Nana bisa balik memeluk perempuan itu dan memanggilnya 'ibu'.
Sayangnya, tubuhnya menolak bekerja sama. Nana merasakan air matanya sendiri mengalir sebelum pandangannya berangsur menggelap. Satu-satunya suara yang Nana dengar sebelum segalanya hening adalah pekik panik Terry yang memanggil namanya.
*

Ryona mengerti kenapa banyak orang merasa tidak nyaman di rumah sakit. Segala sesuatu yang ada di sana selalu identik dengan luka dan duka. Itu juga yang membuat rumah sakit jadi tempat yang sesak oleh doa, bahkan lebih dari rumah ibadah manapun. Dia betul-betul tidak mampu lagi berpikir setelah melihat anaknya terhantam oleh kendaraan yang melaju dengan begitu keras, lalu terbaring di aspal dan berlumurkan banyak darah. Ketakutan menghantuinya, membuat sekujur tubuhnya bergetar hebat tak terkendali. Namun anehnya, sesaat sebelum Nana kehilangan kesadaran di pangkuannya, dia justru mendapati tatapan yang tidak biasa di mata anak itu. Bukan rasa sakit, apalagi gentar menghadapi kematian. Kebalikannya, sesuatu itu mengingatkan Ryona pada rasa senang... dan kelegaan.
Apa Nana sudah tahu kenyataannya?
Ryona tertunduk, menatap jari-jari penuh jejak darah merah yang telah mengering. Tangannya masih gemetar. Ryona mencoba mengepalkannya supaya tremor itu tidak terlalu kentara, namun upayanya gagal. Air mata kembali menetes di pipinya tanpa dia sadari, membuatnya menarik satu-dua napas panjang untuk menenangkan diri. Dia tidak boleh panik di sini, apalagi sampai menangis histeris. Semua orang sudah terlihat cukup kacau, terutama Terry yang lebih sering terlihat datar. Lelaki itu tidak berhenti mondar-mandir di depan kursi ruang tunggu tempat Yeda, Jeno dan Injun terduduk, sesekali meremas rambutnya sendiri seraya mengeluarkan dengus frustrasi.
Tiba-tiba, Ryona dikejutkan oleh Jeno dan Injun yang menghampirinya tanpa suara, lalu berjongkok di depan kakinya.
"Kita di sini mau bantu Tante aja, kok." Injun berkata begitu sebelum dia meraih salah satu tangan Ryona, lalu membersihkannya dengan sehelai tisu basah dari kemasan besar yang Jeno pegang. Ryona sudah bisa menebak jika Injun dan Jeno adalah teman terdekat Nana, terlihat dari bagaimana mereka selalu bersama Nana hampir sepanjang waktu, tapi dia tidak menebak jika dua anak itu bakal menghampirinya hanya untuk membersihkan bekas darah dari telapak tangannya.
"Tante itu... mamanya Nana, kan? Yeda bilang begitu tadi." Jeno mendadak bertanya, meski terlihat ragu.
"Jeno." Injun memperingatkan.
Jeno memberengut. "Cuma nanya."
Ryona menghela napas lagi, berusaha terlihat lebih tenang sebelum akhirnya memaksakan senyum. "Iya."
"Tante dateng buat ketemu Nana?"
Ryona mengangguk. "Iya."
"Kalau begitu, Tante nggak boleh pergi lagi." Ryona dikejutkan oleh nada tegas dalam suara Jeno, tidak mengira jika seseorang sepertinya bisa terkesan begitu memaksa. Setahu Ryona, Jeno adalah yang paling pendiam diantara mereka bertiga. Dia anak manis yang tidak banyak tingkah, itu yang bisa Ryona simpulkan setelah beberapa kali sempat melihatnya, entah itu di mall atau ketika Pensi di sekolah tempo hari. "Nana bakal sembuh. Nana bakal bangun. Tante harus ada di sana waktu Nana bangun. Jadi Tante harus janji, tante nggak akan pergi."
"Saya tahu dia akan sembuh. Tapi, saya masih nggak yakin apa dia mau ketemu saya, setelah dia tahu semua kebenarannya."
"Kalau saya jadi Nana, saya nggak akan mau ketemu Tante. Tante ninggalin saya dari kecil. Tante bikin saya nggak punya Mama kayak anak-anak lain. Tante nggak pernah ada waktu saya ulang tahun, saat saya bagi raport. Nggak pernah ngomelin saya ketika saya nakal, atau pas nilai ulangan saya jelek. Saya nggak ngerasa Tante udah berperan jadi Mama buat saya."
"Jeno!" Injun berseru, kali ini penuh dengan penekanan.
Jeno mengabaikan seruan Injun. "Tapi saya bukan Nana. Nana itu berbeda. Dia... dia selalu punya cara buat memaafkan orang lain, walau orang itu nggak pantas dimaafkan. Dia bisa mengerti orang lain, kadang sampai lupa sama dirinya sendiri. Dia tipe orang yang bakal mengorbankan diri sendiri buat temannya, buat orang-orang yang menurut dia berarti. Dan selama ini... selama ini..." Jeno menggigit bibir ketika suaranya pecah, seperti dia hampir menangis. "Dan selama ini... meski nggak tahu siapa mamanya... Nana nggak pernah berhenti kangen... nggak pernah berhenti berharap suatu hari nanti... dia bisa punya Mama kayak anak-anak yang lain."
Ryona mengangguk lagi, kali ini berkali-kali. "Saya tahu itu."
"Nana baik. Baik banget. Jadi kalau Tante sampai ninggalin dia lagi... kalau Tante sampai ninggalin dia lagi..." Jeno tidak bisa menyelesaikan kata-katanya, sebab isaknya sudah terlanjur pecah. Ryona cepat-cepat meraih anak itu ke dalam pelukannya, mengusap punggungnya seiring dengan tangis Jeno yang kini sesenggukan. Bahu remaja itu berguncang. Injun ikut tertunduk, menyadari ada air mata yang jatuh begitu saja di wajahnya. Yeda dan Terry menatap dari tempat mereka berada, hingga Terry jadi orang pertama yang buang muka.
"Saya tahu, Ezekiel. Saya tahu. Saya nggak akan meninggalkan dia lagi. Saya nggak akan pernah bisa memaafkan diri saya kalau saya sampai melakukan itu."
Jeno tidak menjawab. Lidahnya kelu. Dia terus menangis sambil tak henti membisikkan bahwa Nana akan baik-baik saja, jadi Ryona harus menepati janjinya. Ryona tetap memeluknya, mendekapnya erat sampai isak Jeno reda dan dia sudah lebih tenang. Mereka masih harus menunggu hingga berjam-jam berikutnya. Berjam-jam yang terasa seperti seabad. Detik demi detik berlalu dengan begitu lambat, begitu menyiksa. Bahkan hingga Nenek, Mama Jeno dan Mama Injun datang, masih belum ada kabar dari mereka yang berada di balik pintu. Entah itu pertanda baik atau pertanda buruk, Ryona tidak ingin memikirkannya.
Dia masih terdiam di kursi ruang tunggu yang dia duduki tatkala Nenek menghampirinya, lalu duduk di sebelahnya. Wanita itu menoleh sedikit, yang berbalas senyum sedih dari Nenek. Hening sejenak, sampai akhirnya Nenek berinisiatif membuka percakapan lebih dulu.
"Kamu kembali." Katanya singkat.
"Ibu... keberatan?"
"Nggak sama sekali." Nenek mengakui. "Mungkin ini yang terbaik, setelah semua yang terjadi. Dia sudah terlalu lama kesepian, nggak punya orang tua yang bisa diandalkan, terutama setelah ayahnya nggak ada. Saya nggak bilang kalau ayahnya itu ayah yang baik, tapi dia ayah yang tahu bagaimana menyayangi anaknya."
"Maaf."
"Saya yang seharusnya minta maaf, untuk semua kesalahan yang diperbuat oleh ayahnya Jevais. Tapi boleh saya minta sesuatu dari kamu? Semua yang sudah terjadi dalam hidup kamu, yang membuat kamu harus kehilangan banyak hal, itu bukan salah Jevais. Dia nggak tahu apa-apa. Dia juga nggak pernah meminta untuk ada. Dia lebih nggak berdosa dari kamu." Nenek melanjutkan, suaranya pelan dan lebih mirip bisikan. "Jevais itu... anak yang baik. Agak nakal, memang, tapi baik. Kalau kamu nggak bisa membuatnya senang, saya harap kamu juga nggak membuatnya sedih."
"Saya ngerti."
"Bagus, kalau begitu."
Hanya beberapa detik setelah Nenek menjawab, pintu ruangan yang tertutup rapat terbuka, menampilkan dua petugas medis dengan setelan dan sarung tangan bernoda darah. Wajah mereka terlihat lelah.
"Keluarga Jevais Nareshwara." Terry berjalan maju lebih dulu, diikuti Ryona. Injun, Jeno dan Yeda ikut beranjak, tetapi Mama Jeno menahan mereka agar tetap di tempat. "Saya perlu bicara di tempat yang lebih pribadi. Jevais akan dipindahkan ke ruang perawatan intensif setelah ini dan..." Dokter itu menatap pada wajah-wajah pucat dan cemas milik orang-orang di depannya. "jumlah orang yang dapat mengunjunginya akan dibatasi. Untuk sementara waktu, karena kondisinya masih sangat lemah sekarang."
Usai bicara begitu, dokter tersebut melangkah agak sedikit menjauh dari orang-orang yang menunggu, sehingga penjelasannya hanya bisa didengar oleh Terry dan Ryona.
"Saya punya berita bagus dan berita buruk."
"Bad news first." Terry menukas cepat.
Dokter itu menghela napas. "Ada trauma tumpul yang berat di bagian dada karena benturan keras yang terjadi. Pendarahannya meluas, nyaris membanjiri paru-paru dan mendorong jantung. Itu yang membuatnya kesulitan bernapas sebelum kehilangan kesadaran. Trauma tersebut menyebabkan cedera berat pada jantungnya. Saat ini, satu-satunya penyebab kenapa dia masih bertahan adalah karena fungsi otaknya masih baik dan dukungan mesin penopang hidup. Tetapi, jika dia terlalu lama berada dalam kondisi tersebut, jaringan syaraf dan fungsi otaknya bisa terganggu karena lama tidak berfungsi."
Ryona mundur beberapa langkah, tangisnya kembali pecah.
Terry berusaha menegarkan diri. "Good news?"
"Tidak ada trauma berat di kepala. Fungsi otaknya masih baik. Ada kemungkinan besar dia bisa pulih dan sembuh sepenuhnya, jika masalah pada jantungnya tertangani. Cedera berat yang terjadi, jika terus-menerus dibiarkan akan memicu gagal jantung. Satu-satunya jalan keluar yang paling mungkin adalah... memberinya jantung baru."
"Itu artinya, dia membutuhkan donor secepatnya?"
"Kurang lebih seperti itu. Kami akan mengusahakan yang terbaik, tetapi mencari donor organ, terutama jantung bukan sesuatu yang mudah. Bukan hanya keberadaan donor, tapi faktor lainnya seperti golongan darah turut berpengaruh. Ada informasi lainnya yang ingin anda ketahui?"
Terry tidak menjawab, tetapi sorot matanya sukar dibaca. Ryona yang akhirnya menggelengkan kepalanya lantas melangkah menjauh lebih dulu. Nenek menyambutnya, mendengarkan apa yang dikatakan Ryona, kemudian tangis keduanya pecah sembari mereka berusaha saling menguatkan dengan dekap. Terry tetap berdiri di sana, memandang pada udara kosong dengan hampa hingga dia merasakan tangan-tangan melingkarinya—tangan-tangan milik Jeno dan Injun. Di kejauhan, Yeda hanya menatapnya, terlihat sama muram.
Terry membiarkan Jeno dan Injun memeluknya beberapa lama dan saat pelukan itu terlepas, dia memaksakan senyum. "Jevais bakal baik-baik aja."
"Pak—"
"Saya yang akan memastikan itu. Jevais bakal baik-baik aja."
Terry tidak butuh jawaban karena setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berjalan pergi, meninggalkan Jeno dan Injun tanpa sekalipun menoleh lagi.
Berbeda dengan Injun dan Jeno yang tampak tidak bisa mengartikan makna di balik kata-kata Terry, kecemasan yang begitu besar justru membayang di mata Yeda.
*

Malam harinya, ketika Terry kembali ke rumah sakit untuk mengunjungi Nana, dia disambut oleh Ryona yang berada di sisi tempat tidur remaja itu. Tangannya menggenggam tangan Nana erat, terlihat enggan melepaskannya bahkan hanya sedetik. Pipinya sembab dan matanya tampak lelah, namun dia telah mengganti pakaiannya yang bernoda darah. Kala menyadari keberadaan Terry di luar kaca ruang perawatan intensif rumah sakit, Ryona beranjak dari kursi, melepas jasnya di ruang pre-steril dan melangkah keluar untuk menemui Terry.
"Boleh saya bicara dengan dia? Sebentar aja, nggak akan lama."
Ryona mengangguk, hanya saja, sebelum Terry sempat melangkah lebih jauh, dia memanggil ragu. "Terry."
"Apa?"
"Apa pun yang kamu pikir mau kamu lakukan... saya rasa kamu tahu apakah Jevais bakal senang dengan itu atau nggak."
Terry membalas tenang. "Saya tahu."
"Adik kamu cemas sama kamu."
"Sudah bisa ditebak."
"Kita masih punya harapan, Terry." Ryona berujar cepat. "Hari ini, saya sudah menyebar informasi soal kebutuhan terkait donor jantung pada setiap relasi dan kolega yang saya punya. Bukan hanya saya, tapi keluarga saya pun ikut melakukannya."
Terry memiringkan wajah. "Bagus."
"Jadi... saya harap kamu nggak perlu... melakukan sesuatu yang nggak bakal Jevais sukai."
"Loh, memangnya kamu pikir saya mau melakukan apa?"
"Hanya antisipasi."
Terry mengangkat bahu, lalu memilih meneruskan langkahnya menuju ruang pre-steril untuk melepas alas kaki dan mengenakan jas pengunjung—bagian dari upaya untuk menjaga agar ruangan perawatan intensif tersebut tetap steril. Saat dia semakin dekat dengan Nana, dia hampir tidak bisa mengenali anak itu. Sosok itu bukan siswanya yang tengil dan hobi bercanda, dengan gaya tukang gombal ulung yang katanya hanya menyukai satu orang saja. Ada luka di dahinya, tertutupi oleh kassa. Memar menghiasi wajahnya, membuat salah satu pipinya dan ada luka lecet di garis rahangnnya. Lengannya yang tak tertutupi pakaian tampak lebam. Salah satunya penuh dengan tusukan jarum. Selang mencuat dari tubuhnya, melekat di dada, di lengan. Dia terlihat seperti robot karena begitu banyak alat melekat pada badannya.
Terry duduk di atas kursi yang berada di samping tempat tidur, meraih jemari Nana. Tangannya hangat, seperti biasa. Ruangan senyap, hanya terdengar suara mesin penopang hidup yang menandakan remaja itu masih bernapas. Terry menunduk, menghirup udara dalam-dalam diantara jemari Terry dan hanya begitu saja, air mata mengalir di pipinya.
"Apa yang akan dan tidak akan Jevais Nareshwara sukai?"
Tidak ada jawaban.
Terry tertawa sedih. "Kamu tahu, apa yang terjadi bikin saya berpikir, hidup memang bisa selucu itu, atau justru sekejam itu. Kayak... dia suka bermain-main dengan kebahagiaan kita. Ada saatnya kita merasa kita tinggal selangkah menuju bahagia dan tiba-tiba aja... segalanya direnggut dari kita. Dalam sekejap, bisa jadi lebih lekas dari menarik napas. Saya bisa menerima jika itu terjadi sama saya. Saya bukan orang baik. Saya membuat banyak kesalahan. Saya menyakiti banyak orang."
Terry mengatur napasnya sejenak sebelum dia mulai terisak lebih keras.
"Tapi nggak dengan kamu, atau Jeno atau Injun. Kalian semua anak-anak baik. Kalian berbuat kesalahan bukan karena kalian mau, tapi karena kalian perlu belajar. Kalian nggak pernah menyakiti banyak orang. Hidup... harusnya nggak bermain-main dengan mereka yang seperti kalian. Sayangnya... hidup nggak mau peduli, dan saya nggak bisa diam aja membiarkan itu terjadi."
Terry mengeratkan genggamannya pada tangan Nana.
"Apapun yang saya lakukan nantinya, Jevais, kamu suka atau tidak suka, itu kemauan saya. Jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri." Terry menggigit bibir, suaranya bergetar saat dia menyambung dengan bisikan. "Jangan sedih, Jevais. Banyak orang yang peduli sama kamu. Saya hanya salah satu diantaranya."
Jeda lagi.
"Jangan sedih, Jevais." Terry mengulang diikuti oleh tetes-tetes air mata lainnya. "Jangan sedih, apalagi karena kesepian. Kamu dicintai. Selamanya akan terus dicintai."
Terry meninggalkan sisi tempat tidur Nana sesaat kemudian, tanpa menyadari sesuatu;
Ada air mata di sudut mata Nana ketika dia melangkah pergi.
*

Seminggu setelahnya.
Malam ini, Terry sengaja check-in di salah satu hotel yang tidak terlalu jauh dari apartemennya untuk menuntaskan apa yang telah dia niatkan selama beberapa hari belakangan. Dia bisa menduga, setidaknya ada tiga orang yang sudah menunggunya di apartemennya—orang yang tidak lain dan tidak bukan adalah Jeno, Injun dan Yeda. Mereka mengawasinya seperti anggota FBI mengintai buronan selama satu minggu ini. Terry harus pintar-pintar mengatur siasat supaya mereka tidak bisa menduga apa yang sedang dia coba lakukan.
Yah, satu minggu telah berlalu dan Nana masih terbaring di rumah sakit, tidak kunjung sadar—dan mungkin itu yang terbaik buatnya sekarang, karena jantungnya tidak bisa lagi melakukan pekerjaan berat. Terry mengunjunginya, setiap hari, walau melihat memar dan luka di tubuh remaja itu terasa sangat menyiksa. Nana menerima banyak tamu setiap hari, mulai dari Injun dan Jeno yang selalu bercerita tentang apa yang terjadi di sekolah menjelang musim ujian sampai Kasa yang rajin melipat bangau kertas menggunakan kertas berwarna, lalu menempelkannya di tiang-tiang besi tempat tidur Nana. Jumlahnya makin banyak seiring dengan hari yang bergantian, membuat tempat tidur Nana tampak serupa instalasi seni origami.
Satu minggu tanpa kemajuan, sebab mencari donor jantung bukan sesuatu semudah membalikkan telapak tangan.
Terry menghela napas sebelum dia melipat selembar kertas yang usai dia tulisi dengan rapi, memasukkannya ke dalam kotak sarat beraneka benda. Kali ini, dia merasa bangga karena dia bisa menyelesaikannya tanpa membuat tintanya pudar karena terkena tetesan air mata. Hanya butuh waktu sekian detik bagi kertas tersebut buat bergabung dengan benda-benda lain dalam kotak, membuat Terry memandangnya sejenak. Untuk sesaat, pikirannya terculik oleh ruang nostalgia.
Hidup adalah sebuah keberanian.
Bapak bikin kita jadi berani, sekarang bisa Bapak balik berani buat kita?
Indeed, Jevais, Terry membatin seraya menutup kotak tersebut, menempatkannya di atas meja, diikuti menempelkan sticky notes berisi serangkaian kata. Dia menatap pada salah satu sisi tembok, pada bagian di mana dia menempelkan selembar kertas HVS yang juga bertuliskan beberapa kalimat, diikuti sebuah senyum.
Terry mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan singkat pada Yeda, diikuti mendial nomor darurat untuk ambulans. Seseorang mengangkat teleponnya. Terry menerangkan situasi yang akan mereka dapati begitu mereka tiba nanti, diikuti alamat yang harus mereka datangi. Orang di balik telepon terdengar gugup, memintanya buat terus bicara, namun Terry mengabaikannya. Dia memutus sambungan telepon secara sepihak dan menjatuhkan ponselnya ke lantai.
Tangannya beralih meraih tas, mengeluarkan sesuatu yang terasa dingin dalam genggaman. Benda yang hampir terlupakan, saking lamanya dia membiarkan benda tersebut tergeletak tanpa tersentuh di dasar. Benda itu adalah senjata genggam revolver kaliber 32.
Saya mau Bapak bahagia.
Dengan caranya sendiri, suara Jevais bergema dalam telinga Terry.
Dengan begini, kita menemukan cara menuju kebahagiaan kita masing-masing, Jevais.
Ponselnya meraung tanpa henti.
Jangan sedih, apalagi karena kesepian. Kamu dicintai. Selamanya akan terus dicintai.
Terry menutup matanya, menempelkan moncong senjata ke lehernya kemudian tanpa berpikir dua kali, dia menarik pelatuk.
Suara letusan terdengar. Kemudian hening, sampai ponsel Terry berdering lagi. Dalam keriuhan telepon yang tak akan pernah terjawab, darah mengalir, membasahi karpet.
Jangan sedih, apalagi karena kesepian. Kamu dicintai. Selamanya akan terus dicintai.
bersambung ke final verse
***
Catatan dari Renita:
i cried writing this.
so sorry, it has to ended like this. gue akan menjelaskan kenapa, nanti setelah final verse atau di bagian outro. told ya before, i dedicate this story to two people.
to chester bennington of linkin park, and to jonghyun of shinee.
gue akan menjelaskan point of view gue sendiri terkait karakter dalam cerita ini tapi well, kita masih punya final verse dan outro.
jadi, sampai ketemu di bagian final verse dan outro. mari berharap, gue hanya perlu membunuh satu orang dalam cerita ini.
(mau ngetik 'haha' tapi takut kena timpuk seumat).
dah ya.
sekian.
sampai ketemu di chapter berikutnya.
ciao.
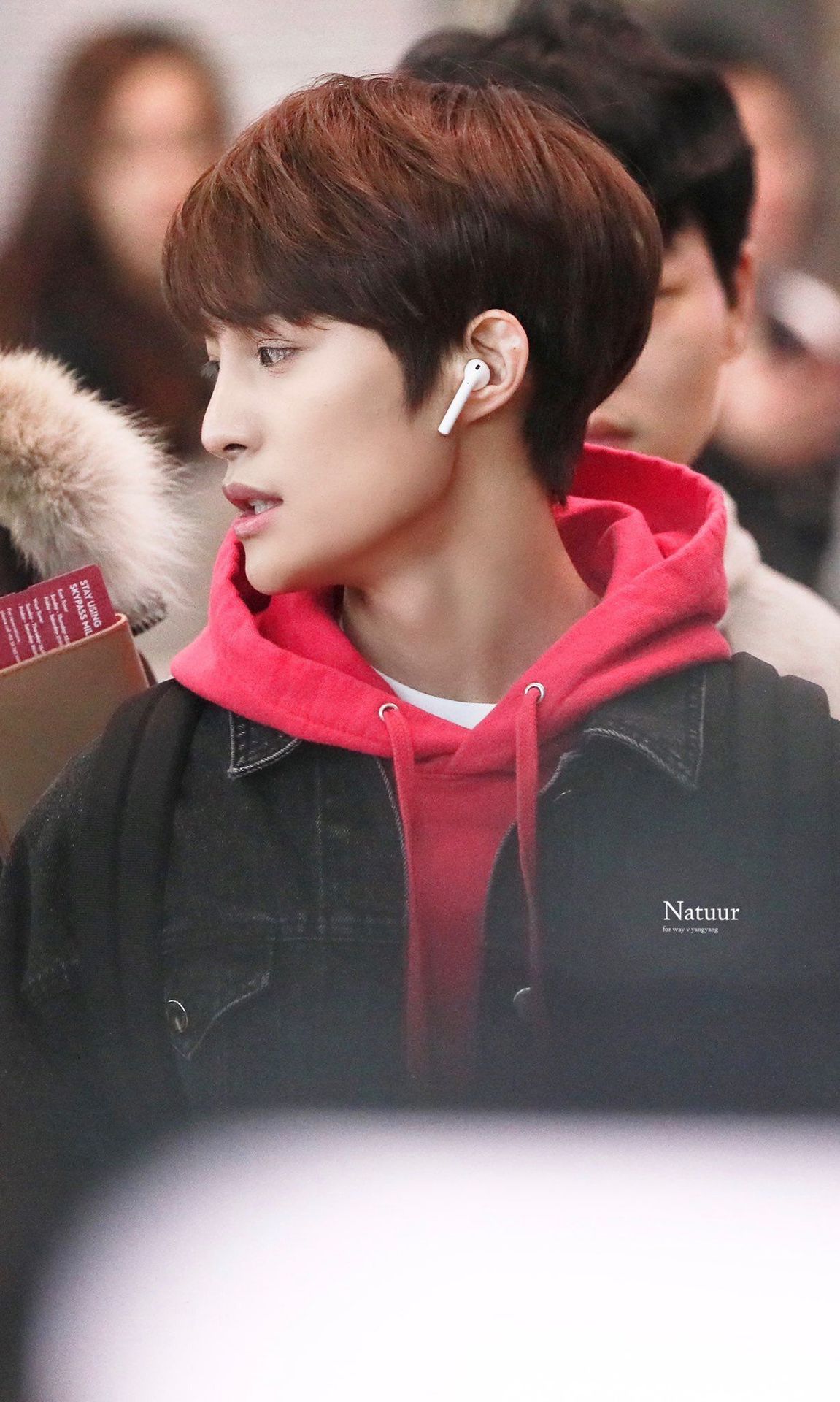
Semarang, September 2nd 2019
20.47
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro