32
"Damn, I know it, we're going to make a mess."
"A lovely mess. Now shut up and kiss me again."
— J to J
***
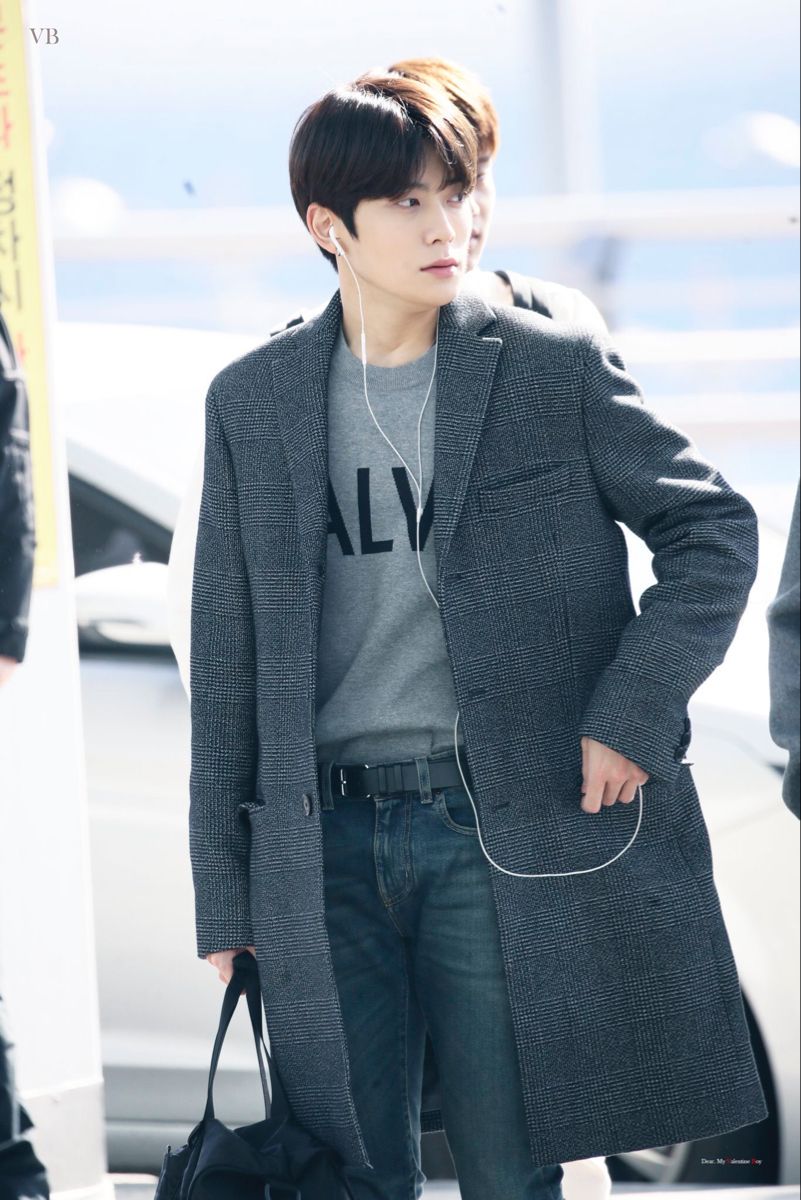
Jef sedang tepekur di ruang tengah dengan laptop terbuka di pangkuannya saat dia mendengar suara derum mobil masuk lewat pagar depan. Lelaki itu mengembuskan napas lega, menerka jika itu Sashi. Dia sudah menghubungi Sashi tadi sore, berniat mengajak anak perempuannya minum kopi sekalian berdiskusi soal syarat dari Jennie yang mesti dia penuhi jika dia mau Jennie membatalkan kerjasamanya dengan Theo. Jef ingin mengutuki dirinya sendiri sebab dia mengajak Jennie membuka restoran bersama tanpa persiapan, namun hanya itu satu-satunya yang melintas di pikirannya tadi.
"Bagus lo udah pulang, karena gue butuh—" Kata-kata Jef terputus kala dia menyadari wajah Sashi yang sembab, juga matanya yang merah. Dahinya kian berlipat saat Jo menyusul di belakang gadis itu. Dia tidak lagi mengenakan jasnya, hanya kemeja putih yang sudah tidak dimasukkan. Jef tidak dekat dengan Jo, tapi dia tahu bagaimana lelaki itu selalu berpenampilan rapi dan pantas dalam segala situasi. "Kenapa?"
"Nggak apa-apa."
"Jelas lo kenapa-napa—" Sashi mengabaikan ucapan Jef, langsung bergerak menuju tangga. Jef mendengkus, terlalu mumet untuk berpikir lebih panjang sebelum lanjut berseru. "Gue masih ngomong sama lo!"
Sashi tersentak mendengar nada tinggi dalam suara Jef, refleks berhenti di mulut tangga. "Apa?"
"Kalau ditanya orang tua itu jawab yang benar!"
"Bisa nggak, berantemnya dialihkan ke besok aja? Aku capek."
"Gue—"
"You can go to your room, Acacia." Jo memotong, membuat Sashi menghela napas panjang diikuti kakinya yang terayun menapaki tangga. Jef melotot kesal pada Jo, tapi Jo hanya berdeham, sengaja menunggu hingga Sashi sepenuhnya tiba di lantai dua, baru berujar dalam suara pelan. "She had a mentally tiring day. Give her a break, I beg you."
"Kenapa?" Jef menuntut jawaban, sejenak lupa pada draft proposalnya yang baru memiliki dua kalimat.
"Later." Jo menyahut singkat, hampir tanpa ekspresi sebelum berlalu menuju kamarnya sendiri.
Jef mengepalkan tangan, menahan geram yang kini memenuhi dadanya. Tapi dia mencoba bersabar. Masalahnya dengan Jennie sudah cukup rumit, tak perlu ditambahi dengan pertengkaran lain. Maka Jef kembali menghempaskan badan di sofa, berupaya berkonsentrasi pada layar. Bantuan Sashi tidak bisa diharapkan, jadi dia mesti mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini.
Ini soal tawaran membuka restoran yang telah dia katakan pada Jennie. Perempuan itu tidak langsung menolak, tapi juga tidak menunjukkan tanda-tanda jika dia berencana menerima. Dia memberi Jef syarat agar tawarannya bisa dipertimbangkan; Jef harus menemuinya besok, di jam makan siang, sambil membawa proposal kerjasama yang telah diketik dan dicetak rapi.
Sumpah, terakhir kali Jef dikejar deadline adalah waktu dia kuliah dan itu sudah belasan tahun silam.
Tadinya, dia ingin minta pertolongan Sashi. Meski rada bawel juga jahil, Sashi tampaknya adalah pribadi yang penuh ide-ide cemerlang. Tapi menilik dari raut mukanya tadi juga ucapan Jo, rasanya tidak mungkin. Jef membuang napas kesal, menarikan jari-jarinya di atas keyboard laptop hingga menimbulkan suara keras pemecah keheningan. Lalu jarinya menekan tombol backspace berkali-kali.
Dia menyerah, memilih membuka kontak ponselnya dan menelepon Dery. Kelihatannya, Dery memang sesuka itu pada anak perempuannya. Tak butuh lebih dari tiga detik buat Dery untuk mengangkat telepon dari Jef.
"Selamat malam, Om." Nada suara Dery kaku, persis ajudan TNI yang tengah memberi salam pada presiden.
"Malam. Langsung aja ya, gue mau nanya."
"Nanya apa, Om?"
"Lo sama Juanda pinteran mana?"
"Hah?"
"Hah-hoh-hah-hoh aja. Kayaknya emang pinteran Juanda daripada lo ya."
"Nggak, Om! Ampun!" Dery hampir panik. "Tergantung dalam apa dulu, Om, pinternya. Kalau olahraga, jelas lebih jago saya. Kalau soal hitung-hitungan, mohon maaf, Om, ngitung saldo rekening bank saya aja saya suka kesusahan."
"Nek ngono podho wae karo aku. Yawes, sek aku telpon Juanda."
"TUNGGU OM—"
"Apa lagi?"
"Saya memang nggak lebih pintar dari Juanda, Om, tapi tekad saya lebih kuat!"
"Cuma itu doang?"
"Ada satu lagi."
"Apa?"
"Bapak saya lebih tajir."
"Hm, bisa dipertimbangkan." Jef batal memutus telepon. "Gue butuh bantuan buat bikin proposal. Lo bisa nggak? Harus dibawa ke orang yang berkepentingan besok, pas jam makan siang."
"Wah, saya belum pernah bikin proposal, Om. Kan masih kecil..."
"Juanda tuh pengurus OSIS ya kalau nggak salah? Kayaknya bisa dia—"
"—TAPI DENGAN BAPAK SAYA, NGGAK ADA YANG NGGAK BISA, OM!"
"Maksudnya?"
"Om butuh bantuan buat bikin proposal? Kapan dan di mana maunya?"
"Di McDonald's dekat rumah gue aja, deh. Soalnya suasana rumah gue lagi nggak enak terus bahaya kalau di sini ntar lo sekalian modusin anak gue." Jef menukas seenaknya. "Terus lo masih nanya kapan? Sekarang lah, Bedul! Masa tahun depan!"
"Siap, Om! Tim akan meluncur ke TKP seenggaknya setengah jam lagi!"
"Oke—wait, tim apaan?!"
Terlambat, Dery sudah menyudahi telepon.
*
Menjelang jam sembilan malam, Jo keluar dari kamarnya dengan gelas kaca tebal berisi lilin dengan tabung penutupnya. Lelaki itu meletakkannya di meja hias kayu yang berada tidak jauh dari pintu kamarnya, lantas menyalakannya. Api lilin yang jingga meliuk, tak besar namun menyala terang. Jo baru saja menyatukan tangannya, berniat berdoa untuk Tris. Tapi perhatiannya sudah lebih dulu tersita oleh suara langkah seseorang di belakangnya.
"No, please don't mind me." Sashi berujar sewaktu Jo menoleh.
"It's okay. Come here." Jo tersenyum, menyuruh Sashi mendekat dengan gerakan tangan. Gadis itu menurut, berhenti di sebelah Jo. Mereka tidak berkata apa-apa, menghabiskan beberapa menit dalam kesenyapan, berdoa untuk seseorang yang telah berada di dimensi yang berbeda. Berharap sepi tidak mengurungnya dan semoga, sakit tidak lagi menyertainya.
"I just realized that you love her that much." Sashi berkata setelah mereka selesai berdoa. "I envy her."
"Mm-hm, kenapa?"
"Because she had you, Papi."
"You have me too, baby girl."
Sashi menunduk sebentar, merasa kecemasan itu menusuk perasaannya lagi. Namun akhirnya dia mencoba menguatkan diri dan mengangkat wajah, berupaya keras agar dapat bicara dengan suara yang teguh, tanpa getar yang biasa muncul setiap kali dia hampir menangis.
"Udah malem. Papi harus istirahat."
"I will."
"No, let me tuck you to bed."
Sashi meraih tangan Jo, menarik laki-laki itu kembali ke kamarnya. Jo tertawa kecil, membiarkan Sashi memimpin jalan dan menyuruhnya berbaring di atas ranjang. Sashi ingat, waktu mereka baru pertama kali tiba, kamar itu tidak jauh berbeda dengan kamar-kamar lainnya yang terdapat di rumah ini. Ukurannya besar, dilengkapi lemari, ranjang bertiang yang dihiasi kelambu tipis layaknya tempat tidur model jaman dulu, toilet dan beberapa lukisan abstrak yang menggantung. Namun sekarang, Sashi bisa melihat bagaimana Jo telah menempatkan fotonya bersama Sashi dan Tris di atas nakas, juga foto lainnya dalam pigura yang tersemat ke dinding.
"Oke, Papi udah di kasur dan siap tidur sekarang."
Sashi duduk di tepi tempat tidur Jo usai menarik selimut hingga menutupi dada ayahnya. "Aku tahu, tapi aku bakal tetap di sini sampai Papi tidur. Jadi kalau Papi mau aku pergi, Papi harus tidur dulu."
"To be honest, I don't want you to leave. Jadi inget, dulu waktu masih bayi, kamu seringnya baru bisa tidur kalau udah dipeluk."
"Masa?"
Jo mengangguk. "Dan nggak mau dipeluk sama yang lain, maunya dipeluk sama Papi."
Sashi nyengir, tiba-tiba merasa malu. Pipinya mulai dijalari rona. "Maaf."
"Nggak perlu minta maaf. Jujur Papi senang, soalnya ada alasan meluk kamu tiap malam. Kayak punya teddy bear, tapi teddy bearnya bisa nangis... bisa cegukan... bisa ngompol."
"Aku pernah ngompol?"
"Sering."
"... untung sekarang udah nggak."
"Untungnya begitu." Jo tertawa renyah. "Terus sejak ikut kelompok bermain, kamu punya teman-teman baru. Lebih suka main sama boneka Barbie. Terus kenal sama Mandala. Lama-lama kamu jadi jauh dari Papi dan nggak mau dipeluk lagi."
"Papi juga sibuk di kantor." Sashi langsung membela diri.
"Iya, Papi juga sibuk di kantor." Papi mengiakan. "Kadang Papi berharap, kamu tuh bayi aja selamanya. Kalau sekarang kan sudah gede. Dipeluk-peluk juga nggak bisa sering kayak dulu."
"Bayi kerjaannya nangis doang, Pi. Bikin repot."
"Papi nggak pernah ngerasa direpotin sama kamu."
"Masa? Bohong. Dimana-mana, orang pasti nganggep anak yang kerjaannya nangis doang, makan harus disuapin, suka ngompol sembarangan tuh ngerepotin, Pi. Aku bayanginnya aja udah pusing duluan, apalagi beneran ngerawat bocah yang kayak gitu!"
"Mungkin memang merepotkan, tapi Papi nggak ngerasa direpotkan. Mau tahu kenapa?"
"Mm... kenapa?"
Tatapan Jo melembut waktu dia menjawab lagi. "Because you're my daughter and I love you."
Sashi menunduk, menggigit bibirnya dan mesti memaksakan senyum saat dia menyahut. "I love you too. I want to say I love you more, but I know it's impossible to love you more than you do to me. So, please stay close to me, Papi. For a super long time."
"Papi kan sudah bilang—"
"Nggak, aku nggak mau Papi menjanjikan apa pun ke aku. Papi nggak perlu bilang apa-apa. Papi hanya perlu tetap dekat, seterusnya ada dan sama-sama aku untuk waktu yang sangat lama. Oke?"
Jo mengangguk. "Oke."
*

Jika diukur dari harta, kekayaan Keluarga Gouw memang tidak kalah dengan harta-benda milik Keluarga Sunggana, namun ditilik dari koneksi dan kecerdasan—atau mungkin lebih tepat dibilang kelicikan—jelas Keluarga Sunggana juaranya. Jef bahkan tidak tahu jika ada yang namanya tim joki professional untuk menyelesaikan proposal dalam satu malam—dimana tim tersebut berisikan orang-orang hebat pada bidang terkait dan bersedia memenuhi deadline ala Roro Jonggrang dengan bayaran yang selangit.
Jef hanya perlu datang ke tempat janjiannya untuk bertemu tim—yang kedatangannya dipimpin langsung oleh Dery—menjelaskan situasi dan proposal apa yang dia mau lalu besok pagi, tim akan mengirimkan proposal yang telah dicetak rapi ke tempat Jef berada via go-send. Jef dibikin takjub, walau jelas dia tidak bisa menunjukkannya terang-terangan.
Setidaknya, skor Dery jadi naik satu persen lah jika dibandingkan dengan Ojun.
Jef sempat makan McFlurry bareng Dery sebelum pulang. Bocah itu mungkin baru menginjak usia delapan belas tahun, tapi Jef bisa melihat dia punya bakat manipulatif yang sama besar dengan Tedra. Bedanya, Tedra itu shameless sampai-sampai terkesan tidak tahu malu, sedangkan Dery masih punya urat malu sedikit.
Sedikit.
Setelahnya, Jef kembali ke rumah, hanya untuk disambut oleh suasana sepi. Dia sempat iseng berjalan ke arah kamar Jo, mendapati ada lilin besar yang telah dinyalakan, ditempatkan di atas meja hias tepat di bawah bingkai foto berisi wajah tersenyum Tris yang sengaja mereka gantung di sana. Pasti Jo yang menyalakannya.
Jef mereguk ludah, menatap pada foto Tris sebelum dengan ragu, dia mendekati lilin tersebut. Jef bukan orang yang religius. Bisa dihitung jari berapa kali dia berdoa dalam setahun. Tapi malam ini, dia menyatukan tangannya, membisikkan kata-kata yang dia harap bisa mencapai seseorang yang sekarang telah berada di dunia yang berbeda.
"Father of all, I pray to you for Patricia, for someone whom I love but see no longer. Grant to her eternal rest and let light perpetual shine upon her. May her soul, through the mercy of God, rest in peace. Amen."
Usai menyelesaikan doanya, Jef membuka mata. Wajah tersenyum Tris lagi-lagi menyambutnya. Jef memandang foto itu beberapa lama, lalu perlahan senyumnya tertarik, memunculkan dua dekik dalam di kedua sisi wajahnya.
"I miss you everyday, Tris."
Perhatian Jef tersita oleh suara berisik yang terdengar tiba-tiba, datang dari arah dapur disusul gerutuan seseorang. Dia pun memutar langkahnya menuju sumber suara, hanya untuk mendapati Sashi tengah berjinjit, mencoba menggapai wadah susu bubuk yang ditempatkan Jef di rak paling tinggi. Jef berdecak, berjalan mendekati anak perempuannya dan dengan mudah meraih wadah susu bubuk yang hendak Sashi ambil.
"Anaknya siapa sih? Pendek banget."
Sashi merengut, menerima wadah susu yang Jef ulurkan dan mendekapnya ke dada. "Anaknya Mami aku."
"Emang Mami kamu bisa bikin anak sendiri?"
"Anaknya Mami sama Papi aku."
"Heh!"
"Habisnya, malah ngeledekin! Lagian cewek tuh walaupun pendek juga nggak apa-apa kali, Dad! Kan bisa pake high heels."
"Mau nyusu ya?"
"Mau bikin susu."
"Sama aja, itu namanya mau nyusu." Jef merebut wadah susu dari tangan Sashi, membukanya dan menuang beberapa sendok ke gelas.
"Emang Daddy bisa bikin susu?"
"Jago ngocok susu, malah."
"Ih, menjijikkan."
"EMANG LO MIKIR APA?" Jef mendelik. "Chef ya harus jago ngocok susu, apalagi kalau lagi bikin dessert atau kue-kue-an! Jennie tuh lebih jago lagi dari gue karena emang concern dia lebih ke kue-kue dan pastry!"
"Oh, kirain yang lain."
"Emang yang lain apaan?"
"Masa cowok brengsek kayak Dad nggak ngerti."
"Ck." Jef berdecak, menambahkan air panas dari dispenser dan mengaduk susu agar larut dengan gula menggunakan sendok. "Mau sekalian dibikinin cookies apa nggak?"
"Lah, bisa?"
"Bikin cake red velvet aja bisa, bikin cookies mah urusan gampang."
"Oh." Sashi tercengang saat kata-kata Jef justru membuatnya menyadari sesuatu yang lain. "Ngomong-ngomong soal kue red velvet—jangan bilang kalau kue ulang tahunku waktu itu—"
"KUE ULANG TAHUN APA?!" Jef panik.
"Waktu aku ulang tahun, ada yang bikinin kue red velvet."
"Jelas bukan gue."
Mata Sashi menyipit. "Aku juga nggak bilang kalau itu Daddy dan jujur, nggak kepikiran kesana."
"Emang bukan gue."
"Tapi karena reaksi Daddy sekarang, aku jadi kepikiran kesana."
"BUKAN GUE!" Jef masih saja ngeles.
"Iya juga nggak apa-apa kok."
"BUKAN GUE!"
"Iya, iya, bukan Daddy, iya." Sashi mengalah. "Tapi kalau Dad mau bikin cookies, aku mau! Tapi bukannya bikin cookies tuh lama?"
"Lama, kalau yang bikinnya nggak jago alias amatiran."
"Berarti Dad barusan ngatain Mami." Sashi melipat tangan di dada. "Soalnya Mami kalau bikin cookies tuh lama."
"YA NGGAK GITU JUGA!"
"Jangan nge-gas dong, Dad. Muncrat."
"Nggak apa-apa, muka lo kalau kena iler gue tambah cakep."
"IEW."
Jef justru merunduk sambil tertawa kecil, membuat lesung pipinya kembali tampak jelas. Sashi tahu, ayahnya yang satu ini memang setampan itu. Namun ketampanannya meningkat berkali-kali lipat saat dia tersenyum seperti sekarang. Kini, Sashi mengerti kenapa mendiang ibunya bisa sejatuh itu pada Jef sampai-sampai tetap tidak mampu melupakan lelaki ini meski telah memiliki seseorang seperti Jo dalam hidupnya.
"Tunggu aja di ruang tengah." Jef berkata usai dia mengeluarkan bahan-bahan untuk membuat kue dari laci pantry dan beberapa lainnya dari kulkas.
Sashi justru naik ke stool tinggi yang sengaja Jef tempatkan menghadapi meja marmer dapur. "Aku mau lihat Dad masak."
"Bayar."
"Pake cium pipi?"
Jef berhenti menata barang-barang di atas meja marmer, ganti menyipitkan matanya pada Sashi. "You know my weakness so damn well, don't you?"
"Iseng doang, tapi ternyata Dad memang semurahan itu."
Jef menyentakkan kepala. "Terserah."
"Sambil ngomong dong, Dad. Kayak chef di tivi-tivi."
"Bawel." Jef menggerutu, tapi tetap menjelaskan. "Biar cepat, gue mau bikin cookies yang simpel aja. Bahan-bahan yang kita butuhkan tuh ada cooking cream—"
"Whipped cream sama cooking cream sama?"
"Sama aja, tapi whipped cream lebih lembut." Jef menjawab. "Selain itu kita juga perlu butter, gula, telur, vanilla, tepung, baking soda, baking powder dan choco chips."
"Terus?"
"First of all, panaskan oven ke suhu 375 derajat Fahrenheit—atau sama dengan berapa derajat Celcius, Acacia?"
"Loh, kok jadi ujian mendadak?!"
"Sekalian ngetes kemampuan otak lo. Kalau bodoh, berarti lo bukan turunan gue atau turunan nyokap lo. Soalnya jaman sekolah dulu, kita sama-sama pinter."
"Dad nyadar nggak, muka aku tuh carbon copynya kalian. Nyadar, nggak?"
"Jawab aja!"
"Hng... 190 derajat Celcius?"
"Pinter." Jef berdecak seraya menggulung kedua lengan bajunya hingga sebatas siku, lalu mencuci tangannya pada wastafel yang berada tidak jauh dari meja marmer dan setelahnya, baru meneruskan kembali memasak. Geraknya gesit dan teratur. "Sambil nunggu oven panas, ambil mangkuk kecil dan campurkan tepung—baking soda, baking powder. Taro dulu di samping dan kita beralih ke mangkuk besar."

(mam tuh tangan daddy)
"Dad kayak chef beneran kalau lagi masak."
"GUE EMANG CHEF BENERAN!"
"Hehe, santuy, Dad! Kita lagi mau bikin cookies, bukan bakso. Nggak usah pake urat!"
Jef mendelik, lanjut mencampurkan bahan-bahan ke mangkuk yang lebih besar. "Dalam mangkuk besar ini, kita bikin campuran cream, butter dan gula. Kocok sampai smooth." Jef mulai mengocok secara manual, membuat Sashi bertepuk tangan takjub karena kekuatan lengan ayahnya jadi terlihat jelas.
"Dad ganteng kalau lagi kayak gitu, tapi bisa nggak sih pake mixer aja?"
"Bisa."
"Terus kenapa nggak pake mixer?"
"Sengaja, biar dibilang ganteng."
"Idih, narsis!" Sashi mencibir dan Jef hanya tersenyum sambil meneruskan mengocok campuran bahan hingga mencapai kondisi yan dia inginkan. "Masukkan telur—" Jef membenturkan cangkang telur ke tepi mangkuk, menjatuhkan isinya ke dalam mangkuk dengan luwes, lanjut menambahkan vanilla. Jef melanjutnya mengocoknya lagi, lalu perlahan mencampurkan bahan kering yang terdiri dari tepung, baking soda dan baking powder. Di akhir, choco cips turut bergabung ke dalam mangkuk Dia melakukannya dengan cepat, lanjut meraih sendok dan membuat adonan ke dalam bentuk bola-bola yang lantas dipipihkan. Setelahnya, Jef beralih mengeluarkan cookie sheets, membentangkannya di atas tray.
"Terus habis itu dimasukkin ke oven?"
"Yes." Jef membenarkan pertanyaan Sashi seraya memasang sarung tangan tahan panas, meraih tray dan menempatkannya dalam oven. "Kita tunggu selama delapan sampai sepuluh menit dan selama itu, sisa waktunya bisa dipakai membereskan station yang kita pakai buat memasak." Jef berujar sambil menumpuk mangkuk-mangkuk dan alat masak yang tadi dia gunakan, membawanya ke wastafel dan mencucinya di bawah guyuran air. Hanya dalam waktu singkat, tidak tersisa jejak yang menunjukkan jika meja marmer dapur habis digunakan untuk memasak.
Timer oven mengeluarkan suara denting saat waktu sepuluh menit sudah berlalu. Jef mengeringkan tangannya pada handuk di sisi wastafel, kembali mengenakan sarung tangan tahan panasnya dan mengeluarkan tray berisi cookies yang sudah matang dari dalam oven. Bau manis yang enak memenuhi ruangan dan Sashi hampir saja bertepuk tangan keras-keras.
"Let them cool down for two minutes." Jef berkata seraya melepas sarung tangan tahan panas dari tangannya. "Selama itu, kita bisa beresin sisa bahan yang berlebih."
"Sumpah, Dad jadi kelihatan kayak orang bener." Sashi berkomentar usai Jef memasukkan lagi wadah butter ke dalam kulkas dan meneruskan menempatkan cookies yang telah mendingin ke atas piring. "Bersih dan teratur. Coba hidup Dad juga kayak gitu."
"Justru itu, kalau hidup gue juga bersih dan teratur, gue nggak bakal butuh lo."
"Kok gitu?"
"Kan lo dikirim Tuhan buat bikin hidup gue jadi bersih dan teratur." Jef mengedikkan bahu sambil tak berhenti memindahkan cookies dari tray. "To be honest, gue nggak tahu apa yang mau gue lakukan dengan hidup gue selain well, you know, bersenang-senang seakan gue bakal muda selamanya. But then you came, and transformed into a purpose of my life."
"Emang sekarang tujuan hidup Dad apa?"
"Ada, deh."
"Daaaaaadddd..." Sashi mulai merengek.
"Oke, gue jawab, tapi jangan ge-er ya? Dan dengar baik-baik, soalnya gue hanya bakal bilang ini satu kali."
"Iya, apa?"
"Hm."
"Dad!"
Jef terkekeh, namun kemudian ekspresi wajahnya berubah serius. "To live a happy life with my daughter."
"What?"
"Nggak ada siaran ulang." Jef memindahkan tray ke sisi lain meja sebelum meraih gelas susu yang sudah menghangat. "Cobain susunya, gulanya pas nggak? Harusnya sih pas ya."
Sashi meraih gelas yang Jef letakkan di depannya, menyeruput seteguk. Itu adalah susu paling enak yang pernah dia minum. Takaran gulanya pas, begitu juga suhunya yang sudah tidak terlalu panas karena telah didiamkan hampir setengah jam. Jelas soal memasak, kemampuan Jef dan Jo ibarat langit dan bumi.
"Enak."
"Good." Jef membawa piringnya ke ruang tengah dan Sashi mengikuti sembari menggenggam gelas susunya menggunakan kedua tangan. Ada sofa di ruang tengah, namun Jef dan Sashi memilih duduk bersila di atas karpet. Mereka menyalakan televisi, menyetel sinema tengah malam yang tengah disiarkan sambil makan cookies—atau lebih tepatnya, hanya Sashi yang makan cookies sementara Jef menontonnya seolah gadis itu adalah atraksi menarik SeaWorld.
"Dad, filmnya di depan, bukan di samping!"
Jef justru membalasnya dengan kata bernada hati-hati. "So, will you tell me about what happened today?"
Sashi berhenti mengunyah cookiesnya. "Maksudnya?"
"Lo bukan tipe yang bakal turun ke dapur tengah malam hanya untuk bikin susu dan kalau lo melakukannya, itu berarti lo nggak bisa tidur. Jadi, kenapa?"
Sashi terdiam, kelihatan ragu-ragu.
"Gue tahu gue bukan orang paling menyenangkan di dunia, tapi lo bisa percaya gue." Jef menghela napas. "I am your father, remember that?"
"Ini... soal Papi."
"Kenapa lagi ama tuh orang?"
Dengan nada getir, Sashi bercerita soal cedera punggung yang Jo alami karena kejadian yang menimpa mereka di Jepang waktu itu. Juga kemungkinan-kemungkinan terburuk dan prosedur penyembuhan yang mesti Jo jalani. Jef mendengarkan tanpa menyela, lantas di luar dugaan, setelah Sashi menyelesaikan ceritanya, lelaki itu beringsut mendekat untuk memeluk Sashi dengan erat.
"Aku... takut Papi bakal kenapa-napa." Sashi berbisik di dada Jef.
Jef mengubur jarinya di rambut Sashi, mendekap gadis itu sedemikian rupa hingga tubuh mungilnya seakan terlindung dalam sangkar. Rahang Jef menyentuh puncak kepala gadis itu. "If something happens to him, will it make you unhappy?"
Sashi mengangguk masih dalam pelukan Jef.
"If so, then I will never let it happen, because your happiness is important to me."
"Tapi—"
"Sshh—don't worry. Everything will be alright. Even if I have to fight the grim reaper for your sake, I'll do it without second thought. Trust me, okay?"
Sashi akhirnya mengangguk.
Harus Sashi akui, cara Jef memeluknya dan kata-kata pria itu berhasil membuatnya lebih tenang. Perasaannya jauh lebih baik usai dekapan mereka terlepas. Mereka lanjut menonton film dan menghabiskan cookies yang tersisa, sempat berdebat tentang hal-hal kecil dalam film sampai akhirnya, Sashi jadi yang ketiduran lebih dulu.
Jef membawanya ke kamar, menggendongnya seperti membawa boneka kain dan meletakkannya dengan hati-hati di atas ranjang. Dia menarik selimut, menyempatkan diri menunduk dan menjatuhkan kecupan di kening Sashi.
"Sleep tight, anak Ayah."
*

Dery tidak berbohong.
Proposal yang Jef inginkan diantarkan sebelum jam sembilan pagi ke rumahnya, sudah diketik dan dijilid rapi, dilengkapi rincian pembiayaan, pasar yang disasar, opsi lokasi beserta nama—yang Jef tahu konyol, tapi bisa dikoreksi nanti.
Sekarang, kemungkinan Jef untuk lebih merestui Dery daripada Ojun naik lagi—tapi tetap, naiknya tidak lebih dari satu persen.
(Dery sih tidak merasa dirugikan ya soalnya buat dia, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit).
Terimakasih atas bantuan Dery dan ayah gendhengnya yang tajir-melintir, Jef bisa membawa proposal tersebut ke apartemen Jennie sebelum jam makan siang. Selepas dari Jepang, Jef memang tidak terlalu banyak melakoni pekerjaan. Dia hanya mendatangi acara atau melakukan pengambilan gambar untuk brand-brand besar yang memang telah mendapuknya sebagai brand ambassador. Dia rehat sejenak dari urusannya di channel Youtube dan berhenti menerima endorsement—yang sebetulnya tidak dia butuhkan banget berhubung Keluarga Gouw itu tergolong salah satu keluarga terkaya di Asia. Jennie juga tidak sibuk, soalnya kan sudah jadi pengangguran.
Jennie ogah bertemu di apartemennya. Katanya, mereka perlu bicara di zona netral. Jadi Jef menunggu di kafe yang berada di lantai dasar apartemen Jennie.
Orangnya muncul sekitar sepuluh menit kemudian, dengan setelan piyama, sandal bulu dan bando kuping kucing yang terus terang saja, Jef anggap cute setengah mati.
"Mana proposalnya?" Jennie menukas malas seraya menarik kursi dan duduk di depan Jef. Jef nyengir, meletakkan proposal di depan Jennie. Jennie mengernyit, menatap curiga seraya membuka halaman pertama dan bertanya-tanya kenapa hari ini, Jef lebih wangi dari biasanya. Rambutnya juga disisir sedemikian rupa, menyisakan sejumput rambut jatuh di keningnya, mencipta poni berbentuk koma. Dahinya terlihat, membuat Jef tampak berwibawa. "Siapa yang bikinin?"
"Gue bikin sendiri."
"Bohong."
"Dibantuin Sashi."
"Kalau itu, baru gue percaya. Anak lo pintar soalnya, nggak kayak lo." Jennie berujar pedas. "Tapi apaan nih namanya? J's Pantry? Kagak ada nama yang bagusan?"
"Restoran ini bakal jadi bisnis kerja sama kita. Jennie. Jeffrey. J's Pantry kedengeran mewakili."
"Kayak restoran yang jualan ayam goreng buat anak SD." Jennie mengkritik. "Siapa yang ngasih nama?"
"Sashi."
"Oh, ralat, gue rasa namanya nggak seburuk itu."
YEU DASAR.
"Gue memenuhi syarat lo. Jadi sudah sepatutnya lo memenuhi kata-kata lo."
"Fine." Jennie mengedikkan bahu. "Tenang aja, gue orangnya fair, kok. Makanya gue juga udah menghubungi Theo dan minta dia datang ke sini siang ini. Biar sekalian lo berdua gue hadirkan dan dengar keputusan gue."
"You what—" Jef terperanjat, tapi kata-katanya tidak tersambung kala dia melihat sosok Theo yang baru turun dari mobil, tengah melangkah menuju pintu kaca kafe. Spontan, Jef mengulurkan tangannya untuk menangkup kedua sisi wajah Jennie.
"What are you doing—"
"I have to be honest that all these years, I've been thinking of you as someone more than a friend." Jef berujar cepat, membungkuk untuk mencium Jennie di bibir. Bibir mereka bertemu, saling bertaut dan untungnya, kafe sedang sepi ketika itu terjadi—atau bisa-bisa, video ciuman Jennie dan Jef pasti sudah berseliweran di sosial media sore nanti.
Theo kontan melotot, batal meraih pintu dan membeku di depan kafe.
Mata Jennie yang terpejam baru terbuka lagi setelah Jef menarik wajahnya, diam-diam lega sebab Theo batal masuk dan malah berbalik, menjauhi pintu kafe.
"Sorry, I was—"
"Foolish jancok, indeed." Jennie merutuk, lalu meraih kerah baju Jef, menariknya untuk menciumnya lagi. Kali ini, ciuman mereka berlangsung lebih lama. Jennie tidak peduli sekalipun ada yang melihat. Jef awalnya terkejut, tapi pada akhirnya dia tersesat ke dalam mantra yang ditebarkan Jennie melalui gerak bibirnya. Napas mereka hampir habis ketika bibir keduanya terpisah dan Jennie bergumam samar pada dirinya sendiri. "Damn, I know it, we're going to make a mess."
"A lovely mess. Now shut up and kiss me again."
"Silly." Jennie menempatkan jari telunjuknya di bibir Jef. "Let's save the talk for later and go to my bedroom instead."
"Oh well—but—"
"Kenapa?"
"—I didn't bring any condom."
"I have some... in your size."
*

Dery benar-benar tidak bisa menahan emosinya usai melihat apa yang baru saja dia saksikan. Dalam hati, dia bersyukur Sashi tidak ada di sana, karena bahkan tanpa kehadiran Sashi, darahnya serasa telah mendidih. Dia menunggu dengan tangan terkepal di luar area kolam renang indoor, sengaja menunggu hingga Ojun keluar melalui pintu dengan seragam dan rambut yang basah. Sisa-sisa kepanikan masih tampak di wajah Ojun dan terus terang saja, itu membuat Dery kian muak.
Hanya sejenak setelah Ojun keluar, Dery langsung menarik tangan cowok itu. Ojun terkejut, meringis ketika Dery menyudutkannya ke tembok. Suaranya keras, sehingga bisa dipastikan punggung Ojun pasti terasa sakit. Suara ribut-ribut yang mereka timbulkan menarik perhatian siswa lainnya yang berada di sekitar area kolam renang sekolah, termasuk Felix yang langsung beranjak dan melangkah keluar dengan kepala dijejali tanya.
Dery tidak peduli.
"Mau lo apa?!"
Ojun menyipitkan matanya pada Dery. "Maksud lo apa?"
"Gue tanya, mau lo apa?!"
"Apanya?!"
"Lo suka Sashi atau nggak?!"
"Itu bukan urusan lo." suara Ojun dingin saat dia menyahut. Matanya yang dinaungi sepasang alis tebal menatap tajam ke kedalaman mata Dery.
"Itu jadi urusan gue! Lo mau tahu kenapa?! Karena barusan gue lihat lo menatap dan bicara sama cewek lain dengan cara yang berbeda! Kalau lo nggak sesuka itu sama Sashi, jauhin dia!"
"Kenapa lo peduli?" Ojun memiringkan wajah, lalu tawanya yang terkesan melecehkan pecah. "Ah ya, I see. Cinta yang bertepuk sebelah tangan sama sahabat lo sendiri, eh?"
"Gue—"
"Apa yang ada antara gue dan Tamara, itu bukan urusan lo." Ojun berkata. "Begitu juga apa yang ada diantara gue dan Acacia. Nggak usah sok tahu dan nggak usah sok pahlawan, oke?"
Dery menjawab ucapan Ojun dengan melayangkan tinju ke wajah cowok itu sedetik setelahnya.
Bonus -1-
Erina tidak berpikir apa-apa ketika Jajang mengajaknya makan lasagna di restoran favoritnya siang ini. Meski sering jadi bahan ledekan, Jajang sangat dekat dengan ketiga anaknya. Dia bisa tahu ada sesuatu yang salah dengan mereka hanya dengan memperhatikan gerak-gerik ketiganya. Dia sempat bertanya pada Talitha, tapi Talitha menyuruhnya bertanya langsung pada Erina. Dia juga mencoba mengorek informasi dari Felix—yang paling jago bergosip diantara saudara-saudaranya yang lain, namun apa yang Jajang dapat justru di luar dugaan.
Felix malah bilang. "Felix tidak bisa ikut-ikutan urusan Mbak Erina, Papa. Lebih baik Papa langsung tanyakan pada Mbak Erina."
Jadilah, Jajang sengaja mengajak anak sulungnya makan siang bersama hari ini.
"Mbak, Papa mau tanya sesuatu, deh."
"Mmm... tanya apa, Pa?"
"Akhir-akhir ini kayaknya kamu banyak pikiran." Jajang memulai, tampak sekali berhati-hati. "Ono masalah karo Mama atau masalah karo cemewewmu seng jare Felix mirip kingkong kui?"
"Soal Lucas..." Erina menghela napas panjang. "Aku mau cerita, tapi Papa janji nggak akan marah ya."
"Memangnya kapan Papa pernah marah sama kamu?"
Erina nyengir. "Nggak pernah, sih. Soal Lucas... Papa tahu kan dia orangnya baik."
"Iya. Terus?"
"Terus lebih ganteng dari Papa."
"Oalah, wuasem." Jajang bereaksi spontan. "Iya. Terus kenapa?"
"Dan meski nggak sekaya keluarga kita, Lucas itu pekerja keras dan penyayang."
"Iyo, Ndhuk. Papa wes reti kalau bagi kamu, kingkong kui iku segalanya. Terus kenapa?"
"Lucas nggak ke gereja, Pa."
"Oh, dia malas ke gereja? Nggak apa-apa, sih. Namanya masih muda. Dulu, Papa juga suka gitu."
"Bukan, Pa. Duh... gimana ya jelasinnya..." Erina menggigit bibir. "Gini, Papa tahu Istiqlal sama Katedral nggak?"
"Tau lah, Papa kan ndak hidup di bawah batu!"
"Aku Katedral, Lucas Istiqlal, Pa."
"Lah, bukannya kalian berdua tuh orang?"
"PAPA!"
"Sek, sek, piye maksudmu?"
"Aku sama Lucas beda agama, Pa."
"OALAH."
"Kok oalah?"
"Habisnya Papa nggak tahu harus ngomong apa."
"Papa marah ya?"
"Nggak sama sekali." Jajang menggeleng. "Papa tahu, perbedaan yang seperti ini itu perbedaan yang berat, karena urusannya sudah ke masalah kepercayaan. Tentang Tuhan yang kalian yakini. Sebagai ayah kamu, Papa tentu berharap kamu dapat pasangan hidup yang seagama. Tapi Papa juga ngerti, kamu manusia mandiri. Kamu punya hak menentukan hidupmu sendiri, karena Papa dan Mama nggak pernah memiliki kamu. Kamu memang anak kami, tapi kamu juga manusia merdeka, Erina."
"Aku... sayang banget sama Lucas, Pa."
"Papa tahu, kok. Soalnya Papa juga sesayang itu sama Mama." Jajang tersenyum penuh pengertian. "Kalau kata Papa, jalani saja dulu. Pada akhirnya, keputusan ya nanti kalian yang menentukan. Apakah kalian mau sama-sama dengan tetap percaya pada Tuhan masing-masing, atau Lucas ikut kamu, atau kamu ikut Lucas, Papa nggak bisa melarang. Kembali lagi,kamu punya hak menentukan hidupmu sendiri. Papa dan Mama hanya bisa memberi saran dan berharap yang terbaik untuk kamu. Papa mau kamu bahagia."
"..."
"Lagian, pasangan adalah satu-satunya anggota keluarga yang bisa kamu pilih, Nak. Papa mau kamu memilih sesuai keinginan hati kamu."
"Papa... nggak takut masuk neraka karena aku atau aku yang masuk neraka karena suka sama orang yang berbeda agama?"
"Erina, saat kita memilih satu kepercayaan, kita otomatis masuk neraka menurut kepercayaan lain yang tidak kita percayai. Mana yang benar? Kita nggak pernah tahu. Kita meyakini apa yang menurut kita pas di hati."
"... aku ngerti sekarang."
"Ngerti apa?"
"Ngerti kenapa Mama secinta itu sama Papa padahal Papa tuh jamet banget."
"Lambemu, Ndhuk."
Erina nyengir, beranjak dan memeluk Jajang. "Makasih ya, Pa."
"Anytime, Sayang." Jajang mengusap bahu Erina.
Bonus -2-
"Mas Awan nggak balik ke Jakarta lagi summer break ini?"
"Nope."
"Mas Awan jahat!" Trea menggerutu lewat telepon. "Mas Awan betah amat sih di sana! Udah kecantol bule Amrik ya?! Inget apa kata Mommy! Mommy nggak mau punya mantu bule!"
"Salah tuh, yang bener, Mommy nggak mau punya menantu white people!" Awan menukas ucapan Trea sambil terkekeh. "Kalau american born-chinese, Mami mau-mau aja, kok!"
"Nyebelin banget Mas Awan!"
"Emang kenapa sih pengen banget Mas pulang?"
"Mau kupamerin di kafeku yang buka bulan Mei nanti! Lumayan kan pasti pengunjung meningkat kalau mereka tahu Mas Awan mau nampil waktu sesi live music di sana!"
"So sorry, little sister. Mas Awan pertimbangin pulang tahun depan, deh. Lagian, nanti juga Mommy sama Daddy bakal ke New York dekat-dekat ini. Kamu ngikut aja, soalnya kayaknya Mommy juga mau mampir di Oakland."
"Tetap aja nyebelin!" Trea mendengus. "Aku doain Mas Awan kepincut sama cewek Jakarta biar Mas Awan nggak kepengen balik ke Oakland lagi!"
"Teruslah mendoakan sesuatu yang mustahil kalau gitu." Awan terkekeh, lalu secara sepihak, dia menutup telepon.
Dia tidak tahu apa yang tengah menunggunya.
INTRODUCING – THE SARAKUSUMAS

SENO IRAWAN SARAKUSUMA (DADDY)

IRINA TUNGGADEWI (MOMMY)

MEIDIAWAN SARAKUSUMA (MAS AWAN)

MAITREA SARAKUSUMA (TREA)
to be continued.
***
Catatan dari Renita:
gabisa upload gif gatau kenapa bre
jadi foto aja
dah lah karena udah malem juga.
btw cerita ini ngga akan nyampe 40 chapter kayanya atau ya mungkin 40an tapi ganyampe 50 wkwkwkwk
dah lah daripada kepanjangan.
ciao.
mwah
wkwkwkw
(kasi target ngga ya).
gaada bonus maap.
(kosong)
Rumah Tuan Kim, February 18th 2020
23.40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro