02
Gue selalu ada buat Sashi.
Bukan cuma gue yang ngerasa gitu, kok. Dianya juga mengakui. Gue selalu ada buat jadi payung dadakan yang melindungi dia dari terik matahari waktu upacara—soalnya dianya kan juga ucrit banget badannya. Gue selalu ada buat dengerin semua curhatan dia soal cowok-cowok yang pernah dia taksir. Gue bahkan pernah jadi badut dadakan di perayaan ulang tahunnya setelah badut benerannya nggak dateng gara-gara mencret tiba-tiba.
Suatu kali, Sashi pernah nanya ke gue, "apa sih yang nggak bisa lo lakuin buat gue, Drol? Kayaknya nggak ada."
Gue nyengir, padahal jawab begini dalam hati;
"Milikin lo, Bol."
— Mandala Deryaspati
***
note: karena saya seperti prudential yang always listening always understanding, subtitle untuk boso jowo and english will be given in inline comment. thx nomu kamsa.
***

Waktu lihat perubahan ekspresi wajah Sashi setelah telepon singkat yang diterimanya berakhir, Dery sudah menebak pasti ada yang tidak beres. Sashi tidak langsung bicara, diam saja sambil menunduk menatap ramennya yang baru dicicip sedikit.
"Bol, kenapa?"
Sashi tak menjawab.
"Bol, jangan bikin gue takut, ah!"
Sashi akhirnya menatap Dery, kemudian berbisik pelan. "Mami..."
Dery langsung paham. "Mau ke rumah sakit sekarang?"
"Nanti dulu."
"Emang mau ngapain dulu?"
Sashi membalas kata-kata Dery dengan air mata yang berjatuhan di pipinya. Gadis itu tidak terisak, bahkan tak bersuara sama sekali. Namun melihatnya bersikap begitu justru bikin dada Dery dua kali lebih sesak. Cowok itu mencabut beberapa helai tisu dari kotak di atas meja, mencondongkan badan ke arah Sashi untuk mengeringkan air matanya. Sashi diam saja, membiarkan sahabatnya melakukan itu. Mereka tetap duduk diam hingga sekitar sepuluh menit berikutnya, diikuti Dery yang menghubungi supirnya untuk menjemput mereka.
Iya, keluarganya Dery tuh bisa dibilang keluarga ala-ala crazy rich surabekan gitu deh—soalnya papanya Dery nih asli orang bekasi sementara mamanya itu orang Tionghoa asal Surabaya. Walau begitu, Sashi masih belum terbiasa sama tajirnya keluarga Dery. Soalnya memang baru-baru ini juga sih mereka jadi sugih ampun-ampunan. Sebelumnya, papanya Dery memang punya perusahaan sendiri—dan baru berkembang pesat dalam lima tahun terakhir ini. Usut punya usut, dulunya orang tua Dery kawin lari soalnya papa Dery bukan apa-apa kalau dibandingin sama keluarga mamanya. Papa Dery baru diterima sama keluarga mama Dery setelah dia bisa membuktikan bahwa dengan usahanya sendiri, dia bisa selevel dengan mereka.
Jadi ya seberapa kekayaan Dery yang tinggal diumpamakan semacam duitnya papa Dery itu cukup buat beli tiga gunung, sementara duitnya mama Dery bisa banget dipake buat beli tiga negara—itu juga masih kembalian kayaknya. Makanya urusan beli saham mall besar di ibukota sih kecil buat papanya Dery.
Dery dikasih supir sendiri juga kartu ATM dari berbagai bank berikut black card sakti, tapi jarang dia pake sih. Dia lebih sering naik taksi online atau busway sama Sashi. Gara-garanya dari kecil, Sashi tipikal orang yang nggak neko-neko meski papinya tergolong pengusaha kaya. Semua karena didikan maminya.
Dan bicara soal maminya Sashi, Dery paham kenapa Sashi bisa sampai se-down itu dengar berita buruk soal maminya—sampai-sampai dia merelakan ramen favorit yang baru dicicip sedikit untuk ditinggal begitu saja. Padahal Sashi nih anaknya doyan makan banget—walau berat badannya nggak pernah nambah sampai Dery curiga kalau Sashi miara siluman naga dalam perutnya. Sashi dekat banget sama maminya. Dari dulu, apa-apa tuh pasti ke maminya.
Maminya Sashi adalah sahabat terdekat dia selain Dery.
Sekitar setahun yang lalu, maminya Sashi didiagnosis kena kanker rahim. Habis itu, tiba-tiba semuanya berubah dengan drastis hanya dalam hitungan bulan. Papinya Sashi yang biasa sibuk keluar negeri buat meeting dan segala macam mendadak jadi sering di rumah—yang bikin Sashi canggung, karena dia tidak sedekat itu sama papinya. Dari Sashi masih anak-anak, papinya memang lebih banyak berada di kantor daripada di rumah. Mami sering ke rumah sakit, beberapa kali dirawat, terus minta pulang, hanya untuk drop lagi beberapa lama kemudian dan dirawat lagi.
Tiba-tiba, Sashi merasa asing dan kesepian, terus jadi lebih muram dari biasanya.
Akhir-akhir ini kondisi kesehatan maminya Sashi memburuk dan itu juga yang jadi alasan kenapa dia lebih sering sedih beberapa minggu belakangan. Dery benci sama dirinya sendiri karena merasa hopeless. Kalau saja dia Tuhan yang punya banyak kuasa, maunya dia yang bikin Sashi selalu bahagia.
Asal gadis itu bahagia, Dery sudah merasa cukup, kok.
Sepanjang jalan, Sashi sibuk menangis. Dery sengaja tidak bertanya, karena orang kalau lagi nangis terus ditanya-tanya ya bakal makin sesak dan susah napas. Jadi dia merangkul Sashi sambil usap-usap bahunya, berusaha menenangkan. Supirnya sih tidak banyak berkomentar, hanya sesekali melirik ke belakang lewat rear-view mirror.
"Drol." Sashi tiba-tiba bicara waktu mobil berbelok masuk ke pelataran depan rumah sakit.
"Apa?"
"Temenin gue ya nanti? Jangan pulang dulu."
"Iya."
"Kok nggak tanya kenapa?"
"Emang lo mau ditanya?" Dery malah balik bertanya.
"Mau."
"Cebol, kenapa cebol?"
"Badrol!"
Dery tertawa. "Kenapa nangis? Mami lo baik-baik aja, kan?"
Sashi menggeleng. "Mami nggak baik-baik aja. Tadi yang telepon Oma. Katanya... Mami udah bener-bener drop. Makin sering mengigau waktu tidur. Rambutnya makin banyak yang rontok, udah hampir botak. Oma bilang... mungkin sekarang waktunya gue buat merelakan."
Dery menelan ludah, menghela napas dan menepuk-nepuk pelan bahu Sashi. Sebetulnya, tanpa bertanya, dia sudah bisa menebak apa yang akan Sashi beritahu padanya. Itu juga yang jadi alasan kenapa papi Sashi mengajaknya bicara beberapa hari yang lalu. Papi tidak mau melihat Sashi sedih terus-terusan, jadi beliau meminta Dery untuk menghibur Sashi, atau bikin Sashi sibuk setiap hari, jadi gadis itu tidak akan terlalu kepikiran dan hanya mengunjungi Mami seperlunya saja.
"Gue nggak tahu harus bilang apa, Bol. Soalnya gue nggak mau menjanjikan sesuatu yang nggak bisa gue jadikan kenyataan. Dari semua orang di dunia ini, lo adalah orang terakhir yang mau gue bohongi." Dery mengelus rambut Sashi dengan sayang. "Tapi gue janji, mau dalam situasi baik atau buruk, gue bakal selalu ada buat lo."
"Ih, udah kayak janji pernikahan aja!"
"Gue nikah sama lo? Ngimpi."
"Lo tuh ya, ngomongnya! Awas kualat!" Sashi meninju dada Dery.
Maka itu akan jadi kualat terindah dalam hidup gue, Bol.
Tapi Dery diam saja, malah nyengir lagi. "By the way, bomber gue mahal! Jangan buang ingus pake itu!"
"Iya ih, bawel!" Sashi cemberut, tapi lalu meneruskan. "Makasih ya, Drol. Lo tuh emang deh, bener-bener sosok serba bisa dalam hidup gue. Dari dulu sampai sekarang, apa sih yang belum lo lakuin untuk gue?"
Jadiin lo punya gue.
"That's what friends are for, isn't it?"
"Thankyou, friend."
Ada nada pahit dalam suara Dery waktu dia jawab. "Anytime, friend."
*

"Sopo iku?"
Orang yang menelepon Jef baru saja mengakhiri sambungan saat Jennie memberondongnya dengan pertanyaan.
"Uwong."
"Wanna di-slepet koen?" Jennie menyahut sangar sambil menekuk jari-jarinya, persis seperti jago beladiri yang sedang melakukan pemanasan sebelum menghajar lawan.
"Suaminya mantan gue." Jef menghela napas panjang, kemudian sibuk berpikir.
"Suami mantan lo yang punya anak sama lo itu?"
Jef mengangguk. "Yoi."
"Dia bilang apa?"
"Dia nanya, kira-kira gue bisa ke rumah sakit nggak sore ini. Soalnya kondisi Tris udah drop banget. Mumpung kesadarannya masih ada, dia mau ketemu gue."
"Lah, terus apa lo tunggu sekarang, bajingan?!" Jennie jadi naik darah lagi. Emang ya, kalau punya teman rupanya macam seorang Jeffrey Gouw ini, kurang afdol kalau nggak nge-gas at least tiga kali dalam setiap pertemuan mereka.
"Gue bingung, Jen."
"Bingung apa?!"
"Gue takut. Gimana kalau saat gue sampai sana, gue udah ditunggu anak gue?"
"Terus mau lo apa?"
"Apa mesti gue tetap datang?"
"Bless you and your brainless head, Jeffrey. Lo masih nanya?! Gue gebuk nih!"
"Gue butuh waktu buat mempersiapkan diri, Jen. Ini... terlalu mengejutkan buat gue." Jef berkata begitu sambil menyedot ocha yang dia pesan. Itu gelas keduanya setelah sisa gelas pertama tandas oleh Jennie.
"Terus mau kapan nemuin mantan lo itu?"
"Besok kali. Atau lusa. Atau besoknya lagi."
"You know what? I'd slap you but that would be animal abuse. Enak bener lo mikir begitu ya? Coba lo tempatkan diri lo di posisi mantan lo sekarang. She has cancer, dumbass. Fucking cancer. Her days are numbered. Lo sendiri yang bilang, dia menghubungi lo karena merasa waktunya udah nggak lama lagi. Terus sekarang lo mau mengulur-ulur waktu?"
"Tapi kan—"
"Lagian nggak usah kege-eran gitu."
"Maksud lo?"
"Kedengarannya dia punya suami baik yang bertanggung jawab. You know, nggak semua laki-laki mau menghubungi mantan pacar istrinya yang lagi sekarat, terutama ketika istrinya punya anak sama tuh mantan pacar. Dia mau berbesar hati melakukan itu. Bisa jadi, dia sudah mengambil alih peran lo sebagai ayah dari tuh anak dengan baik. After all, selama tujuh belas tahun ini, lo nggak pernah sekalipun ada untuk anak itu, kan?"
"Gimana mau ada?! Gue aja baru tahu eksistensi dia kemarin!"
"Kalau lo tahu eksistensinya dari dulu-dulu, apakah lo bakal jadi ayah yang baik buat dia?"
Jef tidak bisa menjawab.
"Tetot tentu saja jawabannya tidak. Benar kan begitu, saudara Gouw?"
"Ck."
"Lo nggak bisa jawab karena lo tahu apa yang gue bilang itu benar."
"Yaudah." Jef memijit batang hidungnya, merasa diserang pening tidak terduga. "Gue bakal kesana abis dari sini. Tapi ada syaratnya."
"Syarat apaan?"
"Lo mesti temenin gue."
"You're indeed the jancuk-est jancuk ever, Jeffrey Gouw."
*
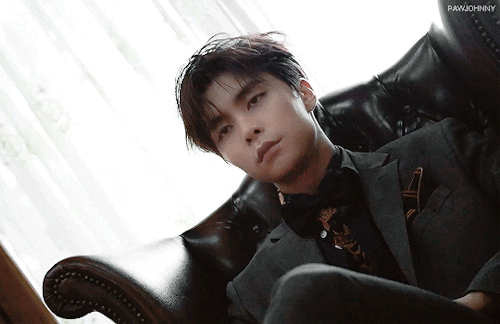
"I'm so sorry that you have to do this."
Jo baru membalas pesan teks dari salah satu partner bisnisnya ketika suara seorang perempuan membuatnya menoleh. Dengan cepat, lelaki itu berjalan mendekati sisi ranjang, meraih tangan perempuan tersebut ke dalam genggamannya. Jari-jarinya jauh lebih kurus daripada yang terakhir kali Jo ingat. Kulitnya pucat, ternoda oleh memar dan warna kehitaman di beberapa bagian. Efek samping dari kemoterapi membuatnya kelihatan tidak sehat. Terutama karena rambutnya yang makin tipis hingga hampir botak.
"Darling, you're awake." Dia berbisik, diikuti satu kecupan di pergelangan tangan perempuan itu.
"Kamu sudah telepon dia?"
Jo mengangguk. "About an hour ago."
"What did he say?"
Tidak ada yang berubah dari ekspresi tenang di wajah Jo. Pat mengira dia akan melihat setidaknya sedikit kecemburuan dalam sorot mata laki-laki itu, tapi tidak apa-apa. Emosinya tetap sukar dibaca. "Dia bilang dia butuh pikir-pikir dulu."
"Too bad."
"No, don't worry too much. Kamu masih punya banyak waktu. Jangan mikir yang macam-macam dulu, oke?"
Pat tersenyum tipis. "We both know that it's not true."
"Patricia..."
"Aku tahu, kamu mungkin lebih suka kalau aku nggak menyinggung apa yang sudah lalu. Bisa jadi, yang terbaik adalah kalau baik Jeffrey maupun Sashi nggak pernah tahu soal hubungan mereka. Tapi aku nggak bisa. It doesn't feel right. Dan aku nggak mau gara-gara ini, aku nggak bisa pergi dengan baik-baik. Karena itu juga, aku minta maaf ke kamu. Maaf karena aku harus begini. Maaf kamu harus melakukan ini."
"We've been together for 18 years. Kamu sudah cukup bilang maaf setiap hari. Se-nggak percaya itu setiap kali aku bilang kalau nggak ada yang perlu dimaafkan?"
"Jo—"
"No, don't say anything." Jo menghela napas, mengeratkan genggamannya pada jari-jari perempuan yang terbaring lemah di depannya. "Daripada meminta maaf terus-terusan, lebih baik kalau kamu nggak ngomong apa-apa. Semua permintaan maaf kamu bikin aku ngerasa awful. I made a promise to protect you, to protect your daughter, years ago. To be there for both of you until my last breath. Janji yang kubuat bukan cuma di depan kalian, tapi juga di hadapan Tuhan. Apapun itu, asal kamu bahagia, aku juga bahagia."
Pat tidak menyahut, tapi ada setetes air mata jatuh di pipinya.
Momen itu tidak berlangsung lama, karena beberapa saat kemudian, pintu diketuk. Seraut wajah milik Oma adalah apa yang terlihat awalnya, sebelum wanita berambut putih itu membuka pintu lebih lebar, menunjukkan kehadiran Sashi yang datang masih dengan mengenakan seragam sekolah—yang ditutupi dengan jaket bomber hitam kebesaran. Pat tidak perlu bertanya. Dia tahu, jaket itu pasti milik Dery.
"Oh, my babygirl. Come here."
Sashi menurut, mendekat tanpa mengatakan apa-apa walau dia sempat agak canggung karena kehadira Jo di sana. Well, hubungan diantara mereka sebenarnya tidak buruk. Hanya saja, Jo sejarang itu berada di rumah, terutama ketika Sashi masih kecil. Hubungan anak-ayah diantara mereka terkesan formal—walau Sashi tahu, dalam beberapa kesempatan, Jo pernah diam-diam terjaga semalaman di sisi tempat tidurnya saat dia sakit demam atau bersikap defensif kala tahu Sashi dan Dery suka nyantai berdua saja di kamar Sashi.
"Baby, can you leave us alone?"
Jo menghela napas, mengangguk setuju. Dia menyempatkan diri mencium kening Pat dan mengelus pelan puncak kepala Sashi sebelum melangkah keluar dari kamar. Sashi ditinggal berdua saja bersama maminya.
"Listen, Mami needs to tell you something right now."
"Aku nggak mau dengar wasiat."
Pat tertawa. "Kok mikirnya gitu, Sayang?"
"Janji dulu, ini bukan pesan terakhir dari Mami buat aku. Soalnya kalau iya, aku nggak mau dengerin."
Sahutan Sashi bikin Pat harus mati-matian menahan air mata. "Nggak, kok. Bukan itu. Tapi sebelumnya, Mami mau nanya dulu. Kamu kesini sama Dery?"
Sashi mengangguk.
"Bagus."
"Mi..."
"Minggu depan kamu ulang tahun." Pat memotong. "Sudah kepikiran, mau kue ulang tahun apa buat tahun ini?"
Pertanyaan itu malah bikin Sashi ingin menangis. Setiap tahun, Pat selalu membuatkan kue ulang tahun untuk Sashi. Betul-betul dibikin sendiri, bukan hasil beli jadi dari bakery. Biasanya, Sashi akan ditanya, untuk ulang tahunnya, dia menginginkan kue yang seperti apa. Pat tidak pernah tidak mengabulkannya. Semua kue yang dia buat selalu sesuai dengan keinginan dan bayangan Sashi—tak peduli sesusah apa kue itu dibuat.
"Mi, ini bukan waktunya ngomongin kue ulang tahun."
Pat justru tersenyum, menelusuri sejumput rambut di tepi wajah Sashi dengan tangannya. "My daughter will turn 17 next week. It's a special day. You have to wish for something special too, babygirl."
I wish you'll be there to celebrate it with me, just like you always did before. Sashi berbisik dalam hati, tidak menyuarakannya karena mengatakannya tanpa suara saja sudah membuatnya ingin menangis. Gadis itu diam saja.
"Sashi—"
"Aku—aku mau ke toilet."
Pat terperangah sejenak, tapi kemudian mengangguk. "Pake toilet di kamar ini aja ya?"
"Nggak mau."
"Acacia—"
Sashi sengaja tidak memberi kesempatan pada Pat untuk menyelesaikan ucapannya. Dia langsung saja berlari kecil menuju pintu, membuat Pat hanya bisa menatap kepergiannya. Di depan pintu, Jo sempat menahan Sashi, tetapi membiarkannya meneruskan langkah untuk pergi saat Pat memberinya kode melalui tatapan mata. Lelaki itu menghela napas panjang, sementara Dery yang ikut menunggu di luar ruangan langsung gesit mengejar Sashi.
"It's okay." Pat bilang begitu. "She has her bestfriend."
Jo mengangguk, bermaksud untuk kembali masuk dan menutup pintu saat dia mendengar suara baritone milik seorang laki-laki yang berjalan mendekati Oma melalui ujung koridor. Lelaki itu kelihatan canggung, ditemani seorang perempuan bersetelan kemeja dan celana jeans.
"Um... sorry... apa ini kamar perawatan Patricia Gunawan?"
Jo membiarkan pintu agak terbuka, mengangkat alis dan balik bertanya meski dia bisa menduga siapa lelaki itu. "Iya. Boleh saya tahu siapa anda?"
"Jeffrey. Jeffrey Gouw."
*

Jef mendadak ketar-ketir begitu dia menyusuri koridor rumah sakit ditemani oleh Jennie. Bukan hanya karena dia dan Jennie jadi pusat perhatian dan bikin orang-orang yang berpapasan dengan mereka menoleh, juga karena tiba-tiba saja, membayangkan bertemu lagi dengan mantan terindahnya masa SMA membuatnya gentar. Tetapi tentu Jennie tidak akan semudah itu membiarkannya lepas dari jerat siksa. Bahkan sejak mereka baru menapakkan kaki di pelataran depan rumah sakit, Jennie sudah mencengkeram lengan Jef keras-keras, bikin dia tidak bisa lari.
"Jen, awakmu ki sadar ora?"
"What?" Jennie balik bertanya dengan alis terangkat.
"You hold onto my arm like there's no tomorrow."
"Oh, baper?"
"Yeu, arek iki. I'm serious, cuk."
"Terpaksa, ndes. Gue udah paham semua akal bulus lo. Kalau nggak dipegangin gini, lo pasti bakal lari! A-a-a, ngapain mangap? Mau bantah? Mau ngeles? Gue jadiin ganjelan knalpot bajaj juga lo lama-lama."
"Masalahnya kita tuh dilihatin sama orang-orang!"
"Jelas toh mereka ngelihatin? They have eyes duh Jeffrey Gouw, jangan ge-eran gitu ah! Bikin pengen gaplok nih jadinya!"
"Lagian lo nggak takut apa kalau kita jadi korban kamera handphone jadul yang tidak bertanggung jawab?"
"Maksudnya?"
"Kali aja ntar malem ada berita nongol judulnya 'Jennie Kartadinata dan Jeffrey Gouw Tertangkap Basah ke Rumah Sakit Bersama. Kebobolan?' gitu gimana?"
"Lo kira gue gawang?!"
"Serius ini loh gue!"
"Hahahaha jelas cuma wong gendheng yang bikin gosip gue sama lo sebagai couple. Apalagi hamil anak lo. Dih, mending gue dihamili Jin Tomang aja sekalian!"
"Awas kualat."
"Daripada dihamilin lo masih mending Jin Tomang kemana-mana."
"Sehina itukah gue di mata lo?"
"Kasihan anak gue kalau mesti punya bapak kayak lo."
Kata-kata Jennie sontak bikin Jef terdiam. Dia jadi kepikiran lagi soal anaknya—bisa disebut anaknya dong, walau dia nggak pernah ketemu. Gitu-gitu juga, dia turut menyumbang dalam proses pembuahan si anak. Dia harus bagaimana sekiranya anaknya tidak mau punya bapak sepertinya? Tuh kan, Jef jadi makin deg-deg-an.
Namun sudah terlalu terlambat untuk lari. Tidak berapa lama, mereka sudah tiba di depan pintu ruang perawatan intensif. Ada seorang perempuan berambut putih di depan pintu ruangan tersebut. Jef meneguk ludah, nyaris panik, tapi tidak punya pilihan selain bicara saat Jennie mendorongnya ke depan perempuan tua tersebut.
"Um... sorry... apa ini kamar perawatan Patricia Gunawan?"
Tanya Jef malah dijawab seorang laki-laki yang melihat ke luar melalui celah pintu. Dia tinggi, terlihat gagah dan kalem. Jef menebak, ini pasti suami mantan pacarnya.
"Iya. Boleh saya tahu siapa anda?"
"Jeffrey. Jeffrey Gouw."
"Oh. Istri saya sudah menunggu anda. Mari."
Jef jadi kikuk ketika lelaki itu membuka pintu lebih lebar, mengizinkannya masuk. Tidak lama, dia keluar, meninggalkan mereka hanya berdua dalam ruangan tersebut. Jef berdiri beberapa lama di depan pintu, lantas berdeham dan mendekat untuk menghampiri Pat yang terbaring di atas ranjang dengan aneka selang dan jarum terhubung pada tubuhnya.
Cancer is indeed, one of greatest motherfuckers. Dalam ingatan Jef, Patricia Gunawan adalah salah satu gadis paling cantik yang tangannya pernah dia genggam. Tapi kini, dia terlihat begitu kurus dan pucat. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Rambutnya telah menipis, tampak kasar.
"Well, hello."
"You look great." Pat memuji. "Long time no see, Kak Jeffrey. How's life?"
"Great."
"Masih betah sendiri?" Pat bergurau, langsung meneruskan begitu melihat ada kerut muncul diantara kedua alis Jef. "Kamu celebrity chef terkenal sekarang. Saya sering lihat kamu di televisi. Walau nggak sesering beberapa tahun yang lalu."
"So unfair." Jef berkomentar spontan, kini sudah lebih santai. Dia berjalan kian dekat dan mengambil tempat duduk di samping ranjang Pat. "Kamu tahu tentang saya dan saya nggak tahu kabar apa-apa tentang kamu."
"Am I the one to blame? Kamu juga nggak pernah mencari saya."
Jef tersenyum pahit. "Saya nggak menduga kamu ingin dicari."
"Well, in some parts, you're right." Pat sependapat. "Sejujurnya, saya ingin ketemu kamu bukan untuk mendapat sesuatu dari kamu. Hidup kami baik-baik aja. Acacia—"
"Acacia?" Jef memotong.
"Our daughter."
"Oh." Rasanya tetap terdengar aneh buat Jef.
"Acacia tahunya dia punya keluarga yang normal dan orang tua lengkap yang sayang sama dia sejak kecil. Nggak ada masalah. Hidupnya baik-baik aja. Hidup kamu juga baik-baik aja. Tapi saya ngerasa, kalian perlu tahu soal masing-masing. Saya tahu ini nggak mudah buat kamu, namun saya yakin, ini juga pasti nggak akan mudah buat dia. Hanya saja, saya ngerasa harus melakukan ini. Both of you deserve to know the truth."
"Jadi... dia juga belum tahu?"
Pat menggeleng. "Saya berencana memberi tahunya sore ini. Tapi anak itu memang agak keras kepala. Jadi—"
Kata-kata Pat terinterupsi oleh batuknya. Batuk itu tidak berhenti hingga setidaknya setengah menit kemudian, membuat Jef buru-buru mengambil kotak tisu dari nakas di samping tempat tidur, memberikannya pada Pat. Perempuan itu menutup mulutnya dengan beberapa helai tisu, baru menurunkannya setelah batuknya reda.
Pat berusaha melipat helai tisu di tangannya sedemikian rupa, tetapi mudah bagi Jef untuk melihat ada bercak merah di sana.
"Well, I'm so sorry."
"No." Jef menyahut tegas. "Don't be."
"You know, I don't have much time left. Saya cuma mau kasih tahu kamu itu. Intinya, kamu dan Acacia sama-sama berhak tahu. Gimana reaksi kalian atas apa yang kalian dengar, saya menghormatinya. Meski saya berharap... kalian bisa punya hubungan selayaknya ayah dan anak."
"Look, Tris, I don't know if I can—" ada sesuatu dalam ekspresi Pat yang membuat Jef batal melanjutkan ucapannya. "—but I'll try to meet her later."
"Senang mendengarnya."
"Oke."
"Saya hanya mau bilang itu. Saya tahu kamu sibuk. Makasih sudah meluangkan waktu untuk datang kesini."
Lidah Jef kelu, membuat hanya bisa mengangguk kaku. Dia beranjak dari kursi, melangkah menuju pintu. Pat masih diam, sementara Jef memandang kenop pintu dengan penuh keraguan. Ada senyap diantara mereka selama seperempat menit, yang terasa begitu panjang. Sampai akhirnya, Jef yang menyerah lebih dulu.
"Delapan belas tahun lalu, setelah malam itu, kenapa kamu menghilang?"
Pat diam sebentar, kemudian menjawab hati-hati. "It was my first time. Aku takut. Aku juga merasa berdosa. Ditambah lagi, kamu sudah lulus dari sekolah dan akan segera kuliah. Aku merasa—well, apapun alasannya, nggak akan bisa bikin waktu diputar kembali kan, Jeffrey? Aku bingung harus bagaimana setelah malam itu. Satu-satunya yang terpikir olehku cuma menghindar dari kamu."
"Why didn't you tell me... about our child?"
"Aku nggak mau membebani kamu."
"Patricia—"
"You told me about your dreams. One of them is to become a top chef, just like your father. To be someone who'll conquer the world." Pat tersenyum sedikit. "Punya anak di usia 19 tahun akan jadi tembok penghalang besar untuk semua cita-cita kamu. Aku nggak bisa membiarkan itu terjadi."
"Kenapa?"
"Bukannya alasannya sudah jelas?"
"Jangan main tebak-tebakan, Tris."
"You know why."
"Tris."
"Because I love you, Kak Jeffrey. I always do."
Ada yang hancur dalam dada Jef saat dia mendengar Pat mengatakan itu.
*

Dery sengaja tidak langsung mendekat saat dia melihat Sashi berhenti lalu duduk di salah satu bangku yang menghadap taman rumah sakit. Gadis itu tertunduk, lalu menangis, menumpahkan air mata pada kedua telapak tangannya. Dery menontonnya begitu selama beberapa saat, lantas dia menghela napas dan mendekat pelan-pelan.
"Bol, gue boleh duduk di sebelah lo nggak?"
Sashi tidak menjawab, hanya mengangguk di tengah isaknya. Izinnya cukup untuk menghilangkan semua keraguan Dery. Dia menghampiri Sashi, duduk di sebelahnya dan menarik kepala Sashi untuk bersandar ke dadanya. Gadis itu sesenggukan, sementara Dery membisu, walau tangannya lanjut mengusap pelan pundak Sashi, berusaha menguatkan.
Butuh hampir dua puluh menit buat Sashi untuk kembali tenang.
"Drol." Sashi akhirnya memanggil usai puas menumpahkan air mata.
"Ho'oh?"
"Gue nggak mau balik ke sana. Gue nggak mau ketemu Mami."
"Terus maunya apa? Pulang? Yaudah, nanti gue yang bilang ke bokap-nyokap lo."
Sashi menggeleng. "Nggak mau pulang."
"Yowes. Nginep tempatku wae, piye?"
Sashi mengangguk, sudah sepenuhnya berhenti menangis dan itu membuat Dery menghela napas lega. Dia menunduk, menatap pada gadis yang kini masih bersandar padanya. Duh, kalau sudah begini ingin deh Dery merunduk sedikit lebih rendah biar dia bisa mengecup puncak kepala Sashi.
Sayangnya, dia tidak siap dengan konsekuensi yang mesti ditanggungnya setelah itu.
Akan tetapi, tak lama kemudian, Dery justru menerima telepon dari papinya Sashi. Lelaki itu menyuruh mereka untuk kembali ke depan kamar perawatan maminya Sashi karena kondisinya yang tiba-tiba menurun drastis dan kini telah memasuki masa kritis. Sashi tentu saja, menangis lagi. Sekujur tubuhnya gemetar dan mendung di matanya menebak, namun Dery menggenggam tangannya seerat yang dia bisa, meyakinkan Sashi bahwa dalam situasi terburuk sekalipun, Sashi akan selalu punya Dery.
Itu cukup bisa menguatkan Sashi.
Bagian depan kamar perawatan Mami sepi waktu Sashi kembali dan mendadak ramai dipadati oleh anggota keluarga yang datang dalam waktu kurang dari setengah jam. Kelihatannya Papi dan Oma sudah mengabari anggota keluarga yang lain. Sashi tidak tahu persis apa yang dikatakan dokter soal kondisi maminya, namun setelah mendengar keterangan dokter tersebut, Papi langsung mengajaknya bicara berdua saja.
"Acacia, Papi tahu, ini semua akan berat buat kita dan—"
Sashi menggigit bibir, menguatkan dirinya sendiri sebelum dia memotong kata-kata ayahnya. "Aku udah gede. Papi bisa langsung ngomong ke intinya."
"Ada beberapa hal di dunia ini yang justru akan bikin keadaan lebih baik jika kita melepaskannya, Sashi. Papi nggak bilang kalau kita harus melepaskan Mami. Papi sayang sama Mami. Papi mau mengusahakan segalanya untuk bikin Mami sembuh. Tapi dokter bilang, nggak ada respon bagus dari tubuh Mami pada kemoterapi. Kemoterapi itu nggak menyembuhkannya, malah menyiksanya. Operasi pengangkatan organ juga sudah terlalu berisiko karena kankernya sudah menyebar kemana-mana. Papi nggak bilang kita harus melepaskan Mami. Di sini, Papi akan ikut semua keputusan kamu."
"Kalau... kalau... kalau aku menyerah... apa Mami bakal marah sama aku?"
"Sashi—"
Sashi berbalik, sengaja memunggungi ayahnya supaya tidak ada yang melihat saat air matanya jatuh lagi. "Apapun itu... asal Mami nggak sakit lagi."
Sashi bukan orang yang penuh harap, tapi malam itu, ketika pada akhirnya dia dan Papi berbesar hati merelakan Mami, dia jadi betul-betul percaya jika mukjizat itu bukan sesuatu yang nyata.
Sashi menangis lagi. Kali ini sendirian. Dia tidak mengizinkan siapapun termasuk Dery mendekatinya. Pekat telah menjemput, mewarnai langit dengan warna kelam yang semuram suasana hatinya. Seperti mengerti, bintang pun enggan bersinar malam ini. Sashi masih tertunduk, membuat air mata menetes ke rok abu-abunya, membuat rok itu dipenuhi titik-titik gelap ketika dia mendengar seorang perempuan berambut panjang sibuk meninju dada sesosok lelaki di depannya berkali-kali.
"Damnit, you pussy, you better—"
"Jen—jen, calm down!"
"Lo—" Jennie gebuk dada Jef sekali. "—pengecut." gebuk lagi. "—tai hidup." masih terus gebuk. "Malu gue jadi teman lo!"
"Sek, sek! Misuhe nggawe boso jowo wae jen wong sing liyane ora ngerti!"
"What—the—fucking—hell?!"
Sashi jadi lupa sejenak pada dukanya, malah menonton pertempuran antara Jef dan Jennie dengan mata basah yang kini melebar. Jennie masih sibuk menghantam bahu, dada dan perut Jef dengan kepalan tinjunya, tapi refleks berhenti kala sadar bagaimana kini Sashi menatap mereka.
"Hng..." Sashi menarik napas supaya tidak ada air yang meleleh keluar dari hidungnya. "Silakan diteruskan, om—tante—wait, wah iki mesti om-om gendheng ndhek restoran ramen—"
"Shit, I'll do it myself!" Jennie memaksa Jef agar berdiri menghadap ke arah Sashi, bikin kedua orang itu sama-sama melotot. "Your ex-girlfriend husband, I saw her on his phone's lockscreen earlier."
Jef menoleh pada Jennie. "Terus urusannya ama gue apa?"
"Tuolol banget arek iki!" Jennie jadi jengkel. "It means, that crying girl, cah wedok kui putrimu, guoblok!"
"HAH?!"
to be continued.
***
Catatan dari Renita:
dikasih target aja pada gercep ya hadeh baru juga update kemaren udah update lagi. tumben bener ngga gue updatenya sering banget kea gini.
tapi ya gimana aku lagi mabok ayah jef dan papi jo.
yak, ini adalah awal coy hahaha
lagi-lagi ojun belum muncul tapi tenang, dia akan muncul pada waktunya. cerita ini tuh bakal cukup banyak kapal sih ya, soalnya daddy-daddy-nya sashi masih pada hot kan. yang satu bapak lajang, yang satu duda keren. belom lagi romansanya sashi.
wkwkwk lets see.
btw kuberi target lagi deh wkwkwk naik ya karena gile aja lo brur tiap hari.
1,2K votes and 1K comments for next chapter
oh ya, buat yang ngga ngerti boso jowo, bakal aku sediakan di inline comment terjemahannya. tapi kalo udah tenggelam yawes hampura pishun. makasih juga buat yang mau repot-repot komen nerjemahin wkwk.
again, cerita ini ngga akan tragic banget kayak DLP meski bakal ada nangis-nangisannya dikit haha btw untuk visualisasi, kalian semua bebas mau membayangkan siapa kok. ngeship siapapun juga bebas.
after all, ini cuma fiksi, bukan cerminan asli kehidupan idolnya.
bonus mb leni (lho dia siapa emang).

Semarang, September 29th 2019
18.11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro