00
My friend once said that having children is like living in a frat house; nobody sleeps, everything's broken and there's a lot of throwing up. I was laughing louder than necessary.
Karma is indeed a cold bitch. Turned out, my life is even a bigger joke than his. Wanna know what it is? I got myself a 17 years old daughter at 36.
— Jeffrey Gouw
***

Mau tahu apa yang bikin Leni lebih malas bangun dari kasur selain hari Senin? Penerbangan internasional jam tujuh pagi. Bayangan aja, at least dia harus sampai di bandara dua jam sebelum waktu keberangkatan alias jam lima pagi. Belum lagi siap-siap, macet di jalan dan segala kerumitan lainnya serta kejadian-kejadian tidak terduga macam kunci kamar yang tiba-tiba hilang hanya sejenak sebelum pergi atau kombinasi nomor kunci koper yanng mendadak terlupakan.
Ditambah lagi, teman sekantornya yang bakal jadi partner kerjanya selama di Bangkok belum juga datang. Maunya Leni sih langsung check-in aja. Lebih enak juga menunggu penerbangan di dalam. Mungkin dia bisa sambil ngopi cantik atau apa kek gitu, daripada terdampar macam dugong kesasar di emperan depan terminal keberangkatan.
Tapi temannya itu tipikal orang yang mudah heboh dan menarik perhatian. Leni tidak bisa membayangkan membiarkannya check-in sendirian. Terus kalau waktu check-in mereka berbeda, bisa-bisa mereka dapat seat yang berjauhan. Itu bakal jadi masalah tambahan buat Leni.
Gara-gara itu, dia mesti pasrah duduk sambil tidak berhenti menarikan jari-jari di atas layar ponsel. Sebuah koper merah muda penuh sticker salah satu karakter BT21 berwarna serupa teronggok dekat kakinya. Matanya masih ngantuk berat, hasil dari bailey coffee ditambah dua shot ekstra espresso yang bikin dia terjaga sepanjang malam.
Bodo amat sih dekil juga, soalnya siapa yang peduli? Di pesawat juga nanti dia pasti bakal lebih banyak tidur.
"Sorry, is this seat taken?"
Leni mengalihkan tatapan dari layar ponsel, agak menengadah hanya untuk mendapati sesosok lelaki—Leni hampir aja mau menyebutnya malaikat karena orang itu... ganteng banget. Sumpah, nggak bohong—walaupun tetap ya, buat Leni, masih Jeon Jungkook yang nomor satu.
"Sorry, is this seat taken?"
"Oh—um—no, no. It's empty."
Lelaki itu tersenyum sedikit, menciptakan dua lesung pipi di wajahnya. Dia mengenakan setelan yang sederhana, tapi entah kenapa bikin aura coolnya makin terasa. Hanya kaus, jaket hitam, jeans dan sebuah baseball cap berwarna senada. Dari tampangnya, Leni menebak umur orang itu tidak jauh beda dengannya.
Dia mengeluarkan ponsel, kelihatannya menelepon seseorang sementara Leni masih terus mengamatinya dari sudut mata. Kulitnya terang. Apa jangan-jangan dia turis? Atau Tionghoa blasteran? Sepertinya bukan orang Indonesia asli karena meski digelari tanah surga gara-gara kekayaan alamnya yang melimpah ruah sampai tumpah-tumpah, Indonesia bukan tanah di mana para malaikat dilahirkan.
Orang yang dia telepon menjawab telepon dan Leni hampir tersedak waktu dia mendengar kata-kata pertama yang meluncur dari mulut lelaki itu.
"Awakmu wes nang endi?"
Leni langsung having mental breakdown.
Kelihatannya, volume ponselnya ada dalam batas maksimal, karena samar, Leni bisa mendengar orang di seberang sana menjawab. "On my way."
"On my way endi?"
"Sudirman, cuk."
Dia memutar bola mata. "Told you my flight schedule and you're still this late? Juangkrek."
"Ih, ngono wae nesu."
"Ngelih banget ki. Arep tuku nasi uduk Mbah Karta. Selak tutup."
Rasanya Leni kepingin membenturkan kepalanya ke pilar gedung terdekat. Aduh, gimana ya. Apakah ini definisi sesungguhnya dari casing David tapi onderdil dalamnya Damar? Bahasa Inggrisnya fasih banget, tapi Jawa-nya juga kental abis. Tampangnya? Nggak kayak kebanyakan orang Jawa. Lebih mirip oriental mixing dengan gen western.
Leni pusing.
Apalagi setelahnya, lelaki itu berdiri, menatap Leni dan tersenyum lagi. Lesung pipi kembar pun kembali menyerang. "Saya duluan ya."
Leni sudah tidak bisa berkata-kata.
Di saat yang sama, temannya datang, lari macam sprinter dengan gagang koper di tangan kanan, paperbag yang isinya entah apa di tangan kiri dan sling bag terslempang begitu saja di badan. Napasnya terengah-engah kala dia tiba di dekat Leni, namun matanya melebar seketika saat dia melihat sosok laki-laki berjaket hitam yang tadi duduk di sebelah Leni. Lelaki itu melenggang santai, berlalu menjauh.
"Anjrit, beneran nih?!"
"Apaan?"
Teman Leni menepuk pipinya beberapa kali. "Buset, beneran gue nggak mimpi!"
"Apaan?!" Leni mulai tidak sabar.
"Itu tadi—yang duduk di samping lo—buset dah—"
"Ganteng?"
"Lo nggak kenal dia?"
"Nggak."
"Hadeh." Temannya berdecak. "Ini pasti gara-gara lo keasikan sama Jongkok—atau siapalah cowok Korea yang lo taksir setengah mampus. Itu tuh chef famous yang lagi sering wara-wiri di televisi! Sumpah ya, dia tuh seksi banget. Ganteng dan senyumnya itu lhoooo... satu negara ini bisa bertekuk lutut kayaknya. Denger-denger sih saking mahalnya, senyumnya ampe di-asuransi-in!"
"Hah?!"
"Namanya Jeffrey. Jeffrey Gouw. Ganteng. Pertengahan tiga puluhan, tapi masih sendirian dan setahu gue sih belum punya gandengan. Lo beneran nggak tahu?!"
Leni menggeleng. "Nggak."
"Aduh, parah banget lo! By the way, tadi dia lama nggak duduk di sebelah lo?"
"Cukup lama."
"Lo minta foto?"
"Nggak."
"Memang ada orang yang kalau bodoh tuh bisa sampe ke sumsum tulang!" Cewek di depan Leni mendengus. "Gue jadi lo sih gue minta foto dan tanda-tangan."
"Kalaupun gue kenal dia kayaknya gue nggak bakal minta foto. Dia kelihatan capek."
"Ow, menghargai privasi nih ceritanya?"
"Terserah, deh." Leni beranjak walau diam-diam matanya menatap pada pintu depan sebuah kedai kopi tempat sosok laki-laki yang katanya bernama Jeffrey Gouw itu lenyap. "Udah telat. Mending check-in sekarang."
"Siap!"
Pagi itu, sepanjang flight dari Jakarta menuju Bangkok, Leni nggak bisa tidur. Padahal dia sudah berusaha memejamkan mata dan nggak melakukan apa-apa. Alasannya sederhana, ada sebaris nama yang terus terngiang dalam kepalanya seperti gema dari suara yang diteriakkan ke ceruk gua.
Jeffrey Gouw.
*
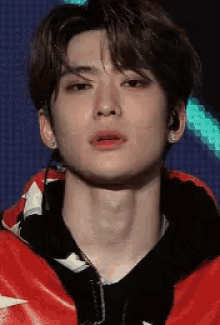
Di luar sana, sebagian besar orang mengenalnya sebagai Jeffrey Gouw, celebrity chef yang lagi menjadi perbincangan hangat terutama diantara kaum wanita, mau itu gadis remaja yang biasa berteriak histeris tiap melihat oppa via layar kaca bahkan sampai emak-emak sosialita yang gemar bergosip dalam berbagai acara, mau itu arisan ataupun temu-kumpul keluarga. Citranya yang ramah dengan senyum yang bisa bikin para perawan garuk tembok saking gemasnya, ditambah skill memasaknya yang mumpuni bikin dia gampang menjadi idola wanita se-Indonesia Raya.
Beberapa tahun lalu, di awal kepopulerannya setelah menjadi juri tamu dalam sebuah kontes memasak yang disiarkan stasiun televisi nasional, Jef sempat sesibuk itu. Silih-berganti muncul di stasiun televisi yang berbeda-beda setiap hari. Acaranya bervariasi, mulai dari yang masih berkaitan dengan dunia masak-memasak sampai acara talkshow yang kebanyakan isinya mengorek soal kehidupan pribadi, keberadaan kekasih yang bisa jadi dirahasiakan hingga sejarah kehidupan percintaan.
Tapi sejak tahun kemarin, dia sengaja membatasi diri dan lebih suka jarang berada dalam sorotan—walau ya, dia masih tetap jadi pusat perhatian.
Dikagumi banyak orang itu menyenangkan, tapi duduk santai di sofa ruang tengah apartemennya sambil memeluk bucket berisi potongan ayam goreng KFC kedengarannya lebih baik.
Setidaknya, sampai pintu depan apartemennya diketuk orang.
Jef ogah-ogahan naro bucket ayamnya ke atas meja. "Bentaaaaaaaar..."
Waktu dibuka, Jef langsung telan ludah campur panik. Rosé berdiri di depan pintu, bajunya hitam-hitam, horor banget udah kayak malaikat pencabut nyawa. Refleks, Jef tutup lagi pintu apartemennya, ngebantingnya tepat di depan hidung Rosé. Reaksi Rosé? Tentu langsung kalap, saudara-saudara sekalian.
"YOU DUMBASS JEFFREY GOUW, BERANI-BERANINYA YA LO PULANG KE JAKARTA TAPI NGGAK BILANG-BILANG GUE?! SEKARANG, BUKA PINTUNYA! JANGAN JADI PENGECUT ATAU GUE BAKAL TERIAK DI LOBI BILANG KALAU GUE HAMIL ANAK LO!"
Jef melotot gusar, buru-buru ngeluarin ponsel buat nelepon Jennie. Jennie ini temannya sesama chef. Mereka dulu sama-sama kuliah di Australia dan sempat dekat—platonic relationship, nggak ada perasaan lebih dari teman. Jennie juga teman dekat cewek setengah sinting yang sekarang lagi menggedor-gedor pintu depan unit apartemennya dengan sepenuh napsu. Maksud Jef nelepon Jennie? Nggak ada sih, tapi berhubung Jennie dekat sama Rosé, siapa tahu dia bisa memberi saran bagaimana cara menjadi pawang yang baik sehingga Jef bisa meredakan emosi membara seorang Roseanne Park dengan benar.
"Hola, Bitches. Dengan Jennie di sini, ada yang bisa dibantu?"
"Lo ngasih tahu Rosé kalau gue landing di Jakarta pagi ini?!"
"Oh. Udah nyampe depan pintu lo dia? Cepet juga." Jennie kayak santai banget gitu jawabnya.
"Heh, gue serius! Mukanya horor banget! Dandanannya udah kayak malaikat maut, khawatir aja gue dijemput dadakan."
"Dia bawa pisau nggak?"
"Mana gue sempat meriksa?!"
"Kalau bawa pisau, udah berarti mending lo pasrah aja."
"Dia masih menggedor-gedor pintu depan gue. Kalap banget kayaknya. Gue harus gimana!?"
"Buka pintu. Jadilah lelaki. Kalau mesti tanding, tanding aja sekalian lo berdua."
"Kagak ada wasit di sini! Kalau gue buka pintu, bisa-bisa gue nggak akan bertahan buat lihat matahari terbit besok pagi!"
"Lo ninggalin dia gitu aja buat cabut ke LA setelah kalian indehoy di apartemen lo dan lo berharap dia nggak bakal kalap? You reap what you sow, Gouw. Man up and face it."
"Gue nggak ninggalin dia!"
"Tapi ganti nomor dan nggak bisa dihubungi?"
"You know, I can't give her what she wants."
"Emang dia mau apa?"
"Dilamar."
Jennie membuang napas lelah. Dia kenal Jef udah lama. Sangat lama, mungkin hampir enam belas tahun. Mulai dari jaman mereka kuliah dulu di Sydney sampai dua-duanya balik ke Indonesia. Jef bukan orang yang bisa diajak berkomitmen, bahkan sejak dulu. Tapi dia rajin banget blind-dating, apalagi setelah ada aplikasi sejenis Tinder. Selama bertahun-tahun, Jennie yang jadi penyelamat Jef sekaligus pemberes huru-hara yang dia timbulkan.
Kayak misalnya gini, ketika blind date dan Jef ngerasa nggak click dengan cewek yang dia ajak janjian, biasanya dia bakal hubungi Jennie via pesan teks. Kalau udah begitu, Jennie bakal datang, berpura-pura jadi istri yang murka setelah memergoki suaminya selingkuh dan narik Jef buat pulang. Dari sana, cerita selesai. Jef nggak harus bikin alasan buat partner blind-dating yang dia tinggal begitu saja. Semuanya senang. Jennie juga nggak keberatan.
Tapi sekarang, sepertinya Jennie juga sudah terlampau muak buat terus meladeni segala urusan drama percintaan sahabatnya.
"Gouw, look, gue rasa mungkin sekarang waktu yang paling tepat buat lo untuk berhenti."
"Apanya?!"
"Kita semua bukan anak-anak lagi. Lo bukan remaja tanggung yang lagi senang-senangnya cari pengakuan diri dengan berpetualang dari satu hati ke hati. Lo suka Rosé. Rosé sayang lo. Banget. Dan—"
"Jen—"
"Gue tahu Rosé itu orangnya kayak gimana. Dia perempuan yang mandiri, cerdas dan asal lo tahu aja, ada banyak cowok yang ngantre buat sama dia. Tapi dia memilih lo. Rosé juga bukan orang yang penuntut—kecuali untuk komitmen dari lo ya. Dia pengertian." Suara Jennie melunak. "Lagian, apa yang segitunya lo takutkan dari sebuah komitmen? Pernikahan itu nggak selalu buruk. Mau sampai kapan lo terus-terusan lari begini, untuk sebab yang selalu lo simpan sendiri?"
"Gue nggak bisa—wait, dia berhenti berteriak."
Itu bukan bohong, karena Rosé tidak lagi menggedor pintu dan keriuhan yang semula mendominasi suasana kini terganti oleh kesenyapan total.
"Pingsan kali dia."
"Jangan nakut-nakutin gue, dong!"
"Lo-nya juga salah!" Jennie jengkel. "Seriously, apa yang bikin lo jiper begini? Dari dulu, mau secakep dan sesempurna apapun pacar lo, lo selalu ninggalin mereka setiap mereka minta dibawa ke jenjang yang lebih serius. Kenapa sih? Lo mapan. Orang tua lo juga udah capek mendesak lo buat segera menikah. Apa lagi yang bikin lo nggak mau?"
"Gue nggak siap jadi bapak."
"What?!"
"Gue nggak siap jadi bapak. Mau lo bilang 'oh, dia bukan penuntut. Dia nggak akan masalah walau nggak punya anak' itu jelas nggak mungkin. Sifat alami manusia itu serakah. Kita menginginkan ini, kemudian kita dapat. Cuma perkara waktu buat kita untuk mulai menginginkan sesuatu yang lain lagi. Nggak habis-habis. Daripada memaksakan diri, mending menyudahi semuanya sebelum terlalu terlambat. Clear sekarang?"
"Alasan paling konyol sedunia yang pernah gue dengar."
"Jadi bapak itu—"
Kata-kata Jef terhenti ketika dia mendengar suara isak perempuan di balik pintu depan unit apartemennya dan itu bikin jantungnya berdebar jauh lebih kencang daripada saat Rosé baru mulai mengetuk pintunya dengan membabi-buta seperti tadi. "Anjrit, Jen! Dia mewek!"
"Bahlul, buka pintu lo! Samperin! Tenangin!"
"Kalau gue ditusuk gimana?!"
"Selow, ada gue."
"Maksudnya?!"
"Telepon gue. Nanti gue kirimin ambulans. Usahain aja lo nggak kehabisan darah sebelum ambulans-nya datang."
"Heh, tai!"
"So sorry, tapi lo harus omongin semuanya dengan baik-baik sama dia. Lo dan dia sama-sama teman gue. Gue nggak bisa taking sides di sini."
"Jen—"
Jennie memutus sambungan telepon mereka, membuat Jef spontan mengacak rambutnya dengan wajah frustrasi. Lelaki itu membuang napas keras, berpikir sejenak sementara suara tangis Rosé masih terdengar. Akhirnya, dia menyerah dan membuka pintu.
Sosok Rosé yang garang tidak terlihat lagi. Gadis berambut hitam itu sepenuhnya telah terduduk di depan pintu, dengan kaki terbalut stiletto dan betis melekat ke lantai yang dingin. Matanya basah. Dia memandang Jef dengan sorot penuh luka.
"Hei, hei, don't cry." Jef berbisik kikuk, ragu-ragu menghapus air mata di pipi Rosé dengan jemarinya. "Please. Jangan nangis. Kamu tahu aku paling nggak bisa lihat perempuan nangis."
"Aku mau nampar kamu sekarang tapi sayangnya tenagaku sudah cukup habis buat gedor-gedor pintu tadi."
"Mau aku wakilin?"
"Nggak." Rosé membalas galak.
Jef kicep sejenak. "Masuk dulu ya? Aku bikinin teh buat kamu."
Rosé tidak menjawab, namun menurut ketika Jef meraih tangannya, mengajaknya berjalan masuk ke ruang tengah dan membiarkannya di sofa. Selama sesaat, lelaki itu menghilang ke dapur, kembali dengan lime tea and honey buatannya yang dia tahu jadi favorit Rosé. Namun gadis itu tidak sedang dalam mood untuk minum teh sekarang. Dia mengabaikan mug yang diletakkan Jef di atas meja, malah menatap lelaki itu tajam.
"Tehnya nggak aku racun, in case kamu curiga."
"Mau kamu apa?"
"What?"
"Mau kamu apa?" Rosé mengulang lebih tegas, pandangannya nanar. "I gave you my all. My love. My understanding. Myself. Semuanya. Tapi apa yang balik kamu kasih ke aku? You left me without words. Pergi begitu saja. No calls. No text messages. You changed your phone number. You treat me like I am just a stranger. Even tadi waktu lihat aku, kamu banting pintu di depan wajahku. Salah dan kurangku apa, Jeffrey? Kasih tahu aku."
"Roseanne—"
"To the point. Aku nggak punya waktu buat omong kosongmu."
Jef menghela napas dengan mata lekat pada wajah sembab gadis di depannya. Oke, dia mungkin bersalah. Sebulan lalu, setelah sebuah malam yang berlalu dengan baik-baik saja—that night was great. They made love, whispering sweet nothings to each other and stuffs—sampai akhirnya Rosé tiba-tiba membawa gagasan tentang pernikahan dan keluarga di masa depan dengan sebuah tanya; "kebayang nggak, kalau kita punya anak di masa depan, nanti kamu mau namain dia apa?"
She lost him at that question.
Dari awal, Jef sudah bilang kalau Rosé mau mencari seseorang yang bisa memberinya komitmen, bukan dia orangnya. Rosé setuju, bilang kalau itu nggak penting buat dia. Namun setelah dua tahun mereka bersama, kelihatannya Rosé mulai menginginkan itu. Bisa jadi karena tuntutan keluarga atau juga karena kebanyakan teman seumurnya sudah settle dan membina keluarga.
Jef masih nggak bisa.
Malah, mungkin nggak akan pernah bisa.
He was too overwhelmed. Pertanyaan Rosé yang terkesan sambil lalu dan nggak serius menjejali pikirannya dengan banyak tanya. Jef terlalu cemas, terlalu takut sampai akhirnya dia memilih pergi begitu saja, meninggalkan Rosé tanpa bilang apa-apa. Waktu dia kembali ke Jakarta tadi pagi, dia kira Rosé sudah lupa. Benar kata Jennie, gadis itu cantik, mapan, mandiri dan cerdas. Ada banyak laki-laki yang antre buat dekat sama dia.
Buat Jef, nggak apa-apa Rosé mencapnya cowok brengsek dan melupakannya sekalian—karena mau didesak sampai kapanpun, dia nggak akan pernah bisa memberi apa yang gadis itu inginkan.
"You know it well. I can't."
"Nggak bisa apa?"
"Ngasih kamu apa yang kamu mau. Berumah tangga. Punya anak. Bukan sesuatu yang aku rasa cocok buatku."
"Aku cuma bercanda."
"Tapi kamu jelas menginginkan itu, kan? Jawabannya tetap sama. Aku nggak bisa."
Rosé bungkam.
"You're precious. You're pretty, talented and smart. Mudah buat kamu nemuin pengganti aku. Mending kita selesai aja, daripada wasting time. Terutama karena kita udah sama-sama tahu apa yang kita mau."
"Jeffrey, what's so scary about marriage? What's so scary about being a father?"
Jef belum sempat menjawab waktu ponselnya tiba-tiba meraung. Dia mengeceknya, mukanya langsung berubah saat dia sadar ibunya yang menelepon. Hanya dengan satu kali swipe pada layar, telepon pun terjawab.
"Nggih, Buk?"
Rosé membiarkan Jef melangkah menjauh menuju balkon buat bicara dengan ibunya. Percakapan mereka tidak berlangsung lama, tapi Jef belum lagi kembali ke ruang tengah ketika ponselnya kembali berdering buat yang kedua kalinya. Jef menjawabnya tanpa melihat, menebak itu masih ibunya.
"Menopo, Buk?"
Tapi itu bukan ibunya. Suaranya terdengar parau dan canggung, seperti orang yang tengah flu atau terlalu banyak berteriak. "Jeffrey? Ini Tris."
Kening Jef berlipat. Dia mengecek layar ponselnya dan benar saja, nomor yang meneleponnya adalah nomor yang asing. "Halo. Tris siapa ya? Dari mana kamu dapat nomor ponsel saya?"
"Patricia."
"Patricia yang man—" kata-kata Jef tertahan ketika mendadak, dia tersadar dia hanya pernah mengenal satu orang dengan nama Patricia sepanjang hidupnya.
"Patricia Gunawan." Perempuan di seberang telepon terbatuk. Ada jeda sejenak sebelum dia meneruskan dengan bimbang. "Tris. Teman kamu... waktu SMA dulu."
Tidak perlu ada keterangan lebih lanjut karena Jef sudah mengingatnya. Seketika, dia membeku di tempat. Dia bahkan lupa pada keberadaan Rosé yang masih duduk di ruang tengah apartemennya, memandangnya melalui pintu balkon yang terbuat dari kaca.
Patricia Gunawan adalah mantan pacarnya ketika dia masih SMA—itu artinya, hampir dua puluh tahun lalu.
Tetapi tentu saja, Jef tidak akan pernah bisa melupakan sosoknya.
"Sori, saya sedang sibuk dan—"
"Kita harus bicara. Ini penting."
Ada sesuatu dalam suara Tris yang bikin Jef batal menutup telepon. "Saya nggak ingat saya punya urusan penting yang belum selesai dengan kamu dan—"
Tris menghela napas. "Bisa dengarkan saya dulu?"
Separuh bagian diri Jef ingin menolak, tapi anehnya, jawabannya justru bertolak belakang. "Go ahead."
"Tentang apa yang terjadi diantara kita hampir dua puluh tahun yang lalu, saya—" suara Tris tersendat dan itu bikin lipatan di dahi Jef kian dalam.
"Iya?"
"—saya mau ngasih tahu sesuatu. Saya tahu, ini kesannya seperti sangat dibuat-buat karena setelah sekian lama, kenapa saya baru menghubungi kamu sekarang. Tapi ini penting dan selain itu, kalau bukan sekarang, saya nggak yakin saya punya waktu lain buat ngasih tahu kamu."
"You scare me. Ada apa?"
"Dua puluh tahun yang lalu—apa yang terjadi malam itu—"
Jef diam menunggu, sampai akhirnya Tris meneruskan kata-katanya—yang tidak dia duga, akan terdengar seperti vonis mati untuknya.
"Kamu punya anak."
to be continued.
***
ea gimana ni beb lanjut ngga.
btw ini kedepannya bakal rada-rada koplak gimana gitu si ya bersiaplah kalian ketemu badrol dan ojun.

Semarang, September 25th 2019
19.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro