17 • sabar dan ikhlasin

Jalanan Malang hari ini masih basah akan sisa-sisa hujan tadi malam. Bahkan sampai detik ini, langit masih muram dan menjatuhkan air matanya. Lelaki yang turun dari punggung sang kakak berjalan terseok-seok. Lemas, ngilu, dan takut menyelimutinya bersamaan. Banyaknya orang berlalu lalang dengan wajah tertunduk, membuat hatinya jauh lebih perih dari segala macam penderitaan yang pernah singgah.
Nanda menelan ludah saat beberapa pasang mata dari mereka tak berhenti menatap. Ia enggan memandang wajah sembap mereka. Pakaian serbahitam lengkap dengan tudung tersebut membuat hatinya berdesir.
"Walaupun nanti udah pisah kota, jangan lupa jengukin aku di sini, ya."
Mata Nanda menatap lurus ke depan. Rumah itu ... semuanya masih sama. Ia sesekali berhenti berkat memori yang kembali tayang di dalam ingatan. Wajahnya, suaranya, tingkah lakunya, semua terputar satu per satu.
"Di Jakarta nanti, jangan lupa cari cewek, Nda. Prinsip mengejar harus totalitas."
Tepat di bawah pohon rindang, sahabatnya itu mengucapkan segelintir nasihat padanya. Kemenangan atas sosok wanita yang sempat Nanda kagumi membuatnya berbangga diri. Binar mata itu membuatnya tersenyum, menemani air mata yang telah menetes.
"Pulang, Nda. Pulang, Fer. Bari butuh kalian."
Tiba-tiba dingin menyerang kulit Nanda. Ia jatuh terduduk saat kaki rapuhnya itu mendekati ambang pintu. Tubuhnya bergetar hebat kala melihat sahabatnya berbaring di dalam peti.
"Nda!" Dian segera mendekat memeluk adiknya dari belakang. "Sstt, tenang, Nda. Sabar," ucapnya lembut, tepat di samping telinga adiknya.
Lelaki itu tak dapat membendung ribuan air mata yang tersimpan. Telinganya seakan tuli, tak bisa mendengar dengan jernih. Tenang, sabar, atau apa pun itu tak kuasa masuk ke otaknya. Matanya kian memburam, dipenuhi dengan air yang tak berhenti terjatuh.
Sahabatnya telah menyambut tepat di hadapannya. Sungguh dekat dan sangat dekat.
Haruskah sekarang? Benarkah hari ini? Bukankah ini terlalu tiba-tiba?
"Nanda?"
Seorang gadis berambut pendek dan mata sembap pun mendekat. Ia mengambil alih Nanda dari pelukan sang kakak. Gadis tersebut ikut menumpahkan air matanya di sana.
Erat sekali, ia memeluk Nanda. Seakan-akan jika melepasnya, ia akan kehilangan untuk kali kedua. Rambutnya sudah acak-acakan, lingkaran di bawah matanya turut menjelaskan bahwa ia telah terjaga semalaman.
Nanda ingin membalas pelukan tersebut, tetapi tangannya kaku, kakinya pun linu. Semua badannya berdemo meminta diistirahatkan. Namun, tidak untuk hari ini.
Ia memilih untuk mendekat. Mendekat pada sang kawan. Kawan yang telah memanggilnya untuk menjenguk. Kawan yang memintanya untuk memeluk. Walau semuanya, telah terlambat.
"La, bantu aku."
Gadis bernama Axela itu mengangguk. Ia terlebih dulu mengusap air mata di pipinya, sebelum membantu itu untuk berdiri. Dian yang melihat hal tersebut berinisiatif untuk turut serta, tetapi dengan sopan Axela menolaknya.
Kedua insan yang sempat bertukar rasa di masa lalu itu berjalan mendekati sosok yang tertidur dengan damai. Tepat saat jarak tak lagi jauh, Nanda melepas bantuan Axela dan duduk di sebelah peti. Ia menyeret kakinya, sedangkan pandangan tak terlepas dari Bari.
Tangannya tergerak untuk menyentuh pipi chubby sahabatnya. "Di-dingin, ya, Bar?"
Axela kembali menitikkan air mata. Mendengar suara Nanda yang bergetar membuatnya ikut runtuh. Ia tak lagi sanggup mendongak.
"Kamu lupa, Bar?"
Nanda tak lagi menyentuh Bari. Tangannya berjaga di peti dan mencengkeram kuat. Ia mulai mengingat percakapan beberapa waktu lalu, sebelum berangkat ke Jakarta.
"Komplikasi itu nyebelin, ya. Sarafku udah kena, sekarang paru-paru tambah parah. Badan udah kayak motor rongsok, bolak-balik masuk bengkel."
"Sabar, Nda. Ini semua karya Tuhan. Anggap aja kita itu ladang rejeki manusia lain."
"Serah, deh."
"Nda!"
"Hem?"
"Berjuang bareng, ya."
"Pasti."
Memori itu mengoyak batin Nanda habis-habisan. Lelaki itu menggeleng kuat dan memukul-mukul peti kayu di depannya hingga meninggalkan luka di telapak tangan.
"Mana? Katanya bareng. Kok kamu duluan? Jangan nyuri start gini, dong. Nggak asik!"
Feri yang sejak tadi terdiam di samping ibu Bari pun beranjak. Hatinya menolak untuk tetap terpaku dan membiarkan sahabatnya meraung-raung seperti itu. Ia lekas duduk di samping Nanda dan memegang pundaknya, mengusap, lalu menarik untuk menjauh.
"Nda, mundur dulu."
"Lepas!" Nanda menghempaskan tangan Feri dari pundaknya. "Aku belum selesai ngomong. Bari masih punya urusan sama aku!"
"Nda--"
"Diem, Fer! Diem!"
Feri hanya dapat memejamkan mata. Ia mengambil napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Sekuat tenaga ia mencoba mendinginkan pikiran. Berdebat saat kalut bukanlah solusi.
"Ikhlasin, Nda."
"Enggak!" Nanda mulai memberontak. Tenaga yang semula hilang tiba-tiba datang entah dari mana. Dengan sigap Feri memeluk sahabatnya, mencoba menenangkan.
"Ini pilihan Bari. Kita harus terima," ucap Feri pelan, menaikkan nada bicara hanya akan mengganggu hati Nanda.
"Enggak! Bari yang kukenal nggak kayak gini." Nanda terus berseru. Tangannya berusaha melepas dekapan Feri, tetapi tidak bisa. "Enggak, enggak ... eng ...."
Tubuh Nanda makin lemas dan ia pun luruh. Matanya terpejam rapat tanpa celah sedikit pun. Kesadaran laki-laki itu telah hilang.
"Nda? Nda?"
Feri merenggangkan pelukannya sebentar. Ia dapat melihat bahwa kawannya sudah tak sadarkan diri. Ia kembali memeluk Nanda dengan erat dan menumpahkan air matanya pada pundak lelaki itu. Ia lelah mencoba tegar. Ia sengaja menunggu Nanda untuk datang. Hanya tubuhnya yang berhak menjadi saksi keruntuhan Feri.
"Jangan ikut Bari dulu, Nda."
Setelah kejadian itu, Nanda lekas dibawa ke rumah sakit. Ia dijaga oleh kedua kakaknya yang belum beristirahat sedari tadi.
Dina lantas mengusap rambut basah milik Nanda. Wajah sang adik masih pucat, lengkap dengan masker oksigen yang membantunya bernapas. Sesekali wanita itu meregangkan otot, lelah karena terlalu lama duduk.
"Mbak pulang aja, istirahat. Kasian keponakanku. Dian bisa jaga Nanda sendirian."
"Mbak tau, tapi bukan itu masalahnya. Mbak takut kalau--"
"Nanda bakal histeris kayak dulu lagi? Iya?"
Dina mengangguk. Masih jelas di ingatannya, bagaimana lelaki kecil itu menolak segala perawatan dan membuat kekacauan. Dulu, berita kehilangan kedua orang tua membuatnya tak memiliki semangat sampai berkali-kali ingin mengakhiri hidupnya. Perasaan bersalah bertubi-tubi mendera dan mengganggu jiwa.
Dian pun berlutut dan menatap Dina. Kemudian ia menenggelamkan wajahnya di perut kakaknya dan memeluk erat. Matanya kosong menatap lantai. Ia tentu juga mengingat hal itu. Kejadian yang membuatnya tak ingin melepas si bungsu jauh-jauh.
"Nanda udah gede, Mbak. Yakin aja, nggak bakal terjadi apa-apa."
Dina mengusap rambut Dian lembut. "Gangguan psikis itu tanpa pandang bulu. Mau tua, mau muda ... terserah mereka."
Dian mengangkat wajahnya, lalu menggenggam pergelangan tangan Dina erat. "Dian tau. Dian paham, Mbak. Tapi Dian juga yakin, Nanda anak yang kuat."
"Oke, Mbak pulang. Tapi kamu harus janji, kalau ada apa-apa segera telpon Mbak atau Mas Syahrul. Jangan apa-apa diatasin sendirian. Paham?"
"Siap!"
Dina tersenyum. Ia memeluk Dian sekali lagi dan tak lupa dengan mencium keningnya. Hal serupa ia lakukan pada Nanda sebelum keluar dari ruang rawat. Meski langkahnya enggan dan berat, ia terus berjalan sampai tak terlihat lagi dari ambang pintu.
Seketika Dian mengacak rambutnya. Ia segera duduk di kursi sebelah ranjang Nanda dan meraih tangan yang tertancap infus dan cairan lainnya itu. Berbagai macam selang yang menembus kulit Nanda selalu sukses membuatnya ngeri.
Dengan sayang, Dian mencium punggung tangan adiknya cukup lama. Matanya terpejam, menghayati waktu yang perlahan berjalan. Ia mengusap pipi Nanda yang dipenuhi ruam. Simbol yang menjadi saksi penderitaannya selama ini.
"Please, jangan kepikiran macam-macam."
"Please, bangun secepat mungkin."
"Please, Nda."
Lelaki itu terus bermonolog. Ia tak henti memanjatkan doa agar adiknya segera bangun. Meski dokter telah mengatakan bahwa tidak ada yang serius, tetap saja bibit khawatir tumbuh dengan baik di hatinya. Dian terus berbisik dan meminta Nanda untuk membuka mata.
"M-Mas ...."
Suara parau muncul dari balik oksigen. Helaan napas lega pun terlepas. Dengan sigap, Dian menekan tombol darurat agar dokter dan perawat segera datang untuk memeriksa.
"Hai, Jagoan."
"Mas ...."
"Hem?" Dian terus tersenyum, berusaha tidak terlihat panik.
"Nanda m-mau pulang."
"Iya, nunggu dokter dulu."
Nanda mengedipkan mata cukup lama. "Pu-lang ... sama Ibu."

Jangan demo aku!
Part ini nggak ada Olin karena takut feel-nya berantakan.
Enjoy your day 😊
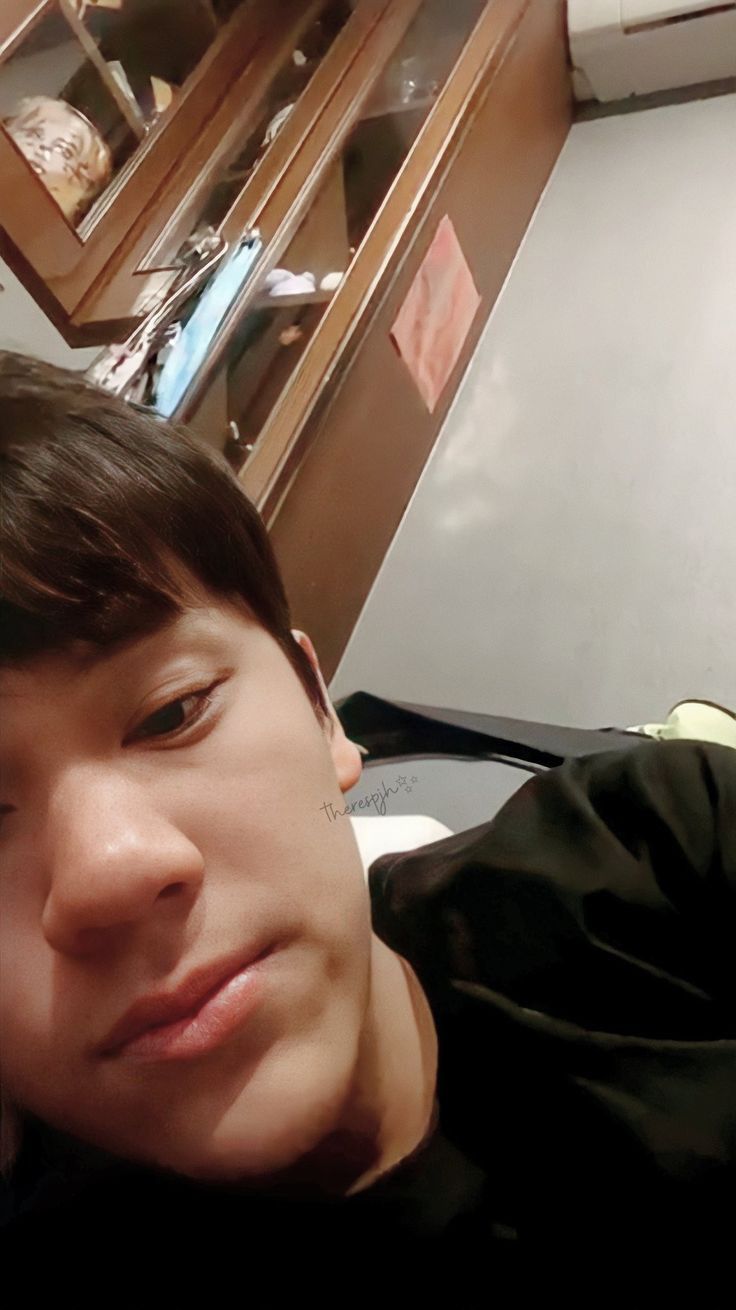
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro