03
3
Yasmin
Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu.
Rinduku hanya kamu, rindu hangat-hangat kuku.
Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali.
Itulah cintaku, yang takkan mungkin terbagi-bagi.
Cukup kamu saja, kamu saja, yang di hati.
Aku tetap setia, tetap setia, sampai mati ....
Suara centil Lavenia menyanyikan Cinta Merah Jambu yang berirama Mandarin terdengar keras di dalam angkot. Mau tidak mau, aku senyum-senyum sendiri. Pikiranku membayangkan 'kencan' malam minggu kemarin. Karena sudah dekat EBTANAS, Papa Mama tidak mengizinkanku ke luar rumah. Jadilah, Kun di rumah, menemaniku belajar Matematika.
"Maaf, ya ... Kun jadi merepotkanmu," kata Mama sambil menaruh teh dan kudapan di atas meja, "Nilai Yas jauh banget merosot. Ayi (Bibi/Tante) jadi khawatir, Yas nanti nggak lulus EBTANAS."
"Nggak apa-apa, Tante. Saya juga kebetulan lowong, kok," Kun lalu mengambil buku ulanganku yang nilainya merah semua. Kernyitan di kening dan gelengannya jelas menyiratkan dia sedang prihatin.
"Sudah tahu benci Matematika, kok malah 'milih jurusan IPA, sih?" omel Kun.
"Kan aku pengin kelihatan pintar, Ko. Dari dulu, anak IPA itu kayaknya keren banget," kataku, "Aku malah heran sama Koko. Anak Teladan kok malah 'milih jurusan IPS."
Kun mengerutkan alis, "Emang kenapa kalau aku 'milih jurusan IPS?"
"Ngg ...." Aku tidak bisa menjawab.
"Yas, Yas. Naik angkot aja harus tahu tujuannya, Yas. Apalagi hidup," kata Kun seraya tersenyum, "Hidup itu harus kita yang tentukan, bukan sekadar ikut-ikutan. Memangnya, kamu nggak pernah rencana nanti mau kuliah apa? Kerja di mana? Menikah sama sia—" ucapan Kun terputus. Dia malah berdeham dua kali setelah itu. Ketika kuperhatikan, muka Kun sudah merah padam.
"Ngg, anu ... ada baiknya kamu merencanakan hidupmu, Yas," Kun kini terbatuk-batuk, "Dari kecil, Papa selalu ngajarin aku untuk hidup terorganisir. Itu membantu banget buat segalanya. Bahkan sekarang, saat aku pisah dengan orang tuaku, aku sudah terbiasa."
Yah, kok Kun mengalihkan pembicaraan, sih.
"Kalau aku pengin kuliah di Trisakti juga, kayak Koko, gimana?" tantangku.
"Ya, boleh aja. Tapi, kamu harus rajin belajar, dong!" Kun menjawab dengan lempengnya.
Ah, nggak asyik! Aku mencibir, "Kalau aku pengin di kerja di tempat yang sama dengan Koko, gimana?"
"Nah, kamu harus memasukkan lamaran kerja dulu, baru tahu diterima nggaknya," ekspresi Kun masih belum berubah.
"Kalau misalnya aku mau menikah sama ..." aku sengaja memanjang-manjangkan jeda kalimatku. Bisa kulihat, rona merah di wajah Kun sudah kembali. Dia mengambil buku lalu membolak-baliknya sembarangan.
"Kalau misalnya aku mau menikah sama Andy Lau, gimana, Ko?"
Wajah Kun makin merah padam, "Kalau gitu, kamu kayaknya harus ngaca dulu," katanya jengkel.
"Apaan, sih ... Ko?" tanpa ampun lagi, kuhajar Kun dengan bantal kursi. Kami baru berhenti berantem waktu Mama datang sambil menggeleng-geleng.
*
Kautahu hatiku, sedih sirna sudah jadi cinta
Terindah bagiku, jangan biarkan kita berpisah.
Mungkinkah, oh, kasih, tinggalkan dirimu dalam sepi.
Hilangkan dukamu, bersama kita merajut cinta.
Lagu di dalam angkot kini berganti. Bisa saja Pak Sopir ini mengombang-ambingkan hatiku. Aku jadi ingat, Kun pernah menyanyikan soundtrack Putri Sinyue ini dalam bahasa aslinya. Tentu, jatuhnya lebih romantis. Apalagi, saat itu Kun menyanyi sambil memandang mataku!
"Stop, Pak!" aku berseru pada Pak Sopir. Masih tersenyum-senyum, aku membayar ongkos ke kernet angkot. Matahari sore yang masih terik tidak mengubah suasana riang hatiku. Mulutku berusaha menyanyi-nyanyi Wo Bu Guai Kan Ni De Yan Shen (= Aku Seharusnya Tidak Memandang Matamu, lagu yang dipopulerkan Su Rui dan Abee). Beberapa kali aku selip lidah dan aku menertawakan diriku sendiri, jauh benar penguasaan bahasaku dengan Kun.
Maklumlah, Keluarga Kun adalah keluarga totok (masih murni) yang dulu tinggal di Batam. Ketika papaku harus puas membaca novel Asmaraman Sukowati alias Kho Ping Hoo (banyak yang bilang, karya-karya beliau sebenarnya tidak sesuai fakta lapangan di Tiongkok), Papa Kun sudah mampu membaca Samkok (Kisah 3 Kerajaan) dalam huruf-huruf Mandarin. Ketika Mamaku membaca novel terjemahan karya Chiung Yao, Mama Kun sudah membaca syair Su Dongpo dan Impian Bilik Merah (salah satu novel sastra klasik Tiongkok). Akses untuk bepergian ke Singapura juga mempengaruhi kebebasan mereka, sih. Maklum saja, kalau di Indonesia, baik bahasa, tradisi maupun budaya Tionghoa adalah suatu tabu bagi pemerintah. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu belajar dan mengakses pengetahuan dari negeri tirai bambu tersebut.
Ah, Kun. Kapan, ya ... aku bisa ke luar negeri juga seperti pujaan hatiku itu? Aku juga ingin ke Singapura lalu melihat kehidupan Tionghoa peranakan di sana. Kun pernah memperlihatkan kepadaku fotonya mengenakan kostum jenderal. Bagiku, dia terlihat tampan sekali. Aku jadi ingin mengenakan kostum tradisional juga lalu berfoto di sisinya.
Tit! Tit!
Lagi enak-enaknya melamun, aku malah mendengar orang mengklaksonku dari belakang. Siapa, sih, yang mengklakson di jalan sepi begini? Lagian, aku jalannya sudah di pinggir! Masa iya, aku disuruh lompat masuk got?
"Yas!"
Panggilan itu seketika membuat bulu kudukku merinding. Ya, Tuhan! Kupikir, aku sudah bebas dari Gatot Trenggana! Ketika dia bilang akan melanjutkan pendidikan di Magelang, aku langsung bersujud syukur. Siapa sangka, hari ini tiba-tiba aku melihatnya kembali?
Kesal sekaligus takut, aku berbalik lalu melihat Gatot. Dengan badan kekar bak Rambo dan rambut cepaknya, sosok Gatot semakin menakutkan. Apalagi, saat itu dia sedang mengendarai motor Harley. Kebiasaan pamer, mentang-mentang keluarganya berada.
"Cantik, kuantar pulang, yuk!"
Sedetik. Dua detik. Aku tidak mampu menemukan jawaban yang tepat. Sebisa mungkin, aku ingin menghindari konflik dengannya.
"Sudah dekat, kok. Nggak apa-apa, aku jalan aja," tolakku sopan.
Gatot menggeleng, sorot matanya menusukku tajam, "Udah lama nggak lihat Om Setio, nih. Yuk, sekalian aku pengin nyapa-nyapa. Papi juga ada titip salam. Dia mau ngundang kalian ke pesta ulang tahunnya."
Cih! Lagi-lagi berusaha menekanku dengan menggunakan nama Papa, "Papa lagi kerja. Nggak ada di rumah."
Gatot menggaruk kepalanya, mulai kehabisan ide tampaknya, "Panas, nih. Makan es campur, yuk!"
"Aku masih kenyang," aku masih berusaha memaksakan seulas senyum. Duh, ini orang maksa banget. Aku menoleh-noleh, bersiap berteriak minta tolong. Biarin, deh ... disangka gila. Daripada dimacam-macamin.
"Kamu masih sombong kayak dulu ternyata," komentar Gatot. Dia mematikan motor, mendongkraknya, lalu berjalan menghampiriku. Tiap langkah, aku merasa jantungku bakal tercerabut. Duh, tolong!
Tangan Gatot meraih daguku. Kilat buas dalam pandangannya semakin menggentarkan hati, "Yas, kudengar, kamu pacaran sama Kun, kan? Kamu pasti sudah pernah gituan sama dia, kan? Nggak pengin coba yang lain? Kujamin, sama aku bakalan lebih asyik! Aku janji, pertama kali, aku akan berlaku lembut sama kamu. Kamu pasti ketagihan."
Ya, Tuhan! Tawaran menjijikkan macam apa ini? Tanpa kusadari, tanganku bergerak begitu saja menampar wajah Gatot. Sayangnya, tamparanku itu bak gigitan nyamuk. Sama sekali tidak menggoyahkan Gatot. Dia justru mengetatkan cengkeramannya di daguku. Mataku berair, rasanya sakit sekali.
"Kun ... nggak ... pernah ... ngapa ... ngapain ...." Susah payah, aku berkata.
Namun, alih-alih menerima, Gatot malah tertawa keras-keras. Dia melepaskan cengkeramannya dengan kasar, bahkan, bisa dibilang dia nyaris melemparku ke dalam got.
"Nggak usah pura-pura, Yas! Nggak ada cowok normal yang tahan pacaran tanpa ngapa-ngapain. Di mana-mana, orang pacaran itu, ya, bersenang-senang! Nggak ada hubungan pacaran yang murni pacaran doang. Kecuali, Kun-mu itu impoten! Hahaha! Apa anunya nggak bisa berdiri? Atau anunya terlalu kecil hingga dia malu sama kamu?"
Kemarahan benar-benar menguasaiku sekarang, "Jadi, kamu pikir, lelaki jantan adalah lelaki yang mengumbar alat kelaminnya ke mana-mana? Hina sekali pemikiranmu! Sayangnya, nggak semua lelaki itu murahan kayak kamu, Bangsat!"
Tak tahan lagi, kuludahi wajah Gatot. Tentu, si maniak begitu marah karena tindakan beraniku itu. Dijambaknya rambutku. Didorongnya aku hingga aku tersungkur di atas aspal. Dia menonjok hidungku. Tinjunya menghantam kepalaku. Dia juga menamparku berkali-kali.
Entah tenaga dari mana yang membuatku bisa mempertahankan kesadaran. Hantaman di kepalaku, rasa mual di perutku, semua masih bisa kulawan dengan pukulan dan tendangan yang kukerahkan sebisa mungkin.
"Tolong! Tolong!" aku berteriak keras saat Gatot mulai menindihku lalu berusaha mengekang tanganku.
"Jangan lupa! Kamu yang minta ini! Siapa suruh, minta baik-baik nggak dikasih," Gatot mendengus gusar seraya berusaha membuka kancing-kancing kemejaku. Seragam sekolahku koyak-koyak tak lama kemudian dan aku mulai menangis.
"Tolong! Tolong!" ratapku. Jangan biarkan iblis ini menodaiku! Tolong!
"Udah, lebih baik elu terima aja! Cepat atau lambat, ini pasti akan terjadi! Orang-orang Cina antek asing kayak elu emang paling pantas diperlakukan kayak gini! Elu tuh cuma numpang di negara ini! Udah untung ada yang mau 'merkosa elu! Dengan gitu, elu nggak akan jadi Cina lagi!"
"Lepasin, Setan!"
"Jangan munafik lu!" Gatot turut berteriak. Kali ini, aku menggigit tangannya. Raung kesakitan Gatot semakin membakar semangat perlawananku. Dengan mengerahkan seluruh tenaga, kuhantam kepalanya dengan jidatku. Serangan ini membuat Gatot lengah dan membukakan celah untukku berdiri lalu berlari sejauh-jauhnya.
Seperti orang gila, aku terus berlari sampai ke daerah perumahan yang lebih ramai. Ini memang semakin jauh dari rumahku. Namun, aku sudah tidak peduli.
"Tolong! Tolong!" aku berteriak seraya menangis tersedu-sedu.
"Babi! Jangan lari, Lu! Gua belum selesai!" aku mendengar Gatot masih berusaha mengejarku. Lagi-lagi, entah kekuatan dari mana berhasil memaksaku menciptakan jarak yang semakin jauh.
Untungnya, di ujung jalan depan, ada sebuah Poskamling. Beberapa bapak-bapak tetangga sedang berkumpul di sana. Mereka mendengar seruanku, lalu segera berlari menghampiriku.
"Anjing!" maki Gatot sebelum dia berbalik, kabur.
"Woy, siapa itu! Jangan lari, woy!" Pak Sunu—bapak berkaca mata yang mengontrak di seberang rumah—ingin mengejar Gatot, tapi tangis ketakutanku mencegahnya. Bapak-bapak yang lain juga tampak lebih khawatir melihat keadaanku. Kata-kata penghiburan mereka terdengar di sela tepukan simpati.
Pak Sunu menyampirkan jaketnya menutup pakaianku. Bapak-bapak Poskamling kemudian membawakanku air minum dan berusaha menenangkanku. Diiringi penjagaan bapak-bapak yang baik itu, aku kemudian kembali ke rumah.
*
Sejak pelecehan yang kualami itu, Papa melarangku naik angkot. Dia memilih meminta izin untuk menjemputku sekolah. Lebih baik dipecat daripada membuat anak celaka, begitu kata Papa. Tentu, pernyataannya ini membuat bos Papa marah. Papa kemudian resmi dipecat dan beralih profesi jadi seorang sopir taksi. Penurunan pekerjaan ini semakin menyusahkan keluarga kami. Aku pun semakin merasa bersalah karena bisa-bisanya dilecehkan Gatot.
Mama sendiri terlihat tidak enak setiap kali pulang arisan. Namanya ibu-ibu kalau tidak merumpi itu kayaknya kurang afdol. Kejadian pelecehan yang kualami tentu menjadi bahan yang sangat hangat untuk dibahas mereka. Beberapa kabar burung menyebutkan kalau aku mungkin memang kegenitan. Apalagi, beberapa kali aku menerima kunjungan Kun ke rumahku. Anak gadis yang dikunjungi laki-laki, apalagi namanya kalau bukan perempuan gampangan, kata mereka.
Aku jadi susah ke luar rumah. Tiap kali, kalau ada ibu-ibu melihatku, Ibu itu akan menggeleng-geleng, lalu menatapku dengan tatapan yang tidak kumengerti. Diam-diam, mereka berbisik-bisik sambil memandangku sinis.
Kalau saja tidak harus menghadapi EBTANAS, ingin sekali aku mengurung diri terus di rumah. Sayangnya, bahkan di rumah pun, aku tidak pernah merasa tenang. Pertanyaan-pertanyaan Papa seperti: 'siapa yang melakukannya?' selalu membuatku takut. Pernyataan Gatot bahwa aku antek asing yang menumpang di negara ini berkali-kali terngiang di telingaku.
"Udah untung ada yang mau perkosa elu!"
Aku menggeleng keras sambil menjambak rambutku. Suara telepon yang dulunya selalu kutunggu, kini menjadi sesuatu yang menakutkan bagiku. Bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada Kun? Apakah dia bisa menerima ceritaku, atau malah membuat asumsi-asumsi aneh seperti ibu-ibu arisan? Selama ini, Kun memegang tanganku dengan takut-takut, tapi Gatot malah mengoyak bajuku dengan begitu kasar.
Aku malu!
Tepatnya, sebelum Kun bertanya, aku lebih dulu marah pada Kun. Aku bilang, dia terlalu mengganggu. Aku bilang, aku mau lulus SMA dengan nilai memuaskan. Aku minta, dia tidak menghubungiku lagi.
Berminggu-minggu, aku menghindar dari Kun. Dia tidak berkunjung ke rumahku. Dia juga tidak meneleponku selama EBTANAS berlangsung.
Lalu, satu pagi di bulan Mei itu, barulah terdengar dering telepon darinya lagi.
Perasaanku teraduk-aduk. Ketika Mama memanggilku, aku ingin sekali berteriak karena Mama menolak mengatakan aku tidak ada. Dengan uring-uringan, aku mengambil gagang telepon lalu menempelkannya di telingaku.
"Yas, itu kamu?"
Kun batuk-batuk. Suaranya sengau. Rasanya lama sekali, aku merindukan suara ini. Ya, Tuhan! Apa yang selama ini kulakukan? Tiba-tiba, aku merasa sangat bodoh.
"Yas, gimana kabarmu?"
"Baik," jawabku pendek.
Kun batuk-batuk lagi, "Baguslah. Aku lagi pilek, nih. Cuaca lagi nggak baik."
"Oh."
"Aku kangen kamu, Yas."
Aku tidak sanggup menjawab. Rasanya ngilu mengingat malam-malam di mana aku tidak bisa tidur sambil mengawasi suara telepon. Hatiku berharap, Kun akan menelepon. Sayangnya, Kun terlalu taat dengan permintaanku.
"Tempo hari, aku pengin datang ke rumahmu. Tapi kata Aik, kamu lagi sibuk."
"Maaf," hanya ini yang bisa kukatakan.
"Yas, boleh nggak aku ngomong sama kamu?"
Jantungku berdentum kuat, was-was kalau Kun akan menanyakan pelecehan kemarin.
Untungnya, Kun hanya menarik napas. Kata-kata Kun selanjutnya malah membuatku bingung. Jika saja aku tahu maksud kata-katanya ini, aku pasti segera berlari padanya.
"Yas, apapun yang terjadi, aku mau kamu tetap kuat. Tetaplah jadi Yas yang senyumannya selalu membuatku gembira," Kun batuk-batuk lagi, "Aku mau, kamu berjanji."
"Aku janji." Perasaan sesak menghimpit dadaku. Kerinduan yang datang tiba-tiba membuatku tidak bisa bernapas.
"Huh, sayang nggak bisa ngomong langsung ke kamu," kata Kun, "Kapan-kapan, kita keluar bareng lagi, ya. Aku pengin jalan-jalan sama kamu lagi."
"Iya, Ko," perasaanku masih tidak karuan. Sebuah firasat semakin mengacaukan pikiranku. Semua kata-katanya tumpang tindih dalam kesedihan dalam yang tidak bisa kumengerti. Setengah hatiku ingin aku berlari padanya, setengah hatiku ingin mengatakan banyak kata 'jangan' kepadanya. Akan tetapi, bibirku tiba-tiba begitu kelu.
"Hari ini, aku dan teman-teman mau berdemo ke gedung DPR/MPR, Yas. Aku mau membuktikan baktiku pada negeri ini. Aku mau berjuang sampai akhir," kata Kun, "Doain aku, Yas."
Setitik air mata turun di pipiku. Ketika Kun mengatakan kalimat-kalimat berikutnya, aku merasakan dingin di sekujur tubuhku. Firasat menakutkan itu mengaduk perutku hingga aku merasa ingin muntah seketika.
"Jaga diri baik-baik, Yas. Aku pergi dulu."
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Cerita lengkap BERANDA KENANGAN bisa dibaca GRATIS di cabaca.id.
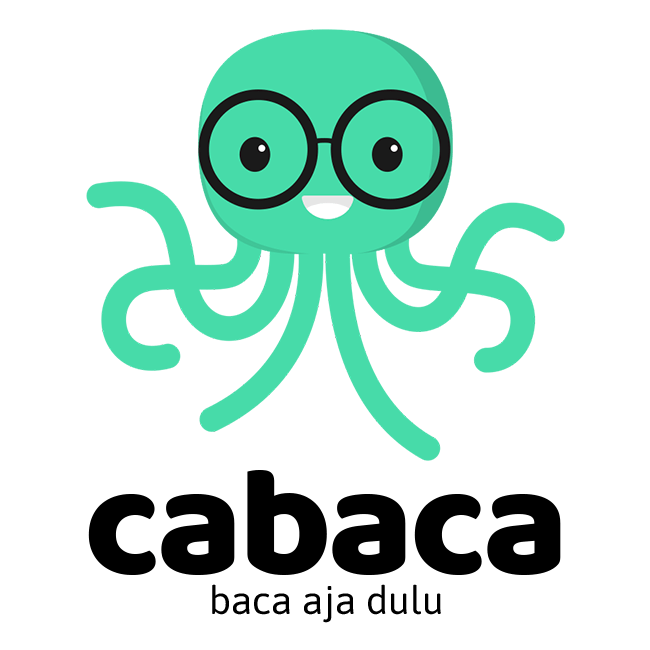
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro