Bab VI | Menangnya Kegelapan
Kabut bergetar oleh amarah tatkala jeritan Erine menggema di antara pepohonan. Cahaya dari tongkatnya meredup, sementara tubuhnya tersentak ke belakang, tangan mencengkeram bahu yang kini tertancap pedang. Ujung bilahnya berlumur darah suci, menetes ke rerumputan hijau yang akhir-akhir ini merebut wilayah angker Hutan Terakhir.
"Alma!" teriaknya. "Apa-apaan kamu!"
Namun, Almaris tidak memedulikan jeritan itu. Begitu pedang mengenai sasaran, ia segera memacu kuda hitam ke arah Dainhart, melompat ke arah sang pria.
"Kau tidak apa-apa?" tanyanya, walau tidak menantikan jawaban Dainhart. Almaris kembali menghadap Erine untuk mengawasi sang penyihir suci yang meronta-ronta kesakitan. Dramatis, pikir Almaris. Padahal cuma tertancap pedang. Coba kalau digigit macan kumbang!
"Kuperingatkan kau, Erine," suara Almaris sedingin ancaman kematian, seolah ia tidak takut untuk memisahkan kepala si penyihir suci dari badannya. "Kau obrak-abrik wilayahku lagi, maka kau yang akan kuumpankan pada macan-macan kumbangku."
Erine memelotot. Ia berusaha meraih tongkatnya lagi, tetapi Dainhart bergerak lebih cepat. Mengabaikan pening di kepala, sang duke menerjang Erine dan memeluntir bilang pedang di pundaknya. Erine menjerit sekali lagi.
"Tuan bangsawan, kenapa kau membela Almaris?" geramnya. "Ia melanggar hukum dengan memangsa manusia biasa, bukan pendosa besar!"
"Dia hanya bertahan hidup, kau mengerti?" Dainhart menggertakkan gigi. Ia tidak menyangka seumur-umur bakal membela seorang penyihir. Yang nyaris mengisap jiwanya, pula. "Raja baru kami justru melindungi pendosa-pendosa besar, sehingga Almaris tidak makan apapun! Apa kau bisa bayangkan hukum dunia tanpa seorang algojo?"
Almaris terperangah menyaksikan pemandangan di hadapannya. Seumur hidupnya pula, baru kali ini pula seorang korban mau membelanya. Sesuatu hangat dan janggal berkeriap di hati, tetapi Almaris buru-buru mengabaikan itu. Ia mengalihkan pandangan pada Erine, efektif menyingkirkan berbagai perasaan selain amarah. Ini bukan waktunya untuk memikirkan hal lain.
Erine mendesis. "Apa maksudmu? Raja kalian seperti itu?"
"Sudah kuduga kau tidak terlalu peduli." Dainhart memeluntir lebih jauh bilah pedang, mengoyak daging dan kesadaran Erine. Si penyihir suci meraung hingga tenggorokannya tersayat, dan serbuk bintang meredup dari rambutnya. "Sebab jika kalian para agen Serikat Sihir benar-benar peduli dengan manusia, maka kau seharusnya berada di kerajaan untuk menindak Raja, sehingga aku tak perlu terlempar ke sini!"
Almaris berusaha menahan senyum mendengar kata-kata Dainhart. "Duke kesatria ini benar," katanya dilambat-lambatkan. "Tapi dunia tak pernah ideal, benar? Semua sibuk mengurus lambung masing-masing. Dan karena itulah, aku mengurus lambungku sendiri." Nadanya berubah sinis di penghujung kalimat. "Karena tak ada pendosa yang dikirim ke sini lagi, jadi aku terpaksa memangsa pendosa-pendosa kecil yang ada."
"Bukan ranahku untuk mengawasi manusia!" Erine mulai meracaukan alasan-alasan lain, membela diri sekeras mungkin sementara kesadarannya dikoyak-koyak pedang. "Ugh, lepaskan aku! Atau kau akan dihukum mati karena membunuh penyihir suci!"
"Dihukum mati dengan dikirim ke hutan ini? Dengan senang hati," Dainhart mencemooh. "Kebetulan aku dan Almaris sudah saling mengenal."
Sementara Dainhart menyiksa Erine, Almaris mengambil tongkat si penyihir suci. Ia mengarahkan ujung kayunya pada diri sendiri, dan dalam sekejap, asap hitam menguar untuk menyelubunginya lagi.
Akhirnya, sihir Almaris pulang.
"Mari kita selesaikan ini, Erine." Ia melempar tongkat itu ke sisi si penyihir suci. Jarinya mengisyaratkan Dainhart agar mencabut pedang.
Semula sang duke ragu-ragu, tetapi melihat sosok Almaris sesempurna kala mereka bertemu pertama kali dulu, Dainhart memutuskan untuk menurut. Ia mencabut pedang dari pundak Erine.
Bagai kesetanan, si penyihir suci menyambar tongkat. Mula-mula ia menyihir lukanya agar menutup, lantas ia berdiri dengan terhuyung-huyung. Matanya memerah menahan sakit dan bibirnya membiru.
"Hukum Serikat Sihir itu di atas segalanya, kau mengerti?" suara Erine gemetar saat mengacungkan tongkat.
"Mari kita lihat," Almaris membalas sinis sembari mengangkat tangan, "biar sihir yang memutuskan permasalahan siapa yang lebih genting."
Dainhart melangkah mundur. Ia tahu ini bukan ranahnya lagi. Sembari menyandarkan punggung pada batang pohon terdekat, ia mengatur napas dan melihat kedua penyihir itu saling merapal mantra yang sama.
Energi sihir mulai berputar di sekitar mereka. Cahaya keemasan meledak dari tongkat Erine, sementara asap hitam pekat menjalar dari tangan Almaris. Keduanya bertabrakan di udara, memercik dan membentuk pusaran kekuatan. Pohon-pohon beringin seolah meringkuk dan tanah bergetar. Kicauan burung-burung redam seketika.
Langit bergemuruh. Seisi Hutan Terakhir menahan napas.
Serangan sihir mereka saling bertubrukan di tengah medan. Cahaya dan kegelapan berpadu, berebut dominasi. Kabut beriak dan mencekik Erine, seolah ingin melindungi penjaga aslinya. Dan perlahan, mantra Almaris mulai mendesak maju. Bayangan hitamnya menjalar lebih cepat, menelan kilau suci sihir Erine sedikit demi sedikit.
Erine tersentak. Napasnya memburu kala tubuhnya terdorong mundur. "Tidak," ia mendesis di antara gigi yang terkatup. Amarah dan kekecewaan yang melingkupi wajahnya seperti seseorang yang baru saja dikhianati kepercayaannya sendiri. "Tidak mungkin ...."
Almaris melangkah maju, memperkuat aliran sihir yang menjulur dari telapak tangan. Peluh membanjiri pelipis dan leher, wajahnya yang pucat ikut memerah. Namun sang Pengisap Jiwa telah mendapatkan sihirnya lagi, dan ia tidak segan-segan menunjukkan seberapa kuat satu-satunya penyihir wanita yang berperan sebagai algojo negeri.
"Jangan kembali sampai kau hukum semua pendosa itu!"
Dengan satu ledakan terakhir, gelombang kegelapan menghantam Erine, melontarkan si penyihir suci keluar batas hutan. Tubuhnya lenyap keluar menembus kabut, tidak terlihat dan entah jatuh ke mana.
Hutan Terakhir pun sunyi, tersisa angin yang berdesir gelisah di antara pepohonan yang membungkuk pasrah.
Seiring rumput-rumput hijau yang menyusut dan bunga-bunga yang melayu, serta kabut yang menjalin erat sekali lagi, Almaris mengatur napas yang tersengal-sengal. Lututnya gemetar bukan karena kekurangan sihir, melainkan gejolak adrenalin. Ia jatuh pada kedua lututnya.
"Almaris!" Dainhart merangsek. Ia buru-buru menghampiri, mengira wanita itu kehilangan sihirnya lagi. "Bertahanlah!" Saat ia menarik dagu Almaris dan menampar-nampar pipinya khawatir, Almaris justru tertawa. Dainhart terperangah.
"Bodoh. Aku hanya terlalu bersemangat."
Mendengar ucapan Almaris, sang duke refleks menghela napas panjang. Ketakutan yang menyerbunya hangus, meninggalkan badan yang selentur jeli. Pria itu menjatuhkan diri di sisinya, telentang pada tanah berlumpur dan memandang kabut yang menggantung di atas.
"Kukira kau kehilangan sihir lagi," gerutunya. "Bahaya. Apalagi si Erine itu sudah kau lempar keluar."
Almaris menyeringai. Ia mencondongkan tubuh, merapat pada Dainhart yang masih mengatur napas. Dari wajah sang duke yang memerah dan pandangan tidak fokus, sepertinya pria itu masih merasakan efek kekurangan darah.
"Sedemikian takutnya kau menjadi penggantiku untuk menjaga hutan ini?Tenang, itu takkan terjadi." Jari-jari lentik Almaris menyusuri dahi Dainhart, mengecek suhu tubuhnya. Suaranya melembut. "Kau masih pusing?"
Wajah Dainhart makin memerah gara-gara sentuhan Almaris yang menggelitik. Ia merinding, bukan karena ketakutan, melainkan kehangatan aneh yang lagi-lagi membuat hatinya berdebar-debar. Almaris tampak bercahaya setelah sihirnya pulih.
"Ya," jawabnya dengan suara serak.
"Aku bawakan buah-buahan untukmu. Semoga tidak hancur gara-gara interupsi Erine tadi." Almaris tersenyum. Ia menarik diri untuk mengambil sejumlah apel merah gelap yang tercecer di tanah. "Ada yang hampir hancur, tapi masih bisa dimakan kok. Kalau kau tidak suka, biar dimakan si kuda saja."
Dainhart memandang buah itu sejenak, lantas menatap Almaris sekali lagi dengan binar yang sulit diartikan. Ia menerima satu, lalu menggigitnya perlahan. Rasa manis yang sedikit asam memenuhi lidahnya, dan entah kenapa, itu terasa lebih menyegarkan daripada apa pun yang pernah ia rasakan sebelumnya.
"Kau tahu," katanya dengan seringai muram, "ini pertama kalinya seorang algojo justru memberiku buah untuk bertahan hidup."
Almaris mendengus geli. Ia duduk di samping Dainhart sambil menginspeksi kembali luka sang duke. Ia mengusapnya perlahan, dan asap hitam yang menguar segera menutup luka dengan sempurna.
"Yah, seumur hidup baru kali ini aku membiarkan mantan korbanku hidup," ujarnya dengan nada menggoda.
Dainhart memutar bola mata. "Ingat janjimu."
"Ya, ya. Aku membebaskanmu. Puas?" Almaris melipat tangan, pura-pura bersikap enggan. Meski, sejujurnya, jauh di dalam lubuk hati terdalam, ia merasa keberatan jika Dainhart benar-benar berniat pergi.
Duke manusia itu tidak terlalu buruk.
"Bukan." Dainhart mengernyit.
"Lantas?"
Melihat ekspresi Almaris yang murni kebingungan, pria itu menghela napas. "Sepertinya kau lupa," katanya pura-pura jengkel juga. Namun, ia tak bisa menahan senyum yang berkutat di ujung bibir. "Bukankah kau berjanji akan membantuku menyeret Raja ke hutanmu?"
Almaris mengerjapkan mata. Jantungnya mulai berdegup cepat. "Kau ... tidak ingin kabur saja?"
Pertanyaan Almaris membuatnya diam. Sejujurnya, pria itu sedang memikirkan sesuatu. Pertarungan sihir antara Almaris dan Erine tadi membukakan celah berpikir baru bagi Dainhart. Bagaimanapun, sihir adalah elemen netral yang tidak bisa dibilang baik atau buruk, tergantung tujuan si penyihir dalam menggunakannya. Sehingga, ketika mantra tadi justru melempar Erine si penyihir suci keluar hutan, ia merenungi kejadian itu dalam-dalam.
Ini bukan mengenai salah atau benar, melainkan kenyataan bahwa ada permasalahan genting yang lebih pantas untuk diperhatikan lebih dahulu.
"Lalu siapa yang akan menghukum pendosa-pendosa itu? Aku tidak percaya pada Erine." Dainhart beranjak. Ia mengulurkan tangan kepada Almaris. "Dan kalau tidak ada pendosa, maka kau akan kelaparan lagi, kan? Aku tidak mau mengambil risiko kau santap sungguhan—atau kehilanganmu. Atau keseimbangan dunia bakal goyah."
Almaris menelan ludah. Ia tidak salah dengar, bukan? Dainhart mengamini pendapatnya? Selama sesaat, ia memandang uluran tangan sang pria, berpikir ini hanya mimpi. Maka ia meraih tangan Dainhart, sekadar mengetes kenyataan, dan jarinya benar-benar menekan kulit hangat pria itu.
"Masa? Padahal kau cocok jadi penggantiku—"
"Tidak."
"Ayolah, Dain. Tidak buruk juga jadi penyihir, kok."
Dainhart menghela napas. Ia mengeratkan genggaman pada tangan Almaris saat menuntunnya ke kuda hitam. Ia memang masih agak pusing, tetapi setidaknya ia kembali tanggap seperti biasa. Saat Almaris memanjat kuda terlebih dahulu, ia refleks mencengkeram pinggang gadis itu—memastikan ia takkan jatuh.
Walau, Dainhart juga tidak kunjung menarik tangannya pergi dari pinggang Almaris.
"Dain?"
Ketika sang penyihir menoleh kepadanya, penasaran mengapa sang duke tidak kunjung menjawab, Dainhart mendongak.
"Kenapa aku harus menggantikanmu?" kedua matanya menatap Almaris lekat-lekat. "Kalau ... kita bisa bekerja sama?"
Almaris mengangkat alis kala pria itu melompat ke punggung kuda.
"Pegangan."
"Aku baik-baik saja."
"Aku akan mengebut. Kau bisa jatuh."
Almaris tersenyum geli. Ia melingkarkan tangannya di pinggang Dainhart sekarang, merasakan hangat dan degup jantung sang duke mengalir di sekujur badan. Sebagai penyihir yang mengisap jiwa, ia lebih peka terhadap reaksi tubuh manusia.
Entah mengapa, Dainhart tahu Almaris seperti sedang menertawakannya. Merasa malu, ia ganti bertanya, "Sepertinya tadi aku mendengar kau menyebutku milikmu saat menyerang Erine."
Benar saja. Kuku-kuku tajam Almaris refleks mencubit perutnya. Dainhart mendesis kaget. Nyaris saja ia menarik tali kekang kuda hitamnya yang mulai berpacu menuju pondok.
"Itu—maksudku, kau urusanku, bukan hak Erine untuk melakukan sesuatu padamu."
"Oh, kau mengurusku sekarang?"
Almaris menggerutu. "Cepat pacu kudanya. Masih banyak yang perlu dilakukan: memasang pintu pondok, membetulkan lantai, lalu ...."
Dainhart memutar bola mata mendengar upaya sang penyihir untuk mengalihkan topik. Meski begitu, ia mendengarkan baik-baik ucapan Almaris. Wanita itu benar. Sebelum memenuhi janji untuk membunuh raja korupsi dan lain-lain, masih ada yang perlu dibenahi dulu. Sebab, di mana lagi Dainhart bakal tinggal, ketika hanya ada satu bangunan di hutan angker ini?
Betul. Hanya Pondok Almaris.
Pondok mereka.
*** TAMAT ***
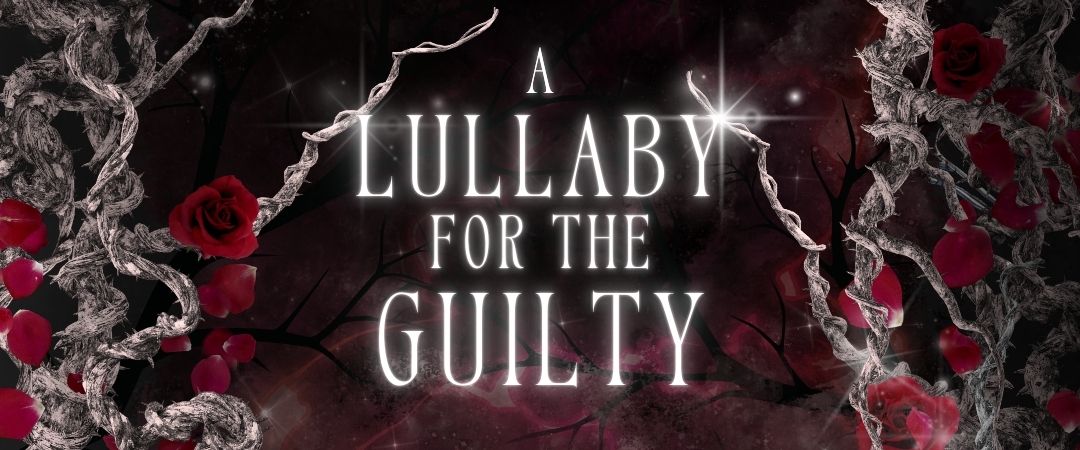
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro