Bab III | Terpaksa Bersepakat
"Jangan berbuat bodoh," adalah pesan Almaris sebelum menutup pintu pondok dan menguncinya dari luar. Nadanya tak berbelas kasih seperti kali pertama mereka bertemu.
Dainhart memutar bola mata. Tentu saja ia sedang mencari cara bodoh untuk bisa selamat. Sudah tiga hari ia mengawasi Almaris dan pondoknya yang dingin, penuh guratan kayu mahogani dan tengkorak-tengkorak tempat lilin dinyalakan. Satu-satunya yang menarik Dainhart adalah pedang-pedang panjang yang terpajang di atas ranjang kusut Almaris. Sepertinya itu koleksi dari para kesatria yang tewas di Hutan Terakhir.
Dainhart mendengus. Selagi Almaris pergi, ia harus berusaha. Pertama-tama, ia mesti meraih sesuatu yang bisa menjadi perpanjangan tangannya.
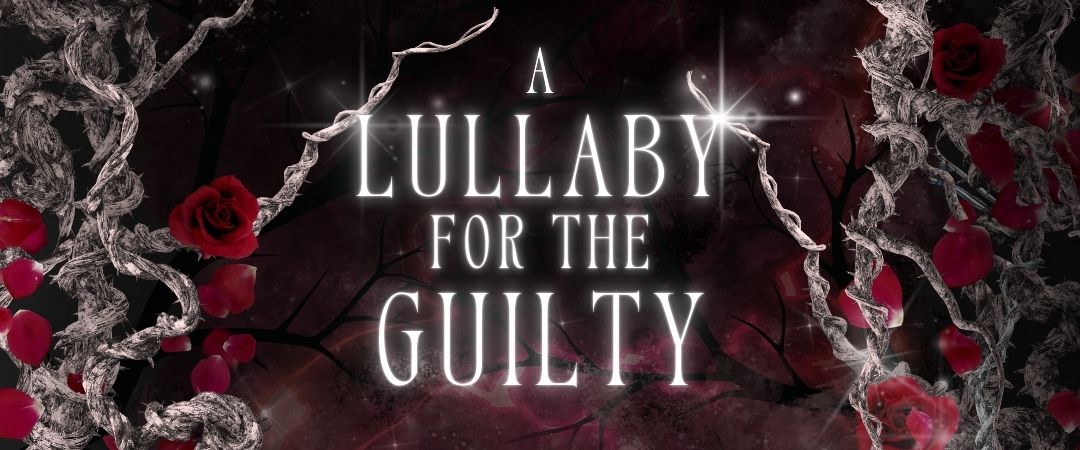
Di sisi lain, Almaris mendekati petak yang terpancar sinar mentari dengan alis bertaut. Kakinya berjinjit macam mendekati api yang berkobar. Tanah dan daun kering yang diinjaknya kian hangat dan pasrah, bukan lagi dingin dan mengisap. Bisikan-bisikan arwah menemani tiap langkah Almaris, menyuarakan ketakutan laiknya iblis yang mau disiram air suci.
Kemunculan sinar mentari di Hutan Terakhir ... itu berarti ada yang sedang mengacaukan hutan! Hanya penyihir yang sanggup melakukannya, dan bukan sembarang penyihir juga. Hutan Terakhir tak pernah diobrak-abrik oleh penyihir selain garis keluarga Almaris, itu pun cukup seorang saja. Melubangi kabut dan membiarkan surya menyorot, itu kejahatan yang setara menggali jurang neraka di tengah-tengah padang bunga.
Jadi, siapa kira-kira yang berani menantang Almaris, yang ditakdirkan menguasai wilayah ini sejak lahir ke dunia 25 tahun lalu?
Almaris mengerjapkan matanya yang terbiasa akan kegelapan. Berkas sinar itu membuat pandangannya berkunang-kunang dan silau. Almaris menyipitkan mata. Tampaklah siluet seorang gadis yang tengah menari di seberang sinar, mengayunkan tongkat dan merapal mantra.
"Hentikan, atau kubunuh dirimu!" Almaris mendesis. "Merapal sihir di wilayahku tanpa diundang, penyihir macam apa kau?"
Kabut beriak di sekeliling Almaris. Kendati sekujur tubuhnya meremang, ia masih mampu membuat kabut berusaha menjalin menutup. Seraya menghela napas berat, Almaris akhirnya mengenali sosok penyihir di seberang.
Berambut putih dan mengenakan gaun lavender yang berkelap-kelip, penyihir itu tak lain adalah Erine, putri tahta dari Persaudaraan Putih yang masyhur. Kedua bola matanya yang sejernih langit biru menatap Almaris sendu. "Alma," katanya. Tiap ucapannya seperti diiringi kicauan burung, walau tak ada burung selain gagak dan kelelawar vampir di sini. Erine menurunkan tongkat sihir, cahaya emasnya masih bertahan macam obor di tengah kegelapan hutan.
"Lama tak bertemu, Alma. Apa kau sudah melupakanku?"
Kejengkelan menggeliat di hati Almaris. Ia merasa bak jelaga parit yang dihadapkan oleh bintang paling bercahaya di langit. "Tentu saja aku lupa, untuk apa aku bersusah-payah mengingat semua makhluk di dunia ini, kalau mereka akan mati pada akhirnya?"
Kilau di wajah Erine meredup. "Benar," katanya pelan, "tapi bukan berarti kau bisa menyeret semua manusia menuju kematian dengan seenaknya."
Almaris mengernyit. "Apa maksudmu?"
Erine menggeleng. Tiap kepalanya bergerak, rasanya ada bintang jatuh dari rambutnya yang berkilau, membuat Almaris bergidik ngeri. Tanahnya tercemar! Ew!
"Beberapa hari lalu, aku bertemu seorang manusia di perjalananku. Ia berhasil kabur dari hutan ini, tetapi seluruh tubuhnya lebam dan kakinya terluka. Ia sudah setengah gila, tak tahu mana arah pulang dan siapa ibunya." Erine meringis kalut saat menjelaskan. "Setelah kupastikan, dia tidak punya dosa yang lebih besar daripada mencuri buah-buahan di tepi hutanmu, dan itu pun karena ia kelaparan! Alma, kenapa kau mulai mencaplok jiwa-jiwa yang masih bisa diampuni dosanya?"
Oh, sialan, pemuda itu! Almaris refleks menarik napas dalam-dalam sembari memijat pangkal hidung. Ia benar-benar melupakannya begitu mendapat mangsa Duke Dainhart. Ternyata si pemuda berhasil kabur, walau tubuhnya sudah terhantam akar-akar ara pencekik yang keras.
Erine mencengkeram tongkatnya. Ada gurat penyesalan sekaligus ketegasan di wajahnya. "Kau memang melakukannya, Alma? Kau menyalahi aturan Serikat Sihir, kau tahu!"
"Berkacalah!" Almaris mendengus. "Jika kau menuduhku menyalahi aturan mereka, maka kuperingatkan bahwa kau juga melanggar batas wilayah!"
Sang Pengisap Jiwa meradang. Telah habis kesabarannya. Ia mematahkan buku-buku jari, siap merapal mantra di ujung kuku-kukunya yang mahatajam. "Pergi, atau kubunuh kau, Erine. Ini wilayahku. Aturanku."
"Tidak." Cahaya emas kembali memercik di ujung tongkat sihir Erine. Kabut beriak sekali lagi di sekeliling mereka, dan daun-daun beringin mendesau gelisah. "Aku kemari sebagai utusan Serikat Sihir. Dan hukum Serikat Sihir berada di atas segalanya, sebagaimana hukum Raja di atas semua aturan personal penduduknya."
Almaris telah memanaskan sihir di ujung kuku, tetapi ada satu yang membuat Erine lebih mengancam daripadanya: Almaris belum makan. Tubuhnya melemah. Ditambah cahaya yang memancar deras dari ujung tongkat Erine laiknya matahari kedua, Almaris diterpa gelombang nyeri yang menyengat kulit. Bisikan-bisikan roh kocar-kacir dan kabut meregang.
Belum sempat melempar mantra, Erine menghunuskan tongkat sihir kepadanya, dan ia terpental menghantam pintu pondok.
Dainhart terperanjat kaget melihat pintu pondok hancur meledak berkeping-keping, serpihannya menghantam jeruji kandang dengan nyaring. Asap hitam mengepul. Pria itu mengibaskan tangan hingga asap memburai, hanya untuk mendapati Almaris terkapar di lantai batu. Asap hitam membumbung dari tubuhnya, memilin dan menjulur ke satu arah di luar pondok.
Gembok sangkar terjatuh. Dainhart spontan menyeruak keluar. Ia menyambar pedang-pedang yang tergantung di atas ranjang Almaris dan merangsek ke arah penyihir.
Namun, pemandangan pilu di hadapannya membuat Dainhart membeku.
Rerumputan hijau tumbuh di bawah pecahan lantai batu. Bunga-bunga beraneka warna bermekaran dan menyebarkan harum melati serta lavender, menyelubungi Almaris yang terbatuk-batuk dan bersimbah darah.
Asap hitam yang semula Dainhart kira adalah serpihan pintu, ternyata adalah sihir Almaris yang meninggalkan sang empunya. Pandangan pria itu mengikuti arah asap hitam menjulur ke luar pondok, merasuk pada tongkat sihir seorang gadis berambut putih di luar sana.
Dainhart tercengang. Siapa penyihir yang lebih kuat daripada si Pengisap Jiwa?
Sementara itu, di seberang, Erine menurunkan tongkat. Peluh membasahi usai ia menyerap sihir Almaris. Badannya gemetaran seperti baru saja dirasuki iblis. Meski begitu, ia berhasil. Kabut terpecah dan sinar mentari mulai menyiram Hutan Terakhir. Daun-daun dan duri-duri terbawa angin, menyingkap jalan-jalan setapak menuju dunia luar yang selama ini disembunyikan. Jamur-jamur darah dan jamur-jamur jari manusia mengerut ketakutan, rerumputan hijau tumbuh di tanah bekas pijakan Erine, bisikan-bisikan roh menghening, dan kicauan burung-burung mendekat.
Erine tampaknya tidak melihat Dainhart karena suasana pondok yang begitu gelap, kontras oleh benderang cahaya di sekelilingnya. Ia juga kelelahan usai merenggut sihir Almaris.
"Ini ... ini hukuman untukmu, Alma." Suaranya gemetar. "Kusita sihirmu sampai kau menyesal, dan kubukakan jalan-jalan tersembunyi di hutan ini, agar manusia-manusia yang kaumangsa bisa melarikan diri."
Sambil terseok-seok, Erine berbalik pergi menuju sisi hutan yang lain, meninggalkan Almaris sekarat.
Ini kesempatan emas bagi Dainhart. Dentam jantung menggedor-gedor relung dada tatkala ia mengangkat pedang tinggi-tinggi. Napasnya memberat membayangkan bahwa ia bakal jadi manusia pertama yang mampu membunuh penyihir dengan citra seburuk Almaris. Tidak hanya para pejabat lain, Raja pun akan ketakutan kepadanya, dan ia mampu membalaskan dendam—
Almaris terbatuk. Wanita itu mula-mula mengerang kesakitan. Lenyap sudah keanggunan dan kekejiannya ketika ia meringkuk, menangisi tubuhnya yang menggigil hebat dan sihir yang lenyap.
"Tidak ...." Dengan mata terpejam, Almaris sesenggukan. Ia seakan lupa ada Dainhart di sisinya, siap menghunjamkan pedang kapan saja. "Sihirku ...."
Dainhart terbengong-bengong. Dalam sekejap, Almaris berubah dari penyihir yang ditakuti menjadi sekadar wanita yang menangis, dan Dainhart benci wanita menangis. Ini mengingatkan pada mendiang ibunya. Apa-apaan itu? Almaris adalah seorang pembunuh dan tak semestinya ia berlagak serapuh manusia. Cengkeraman Dainhart di gagang pedang menguat, tetapi seolah ada perisai kasat mata di sekeliling Almaris yang mencegah bilah pedang mendekati kulit pualamnya.
Selama sesaat Dainhart terpaku, hingga Almaris membuka mata dan melihat apa yang sedang dilakukan pria itu. Air mata menggenang di pelupuk kelam Almaris dan hidungnya kemerahan, sungguh pemandangan yang teramat tidak cocok di mata Dainhart.
"Kau mau membunuhku, hah?" gertakan Almaris bahkan terdengar seperti gonggongan anjing kecil. "Lakukan saja selagi aku jadi manusia biasa. Maka kau yang akan menggantikanku menjadi penyihir penjaga hutan ini."
Alis Dainhart berkedut. "Apa?"
Almaris mendorong tubuhnya supaya duduk. Ia meringis kesakitan ketika pucuk-pucuk lembut rerumputan hijau justru membuat kulitnya kemerahan dan merembes darah. "Setiap bagian alam ada penyihir yang terikat untuk menjaganya. Kalau tidak ada yang menjaga hutan ini, maka siapa lagi selain makhluk haus darah sepertimu?"
"Aku bukan penyihir," tukas Dainhart dingin. "Dan aku takkan sudi menjadi bagian dari kalian."
Almaris mendengus geli. Bahkan di sela-sela kekalutan, ia masih menemukan hal untuk ditertawakan pada sang duke. "Siapapun bisa jadi penyihir, semudah penyihir dilucuti menjadi ... manusia." Nadanya berubah getir. "Dan harus ada yang menjaga hutan ini, sebab siapa lagi yang menjadi algojo bagi para pendosa?"
Dainhart dibuat tercengang, sehingga Almaris memiliki kesempatan untuk merebut kembali pedang itu darinya. Ketika sang pria memasang kuda-kuda perlindungan diri, Almaris justru beranjak menjauh.
"Pedang ini hanya bisa digunakan dengan sihir. Tanpa sihir, bilahnya setumpul batu sungai." Almaris melempar pedang itu ke bawah ranjang. Dencang suaranya memenuhi pondok.
Dainhart tidak terlalu mendengarkan. Ia merenungi ucapan sang penyihir barusan. Harus ada yang menjaga hutan ini, sebab siapa lagi yang akan menjadi algojo bagi para pendosa?
Andaikata ia membunuh Almaris, dan jikalau janji sang penyihir memang benar, bisa-bisa nasib Dainhart makin memburuk: ia diubah jadi penyihir untuk menggantikan peran Almaris, dan selamanya terjerat di Hutan Terakhir. Itu nasib yang lebih muram daripada kematian.
Dainhart mengepalkan tangan. Sial. Semestinya ia kabur saja tadi.
Namun, tak ingin kalah dari Almaris, ia menyahut dengan sinis. "Masih perlukah keberadaan penyihir di sini? Tidak, memangnya Hutan Terakhir masih dibutuhkan? Raja yang sekarang teramat bejat, sampai-sampai semua pejabat korupsi ia lindungi dan tidak lagi dikirim kemari. Yang ia kirim justru orang-orang yang berusaha memberontak."
Kegetiran nada Dainhart begitu personal, dan itu tidak luput dari perhatian Almaris. Sembari mengobati luka dengan ramuan-ramuan dalam botol, ia menjawab, "Benar," katanya. "Itulah mengapa aku terpaksa menyeret manusia dengan dosa-dosa kecil agar aku bisa tetap bertahan hidup. Tidak ada jiwa-jiwa pendosa yang bisa kuisap, itu berarti tidak ada makanan untuk sihirku dan hewan-hewanku."
Ketika mereka bertukar tatap, ada kebencian yang menguar di sana, tetapi bukan untuk satu sama lain. Dainhart menyipitkan mata dan Almaris menghela napas.
"Jika kau ingin pergi, pergilah," kata Almaris seraya melanjutkan pengobatan. "Namun setiap tindakan ada konsekuensinya, Duke Dainhart. Jika aku tewas, maka kau akan terseret oleh hutan ini untuk menjadi penggantiku, sebab aku tak memiliki keturunan, dan jejak pembunuhanmu familiar dengan kehidupanku."
Dainhart menggertakkan gigi. "Dan jika kau hidup?"
"Jika aku hidup ...." Almaris mengulang, tetapi tidak segera melanjutkan. Mendadak, sebuah gagasan terbersit di benaknya.
"Jika aku hidup," ulang Almaris pelan-pelan, tetapi dengan kekuatan yang berbeda. Ia menatap Dainhart sekali lagi. Sinar kekejian dan keinginan balas dendam menari-nari di kedua matanya. "Dan jika aku berhasil mendapatkan sihirku kembali, maka kau akan kubebaskan. Atau apapun yang kau mau."
Tawaran Almaris terdengar menggiurkan, tetapi juga mencurigakan. Kebebasan memang ia inginkan, tetapi bagaimana jika Almaris mampu membantunya membunuh Raja?
Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menekan debar harapan di dada. "Oh, begitu? Sepertinya kau bisa membantuku membunuh Raja, atau takkan ada lagi yang berani mengusik pendosa itu." Ia melipat tangan di depan dada. "Lalu? Bagaimana caranya agar sihirmu bisa kembali?"
"Bukankah kau sudah membunuh dua ratus penyihir?" Almaris tersenyum culas.
Dainhart membeliak. Ia berusaha keras agar tidak tersenyum sama kejinya, membayangkan sensasi menyenangkan tiap kali menebas kepala penyihir. "Dan apa jaminannya kau takkan melanggar janji?"
"Krusial. Hidupku, umurku, entahlah. Tergantung hukum alam."
Dainhart kurang puas dengan jawaban Almaris, tapi selalu ada cara lain yang bisa dipersiapkannya nanti. "Aku tidak punya apa-apa sekarang."
Almaris menunjuk pedang-pedang yang tadi dilemparnya.
"Bukannya kau bilang pedang itu hanya bisa dipakai dengan sihir?"
"Dan kau percaya?" Almaris terkekeh murung. "Kau benar-benar menghiburku, Duke Dainhart. Pakailah, dan bunuh Erine. Usir dia dari hutanku."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro