3. As a Friend, Not as a Stranger
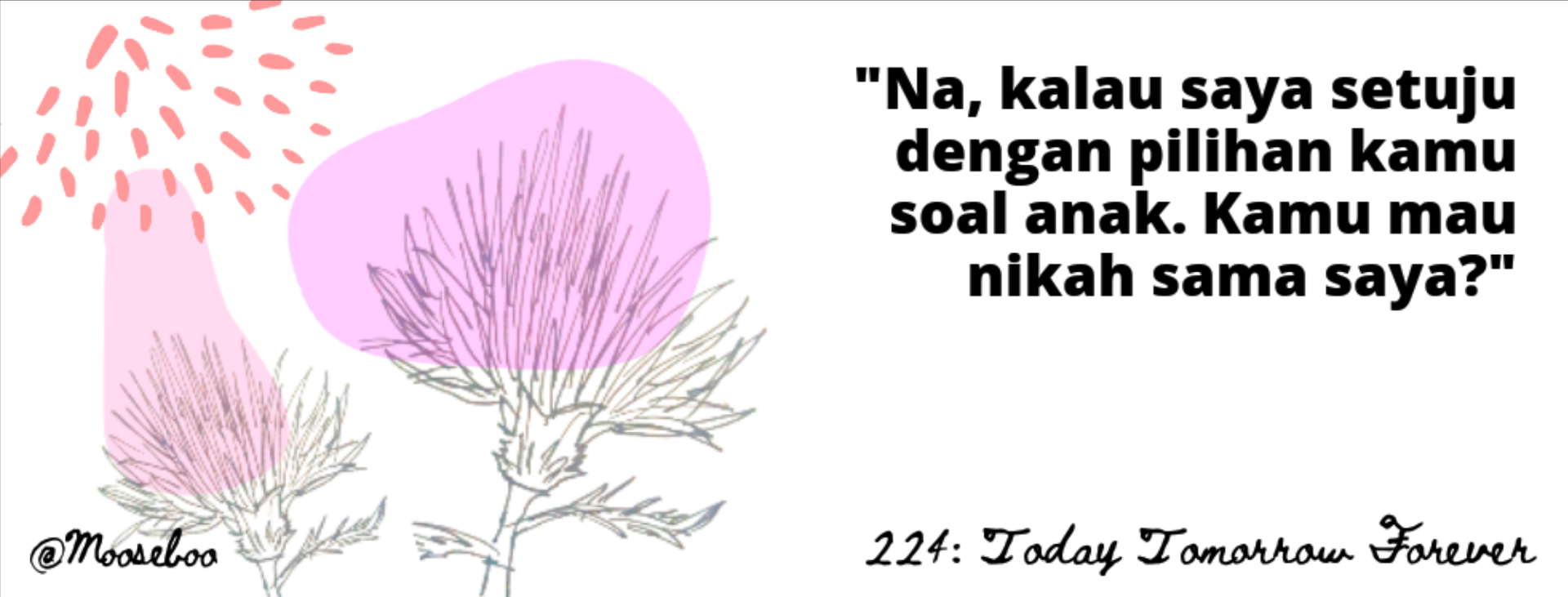
-
Ekspresi Ninna tidak pernah berubah sejak tadi pagi, masih datar. Sementara kedua bola matanya mengawasi tingkah seorang lelaki yang tertawa lepas dan sok akrab di tengah keluarganya. Bahkan, Sam keponakan lelaki Ninna yang tidak pernah bisa dekat dengan orang lain, malah duduk nyaman di pangkuan lelaki itu sambil berkelakar dengan paha ayam bakar di tangannya.
Ninna memijat pelipisnya pelan. Seandainya saja Genna dan Desta tidak tiba-tiba melakukan sidak pagi-pagi buta lalu menculiknya dari kosan mungkin dia berhasil lolos dan pergi dengan Felix. Demi apapun, dia lebih memilih menemani lelaki itu nge-gym ketimbang terperangkap di kondisi seperti sekarang.
"Nin, enggak makan? Ayam bakarnya udah jadi loh," kata Genna menepuk bahu Ninna yang sedari tadi mengasingkan diri di teras samping, sementara keluarganya sedang asyik membuat barbeque party ala kadarnya di halaman villa milik keluarga Desta.
"Enggak laper," jawab Ninna singkat.
"Cemberut melulu, deh. Senyum kali," goda Genna mencolek pipi sang adik. "Kan ada Kais."
"Justru ada dia aku enggak mood. Lagian Mbak ngapain sih ajak dia?"
Genna meletakkan bokongnya di sebelah Ninna. "Bunda yang ajak. Liburan ini juga maunya Bunda. Mana bisa Mbak tolak. Lagian Kais orangnya lucu kok, baik banget malah."
Ninna kemudian bungkam sambil mengamati lelaki yang mengenakan sweater merah bata di depan sana, Kais. Lelaki itu kini sedang mengobrol dengan Farah. Sesekali Kais melirik kepada Ninna, kemudian mengangguk, dan membicarakan sesuatu dengan Farah. Ninna jadi berpikiran yang tidak-tidak.
"Kamu masih ngerokok?" tanya Genna tiba-tiba. "Tadi sore Mbak lihat ada bungkusnya di tas kamu."
Ninna mendelik sebal. "Mbak buka-buka tas aku?"
"Bukan aku yang buka, tapi Sam. Untung enggak sempat dia mainin," ujar Genna melipat kedua tangannya ke dada. "Kamu kenapa sih, Nin? Kamu ada masalah? Mbak tuh paling tahu kalau kamu udah aneh-aneh, pasti lagi mikirin sesuatu."
"Enggak ada hubungannya kali Mbak sama rokok, lagian enggak tiap hari juga," kata Ninna beralasan.
"Sesekali juga sama aja Ninna. Daripada kayak gitu mending kamu cerita ke Mbak, jangan pendam sendiri," pesan Genna merangkul bahu adiknya. "Nanti kalau Kais tahu bisa-bisa dia ilfeel loh."
"Dia udah tahu."
"Serius?"
"Hari gini cewek ngerokok udah enggak aneh kali Mbak," gerutu Ninna.
Genna mencebik. "Hari gini yang namanya ngerokok bahayanya tetep sama kali, Nin."
Ninna diam. Bila sudah begini, Genna pasti tidak akan mau kalah.
"Tapi, Nin. Jangan-jangan Kais mulai suka lagi sama kamu? Ya, kan? Buktinya dia mau nerima kamu apa adanya," kata Genna setelah keduanya membisu selama beberapa menit.
"Mbak lebay. Cuma gara-gara satu dari semua hal yang ada di aku dia terima, bukan berarti kan dia suka sama aku?" gerutu Ninna melepaskan rangkulan Genna dan mengetatkan cardigan di tubuhnya. Setelah itu, dia bangkit berdiri. "Udah, ah. Aku mau ke dalam dulu."
"Mau ke mana sih? Yang lain kan lagi kumpul di sini."
"Ada deck (presentasi) yang mau aku cek," jawab Ninna asal dari dalam rumah. "Lagian ada aku atau enggak, enggak ngaruh juga kok di sana. Udah ada yang gantiin. Enggak tahu deh, anaknya Bunda siapa sebenernya."
Genna terkekeh lalu bangkit dan mengintip Ninna dari balik pintu. "Kamu bawa kerjaan ke sini? Habis makan kita mau jalan-jalan, loh. Enggak mau ikut?"
"Enggak!"
"Dasar batu," gerutu Genna sebal.Jam sudah menunjukkan pukul sepuluh malam. Suasana villa pun senyap dan sepi, hanya ada irama gerimis sayup-sayup di luar villa. Saking tenangnya, suara igauan Mia yang tertidur nyenyak di kamar Genna samar-samar terdengar.
Genna memang tidak membawa Mia pergi jalan-jalan sore tadi, alasannya karena takut bayi itu kecapekan. Lagi pula ada Ninna yang akan menjaganya—dan Kais.
Bila mengingat Ninna hanya bertiga dengan Kais, rasa malas kembali muncul di benaknya. Beruntung, Kais memilih diam dalam kamar sejak keluarga Ninna pergi, perut penuh sepertinya membuat lelaki itu pulas.
Ninna mengambil ponsel dari atas sofa dan membaca sekali lagi pesan dari Genna. Dia menggerutu, ketika Genna bilang mobilnya terjebak macet saat akan kembali menanjak ke atas. Kemungkinan mereka akan tiba tengah malam.
Ninna menguap lebar lalu mengecek deck untuk pitching* dari Mutia yang sudah dia rapikan dan siap dikirim Senin depan. Senyum mengembang. Dia yakin perusahaannya yang bakal memenangkan pitching kali ini. Apalagi direktur perusahaan otomotif itu sudah berhasil dia dekati.
"Oek ...."
Suara tangisan Mia tiba-tiba terdengar memecahkan senyap. Ninna buru-buru bangkit dari sofa lalu menghampiri Mia. Sepertinya, keponakannya itu kelaparan, karena beberapa kali Mia mengulum jempolnya sendiri sambil menangis kencang. Segera, Ninna membawa Mia ke gendongannya, menepuk pelan punggung bayi itu, dan mencari stok asi Genna dalam kulkas di dapur.
Menggendong bayi berumur empat bulan yang sedang rewel sambil menghangatkan asi bukan hal mudah. Ninna sampai-sampai harus menggunakan kakinya untuk membuka kulkas. Benar-benar multitasking.
"Butuh bantuan?"
Ninna menoleh ke kiri. Kais sudah berdiri di belakangnya sambil menahan tawa. Kemudian tanpa menunggu jawaban Ninna, dia sudah membawa Mia ke pelukannya dan menenangkan bayi itu.
"Thanks," jawab Ninna singkat kemudian melanjutkan kegiatannya.
"Mbak Genna bilang mereka kejebak macet?" tanya Kais sembari mengusap punggung Mia. "Kasihan banget. Untung Mia enggak ikut. Kalau enggak dia pasti rewel di mobil."
Ninna mengangguk. Sesekali dia mencuri pandang kepada Kais yang berkeliling dapur sambil menenangkan Mia.
"Sini, biar saya yang bawa ke dalam," kata Ninna mengulurkan tangannya di depan Kais saat asi Mia sudah siap.
"Enggak apa-apa, biar saya yang bawa ke kamar," kata Kais mengambil botol susu di tangan Ninna. Kemudian sambil memberikan susu itu kepada Mia, Kais mengekori Ninna.
Di dalam kamar, Ninna dan Kais memilih diam. Keduanya terlihat kikuk meskipun mereka duduk berseberangan di tepian kasur, mengapit Mia yang sudah tenang dan kembali tertidur.
"Mau kopi? Kita ngobrol di luar, yuk!" ajak Kais lagi menggaruk tengkuknya dan melangkah ke depan. "Enggak asyik loh liburan gini sibuk sendiri-sendiri."
Ninna mengangguk. Di ruang tengah, dia duduk di sofa sambil merapikan berkas pekerjaannya. Setelah itu, Ninna pun menyalakan televisi di ruang tengah untuk mengusir sepi.
"Liburan masih kerja?" kekeh Kais mengangsurkan segelas kopi hangat kepada Ninna.
"Namanya juga dipaksa liburan," kata Ninna merutuk kesal.
"Jadi, itu alasan kamu cemberut dari tadi?" goda Kais menjatuhkan tubuhnya di sebelah Ninna.
"Emang iya? Sok merhatiin banget," cibir Ninna sebal.
"Gimana enggak perhatian, muka kamu itu udah kayak kertas diremas-remas kayak gini loh dari pagi. Bikin kepo orang, kan?" terang Kais memeragakan wajah Ninna yang ditekuk dalam.
Ninna terkekeh geli. "Apaan sih? Enggak gitu juga kali. Lebay."
"Emang iya kok. Tapi ketawa kamu barusan lumayan oke. Kelihatan pas sama tema liburan hari ini," goda Kais dengan tatapan ke arah televisi.
Senyum Ninna memudar. Dia memindahkan tatapannya ke depan, mengabaikan kelakaran Kais. Meskipun, raut wajah Ninna jelas kentara dipaksakan menikmati tontonan drama aneh di televisi. Begitupun, Kais. Keduanya seolah-olah membiarkan dialog di layar televisi bergerak liar sesuai dengan ide gila si penulis skenario.
"Kamu bikinin saya kopi bukan lagi coba ngerayu saya, kan?" tanya Ninna membuka obrolan.
Kais tertawa pelan. "Kayaknya kamu harus sedikit ngurangin kerja, Na. Kelamaan mikirin kerjaan malah bikin kamu negatif thinking melulu, sampai enggak bisa bedain mana ngerayu dan mana yang sekadar cari teman."
Ninna menyesap nikmat kopi buatan Kais. "Masalahnya kalau kamu yang ngomong, saya malah makin negatif thinking."
"Oke. Derita punya tampang cakep emang sering disalah artiin sih," celetuk Kais sambil mengedikan bahunya
"Ka, please," gerutu Ninna geli.
Kais makin tergelak. Suasana di sekitar mereka pun mulai mencair. Ninna tanpa sadar sudah duduk sambil bersila menghadap Kais. Sepertinya, acara televisi di depan Ninna sudah tak lagi menarik.
"Oh iya, saya dengar kamu ambil Phd di Inggris. Di mana?"
"Lebih tepatnya Scotland, GSA (Glasgow School of Art). Jadi, saya sempat ambil Master di GSA Singapura, terus kebetulan tesis saya dilirik sama Professor di sana dan dilanjutin buat disertasi," jawab Kais.
"Glasgow?" tebak Ninna dengan raut wajah tiba-tiba semringah.
Kais mengangguk pelan seolah masih kaget dengan respons Ninna. "Kenapa?"
"Kamu tahu, saya pernah 6 bulan di sana karena ikut program exchange perusahaan," cerita Ninna sepenuhnya melupakan drama picisan di televisi. "Jadi, kantor pusat agency saya itu di Glasgow. Dan, selama di sana saya sempat tinggal di daerah Woodlands."
"Oh iya? Tapi di sana lumayan mahal kan biaya sewa flat-nya?" tanya Kais yang juga ikut duduk menghadap Ninna.
Ninna tersenyum pongah. "Kan kantor yang bayarin?"
"Oke," ucap Kais mengangkat kedua tangannya menyerah. "Kalau saya dulu tinggal di Dennistoun, maklum mahasiswa."
Ninna mengangguk lagi. Obrolan panjang soal Skotlandia pun muncul di tengah-tengah mereka. Dimulai soal Glasgow yang terkenal sebagai kota musik, pub dan kastil tua serta kehidupan malamnya—yang bila diibaratkan seperti paduan musik tradisional, kontemporer, dan EDM yang modern—hingga berlanjut ke Brexit lalu Megxit. Sampai-sampai waktu pun menyerah untuk memberi batas.
"Beda ya rasanya ngobrol sama Dosen," kata Ninna menggoda Kais. "Cukup berbobot."
Kais menyesap sisa kopi di gelasnya sambil menghadap Ninna. "Berarti udah sesuai persyaratan dong?"
"Buat?" tanya Ninna bingung seraya meletakkan gelas kopi ke atas meja.
"Jadi suami kamu."
Ninna mengatupkan bibirnya dan tersenyum kecil sambil memandangi Kais. "Ka, boleh saya tahu alasan kamu setuju sama rencana Mama kamu?"
"Serius kamu mau tahu?"
Ninna mengangguk mantap.
"Karena kamu sebenarnya perempuan kesepuluh yang dikenalin Mama ke saya. Dan, kalau kali ini saya nolak lagi. Bukan enggak mungkin bakal ada yang kesebelas, keduabelas dan selanjutnya."
Ninna mengulum senyum. "Jadi, soal angka?"
"Kurang lebih," jawab Kais masih betah mengamati mata gelap Ninna. "Tapi selain itu, karena perempuannya itu kamu. Makanya saya coba ikutin kata Mama."
Alis Ninna menyatu. "Memang kenapa dengan saya?"
"Seenggaknya kamu bukan orang asing buat saya. Saya tahu kamu," terang Kais meminum kopinya.
"Sok tahu," decak Ninna. "Ka, memang dulu kita sedekat apa sih? Dari Bunda, Mbak Genna, sampai Tante Ria selalu bilang hal yang sama ke saya."
"Kamu lupa?"
Ninna mengangguk cepat. "Lupa apa?"
Kais membisu dan mengalihkan tatapannya dari Ninna. "Lupain aja, enggak penting. Kalau kamu, kenapa kamu selalu nolak buat nikah?"
Ninna merenung. "Sebenarnya bukan nolak sih. Saya cuma malas aja. Dan, takut kalau nanti saya punya anak, dia bakal nyesal pernah lahir di dunia. Karena dunia itu kejam, Ka.
Kita enggak akan pernah tahu respons dunia ke dia kayak gimana. Saya takut dia enggak cukup berani buat ngehadapin dunia dan akhirnya nyalahin kita karena dia pernah lahir. Bisa dibayangin kan gimana rasanya dengar itu dari mulut anak kita sendiri?"
"Wow ... how deep. Tapi enggak semua pernikahan harus ada anak, kan?" kata Kais masih memandangi layar televisi di depannya.
Ninna terbahak. "Bullshit. Bukannya itu tujuan orang buat menikah? Mana ada, Ka, orang nikah tapi enggak mau punya anak?"
"Saya."
Spontan, Ninna mendongak. Air mukanya tampak kaget. Namun, sesaat kemudian dia tertawa pelan.
"Jangan bilang kalau saya lagi coba ngerayu kamu lagi, Na," potong Kais melirik Ninna. "Karena jujur menurut saya, ada atau enggaknya anak, enggak masalah. Selama kita berteman dengan orang yang tepat."
Tawa Ninna berhenti. "Yakin kalau saya orang yang tepat?"
"Who knows? Tapi yang pasti satu jam ngobrol sama kamu, buat saya yakin kalau ngehabisin waktu lebih lama sama kamu justru lebih menyenangkan."
Ninna tersenyum kecut. "Hah ... Kenapa bahasan kita jadi berat gini, sih?"
"Tenang aja. Saya emang udah biasa jadi tempat sampah buat orang-orang butuh diskusi. Mungkin, besok saya bakal buat jadwal bimbingan selanjutnya buat kamu," kelakar Kais dengan mimik belagak serius.
"Apaan sih? Garing banget, Ka," celetuk Ninna mengulum senyum, kemudian menyandarkan kepalanya ke sandaran sofa. Kedua mata Ninna semakin bebas memandangi Kais.
Akan tetapi, alih-alih tertawa Kais mendadak diam. Wajahnya terlihat serius saat mengamati Ninna.
"Na, kalau saya setuju dengan pilihan kamu soal anak. Kamu mau nikah sama saya?" tanya Kais.
Tubuh Ninna menegak. "Kamu gila?"
Kais mengedik. "Seperti yang tadi saya bilang, saya cuma butuh teman."
Segera, Ninna bangkit dari duduk, mengeluarkan pouch dari dalam tas, dan berjalan ke teras samping sambil tertawa hambar.
"Na! Kamu mau ke mana?" tanya Kais mengikuti Ninna.
"Nyebat! Kalau di dalam nanti baunya ketahuan Bunda," kata Ninna mengeluarkan rokok dari dalam pouch.
"Jadi?"
"Jadi apa?" tanya Ninna ketika Kais sudah berdiri di sampingnya.
Kais merebut bungkus rokok dari tangan Ninna, mengeluarkan isi di dalamnya, dan menyalakan satu batang. "Jawaban kamu?"
Ninna tercenung. Tatapannya tidak pernah lepas dari Kais. "Saya masih belum bisa jawab sekarang. Maaf."
"Oke, saya paham," jawab Kais membiarkan asap putih dari mulutnya mengawang ke udara. "Tapi saya tetap bisa dekat sama kamu, kan? As a friend, not as a stranger."
Ninna mengedik dengan salah satu sudut bibirnya naik. "Let's see."
Keduanya terkekeh sambil memandangi langit malam puncak yang gelap di depan mereka. Bau petrikor menguar, sementara gerimis sudah pergi ditelan pekat. Hanya menyisakan tawa, dinginnya udara setelah hujan, dan mereka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro